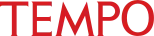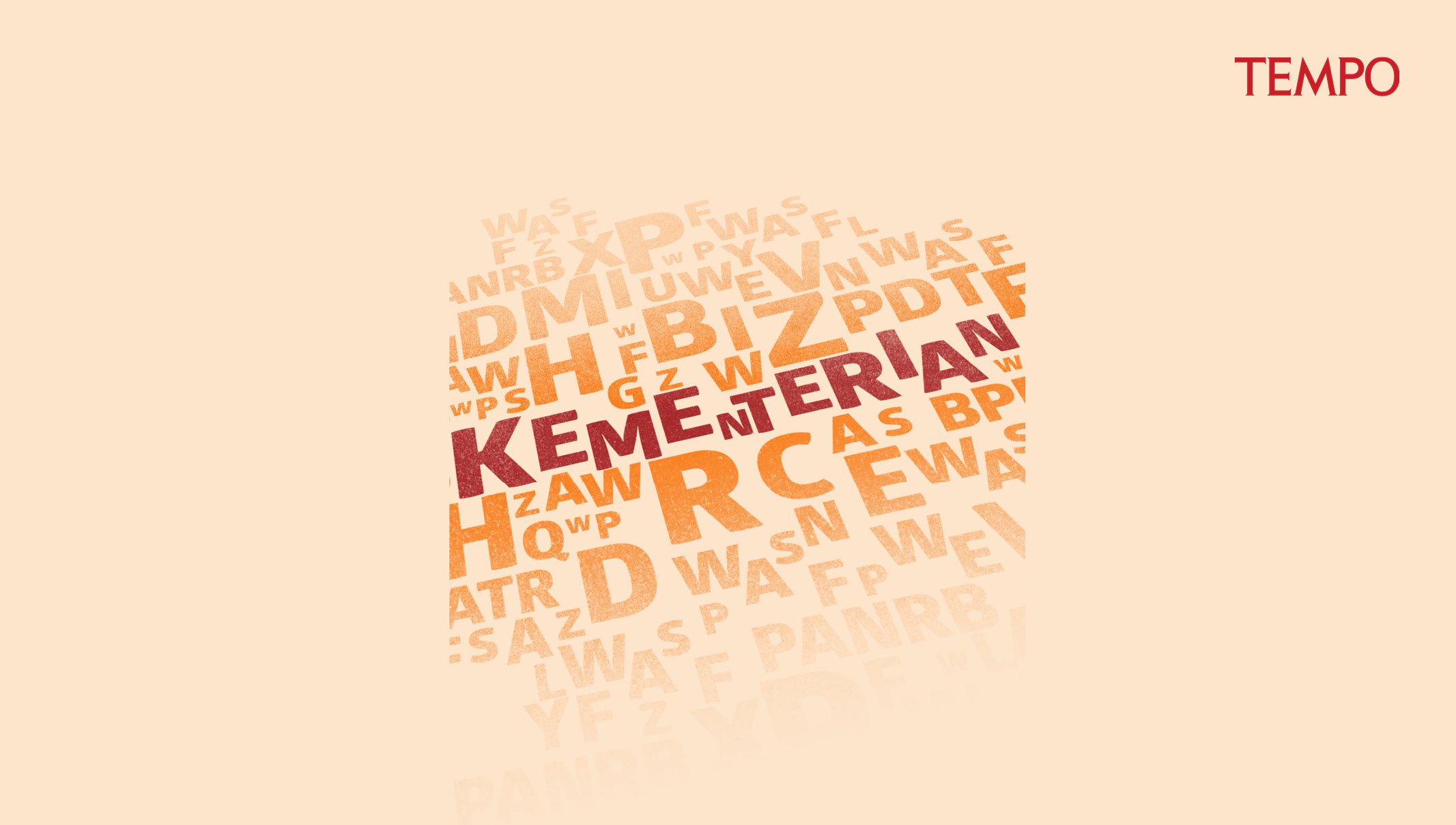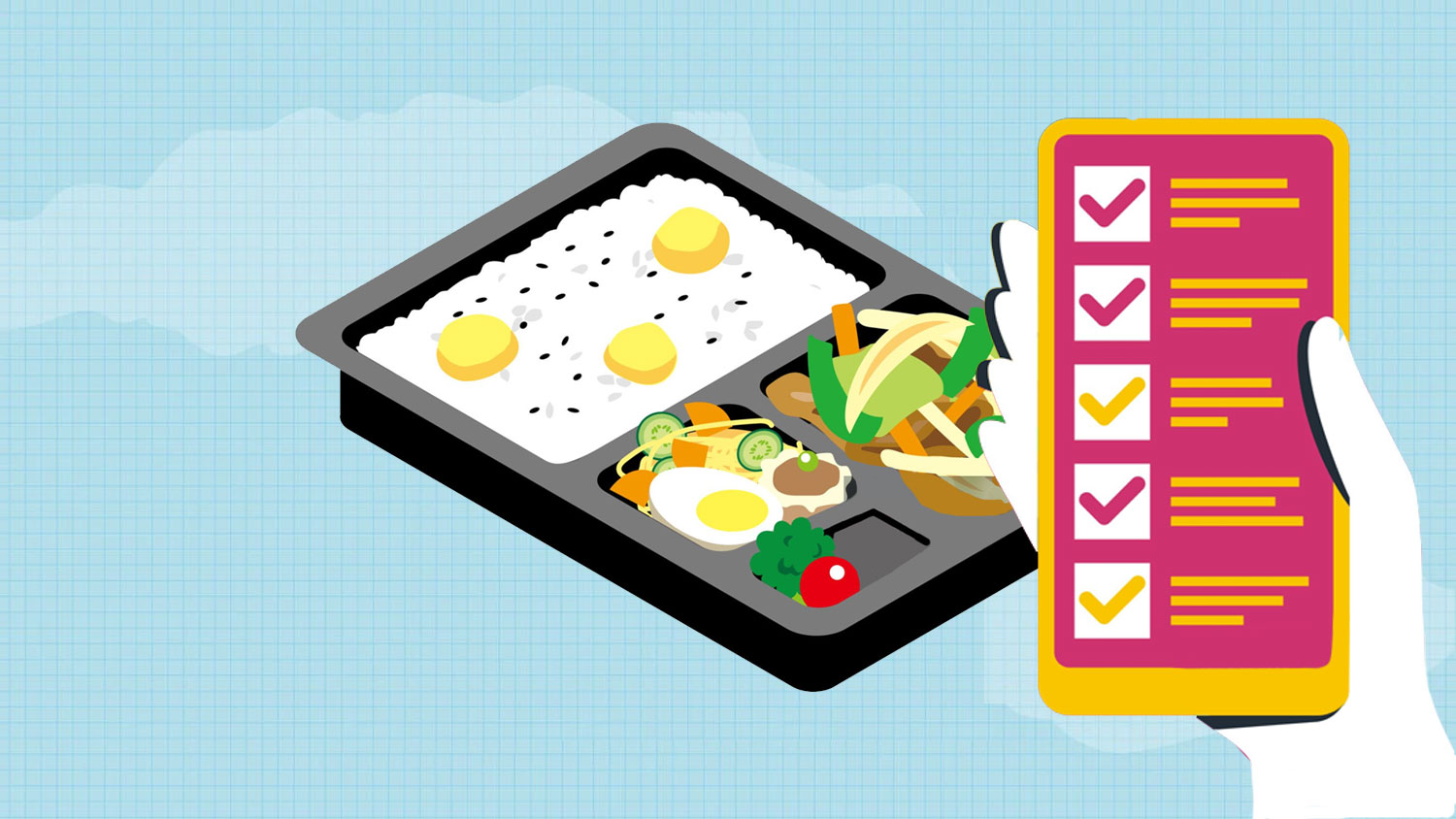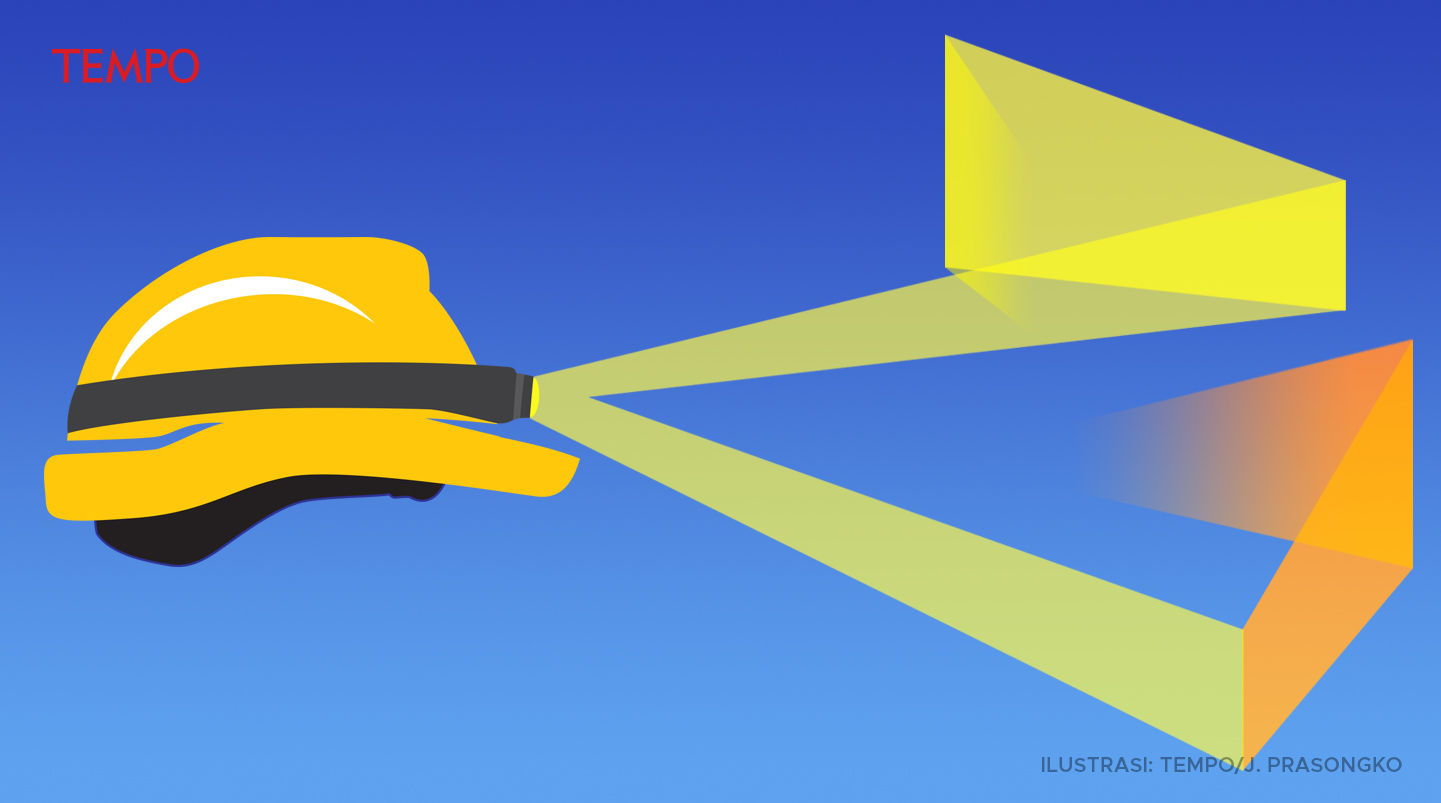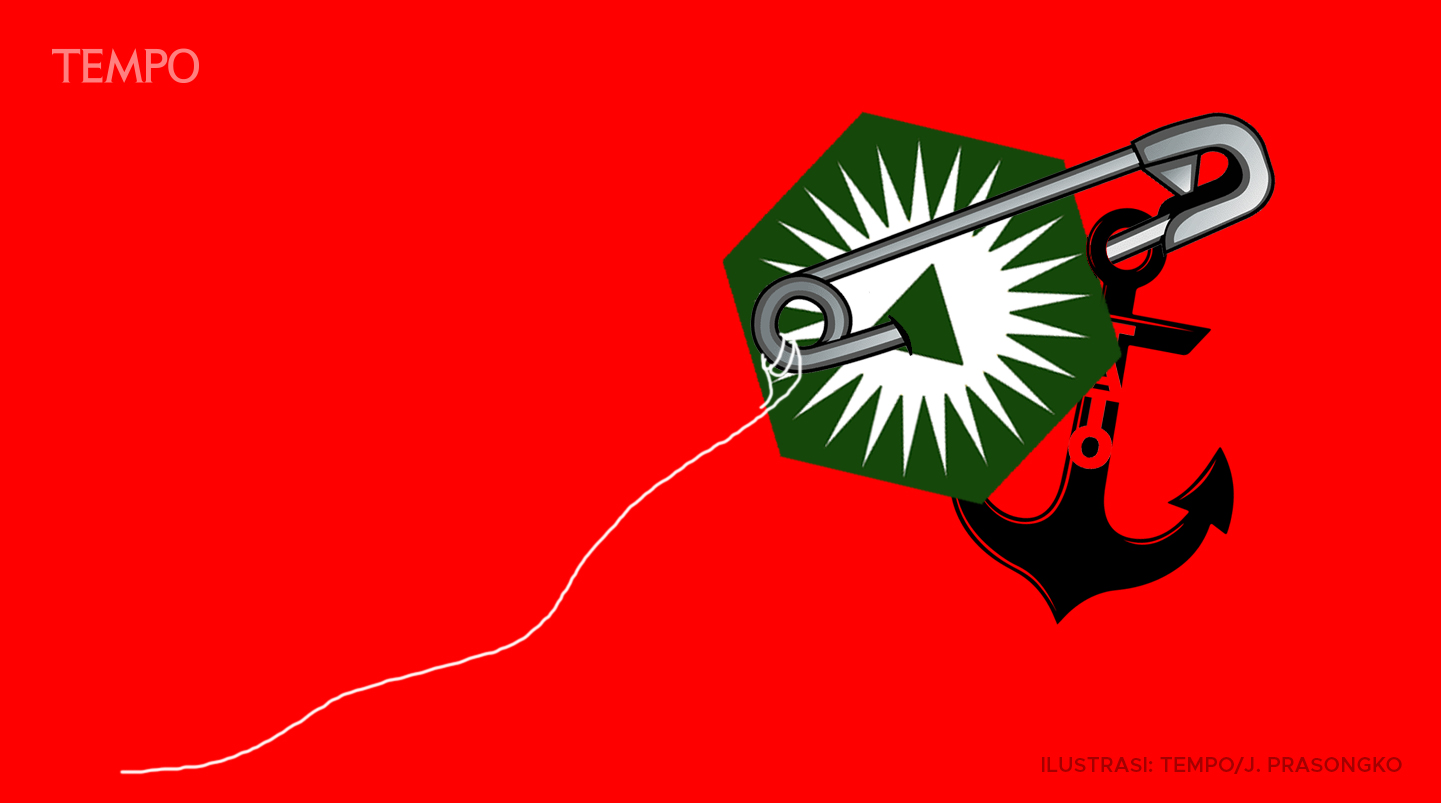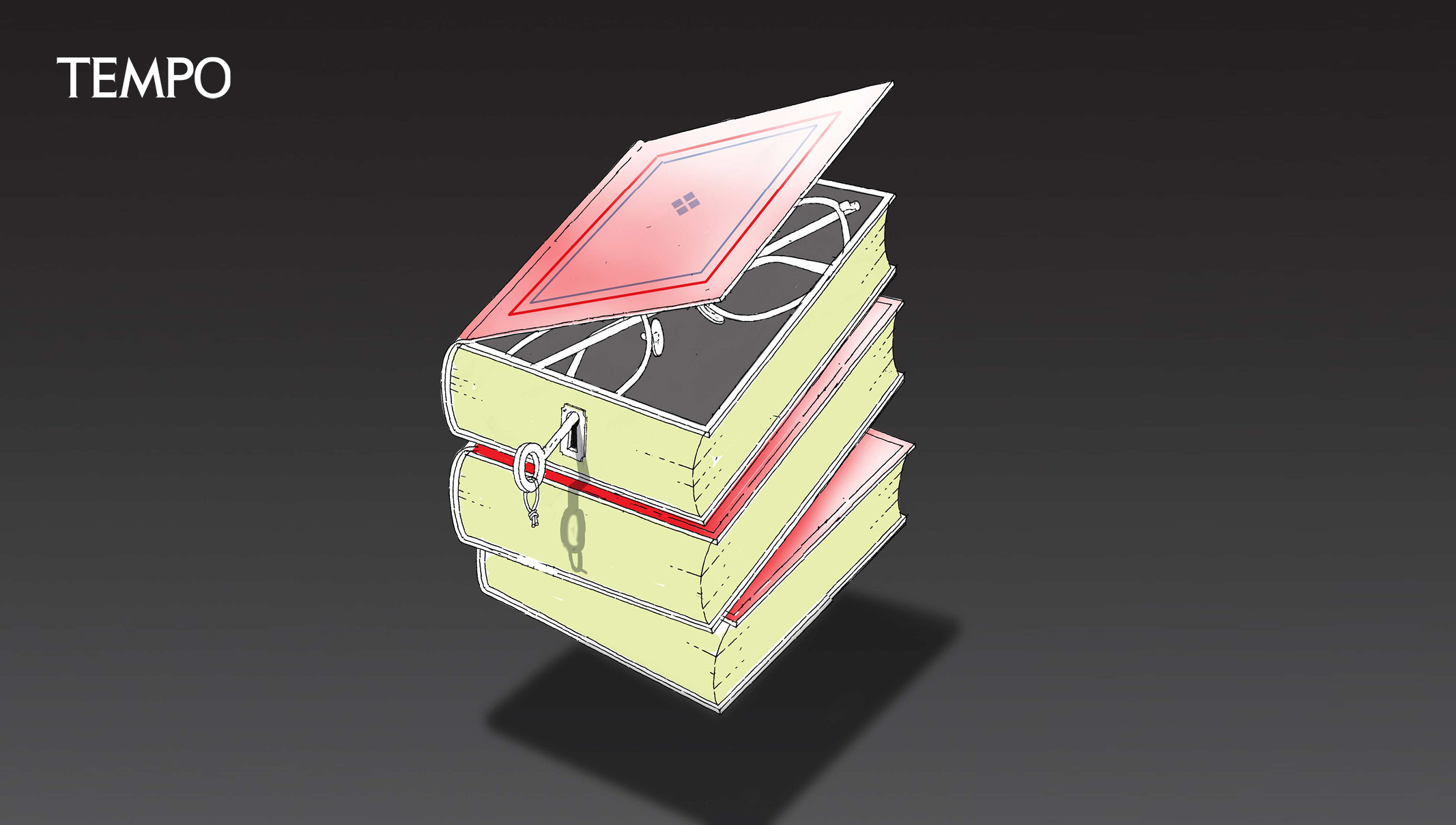Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Seno Gumira Ajidarma
panajournal.com
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Bagaimanakah militerisme mempengaruhi politik? Plato (427-347 SM) memaknai kata "virtue" sebagai semacam pengetahuan bahwa menjadi pribadi saleh (virtuous) berarti mengerti yang "baik" (Oksala, 2013: 14). Tapi Niccolo Machiavelli (1469-1527) memberi makna lain yang bahkan nyaris membingungkan. Meski mendukung kehidupan beragama, Machiavelli berpendapat bahwa bagi seorang pemimpin, moralitas berada di tempat kedua di bawah kebergunaan bagi khalayak dan keamanan negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ini bukan karena Plato seorang idealis, sedangkan Machiavelli realis, melainkan karena Machiavelli mengacu pada kualitas kebajikan (virtue) dalam pemimpin militer zaman Romawi. Dalam kriteria ini, seorang pemimpin termotivasi oleh ambisi mengejar kejayaan-suatu sifat yang bertentangan dengan kebajikan rendah hati dalam ajaran agama. Menurut Machiavelli, ini manifestasi kepentingan pribadi yang menetap dalam sifat manusia dan dengan begitu bisa dimanfaatkan bagi kebaikan bersama.
Machiavelli membuat analogi lebih jauh antara pemimpin militer dan pemimpin politik dengan menunjuk aspek lain virtue, seperti keberanian, disiplin, dan organisasi. Ia menekankan pentingnya menganalisis situasi secara rasional sebelum bertindak dan mendasarkan tindakan bukan atas bagaimana sebaik-baiknya mereka berperilaku, melainkan bagaimana mereka akan berperilaku dalam kepentingan pribadinya. Bagi Machiavelli, konflik sosial adalah dampak tak terelakkan dari sifat mementingkan diri manusia.
Pendapatnya itu bertentangan dengan pandangan keagamaan Abad Pertengahan, yakni mementingkan diri bukanlah kondisi alamiah. Menghadapi sifat mementingkan diri, seorang pemimpin perlu mempekerjakan taktik perang. Meskipun percaya bahwa sebagian besar orang merupakan penentu nasibnya sendiri, Machiavelli mengenali unsur ketakterdugaan, yakni fortuna. Penguasa mesti memerangi kemungkinan ini, seperti juga memerangi kelemahan sifat manusia, yang lagi-lagi berkorespondensi dengan fortuna (Kelly [peny.], 2013: 78-9).
Benarkah Machiavelli menantang Dewi Keberuntungan? Machiavelli, yang terbukti lebih mewarisi kepercayaan Romawi ketimbang Kristen Eropa pada Abad Pertengahan, menganggap separuh dari nasib seseorang bergantung padanya. Yang baru dari Machiavelli adalah pendapat betapa fortuna bisa berpihak, tepatnya diperjuangkan agar berpihak. Dan karena fortuna sebagai Dewi Fortuna adalah perempuan, ia harus ditaklukkan atau dipikat oleh unsur-unsur vir, seperti keberanian, meski yang paling memikatnya tetaplah virtu, eponim bagi kelelakian sejati lelaki (Skinner, 2000: 29).
Machiavelli melihat kehidupan politik adalah kesinambungan persaingan unsur-unsur virtue dan fortuna, dalam hal ini analog dengan keadaan perang. Tentu saja ini merupakan analisis politik dengan menggunakan teori militer yang membuatnya berkesimpulan bahwa esensi kehidupan politik adalah konspirasi. Sama seperti sukses dalam perang yang bergantung pada spionase, intelijen, kontraintelijen, dan tipu daya, sukses politik juga mempersyaratkan kerahasiaan, intrik, dan lagi-lagi tipu daya. Gagasan tentang konspirasi sudah lama dikenal di kalangan ahli militer dan dipraktikkan para pemimpin politik.
Machiavelli adalah orang pertama yang secara eksplisit mengajukan teori konspirasi politik di dunia Barat. Pemikiran ini, seperti penipuan, misalnya, bertentangan dengan gagasan bahwa negara mesti menjaga moralitas warga. Menurut dia, meski intrik dan tipu daya tidak dibenarkan dalam kehidupan pribadi, sangatlah bijak menggunakannya bagi sukses kepemimpinan dan bisa dimaafkan bila digunakan untuk kebaikan khalayak. Dari logika semacam inilah datangnya pendapat kontroversial: penguasa mesti penuh tipu daya dan dengan bijak tak perlu menghormati kata-katanya sendiri.
Ini sahih jika segala tindak terhormat itu membahayakan kekuasaannya dan mengancam stabilitas negara. Bagi sang pemimpin, ini kemudian memaksanya untuk berurusan dengan konflik tak terelakkan yang dihadapi bahwa tujuan memang menghalalkan cara (Kelly, op.cit.: 79). Machiavelli sering dikutuk karena menunjukkan realitas politik pada masanya, tapi banyak pemimpin politik mempelajari, bahkan menjalankannya.