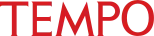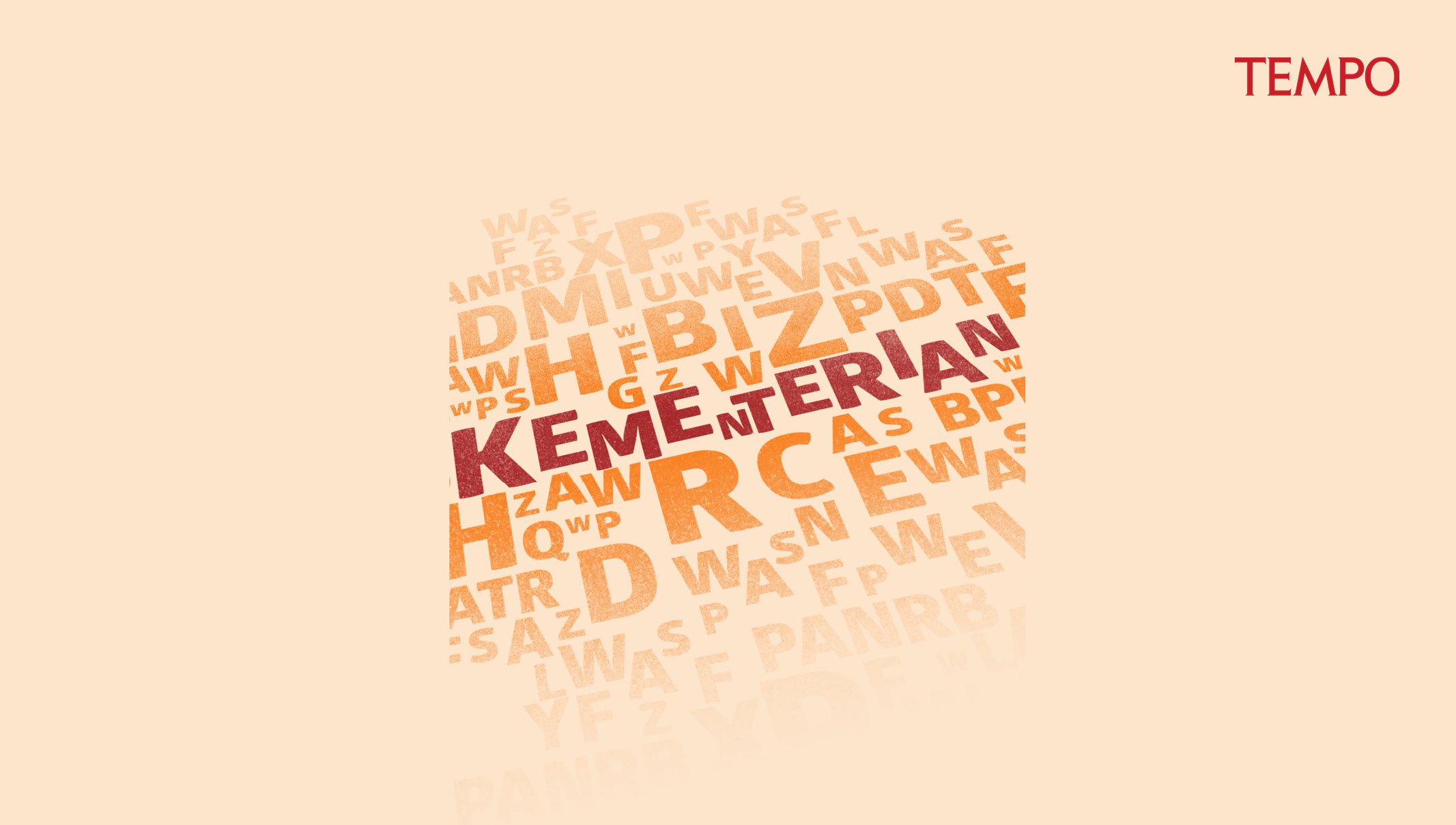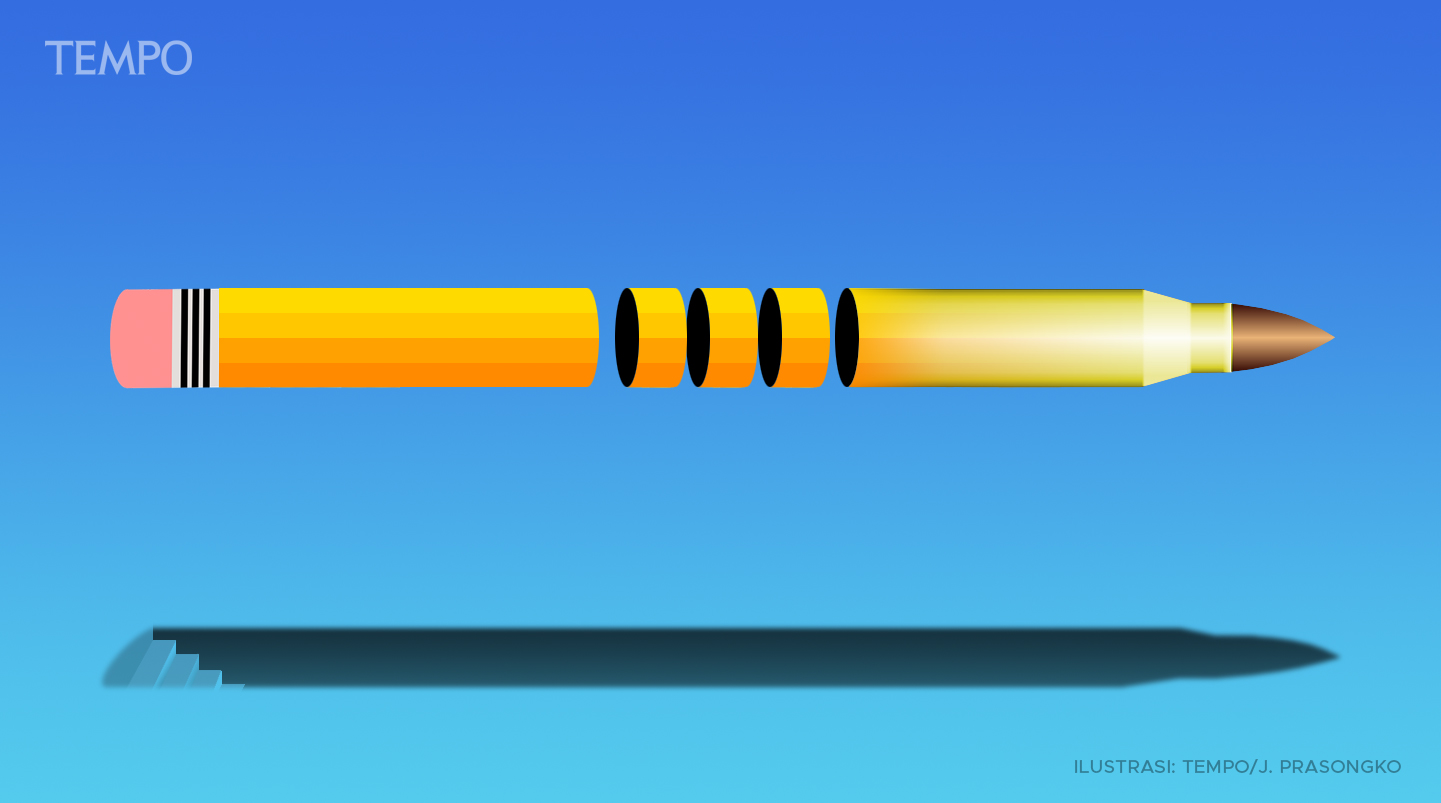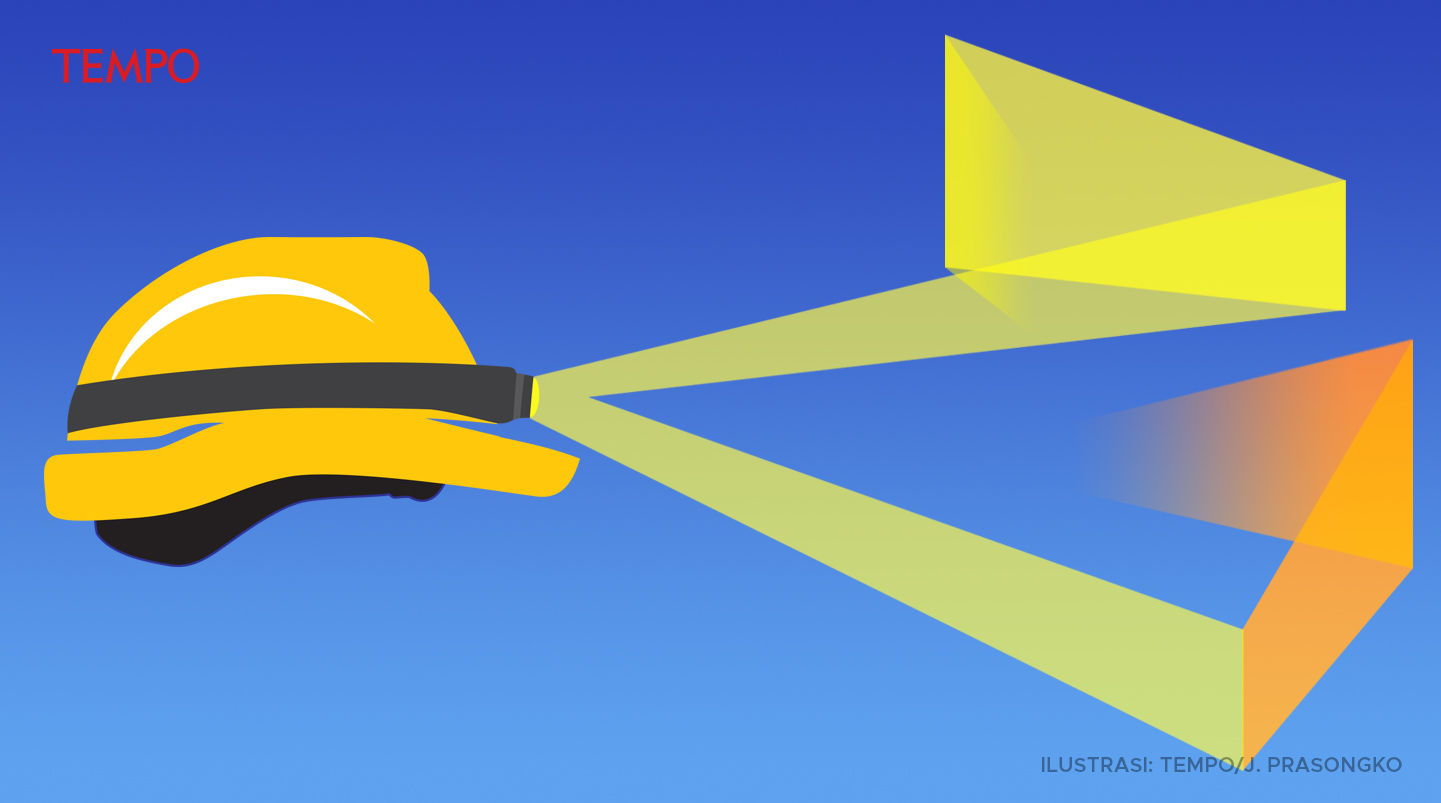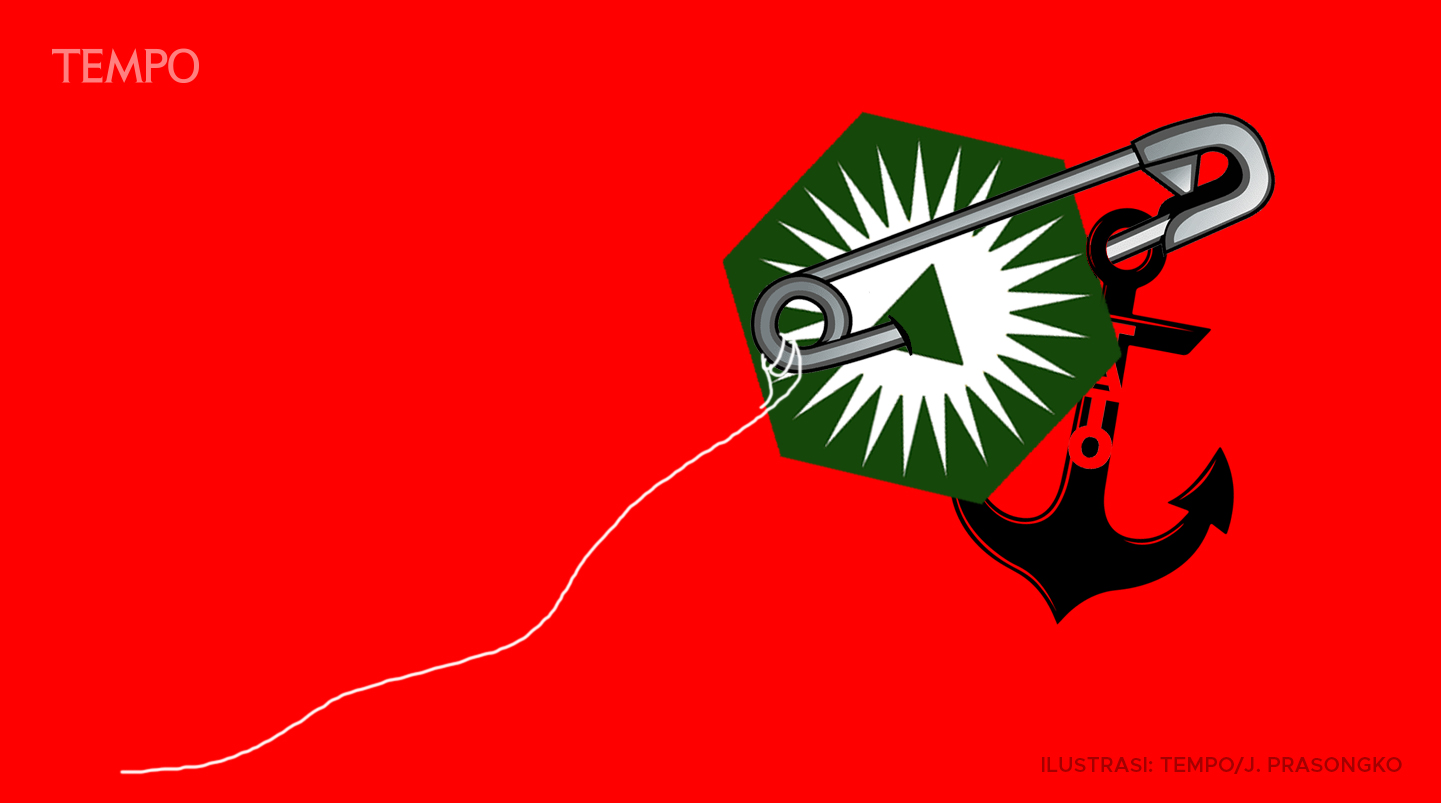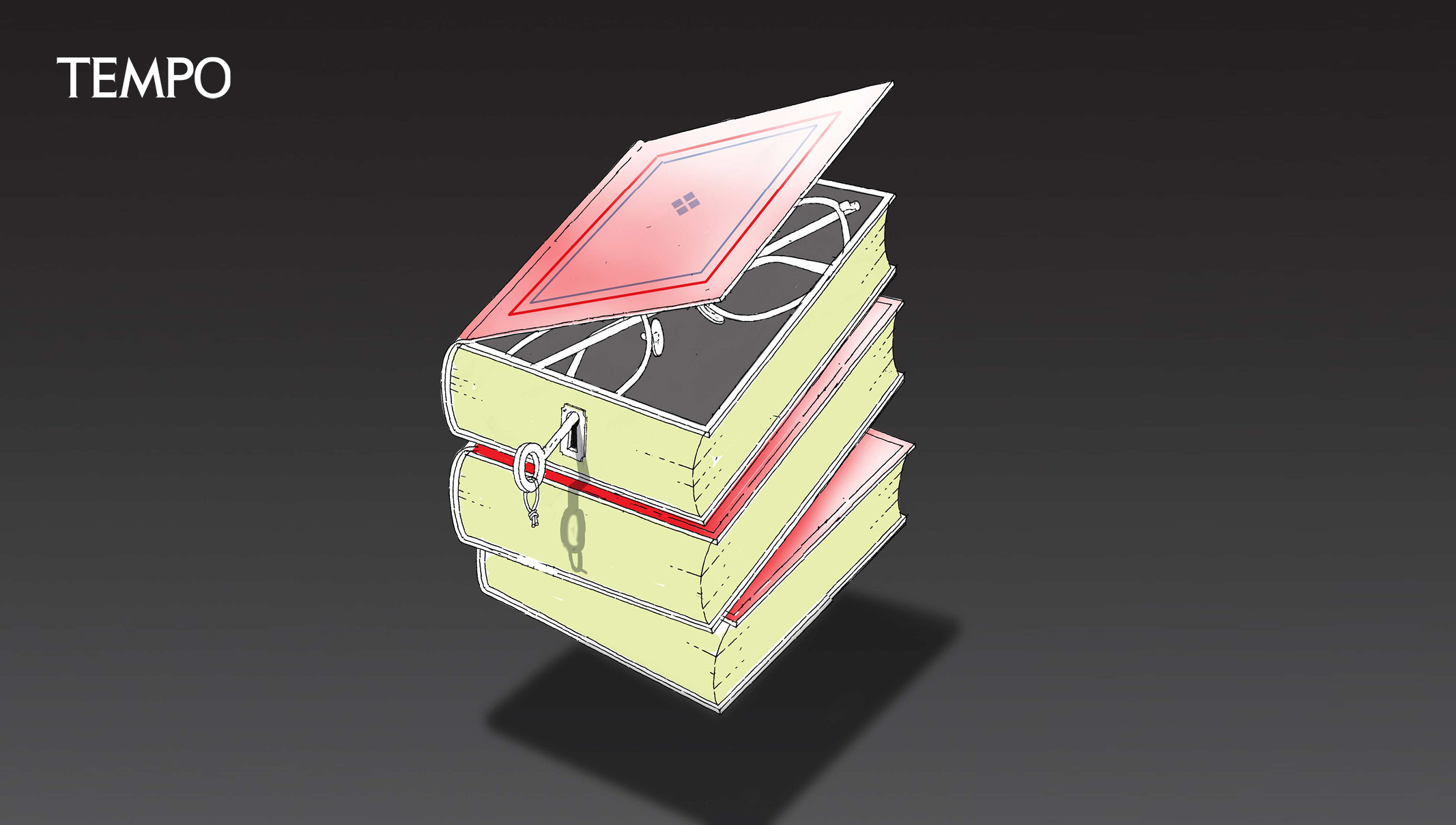Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Umbu TW Pariangu
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, mantan rival Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019, akhirnya terpilih menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju. Harapan agar Gerindra berumur panjang sebagai "partai oposan" dalam konstelasi politik nasional pun kandas. Gerindra akan berkoalisi dengan lima partai lain dalam gerbong pemerintah untuk mengafirmasi seluruh agenda dan program kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selama lima tahun ke depan. Ini bisa menjadi suplemen dalam proses rekonsiliasi politik. Namun, di sisi lain, ia bisa menjadi "duri dalam daging" demokrasi kita.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Scott Mainwaring (1993) mengingatkan bahwa hanya negara yang menganut sistem dwipartai yang mampu mengawinkan presidensialisme dengan demokrasi. Hal tersebut dia nyatakan setelah mengobservasi 31 negara, yang terbukti mampu mempertahankan demokrasinya pada 1967-1982 dengan memberlakukan sistem dua partai.
Mainwaring mau mengatakan bahwa presidensialisme dengan sistem multipartai tampaknya kurang bisa mengakomodasi determinasi kekuasaan eksekutif. Dalam kondisi tertentu, hak prerogatif presiden ternyata bisa "digembosi" superioritas fraksi di parlemen yang bisa sesekali menarik diri dari dukungan politiknya terhadap presiden. Ini bisa dilihat pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang seakan-akan "tidak berdaya" menghadapi sikap Partai Keadilan Sosial yang di satu kaki bersama pemerintah, tapi di sisi lain berlagak oposan dalam menyikapi kebijakan SBY.
Kasus itu semakin memperoleh kaca pembesar kekhawatiran kita manakala posisi strategis di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah dikuasai oleh partai pendukung pemerintah. Kini hanya tersisa PKS sebagai oposisi. Memang masih ada Partai Amanat Nasional dan Demokrat yang juga tidak menyertakan kadernya di kabinet. Namun kedua partai ini tidak secara tegas menyatakan posisinya, selain mengatakan mereka akan menjadi "mitra kritis" pemerintah.
Memang, rekonsiliasi politik pasca-pemilihan presiden dibutuhkan untuk meredam ekses rivalitas politik. Selain itu, infiltrasi gangguan terhadap eksekusi program-program pemerintah bisa dieliminasi, sehingga sasaran kebijakan presiden bisa tercapai dengan baik. Namun yang dikhawatirkan ketika bangunan politik dan kebijakan kita menutup ruang kontrol atau kritik, semangat menjaga dan melindungi kekuasaan dan pemerintahan dari kooptasi kekuasaan yang cenderung korup akan tereduksi. Dengan kata lain, akan terjadi kelangkaan checks and balances dalam konstelasi politik.
Sejatinya hal tersebut secara implisit sudah diingatkan oleh Acemoglu dan Robinson dalam The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty (2019). Intinya, suatu pemerintahan yang demokratis dan kuat hanya bisa dibangun dalam suatu ekuilibrium peran konstruktif serta konsolidatif antara negara dan masyarakat. Negara harus bisa memainkan rasionalitasnya sebagai instrumen (demokrasi) yang inklusif, menjadi ruang yang terbuka bagi segala macam kekuatan oponen agar terjadi kolaborasi yang sehat dalam mengelola kekuasaan. Pada saat yang sama, masyarakat juga harus tumbuh dalam kultur kedewasaan, membangun sikap kritis sebagai tanggung jawab moral kontinumnya dalam memberikan masukan sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Jika salah satunya lemah, entah negara dengan semua aktor politiknya atau masyarakat (sipil), akan muncul paradoks kekuasaan yang ada kemungkinan besar akan memagut efektivitas jalannya mesin demokrasi itu sendiri. Pada konteks inilah kita seakan-akan skeptis bagaimana pembangunan demokrasi ke depan dikelola dengan mengartifisialkan dukungan dan stabilitas politik semaksimal mungkin, persis di tengah "nihilnya" kekuatan watch dog kekuasaan.
Fenomena gerakan ekstra parlementer-yang sebagian menjurus anarkistis-dalam menyikapi pengesahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu sudah memperlihatkan dengan jelas betapa "laparnya" masyarakat, termasuk mahasiswa, terhadap kehadiran ruang-ruang deliberasi yang diharapkan bisa memfasilitasi semua keresahan dan protes sosial. Terlebih ketika kekuasaan tengah diapit oleh pengaruh dan lobi-lobi oligark yang berkepentingan untuk memobilisasi tekanan kepentingannya terhadap kerja pemerintah.
Dalam tekanan seperti itu, sulit untuk optimistis terhadap kerja pemerintah dalam memenangkan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang ada mungkin sebaliknya, semacam tribalisasi suara rakyat untuk melegitimasi keputusan-keputusan politik yang bias kepentingan karena suara kritis rakyat tidak lagi memperoleh tempat memadai. Tidak ada yang menjamin "kohabitasi politik" di gerbong kekuasaan selama lima tahun ke depan akan luput dari "duri dalam daging". Apalagi dengan cacat bawaan sikap elite politik yang cenderung suka bersembunyi dalam selimut pragmatismenya: sekadar meraih kue kekuasaan.
Jangan sampai skeptisisme Gaetano Mosca (1858-1941) benar bahwa demokrasi dalam makna yang substantif kerap kali hanya halusinasi karena pergantian pemerintah sekadar pergantian elite yang satu setelah mengalahkan elite yang lain. Artinya, tidak ada warisan nilai ideologis yang dihasilkan dari suatu proses demokrasi selain pertukaran atau tawar-menawar kekuasaan.