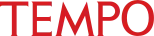Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Petani bergulat dengan tantangan perubahan iklim. Cuaca yang tidak menentu membuat petani harus berhadapan dengan risiko gagal panen.
Setiap daerah memiliki strategi yang berbeda-beda dalam mengatasi perubahan iklim.
Studi merekomendasi kebijakan berbasis gender, peran aktif pemerintah daerah, serta peningkatan akses informasi untuk membantu adaptasi petani.
PETANI kecil adalah ujung tombak ketahanan pangan nasional. Namun kini mereka harus bergulat dengan banyak tantangan, terutama krisis iklim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Anomali cuaca yang sering tak menentu memperbesar risiko gagal panen. Kalaupun petani berhasil panen, kualitas pangan yang dihasilkan cenderung menurun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Mau tidak mau, petani perlu menyesuaikan diri dengan keadaan. Riset terbaru kami menunjukkan setiap daerah punya strategi yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim.
Kami juga menemukan tiga hal yang mempengaruhi strategi adaptasi mereka, yakni gender, akses pada bantuan pemerintah, dan akses terhadap informasi.
Temuan Studi di Enam Daerah
Kami bersama para peneliti organisasi masyarakat sipil lokal dari Aliansi Kolibri mewawancarai 125 petani di Mentawai, Sumatera Barat; Tanjung Jabung Barat, Jambi; Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; Buton, Sulawesi Tenggara; Sikka, Nusa Tenggara Timur; dan Fakfak, Papua Barat, sepanjang Januari hingga Juni 2022. Daerah-daerah tersebut mewakili tiga wilayah iklim Indonesia, yakni monsoon (monsun), ekuator, dan lokal.

1. Wilayah monsun
Petani wilayah iklim monsun di Tanjung Jabung Barat, Kotawaringin Barat, Buton, dan Sikka merasakan peningkatan curah hujan dalam 10 tahun terakhir. Persepsi ini sejalan dengan data NASA Power yang menunjukkan adanya kenaikan curah hujan rata-rata sekitar 2,39 milimeter per hari di wilayah monsun.
Imbasnya, sekitar 88 persen petani di wilayah iklim monsun melaporkan penurunan hasil produksi pertanian dibanding pada 10 tahun sebelumnya. Dampak ini paling terasa pada komoditas utama, seperti sawit, kelapa, kakao, dan kemiri—tanaman yang memerlukan kelembapan seimbang.
Menghadapi situasi ini, petani lokal beradaptasi dengan menggabungkan tiga strategi, yakni diversifikasi tanaman, perawatan lahan, dan diversifikasi mata pencarian.
Di Buton, misalnya, petani tak lagi sekadar menjual kelapa, tapi mulai mengolahnya menjadi produk turunan, seperti minyak kelapa dan kopra. Upaya pascapanen ini memberikan nilai tambah dan membuka sumber pendapatan baru bagi mereka.
Di Tanjung Jabung Barat dan Sikka, komoditas utama pertanian masing-masing adalah sawit dan cokelat serta kemiri. Kini, saat musim tanam semakin tidak pasti, petani mulai menanam beragam tanaman hortikultura, jagung, atau tanaman yang tahan cuaca ekstrem untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. Petani di Tanjung Jabung juga membuat embung atau kolam penampungan air hujan sebagai bagian dari manajemen lahan mereka.
2. Iklim ekuator
Di wilayah iklim ekuator (Mentawai) curah hujan cenderung stabil dan meningkat secara perlahan dalam satu dekade terakhir dengan rata-rata curah hujan bulanan pada 2011 kisaran 367 milimeter dan menjadi 391 milimeter pada 2022.
Tidak seperti di wilayah iklim monsun, petani Mentawai dengan produksi pisang sebagai komoditas utama justru mengalami peningkatan hasil panen. Dengan demikian, petani di sini berfokus pada pemeliharaan lahan dan tidak ada diversifikasi tanaman karena kondisi iklim serta produksi tanaman pisang relatif stabil.
Petani di Mentawai biasanya mengandalkan middlemen atau perantara untuk mendapat informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau kantor syahbandar soal jadwal kapal pengangkut hasil kebun ke ibu kota provinsi di Kota Padang. Informasi ini menjadi dasar bagi mereka menentukan waktu panen sehingga hasil pertanian bisa dijual dalam kondisi terbaik dan tidak busuk selama pengiriman.
Lanskap desa Malacan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Aliansi Kolibri
3. Iklim lokal
Petani di Fakfak merasakan curah hujan cenderung panjang dan kenaikan yang tajam dalam satu dekade terakhir. Rata-rata curah hujan bulanan pada 2011 hanya 304 milimeter dan naik menjadi 407 milimeter pada 2022.
Petani Fakfak berfokus pada pemeliharaan lahan sebagai respons terhadap situasi tersebut. Misalnya, petani pala memangkas pohon secara rutin untuk mengurangi kelembapan, mempertahankan produktivitas, sekaligus menjaga kesehatan tanaman di tengah cuaca ekstrem.
Sama seperti di Mentawai, di Fakfak tidak ditemukan praktik diversifikasi tanaman ataupun diversifikasi penghasilan. Petani tetap bertahan dengan pala sebagai komoditas utama di daerah mereka.
Faktor Penentu Strategi Adaptasi
Riset kami menemukan ragam strategi adaptasi petani di tiga wilayah iklim Indonesia di atas dipengaruhi tiga faktor utama, yakni gender, akses informasi, dan akses bantuan pemerintah.
Kami menemukan bahwa petani yang menerima bantuan pemerintah, terutama subsidi hingga akses modal, cenderung lebih berani mencoba pola tanam yang lebih beragam dan membuka usaha non-pertanian untuk menambah pendapatan seperti yang terjadi di wilayah iklim monsun.
Adapun di wilayah iklim ekuator dan lokal, peran bantuan pemerintah cenderung berfokus pada penguatan kapasitas lokal, seperti penguatan kelompok tani sehingga adaptasi di sana lebih banyak pada pemeliharaan lahan.
Kami juga menemukan strategi pemeliharaan lahan umumnya dilakukan oleh petani laki-laki. Hal ini disebabkan oleh peran sosial dan pembagian kerja berbasis gender. Laki-laki dominan dalam kegiatan yang memerlukan tenaga fisik tinggi, seperti perawatan lahan atau pengolahan tanah, sedangkan perempuan cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan pascapanen.
Akses terhadap informasi juga menjadi kunci adaptasi. Temuan di Mentawai menunjukkan informasi dari jaringan lokal sangat berpengaruh untuk membuat keputusan teknis, seperti waktu jadwal panen terbaik.
Ketahanan Pangan Mustahil tanpa Keberlanjutan Petani
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal menegaskan akan berfokus pada ketahanan pangan. Namun ambisi itu hanya akan terwujud jika didukung oleh keberlanjutan petani kecil—mereka yang menyumbang sebagian besar produksi pangan nasional.
Riset ini menunjukkan petani telah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi, menggabungkan tradisi lokal dan pendekatan ilmiah. Namun kreativitas saja tidak cukup. Mereka butuh dukungan nyata.
Pemerintah harus menjamin akses terhadap teknologi, informasi, pembiayaan, dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, diperlukan penguatan kebijakan adaptasi yang sensitif gender untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pertanian.
Mengingat kondisi alam dan iklim yang beragam, pemerintah tidak bisa menerapkan pendekatan “satu untuk semua”. Adaptasi harus disesuaikan dengan kondisi iklim lokal dan faktor sosial-ekonomi masing-masing daerah.
Dalam hal ini, pemerintah daerah mesti mengambil peran aktif untuk menjamin ketahanan pangan lokal dan memperjuangkan nasib para petani dari dampak perubahan iklim.●