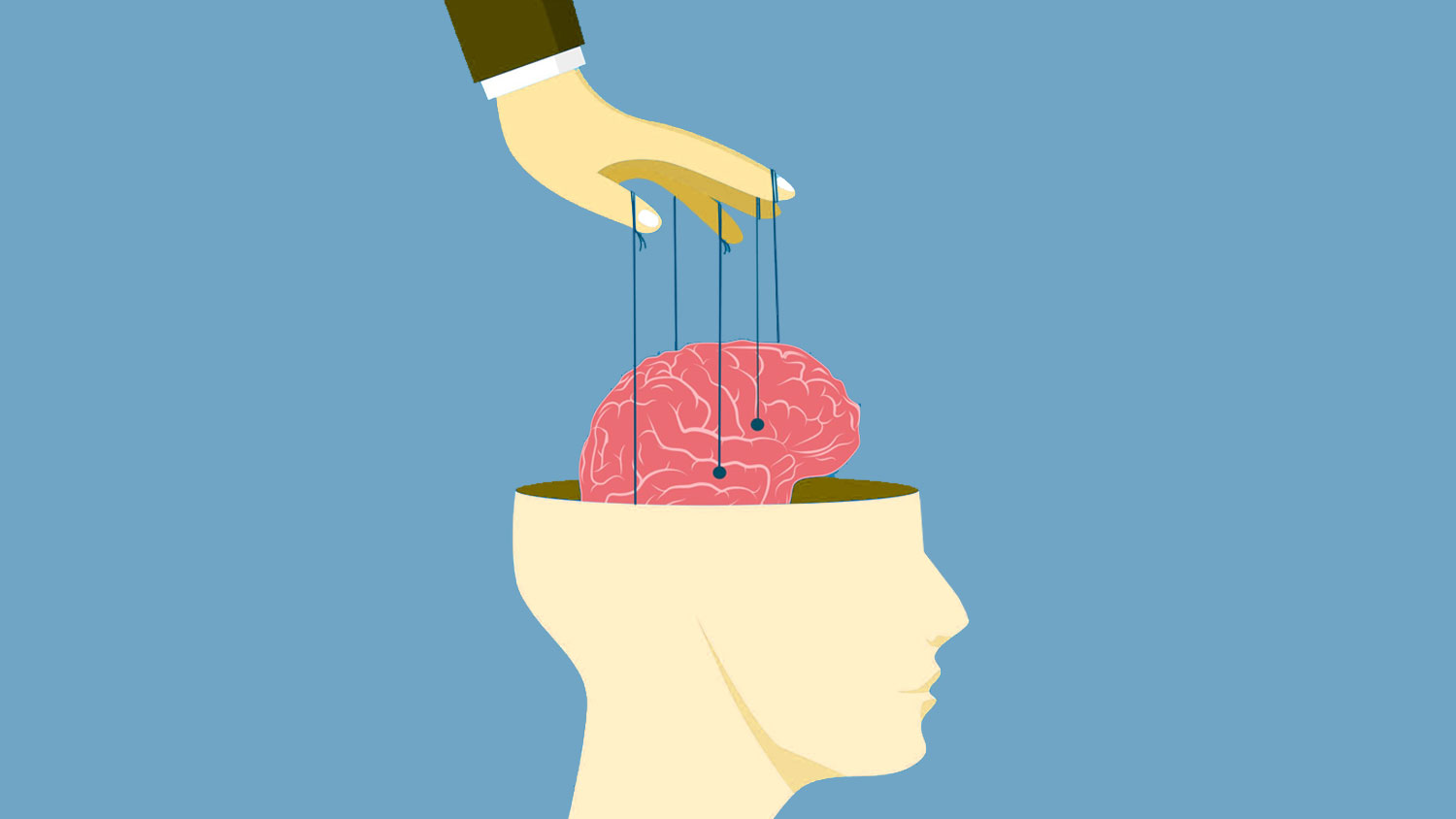Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Entah puasa hari ke berapa saat itu ketika saya diajak ibu mengunjungi rumah Pak Sukri, satu-satunya keluarga muslim asal Madura di kampung kami. Pak Sukri berjualan sate, punya anak laki bernama Zainal Arifin, sekelas dengan saya di Sekolah Rakyat.
Keluarga ini menyewa rumah sempit berdinding bambu. Rumah kami lebih mewah, sudah memakai tembok tanah dengan adonan kapur, meski lantainya sama-sama tanah yang kering. Ibu membawa ketupat yang sudah matang dan seekor ayam bakar. "Mereka tak boleh makan siang hari dan kita harus ngejot agar mereka bisa makan enak di malam hari," ini kata-kata ibu yang saya ingat.
Ngejot artinya membagikan makanan ke tetangga. Kalau ada orang di kampung kami punya hajatan, selesai upacara, sesajen berupa buah dan jajanan dibagi-bagikan ke tetangga. Ibu melebarkan tradisi ngejot ini kepada "warga selam" (sebutan untuk warga muslim di Bali saat itu). Tak ada basa-basi apa pun. Saya dengar ibu berkata bahwa ayam yang dibakar itu sudah disembelih dengan doa dan Pak Sukri menjawab, "Tidak ada masalah, semua doa didengar oleh Yang di Atas."
Tak ada ucapan terima kasih. Semuanya berawal dan berakhir dengan senyum. Saat itu, sebuah sore pada 1960-an, persisnya sebelum Gunung Agung meletus dahsyat Maret 1963, kata suksma yang berarti terima kasih konon belum ada di Bali.
Selang beberapa bulan, kami merayakan Galungan, hari kemenangan, yang menurut ayah sama dengan Lebaran. Pak Sukri datang membawa sebungkus sate ditambah segepok anyaman ketupat. Belakangan, ayah memberi tahu saya kenapa yang dibawa bukan ketupat yang sudah matang. Sebab, Pak Sukri tak tahu kebutuhan kita, apakah ketupat itu diisi beras biasa atau beras hitam. "Anyaman ketupat itu sama saja, siapa pun boleh membuatnya. Setelah diisi beras dan direbus, lalu dijadikan persembahan, barulah ketupat itu beragama," kata ayah, kata yang lama tak saya pahami maksudnya.
Yang tak saya pahami sekarang, dari mana ayah, ibu, dan Pak Sukri belajar agama, kok bisa toleran dan saling ngejot padahal berbeda agama? Saya tak melihat ada buku-buku di rumah Pak Sukri dan saya pun sulit membayangkan di mana Pak Sukri salat. Ayah pun tak pernah baca buku, yang dibaca lontar beraksara Bali dan dari mulutnya keluar tembang. Ibu, ah, malah tak bisa membaca, baik huruf Latin maupun aksara Bali. Sementara belum ada televisi, radio pun sangat jarang karena orang desa tak mampu membayar "pajak radio" ke kantor pos di kota.
Ayah, ibu, dan Pak Sukri sudah lama tiada. Juga anak Pak Sukri, Zainal Arifin, yang pada akhir hidupnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Buleleng dari Partai Golkar. Zainal pernah berkata, yang memilihnya justru orang Bali yang Hindu. Yang menyedihkan, tradisi ngejot juga hilang, baik di antara orang-orang Bali seagama maupun lintas agama.
Kini, anak SD pun sudah belajar agama dari buku. Ceramah agama tak henti-henti dari radio, televisi, dan di tempat ibadah. Negeri sudah maju, orang sudah melek agama. Saya Islam, dia Hindu, dia Kristen. Ini halal, itu haram, ini berhala, itu agama bumi, ini agama langit. Yang muslim tak mau makan di warung orang Hindu, takut ayamnya dipotong memakai doa Hindu. Lihatlah warung di Bali banyak berlabel "warung muslim". Lalu orang Hindu, kata seorang "tokoh", tak boleh beli bunga, pisang, dan ketupat untuk bahan ritual jika pedagangnya muslim.
Inikah kemajuan? Kenapa agama justru membuat sekat-sekat? Yang jelas ini bukan warisan dari persahabatan Pak Sukri dengan keluarga kami, orang-orang yang "tak belajar agama".
Putu Setia
@mpujayaprema
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini