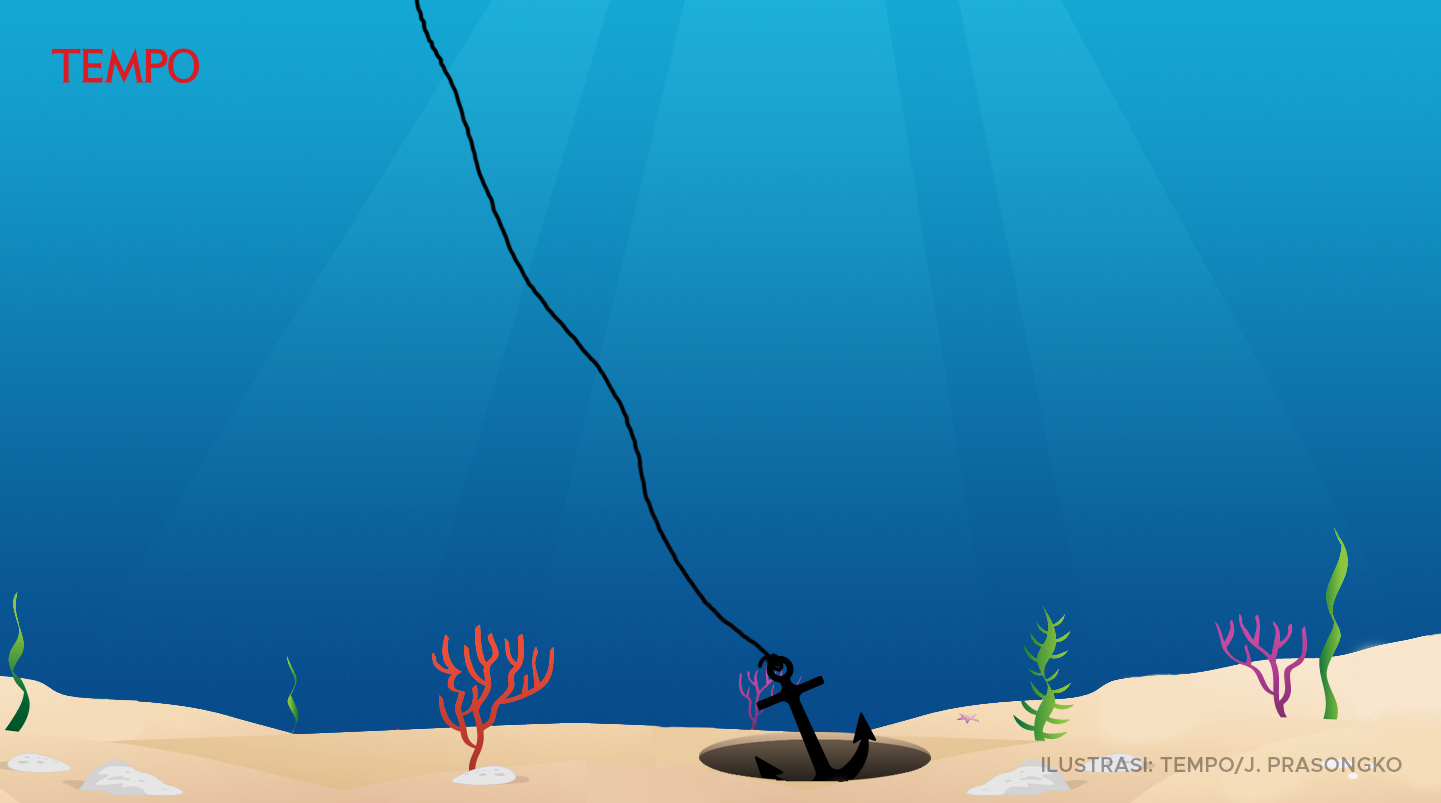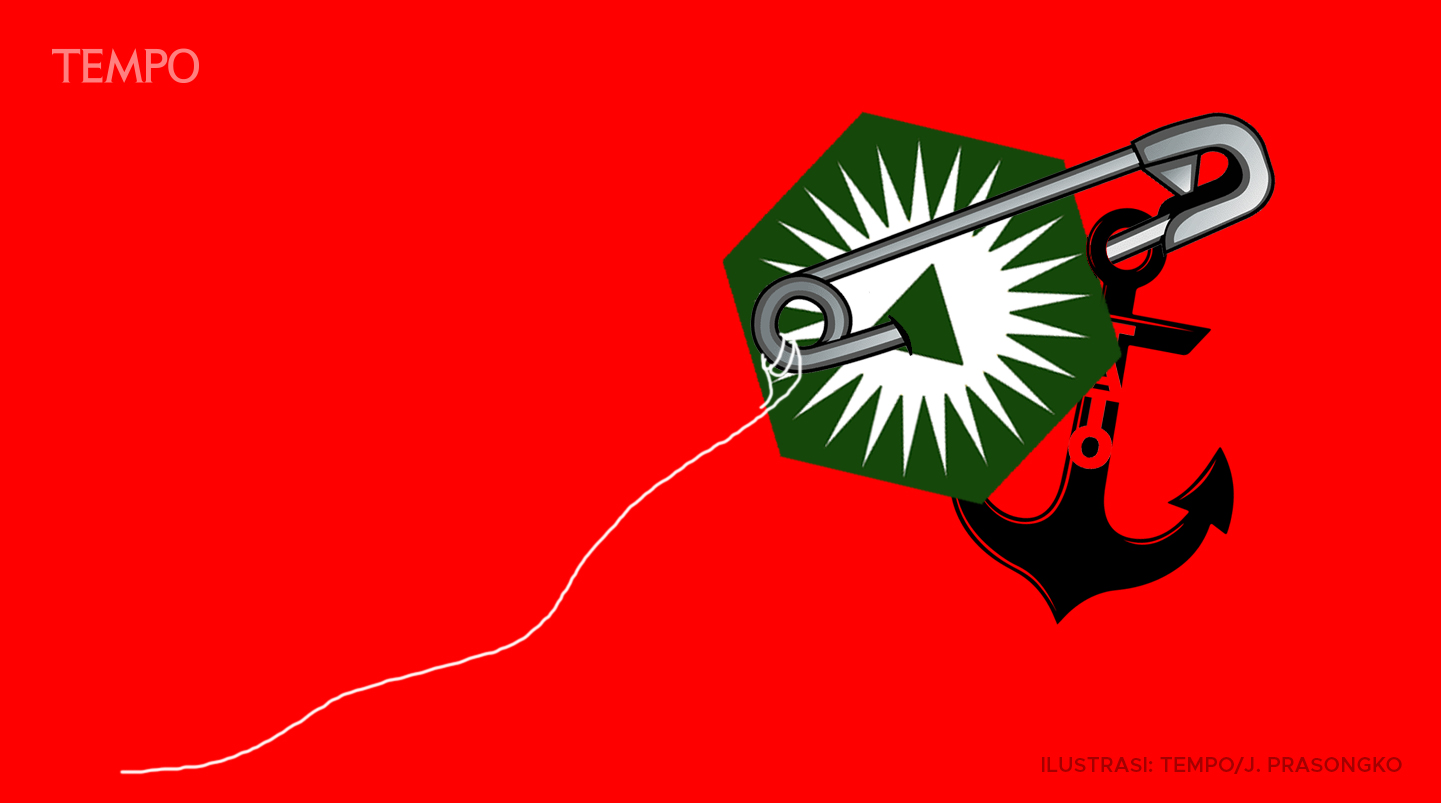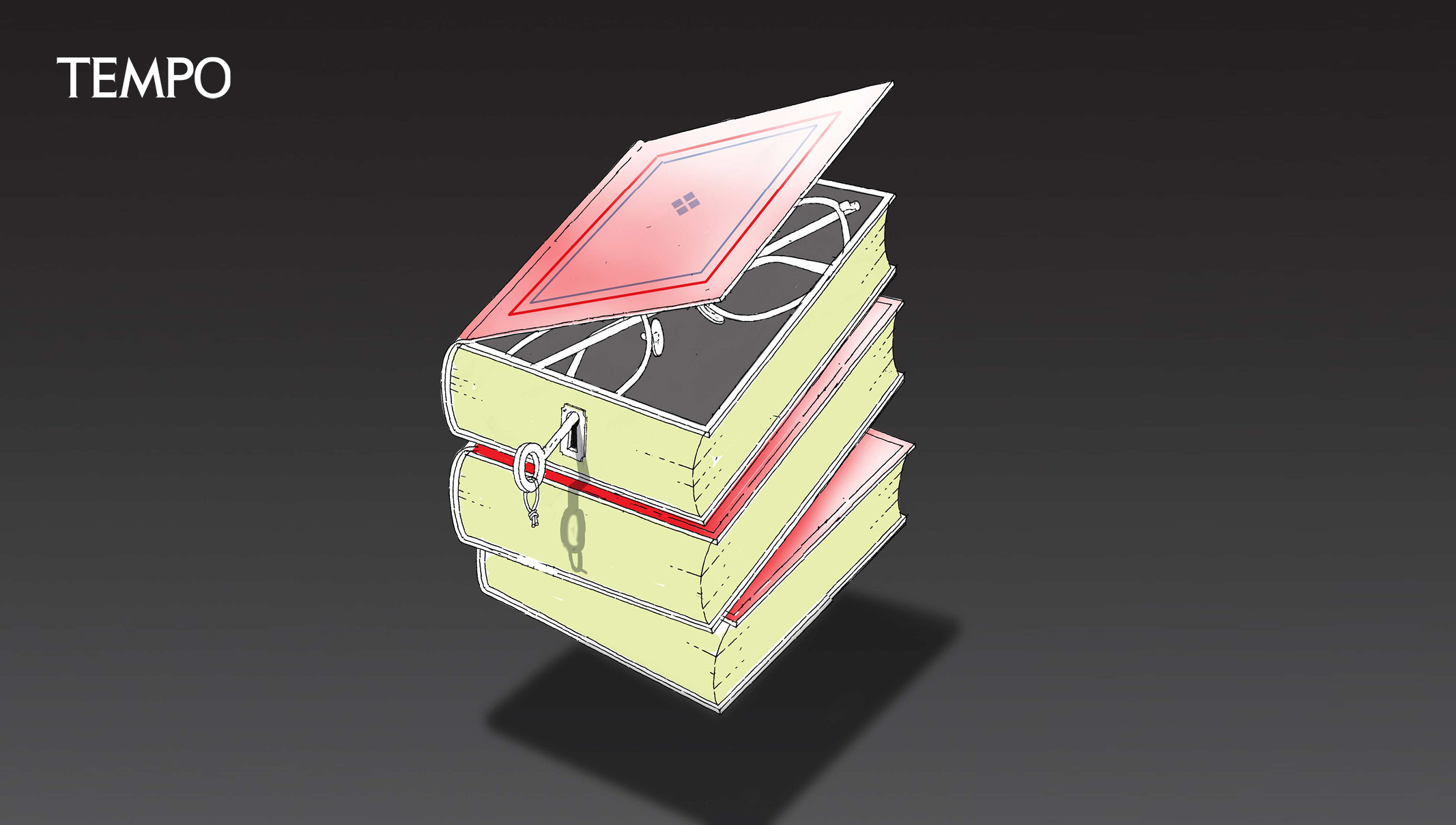Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

PRABOWO Subianto sudah hampir pasti bakal menjabat Presiden RI periode 2024-2029. Hasil ini menguatkan kerisauan publik, baik karena berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan presiden maupun tanda tanya mengenai demokrasi Indonesia dalam lima tahun ke depan. Kecemasan juga dirasakan para penganjur transisi energi. Hasil Pemilihan Umum 2024 menggambarkan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam hal transisi energi—yang gagal masuk jalur tepat—akan berlanjut pada era Prabowo.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Kolom Hijau merupakan kolaborasi Tempo dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan. Kolom Hijau terbit setiap pekan.