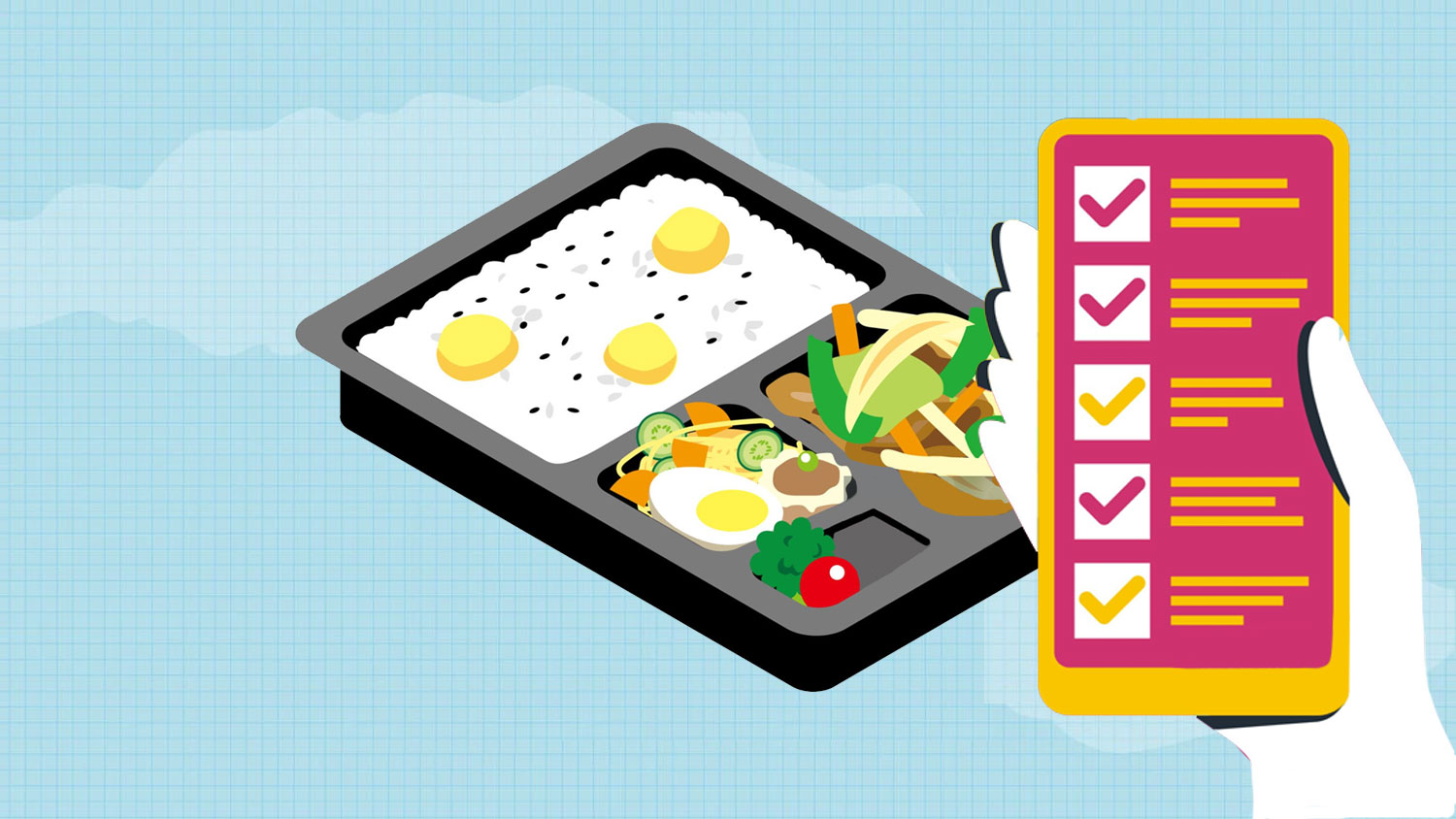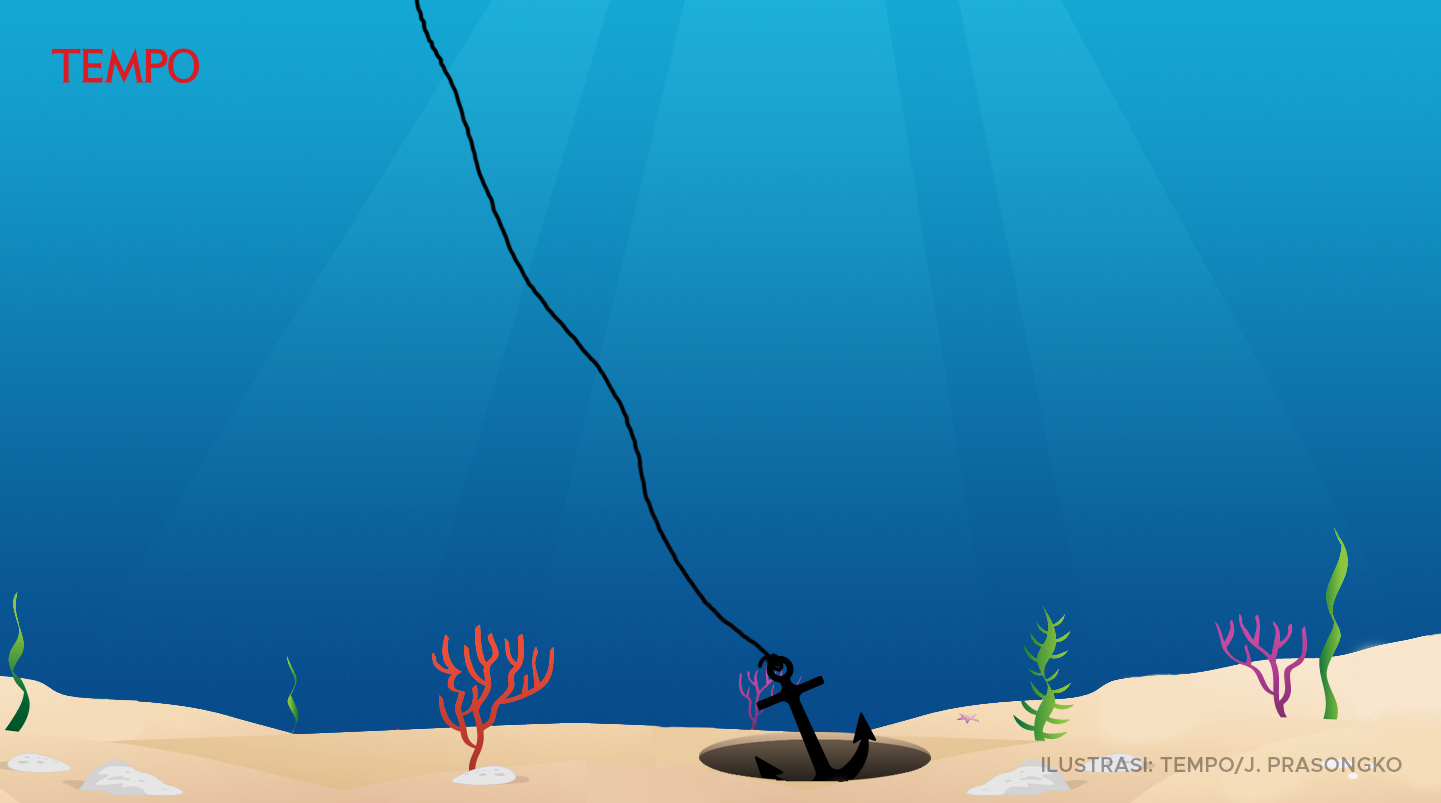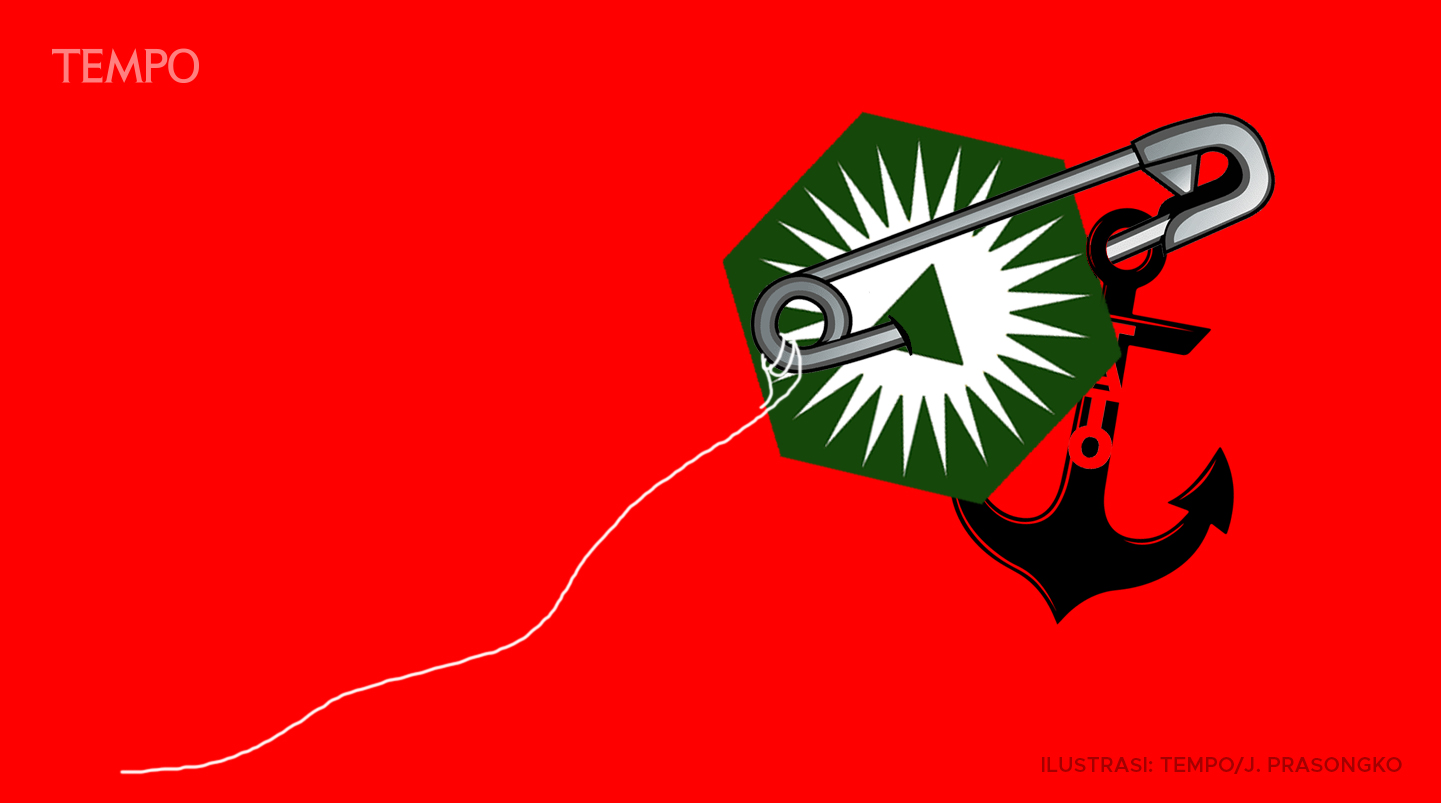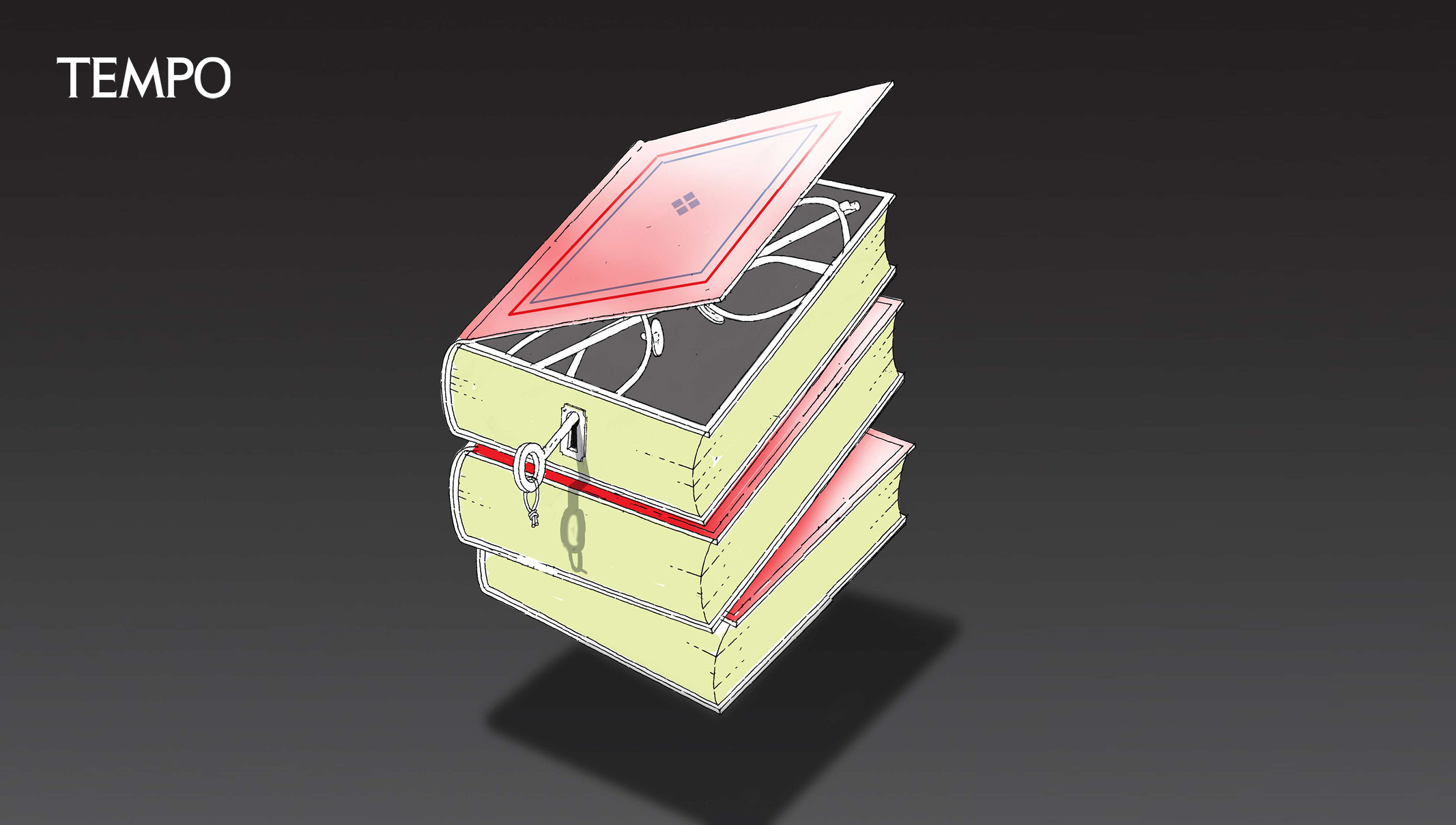Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Khudori
Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Pusat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Hingga kini pelaksanaan reforma agraria oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih berjalan bagai siput. Yang terjadi kemudian, ketimpangan dalam penguasaan tanah yang akut, seperti diuraikan Wiko Saputra dalam artikel "Tata Ulang Penguasaan Tanah" (Koran Tempo, 15 April 2019) tetap lestari. Catatan-catatan sebelumnya menunjukkan betapa timpangnya penguasaan tanah di negeri ini: 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset nasional, dengan konsentrasi aset 87 persen dalam bentuk tanah. Ini berarti aset nasional hanya dikuasai 440 ribu orang (Winoto, 2008). Sebaliknya, 49,5 persen petani di Jawa dan 18,7 persen petani di luar Jawa tak memiliki tanah. Kondisi ini nyaris tak berubah dalam 70 tahun terakhir (Moh. Tauchid, 1952).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Gutomo Bayu Aji dalam artikel "Menimbang Kebijakan Agraria" (Koran Tempo, 12 April 2019) mengidentifikasi penyebab mandeknya reforma agraria ini: kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial prematur. Kebijakan, baik target, luas, lokasi, infrastruktur pendukung, maupun penerima manfaat, dibuat tidak berdasarkan kondisi riil di lapangan, tapi lebih oleh dorongan keberanian ketimbang kecermatan. Karena itu, bagi Aji, merawat keberanian itu penting untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Hal itu sudah tentu dilakukan untuk akselerasi reforma agraria.
Salah satu "keberanian" Jokowi-JK adalah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Lahan Sawit di perkebunan. Tampak ada kemauan politik Presiden terhadap reforma agraria. Peraturan ini menjadi panduan agar kementerian yang bertugas menjalankan reforma agraria berjalan sinergis dan kolaboratif.
Masalahnya, hingga saat ini Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai Ketua Tim Reforma Agraria Pusat belum banyak bergerak. Begitu pula Gugus Tugas Reforma Agraria Nasional, yang dipimpin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kementerian Agraria lebih berfokus mengakselerasi legalisasi aset lewat sertifikasi tanah. "Prestasi" ini selalu dibangga-banggakan. Padahal, alih-alih memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah, kebijakan ini bisa-bisa justru mengakselerasi liberalisasi pertanahan Bank Dunia dalam sistem pasar tanah. Semestinya, Kementerian Agraria berfokus meredistribusi tanah kepada petani kecil dan buruh tani, baik dari hak guna usaha maupun kawasan hutan, selain mengurus konflik agraria.
Selama satu dekade pemerintahan Susilo Bambang Yudhohoyono dan 4,5 tahun duet Jokowi-JK, konflik agraria di wilayah perkebunan selalu menempati posisi pertama. Pada periode 2015-2018, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 1.771 konflik agraria, dengan 642 di antaranya terjadi di sektor perkebunan, yang melibatkan hak-hak guna usaha perusahaan negara dan swasta (KPA, 2019). Tingginya eskalasi konflik menandakan reforma agraria belum berada di jalur yang benar.
Konsorsium mencatat dua hal mengenai pelaksanaan reforma. Pertama, realisasi redistribusi tanah belum menyasar akar masalah. Pemerintahan Jokowi membagi program 9 juta hektare program reforma agraria menjadi 400 ribu hektare redistribusi tanah dari hak guna usaha kedaluwarsa dan ditelantarkan perusahaan; 4,1 juta hektare redistribusi tanah dari pelepasan klaim kawasan hutan; 3,9 juta hektare legalisasi aset; dan 600 ribu hektare legalisasi tanah transmigrasi yang belum disertifikasi. Dari sasaran 400 ribu hektare, per Oktober 2018, baru tercapai sekitar 270 ribu hektare. Itu pun hanya 785 hektare yang sesuai dengan prinsip reforma agraria: daerah konflik dan sesuai dengan sasaran. Sementara itu, untuk 4,1 juta hektare sasaran pelepasan kawasan hutan yang padat konflik belum ada realisasi.
Kedua, sempitnya ruang partisipasi rakyat. Seperti ditengarai Aji, reforma agraria dirakit top-down, tidak melibatkan masyarakat akar rumput dan organisasi tani. Dalam kurun waktu empat tahun, KPA bersama serikat petani dan organisasi masyarakat adat telah mendata Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di kawasan hutan dan perkebunan. LPRA ada di tanah seluas 668.383 hektare, melibatkan 147.446 kepala keluarga, serta tersebar di 461 desa, 98 kabupaten, dan 20 provinsi. Di lokasi ini ada kesesuaian obyek dan subyek penerima reforma agraria. Sayangnya, data yang sudah ada di tangan pemerintah ini belum disentuh.
Untuk mengakselerasi reforma agraria, rekomendasi KPA (2019) bisa menjadi petunjuk kunci. Pertama, membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria yang bersifat lintas sektor, partisipatif, dan langsung dipimpin presiden. Karena reforma agraria hanya sementara, badan ini sifatnya ad hoc. Kedua, memfokuskan agenda reforma agraria di wilayah prioritas sesuai dengan usulan masyarakat. Ketiga, membuka informasi kepada publik mengenai konsesi perusahaan perkebunan negara dan swasta untuk mendorong terciptanya sistem pertanahan yang transparan. Keempat, menghentikan pendekatan keamanan dan represif dalam menangani konflik agraria. Kelima, redistribusi lahan perlu dilengkapi dengan program pendukung, seperti akses kredit, teknologi, pasar, manajemen, dan infrastruktur.