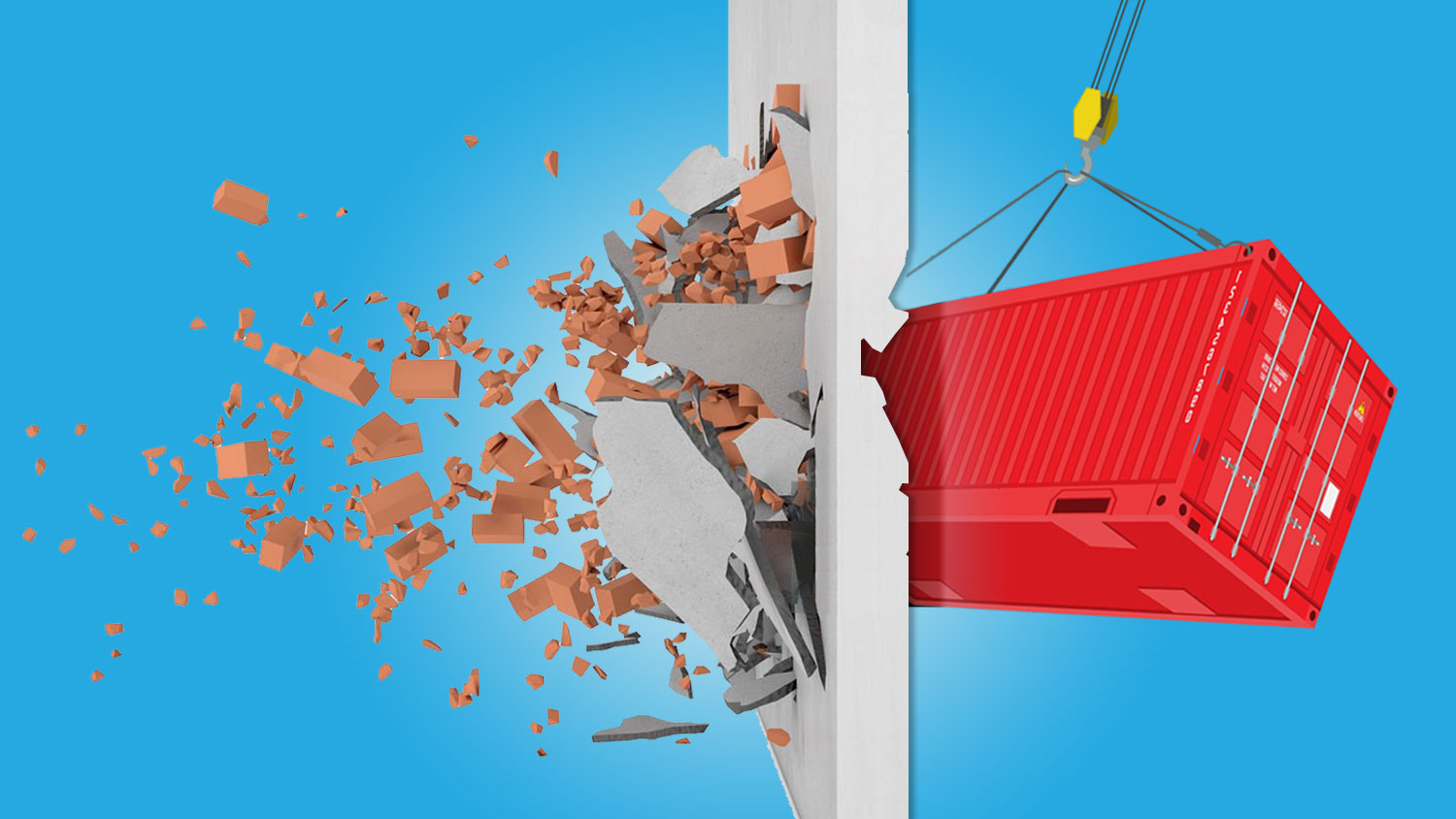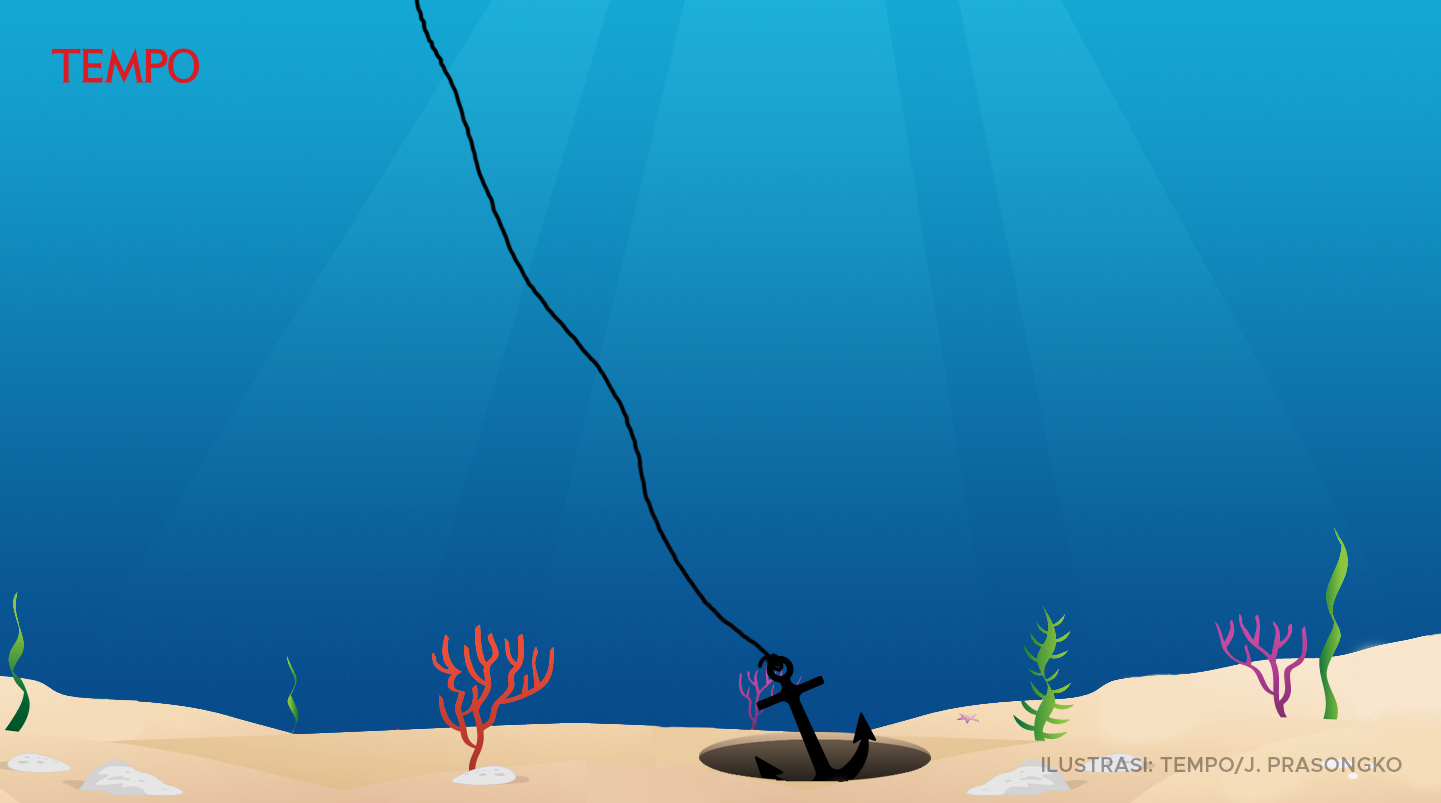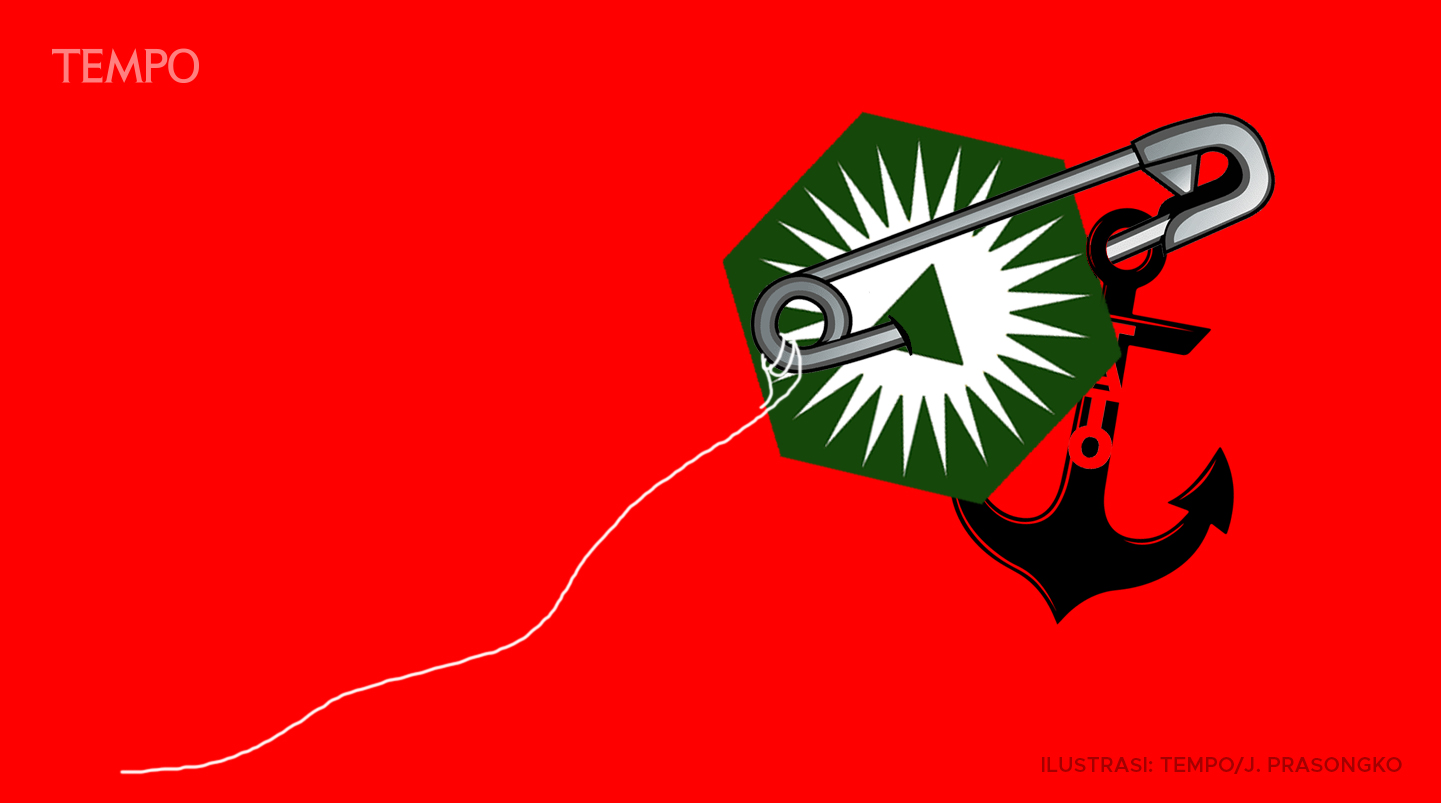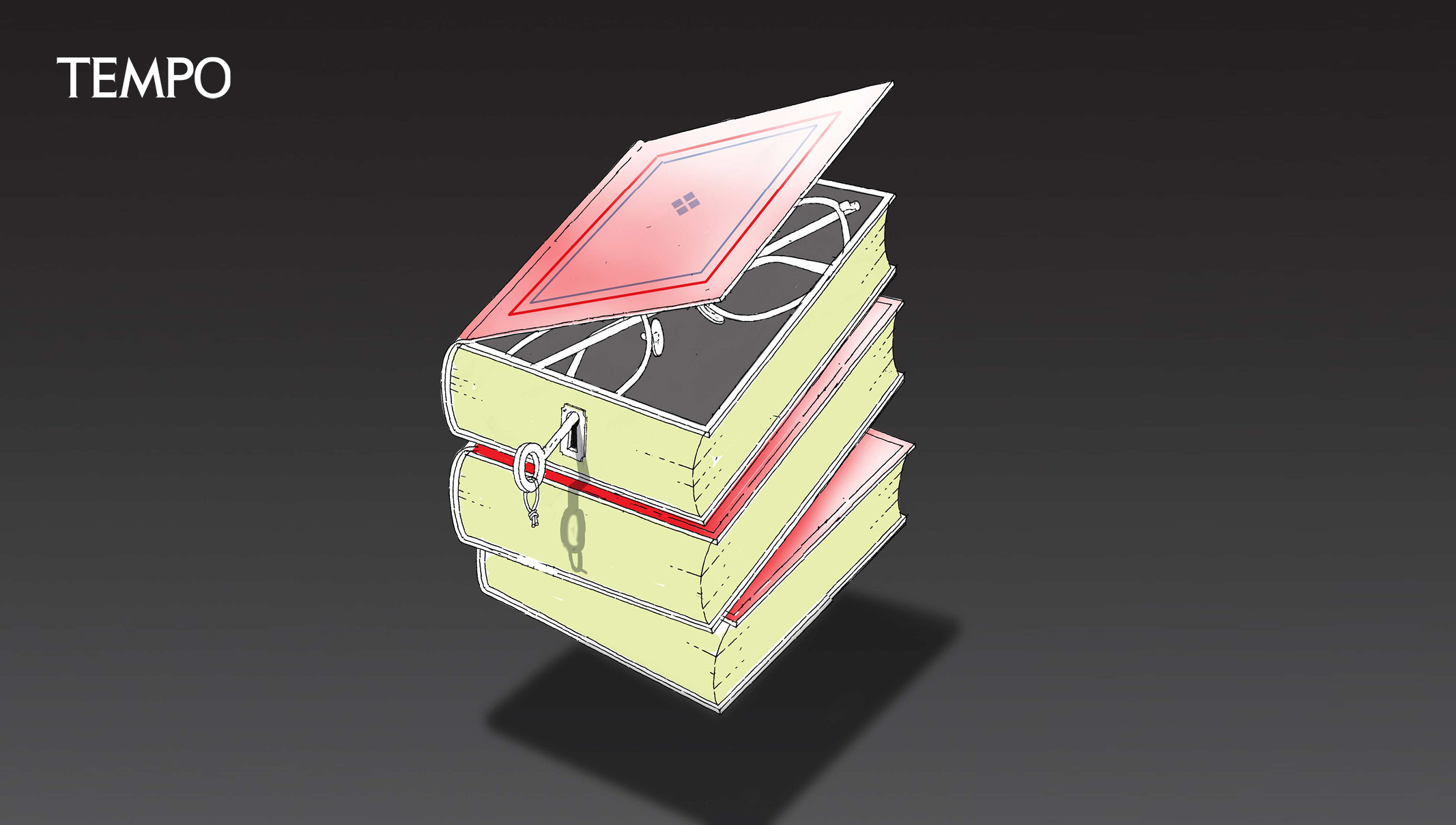Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dari berbagai fakta dalam urut-urutan peristiwa Kampung Pulo, semestinya keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memilih penggusuran bisa dipahami. Dia mungkin terlalu berisik, juga menyengat dalam berkata-kata. Tapi, soal pilihan tindakan, dia sudah berpegang pada aturan.
Penggusuran itu sempat diwarnai bentrokan antara aparat keamanan dan warga yang bertahan. Petugas yang dibantu aparat keamanan baru bisa menuntaskannya sehari kemudian. Muncul dalih bahwa penolakan warga yang bertahan berkaitan dengan nihilnya ganti rugi.
Belum jelas bagaimana asal-usulnya, soal ganti rugi itu telah mengundang perdebatan mengenai status kepemilikan tanah. Warga Kampung Pulo di Jakarta Timur itu merasa hal ini cukup ditunjukkan dengan surat perjanjian jual-beli dan tanda bayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tapi pemerintah DKI Jakarta berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria: bukti kepemilikan adalah sertifikat.
Merujuk kepada undang-undang itu, memang sulit untuk menerima alasan dan bukti surat-surat nonsertifikat sebagai dasar klaim atas tanah. Dan dalih apa pun bisa serta-merta gugur jika dilihat pula kenyataannya: bahwa tanah di bantaran sungai sesungguhnya milik negara, yang seharusnya, karena fungsinya sebagai jalur hijau, tidak boleh disewa-sewakan.
Demi mengembalikan fungsinya itulah sebenarnya relokasi warga tiga rukun tetangga di Kampung Pulo dilakukan. Fungsi bantaran yang dipulihkan merupakan bagian dari proyek normalisasi Sungai Ciliwung demi mengurangi dampak banjir terhadap warga Ibu Kota. Pemerintah Jakarta saat ini sedang mengebut pengerjaannya. Menurut rencana, proyek ini mesti selesai pada tahun depan.
Sebelum keputusan penggusuran diambil, Basuki telah berusaha memasyarakatkan proyek normalisasi itu: apa saja yang akan dilakukan dan apa akibatnya bagi sebagian warga di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Sosialisasi sudah dilaksanakan sejak tahun lalu.
Berkat sosialisasi itu, sebagian warga bersedia pindah ke rumah susun yang disediakan pemerintah Jakarta. Dari sekitar 500 keluarga, 400-an di antaranya sejak awal menyatakan setuju pindah. Belakangan, jumlahnya berkurang setelah Ahok mengubah persyaratan untuk mencegah penjualan rumah susun tersebut. Meski demikian, fakta ini tak mengubah kenyataan bahwa pemerintah Jakarta sudah memberikan informasi.
Sangat disayangkan, relokasi yang semestinya berlangsung aman dan damai diwarnai dengan kekerasan. Timbul silang sengketa dalam hal ini, perihal apa penyebabnya dan siapa biang keladinya.
Untuk meluruskan kejadian yang sebenarnya, juga demi memastikan tak ada aparat pemerintah yang "bermain", Ahok harus memeriksa anak buahnya, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan. Ini penting karena warga menyatakan tak pernah menolak proyek normalisasi dan menyinggung-nyinggung soal ganti rugi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini