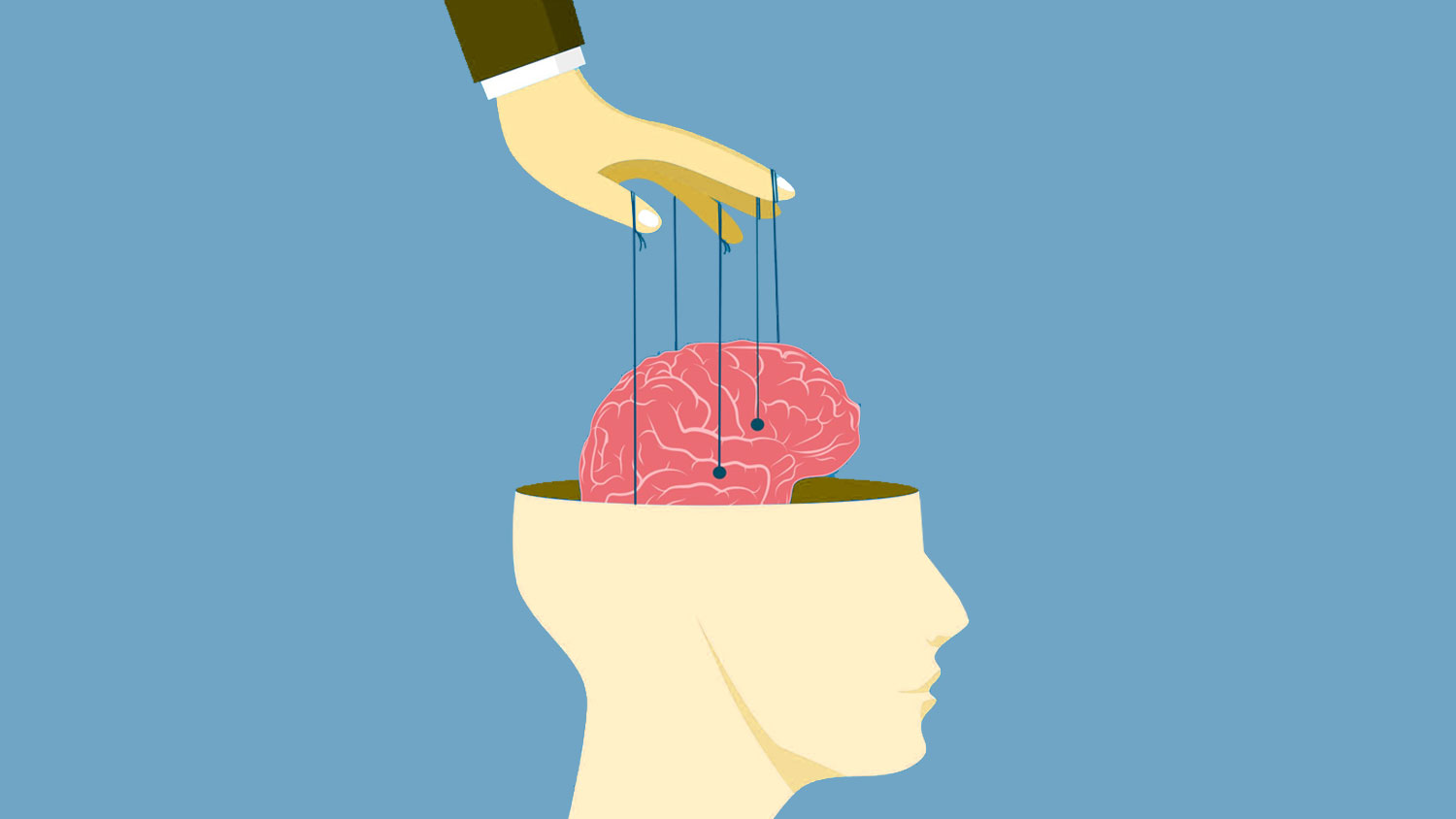Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Parade perayaan 50 tahun ASEAN yang meriah di jalan-jalan protokol Ibu Kota Jakarta, Ahad lalu, ternyata menyimpan ironi. Tepat pada hari yang sama, ribuan warga Rohingya terpaksa menyeberangi perbatasan Myanmar-Bangladesh untuk menghindari amukan tentara Myanmar.
Merasa kecolongan oleh sergapan kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), tentara Myanmar menebar teror kepada kaum minoritas muslim yang tinggal dan bertahan hidup di daerah-daerah sepanjang perbatasan.
Semua hal ini berawal pada Kamis malam pekan lalu, ketika ratusan anggota kelompok militan Rohingya serentak menyerbu 25 pos penjaga perbatasan, membunuh tentara, dan merampas amunisi. Militer dan pemerintah pusat lantas berjanji membalas serta dan menghukum pelaku penyerbuan itu seberat-beratnya.
Sejak Myanmar bergabung dengan ASEAN pada 1999, perlakuan pemerintah di Yangon terhadap warga minoritas Rohingya yang beragama Islam ini terus represif. Ironi ini semakin mencorong ketika Aung San Suu Kyi, kampiun hak asasi dan demokrasi di bawah junta militer, ternyata tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan serangkaian persekusi terhadap mereka. Bukannya menyesalkan, Suu Kyi justru membela represi yang dilakukan pemerintah Myanmar.
Memang, hingga ASEAN menginjak usia 50 tahun, tak ada negara anggota perhimpunan ini yang tidak menghadapi persoalan dalam hubungan mayoritas-minoritas di negeri sendiri. Namun sikap pemerintah Myanmar yang tak bersedia berdiri di atas semua golongan itu- baik warga mayoritas yang beragama Buddha maupun minoritas muslim- perlu mendapat perhatian khusus dari ASEAN. Apalagi konflik di Rakhine diperparah oleh munculnya gerakan bersenjata ARSA sebagai reaksi atas represi terhadap kaum minoritas Rohingya yang tak kunjung berakhir.
Warga muslim Rohingya merupakan "musuh bersama" masyarakat Myanmar, yang kebanyakan beragama Buddha. Lantaran para aktivis hak asasi manusia senantiasa diawasi dan gerakan mereka dibatasi, praktis hanya kelompok bersenjata ARSA yang bisa menyatakan keinginan melindungi orang-orang berkulit gelap yang harus hidup tanpa obat-obatan dan makanan cukup tersebut. Tatkala semua jalan keluar untuk mengakhiri pembatasan ruang gerak, pencabutan status warga negara, pelucutan hak-hak politik, dan diskriminasi yang terus-menerus itu tampak buntu, orang-orang Rohingya di Negara Bagian Rakhine melirik perlawanan bersenjata.
Bukannya memperbaiki perlakuan terhadap orang-orang Rohingya, pemerintah dan militer Myanmar justru mengambil keuntungan dari kemunculan gerakan yang menempuh jalan kekerasan tersebut. Istilah "simpatisan ARSA" dilekatkan kepada siapa saja yang tak disukai militer. Ditemukannya satu-dua orang anggota komunitas yang bergabung dengan kelompok itu sudah cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk menghukum komunitas tersebut.
Menghadapi persekusi terhadap kaum minoritas yang berlarut-larut ini, ASEAN harus meninggalkan prinsip tidak mencampuri urusan domestik negara lain. Kita di Indonesia telah belajar bahwa rezim yang represif pintar bersembunyi di balik prinsip itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini