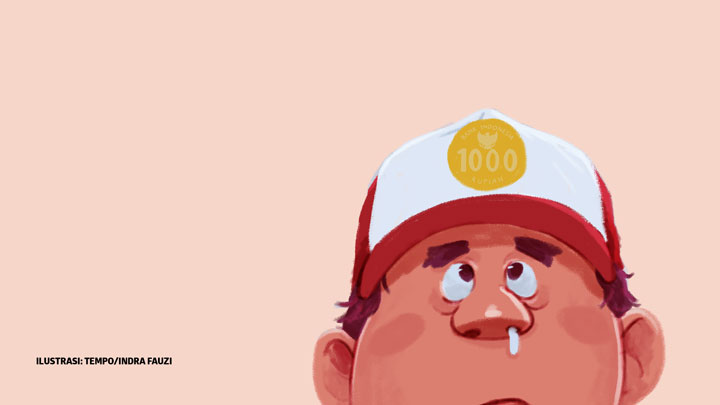Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejatinya, pertemuan ahli hukum dari enam negara itu bersifat kolokium—sebuah kelas atau grup diskusi. Tema yang diangkat juga kontekstual, From Insult to Slander: Defamation and the Freedom of the Press. Inilah wacana yang dibicarakan sejumlah praktisi dan ahli hukum pers dalam acara yang digelar Yayasan Aksara dan Dewan Pers, 28-29 Juli lalu di Jakarta.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo