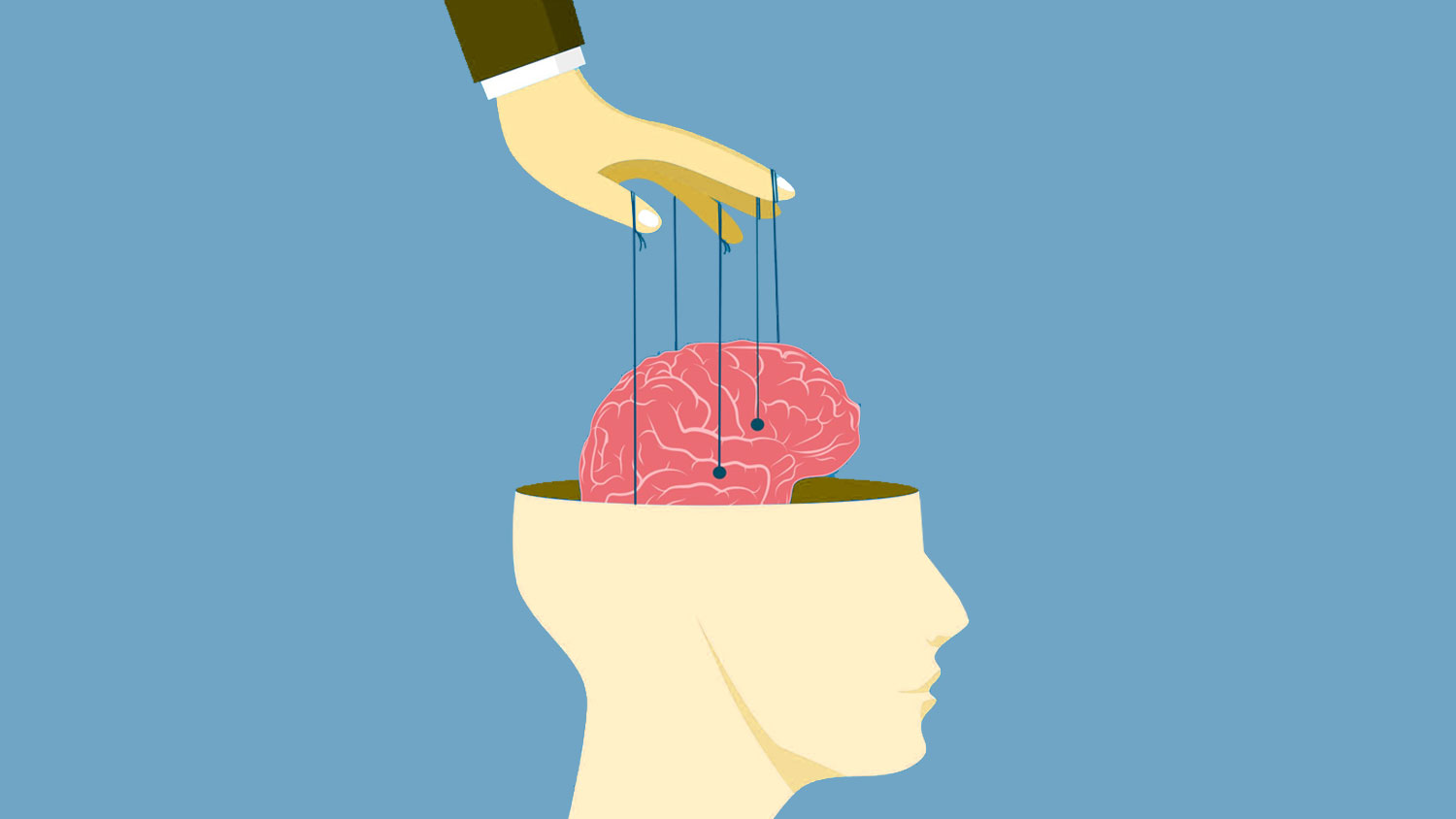Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

PRESIDEN Joko Widodo bisa saja berkilah bahwa pencalonan anak dan menantunya dalam pemilihan kepala daerah pada Desember mendatang tak melanggar peraturan apa pun. Dia bisa juga mengklaim bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dalam pemilihan wali kota Solo dan Medan bukanlah indikasi politik dinasti. Tapi, yang jelas, kemunculan sanak keluarganya dalam percaturan politik Indonesia merupakan rentetan termutakhir dari makin kentalnya nepotisme dalam sirkulasi elite di negeri ini.
Untuk soal satu ini, Jokowi tidak sendirian. Siti Nur Azizah, anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, juga maju dalam pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya, anak Presiden Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, duduk di kursi menteri. Anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, sempat dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Yoes C. Kenawas, kandidat doktor ilmu politik di Northwestern University, Illinois, Amerika Serikat, saat ini ada 117 kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari dinasti politik. Mereka memenangi pemilihan kepala daerah serentak dalam lima tahun terakhir. Di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024, ada 104 anggota Dewan yang memiliki ikatan kekerabatan dengan elite politik. Jumlah mereka yang fenomenal menunjukkan betapa dalamnya racun nepotisme telah menembus urat nadi politik kita.
Realitas ini sungguh memprihatinkan. Kita ingat, pada puncak Reformasi 1998, tuntutan utama gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menumbangkan Presiden Soeharto adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika itu, mahasiswa gerah melihat Orde Baru membangun kekuasaan selama 32 tahun dengan bantuan kroni dan keluarga elite. Mereka merusak semua tatanan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia karena para elite ini naik ke puncak kekuasaan hanya berdasarkan koneksi kekerabatan, bukan kompetensi. Hasilnya adalah para pemimpin yang lebih suka menjilat ke atas dan abai terhadap kepentingan orang banyak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Tuntutan menghentikan nepotisme itu sah dan relevan karena sejak awal Indonesia berdiri, 17 Agustus 1945, para pendiri negara ini sudah menyepakati bentuk pemerintahan republik. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa menyadari pentingnya meletakkan kepentingan publik di atas segala-galanya. Mohammad Yamin, misalnya, mengatakan, dalam sebuah negara republik, kepentingan rakyat harus diutamakan, bukan para pejabat dan elite politik. Nepotisme yang makin mengakar dalam peta politik kita belakangan ini jelas melanggar prinsip dasar bernegara tersebut.
Harus diakui, kondisi ini terjadi akibat banyak faktor yang berkaitan. Namun kesalahan terbesar ada pada partai politik yang gagal membentuk diri menjadi organisasi modern yang menerapkan asas meritokrasi. Hampir semua partai politik Indonesia amat bergantung pada figur personal di semua level, dari daerah hingga pusat. Para politikus kawakan ini menjadi patron yang membuka jalan bagi suami, istri, anak, menantu, besan, dan kemenakan untuk menguasai jabatan-jabatan publik.
Ini diperparah budaya politik lama yang masih kuat bercokol di benak para pemilih kita. Khalayak ramai dimanipulasi agar lebih percaya kepada tokoh daripada sistem. Pemimpin partai bisa menjabat sampai bertahun-tahun tanpa pengganti karena dianggap memiliki karisma menggalang massa, menjembatani berbagai faksi yang bersaing, dan mendanai partai. Akibatnya, seperti virus corona, nepotisme terus viral, tak mati-mati.
Ada yang mengatakan nepotisme politik adalah konsekuensi demokrasi. Dalam sistem ini, setiap orang berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin, siapa pun orang tuanya. Amerika Serikat, Filipina, Jepang, dan India sering dikutip sebagai contoh negara demokrasi dengan problem dinasti politik yang serupa. Argumentasi itu tak sepenuhnya benar. Banyak riset menunjukkan daerah yang dikuasai terus-menerus oleh pemimpin dari keluarga yang sama cenderung mundur, tidak akuntabel, dan pencapaiannya buruk. Ketika rotasi elite menjadi tertutup dan kompetisi politik dimonopoli, rakyat kehilangan kuasa untuk menghukum pemimpin yang menyeleweng. Demokrasi kehilangan esensinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Karena itu, Presiden Jokowi dan para pemimpin politik di Indonesia perlu menyadari ini: negara bukanlah perusahaan keluarga. Demokrasi membutuhkan keterlibatan semua kalangan. Nepotisme yang merajalela tak hanya merusak sistem politik, tapi juga memperburuk kualitas kerja pemerintah. Pada akhirnya yang dirugikan adalah kita semua: rakyat jelata di negeri ini.