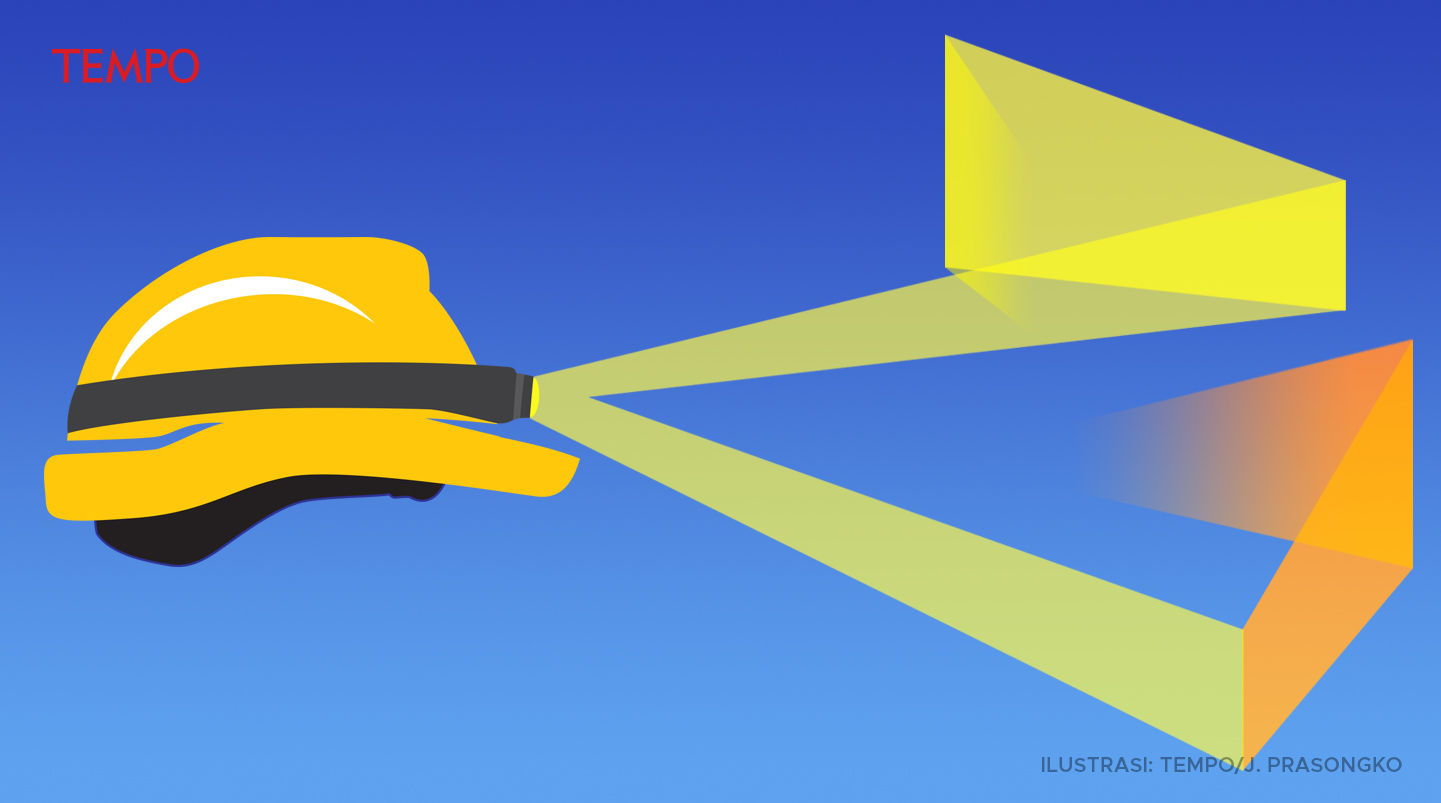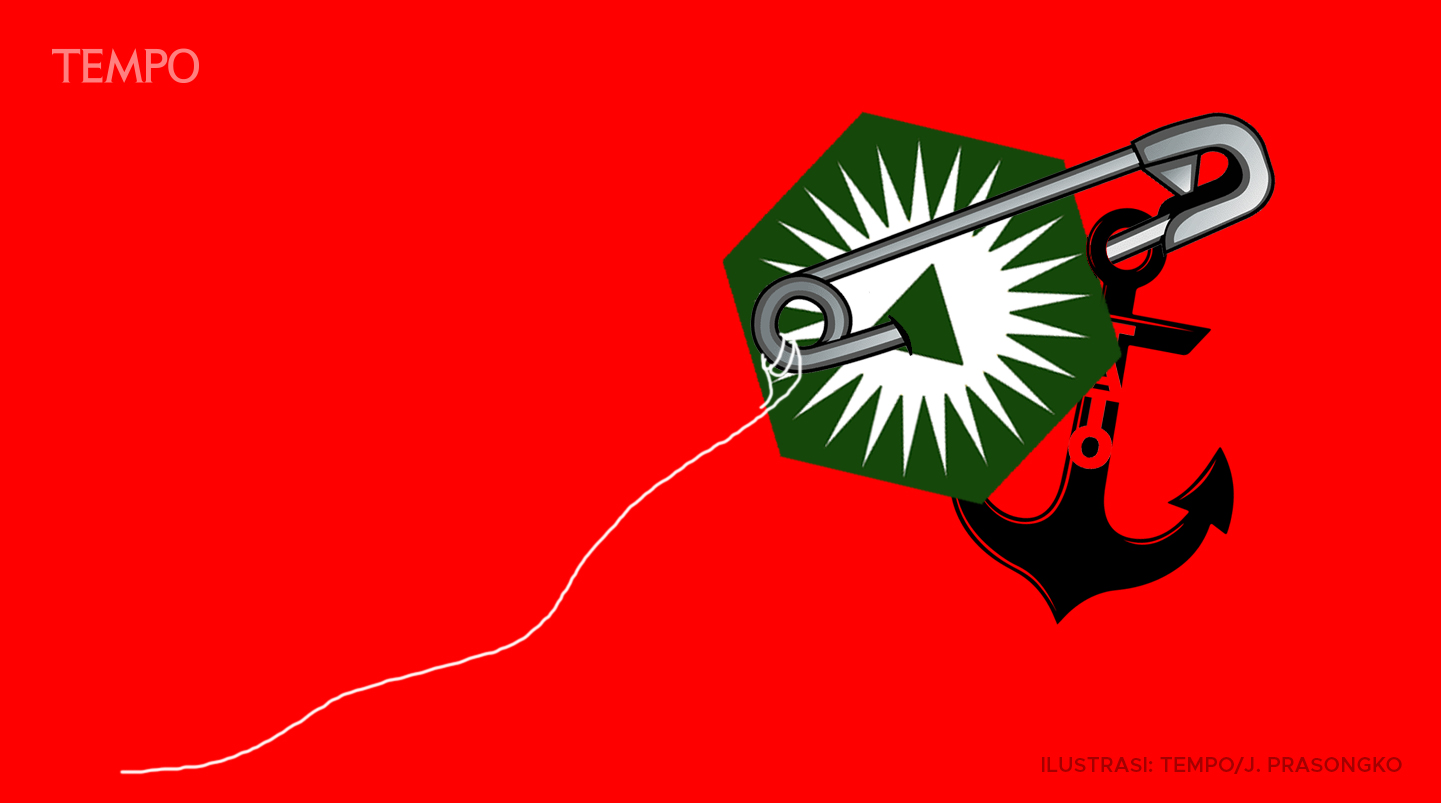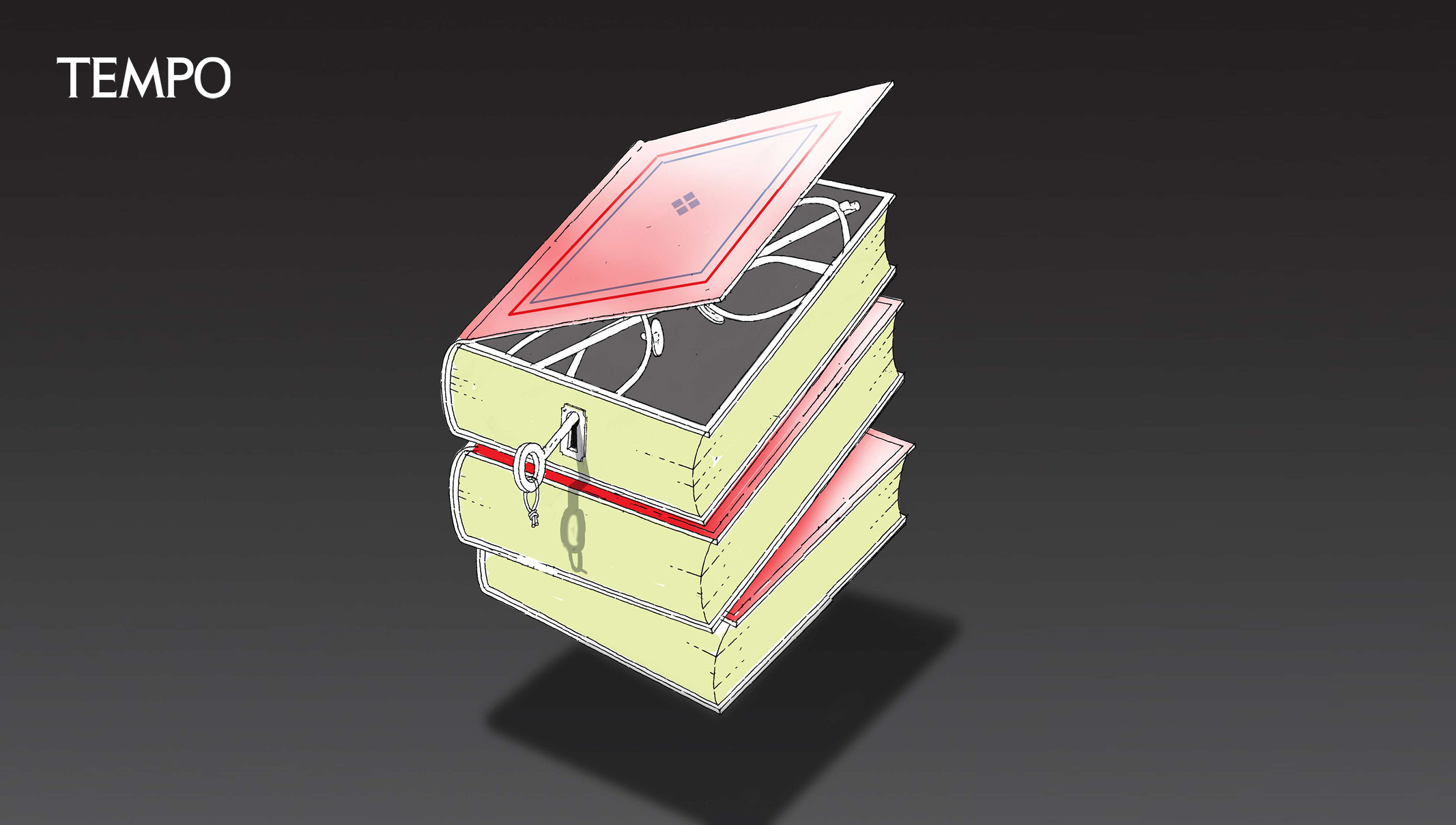Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

MESKI terlambat, pernyataan Presiden Joko Widodo tentang perlunya pemerintah membuka data Covid-19 cukup melegakan. Statemen ini mengoreksi sikap pemerintah yang sebelumnya terkesan menutup-nutupi jumlah pasien positif dan orang yang ditengarai terinfeksi. Awalnya, Jokowi beranggapan transparansi bisa membuat orang cemas. Ia lupa, tanpa sikap terbuka, bahkan karantina wilayah pun tidak akan efektif menyelesaikan pandemi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo