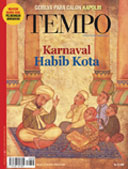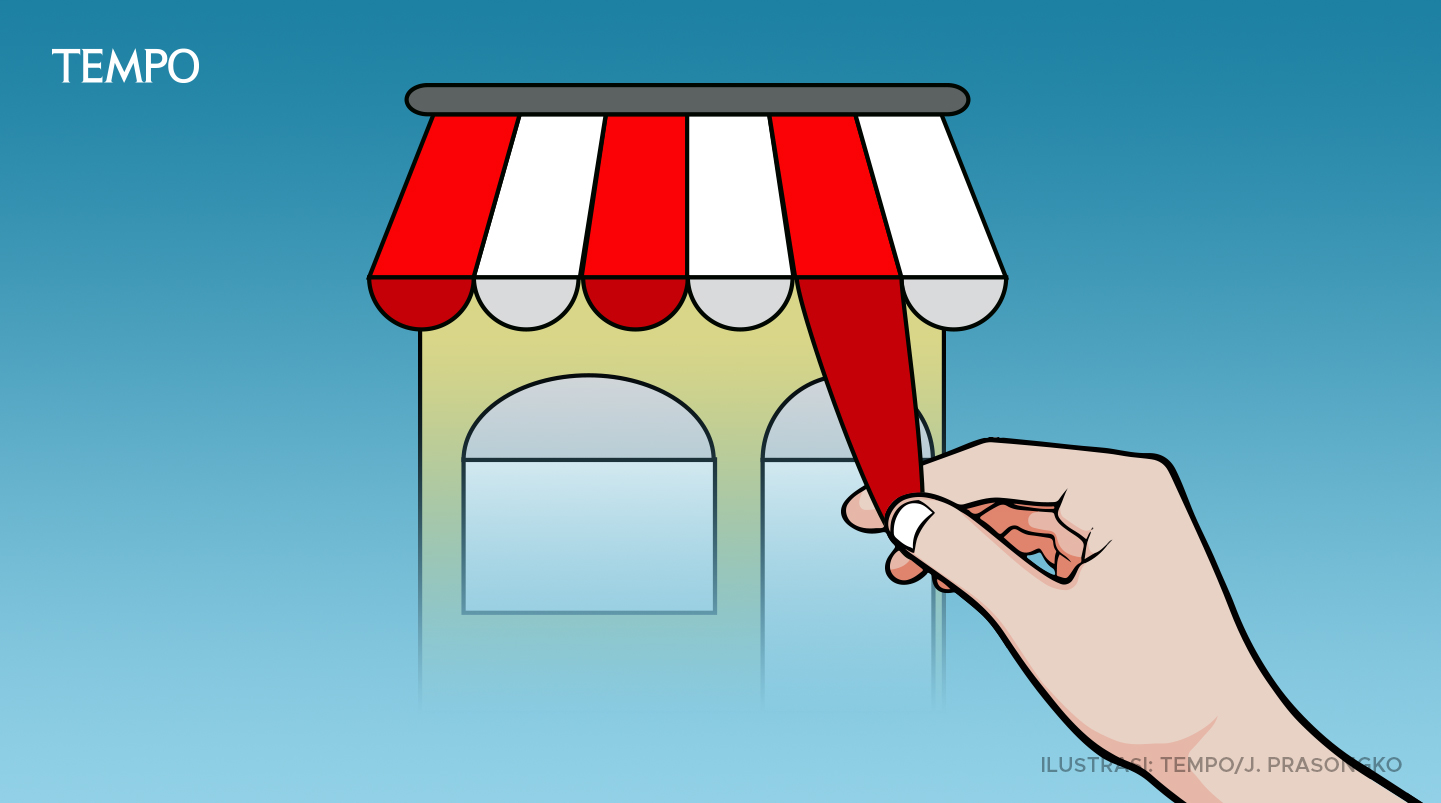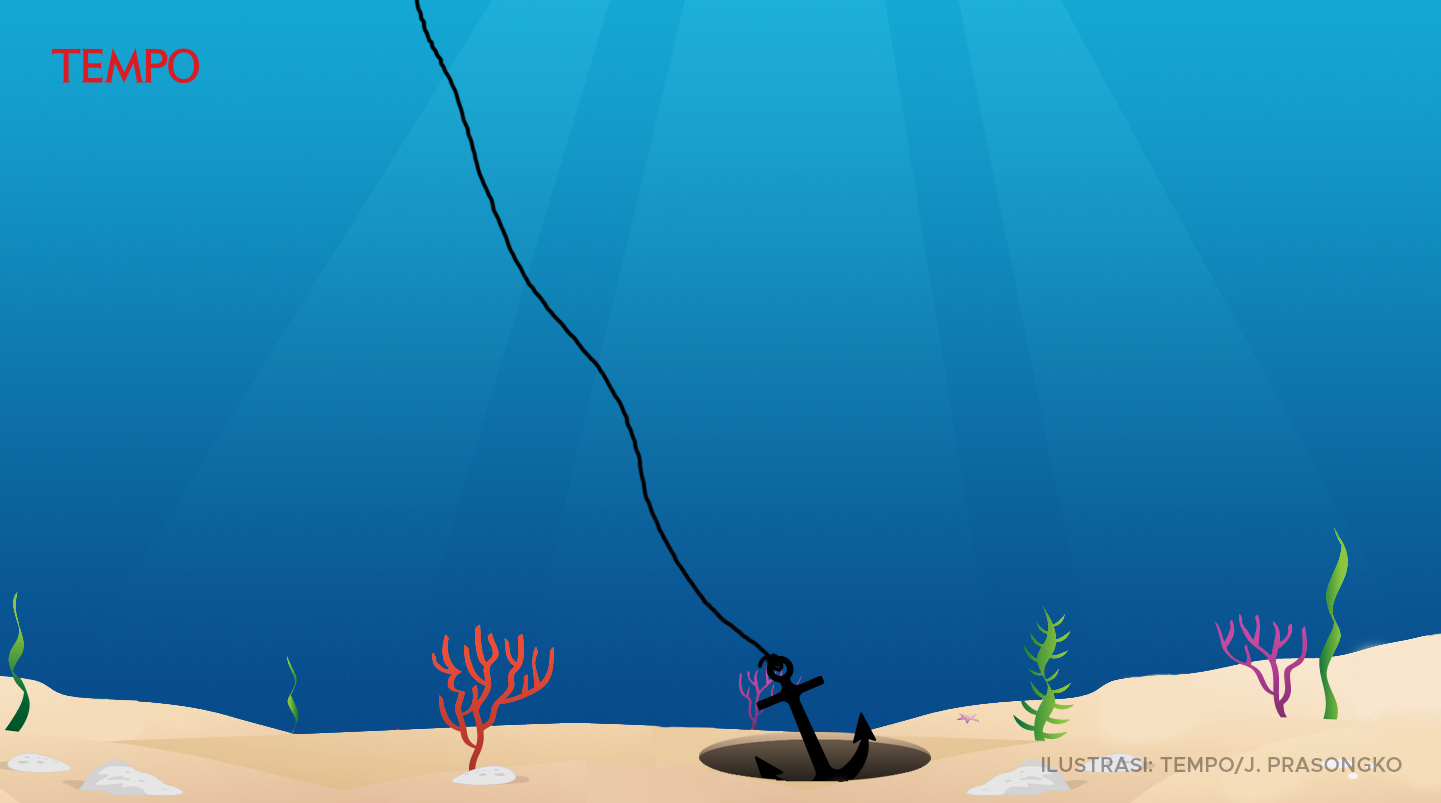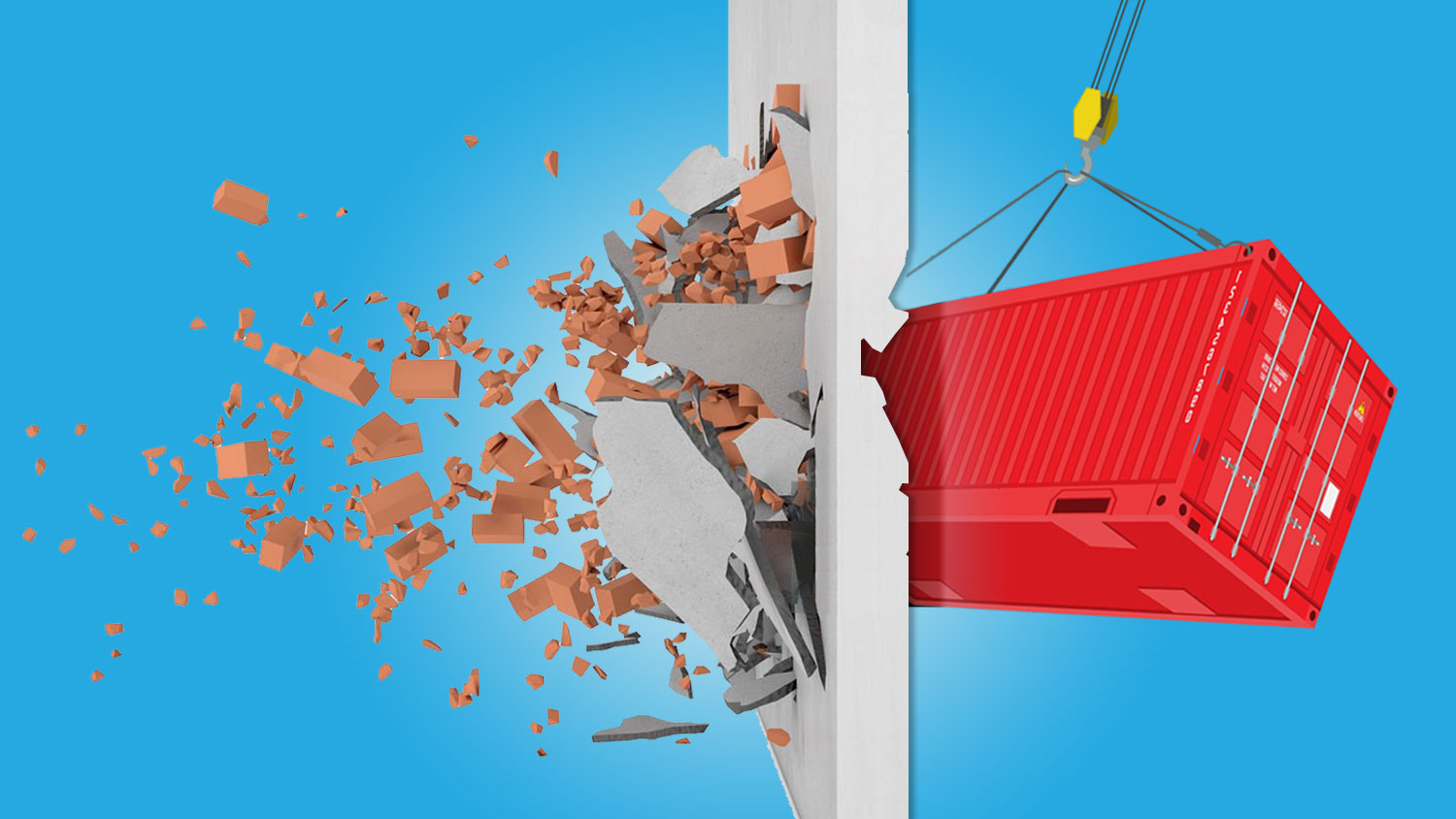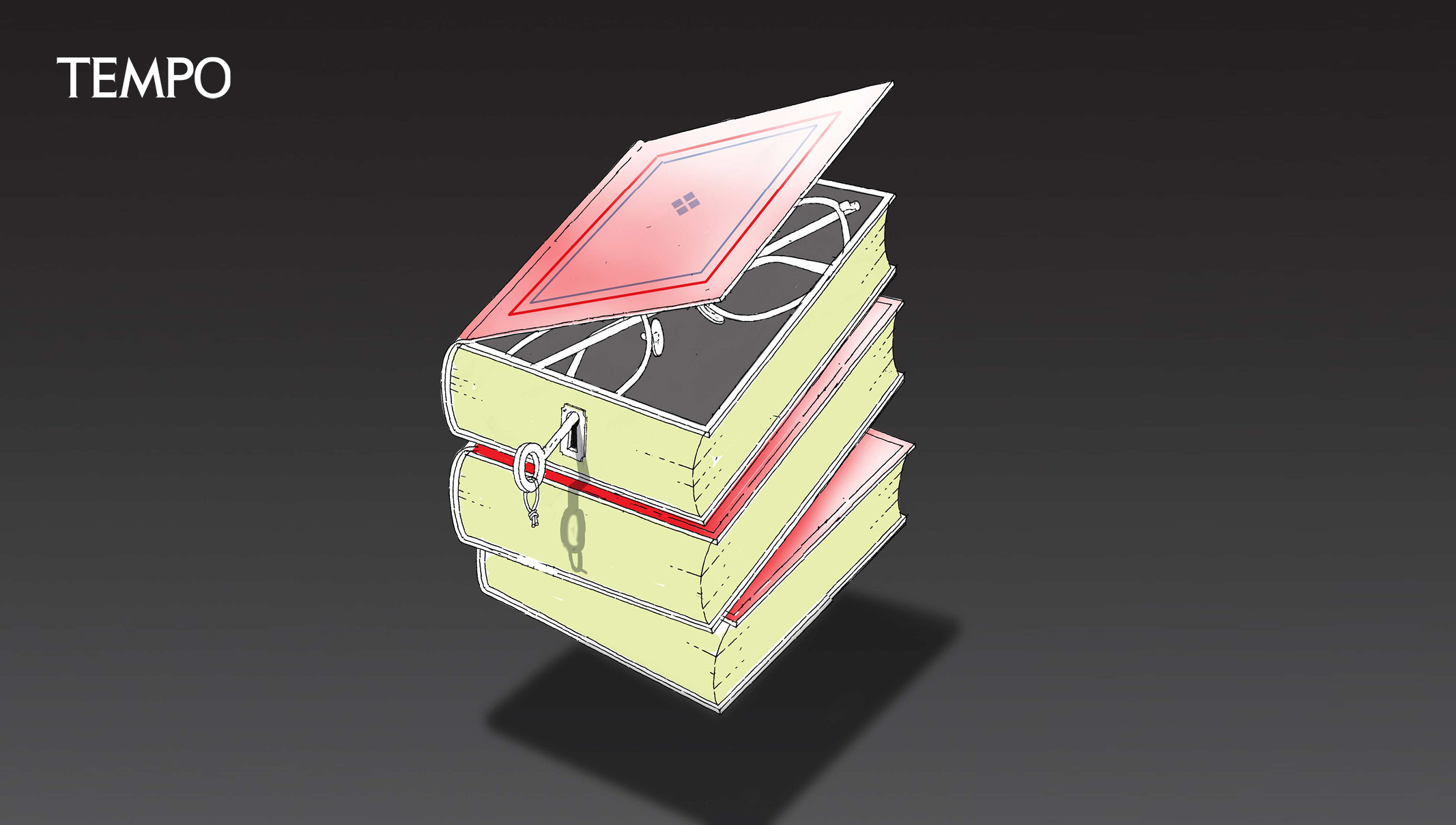Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TREN ber-"habib-habib" belakangan ini dapatlah kita pandang sebagai dinamika sosial belaka. Kita menyaksikan kecintaan masyarakat kepada habaib (bentuk jamak dari habib) tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran beragama. Di negeri berpenduduk mayoritas Islam ini, habaib tak sulit merebut hati masyarakat berkat faktor genealogis sebagai keturunan Nabi Muhammad.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo