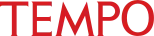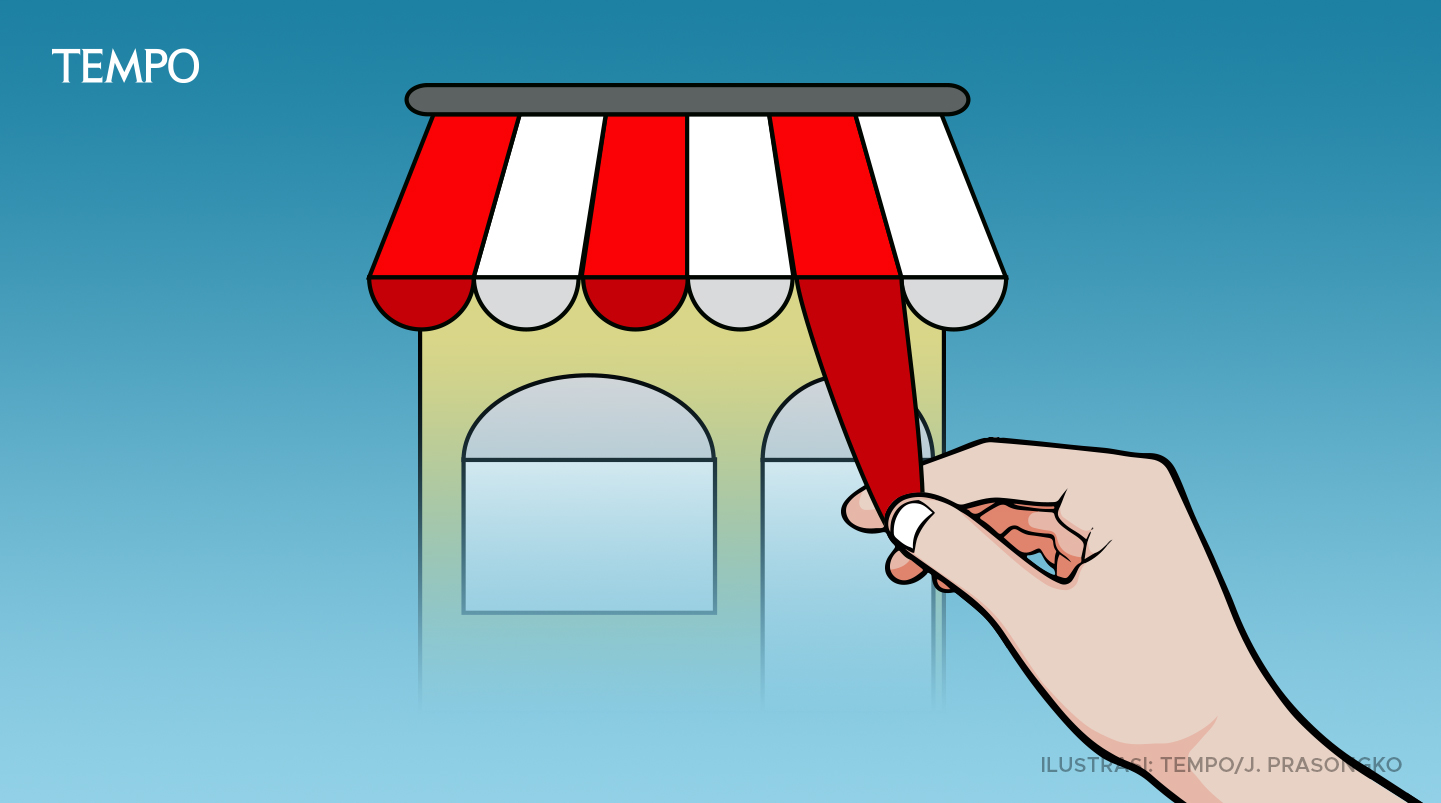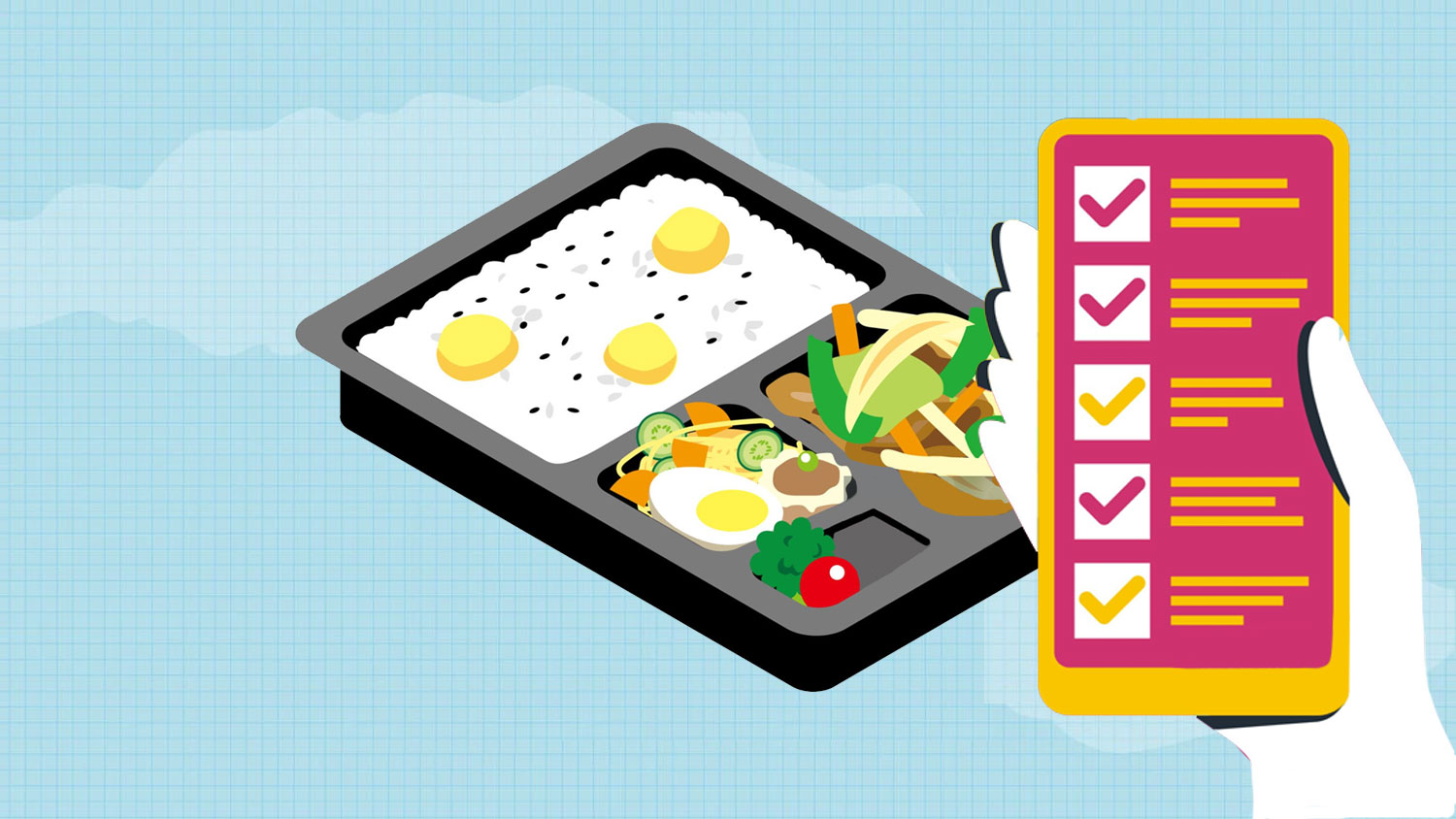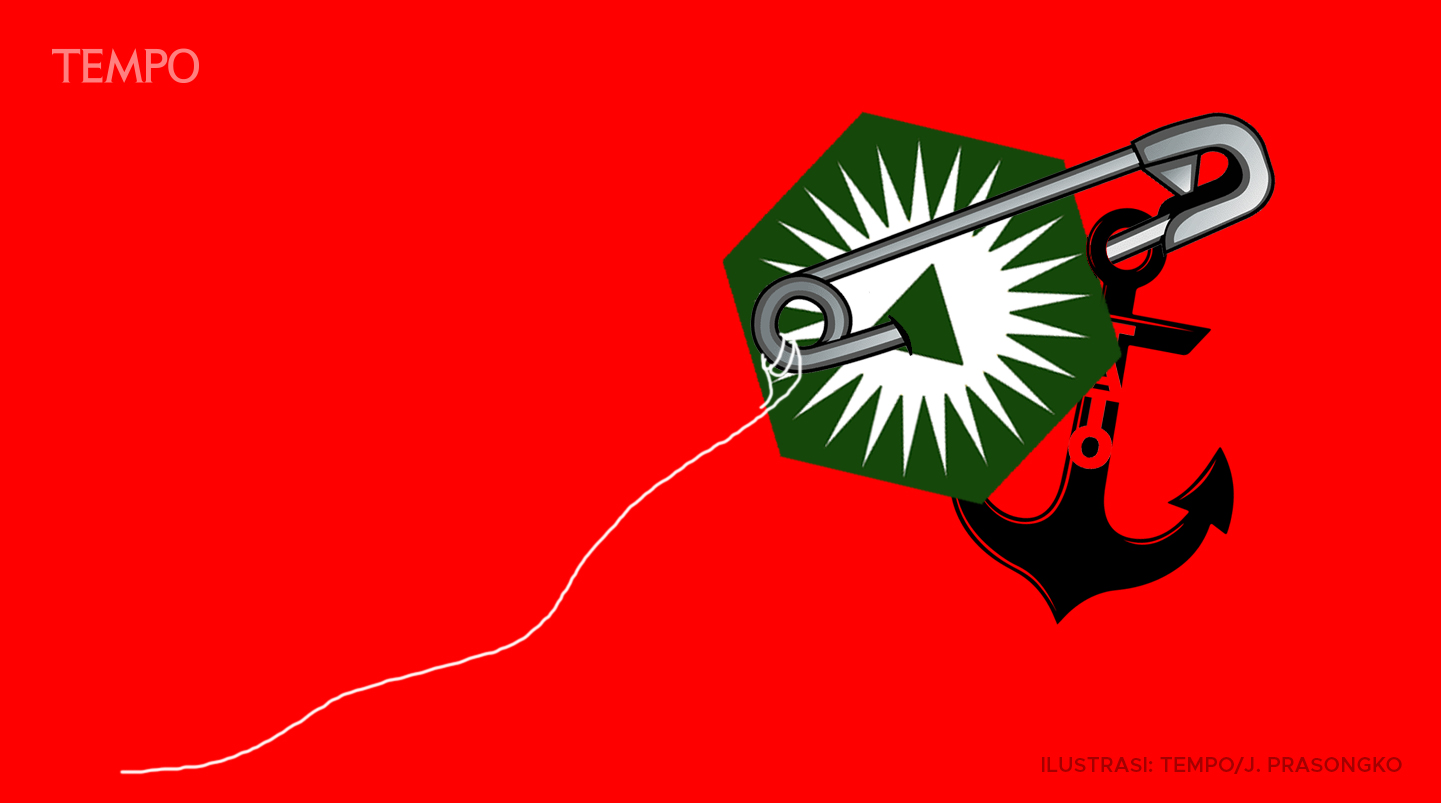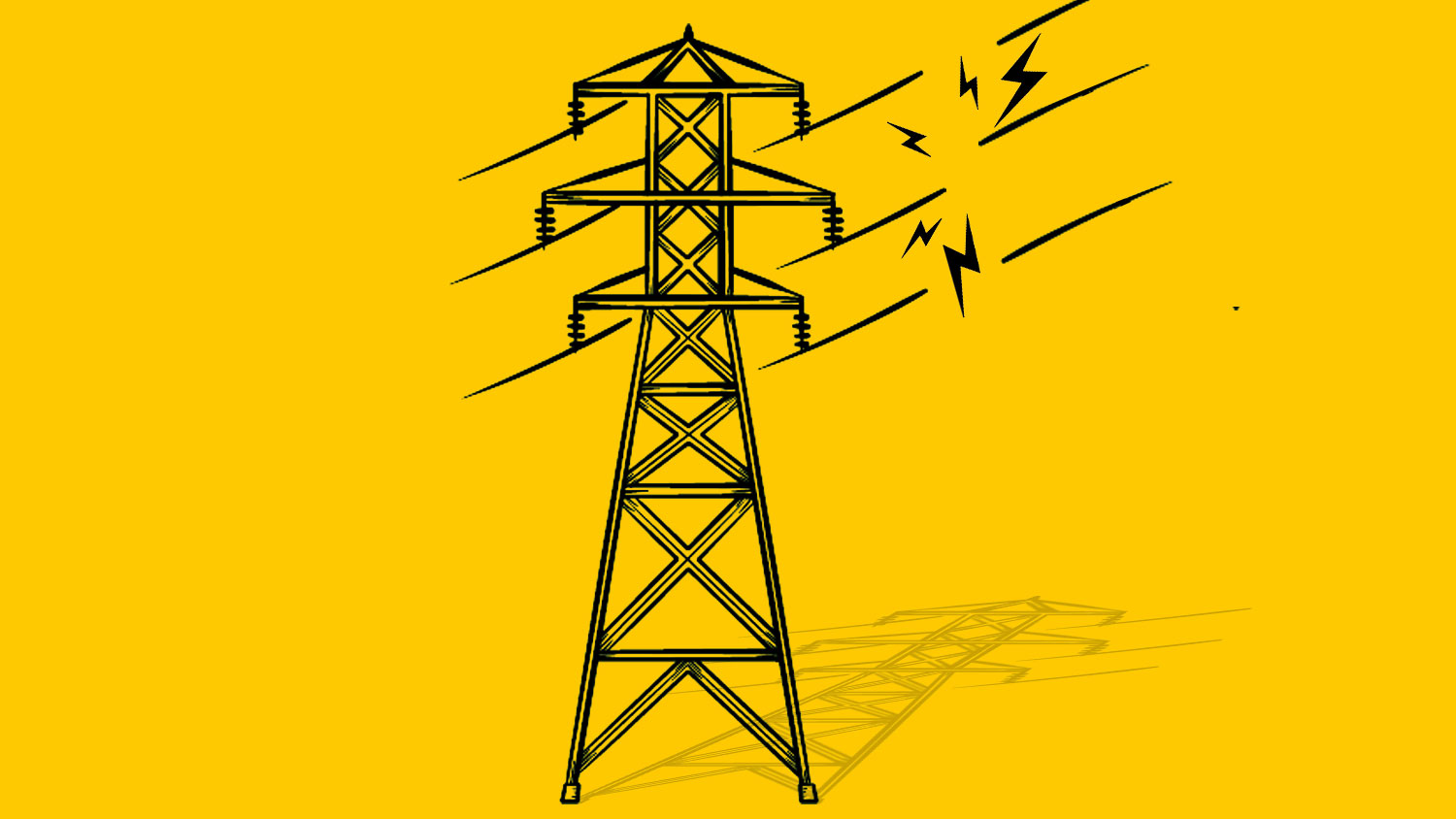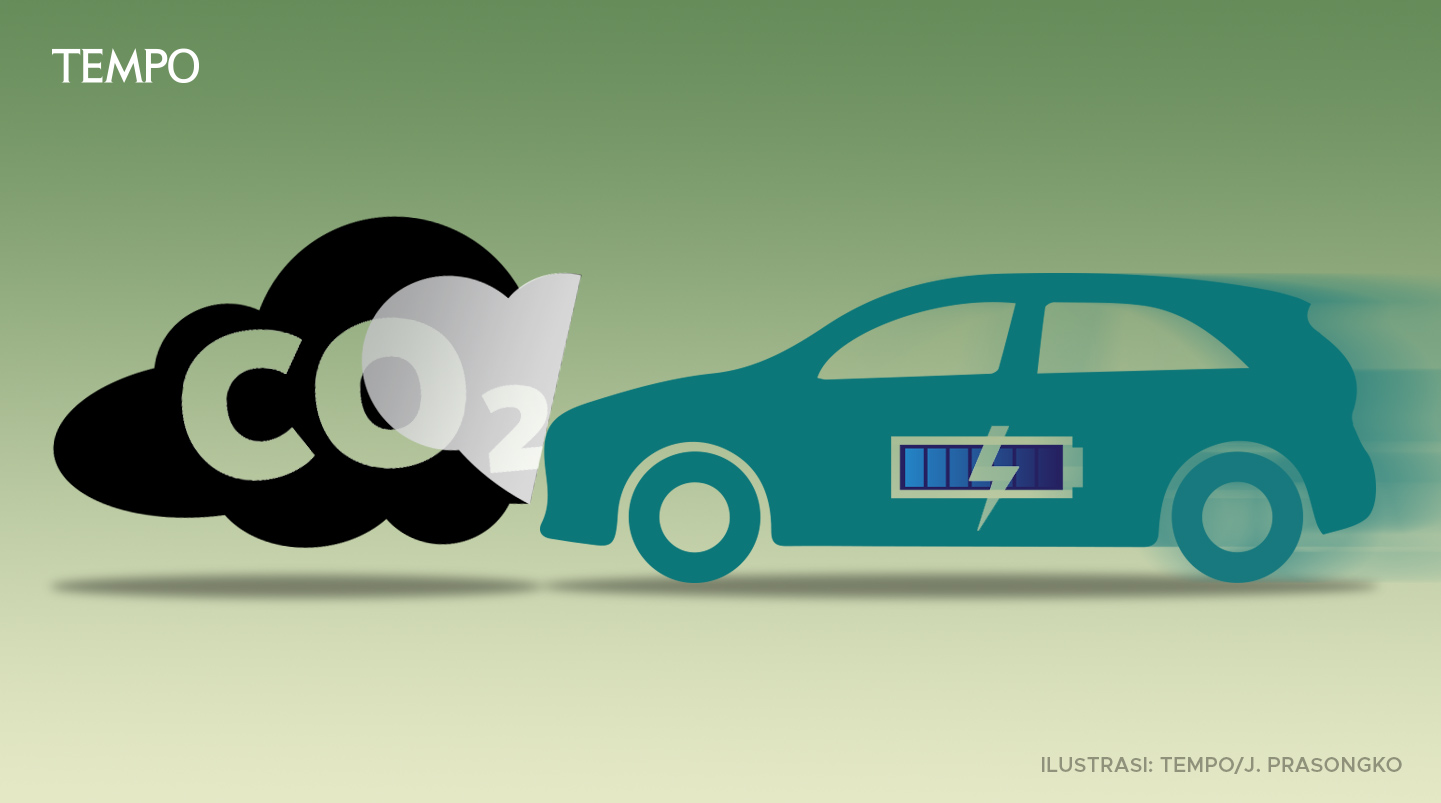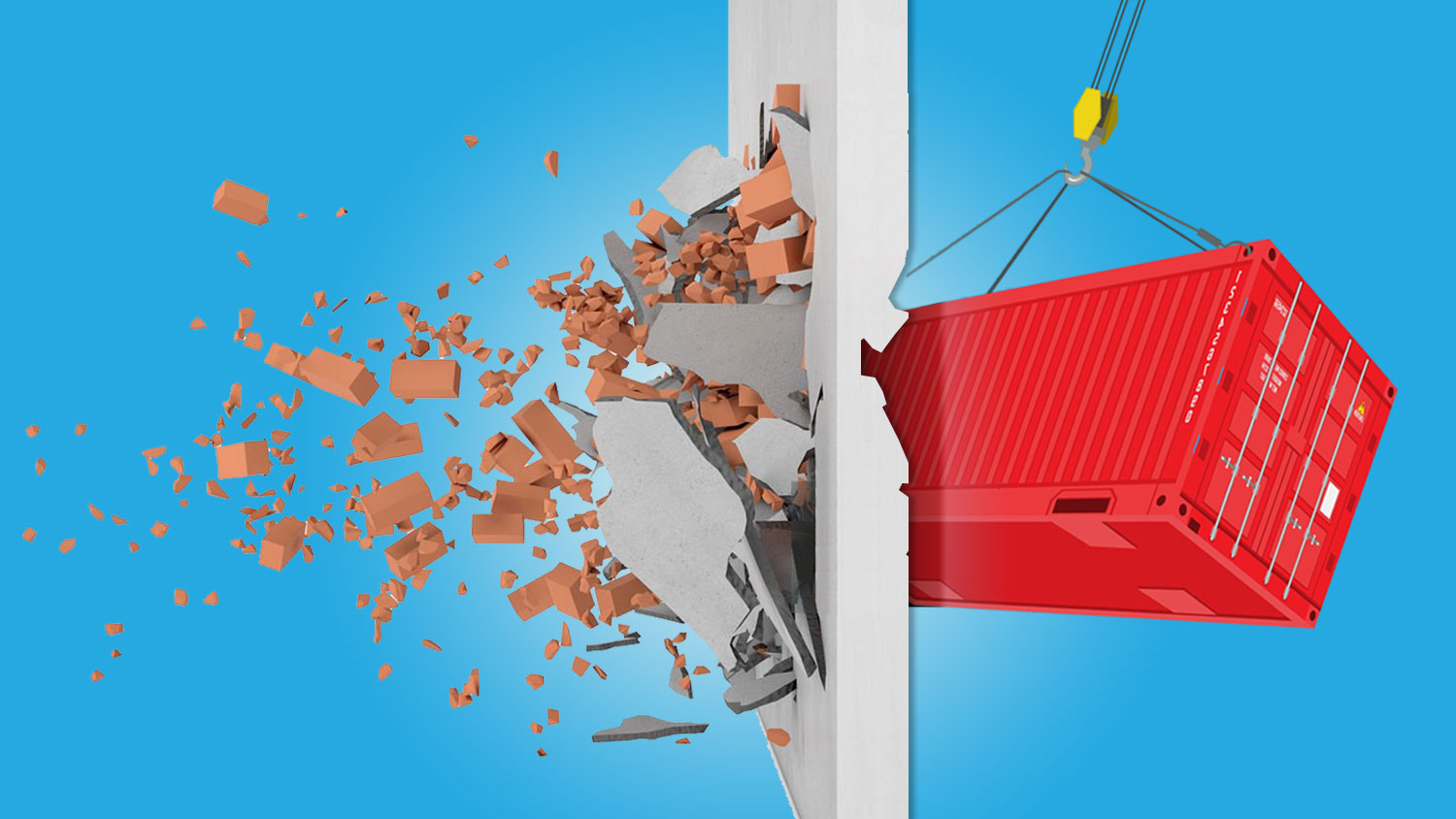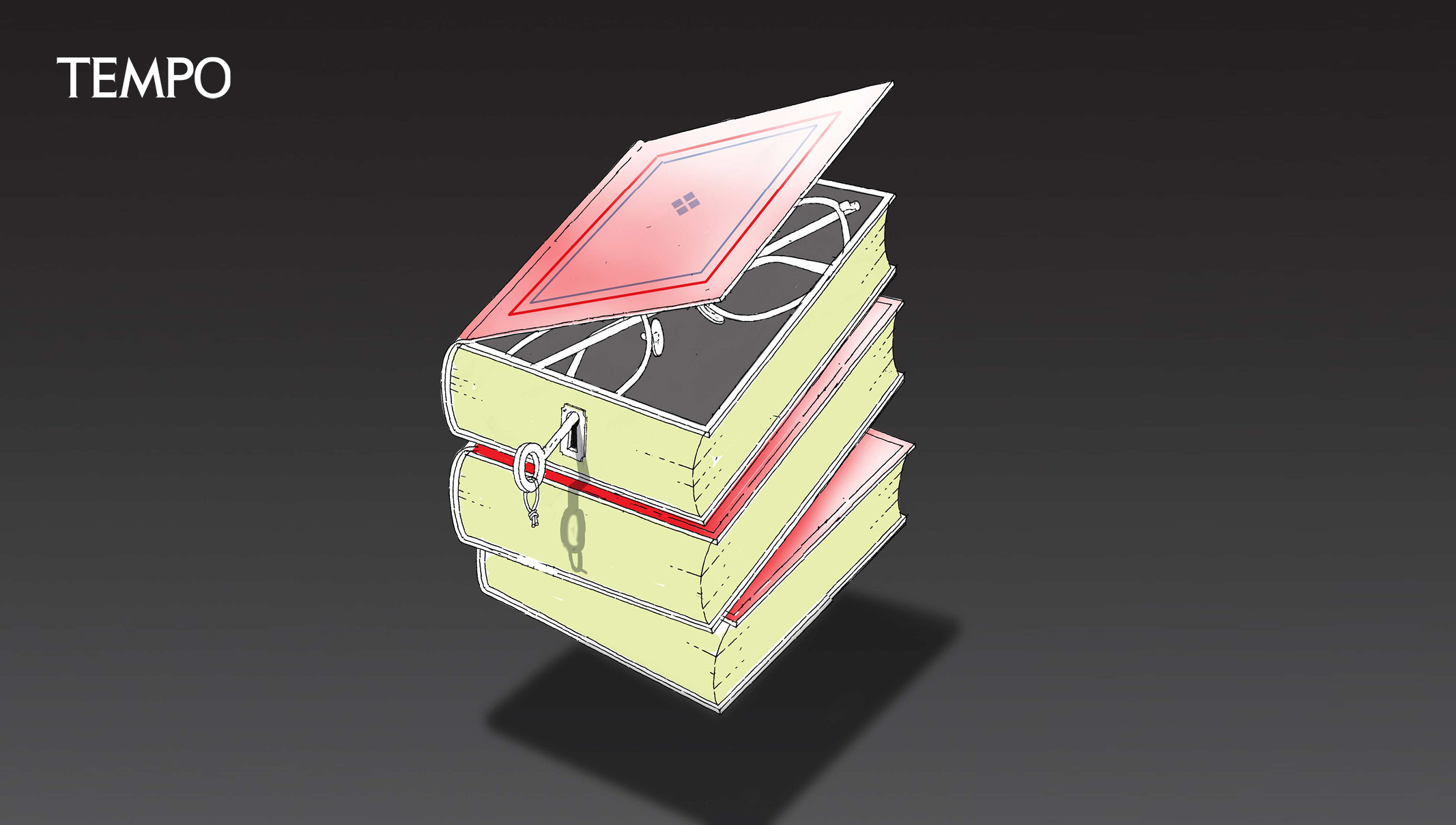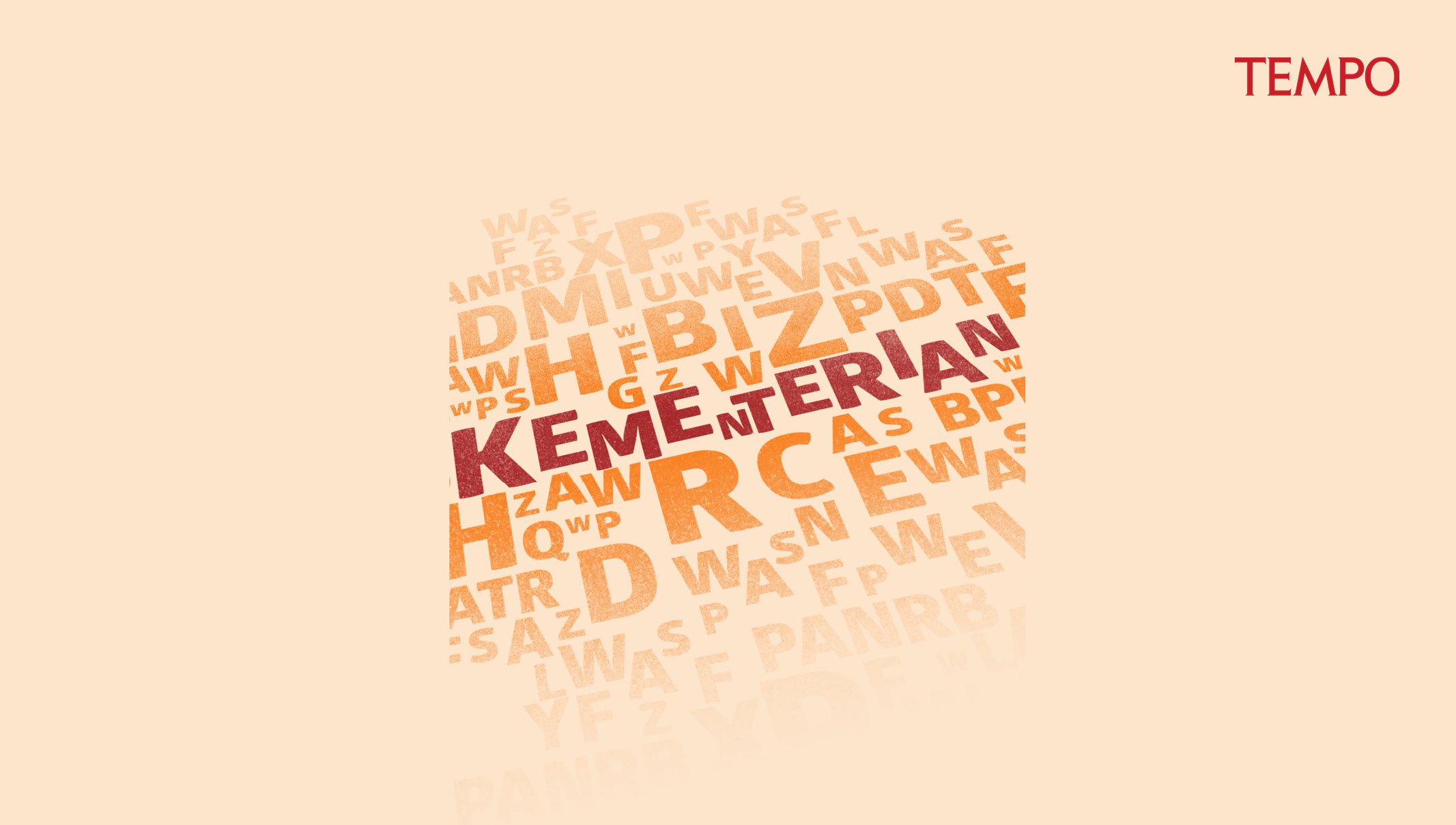Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Penandatanganan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss adalah langkah awal yang baik untuk upaya pengembalian aset hasil tindak pidana di negeri ini. Namun itu saja tidak cukup.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perjanjian tersebut baru bermanfaat jika pemerintah mengambil langkah konkret untuk mendata dan memproses pengembalian aset-aset koruptor dan penjahat lain yang disembunyikan di Swiss. Harus diakui, selama ini program pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia seolah-olah jalan di tempat: kerap didengungkan lembaga penegak hukum, tapi bertahun-tahun tak ada hasil berarti.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Padahal Swiss sudah membuka jalan untuk repatriasi aset hasil kejahatan sejak tujuh tahun silam. Pemberlakuan undang-undang Return of Illicit Assets Act pada 2011 di Swiss adalah undangan terbuka untuk negara-negara yang hartanya dilarikan penjahat dan disembunyikan di sana.
Aturan itu memungkinkan pemerintah Swiss membekukan dan mengembalikan aset yang diduga hasil korupsi ke negara asalnya. Mereka yang keberatan hanya bisa mempertahankan hartanya lewat pembuktian terbalik. Jika mereka bisa membuktikan kekayaan itu diperoleh secara legal, barulah perintah pembekuan dicabut.
Ketika awal diberlakukan, sejumlah negara dengan agresif merespons undang-undang itu. Tak perlu waktu lama sebelum Nigeria berhasil merebut kembali US$ 1,2 miliar yang disembunyikan bekas pemimpinnya, Jenderal Sani Abacha, di sebuah bank di Swiss. Tim pemburu harta koruptor dari Uganda dan Ghana juga berhasil menyita berbagai aset mereka di Inggris dan Prancis.
Di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya. Tim pemburu harta koruptor gagal terus menyelamatkan triliunan aset yang disembunyikan di luar negeri. Sejak awal berdiri pada 2006, tim pemburu koruptor hanya bisa menangkap dan memulangkan satu buron saja, yaitu mantan Direktur Bank Servitia David Nusa Wijaya. Terpidana kasus korupsi dana BLBI senilai Rp 1,3 triliun ini ditangkap di Amerika Serikat pada 2006. Dia kemudian ditahan, namun tak semua asetnya disita.
Kendala utama yang dihadapi tim pemburu harta koruptor selama ini adalah lemahnya mekanisme kerja sama antarnegara untuk pengembalian aset terpidana. Karena itu, penandatanganan perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Swiss ini bisa membawa harapan perbaikan.
Apalagi perjanjian yang terdiri atas 39 pasal itu dengan rinci mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. MLA ini juga dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan, termasuk pengembalian aset hasil kejahatan yang diduga banyak disimpan di bank-bank di Swiss. Meski tak disebutkan terbuka dalam konferensi pers, perjanjian ini juga diusulkan bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.
Memang bukan hal mudah bagi pemerintah untuk melacak dana-dana tersebut, apalagi membuktikannya sebagai hasil kejahatan. Kesepakatan MLA ini seharusnya menjadi momentum untuk mendorong perbaikan sistem agar pengembalian aset hasil kejahatan bisa lebih mangkus di masa depan. (*)