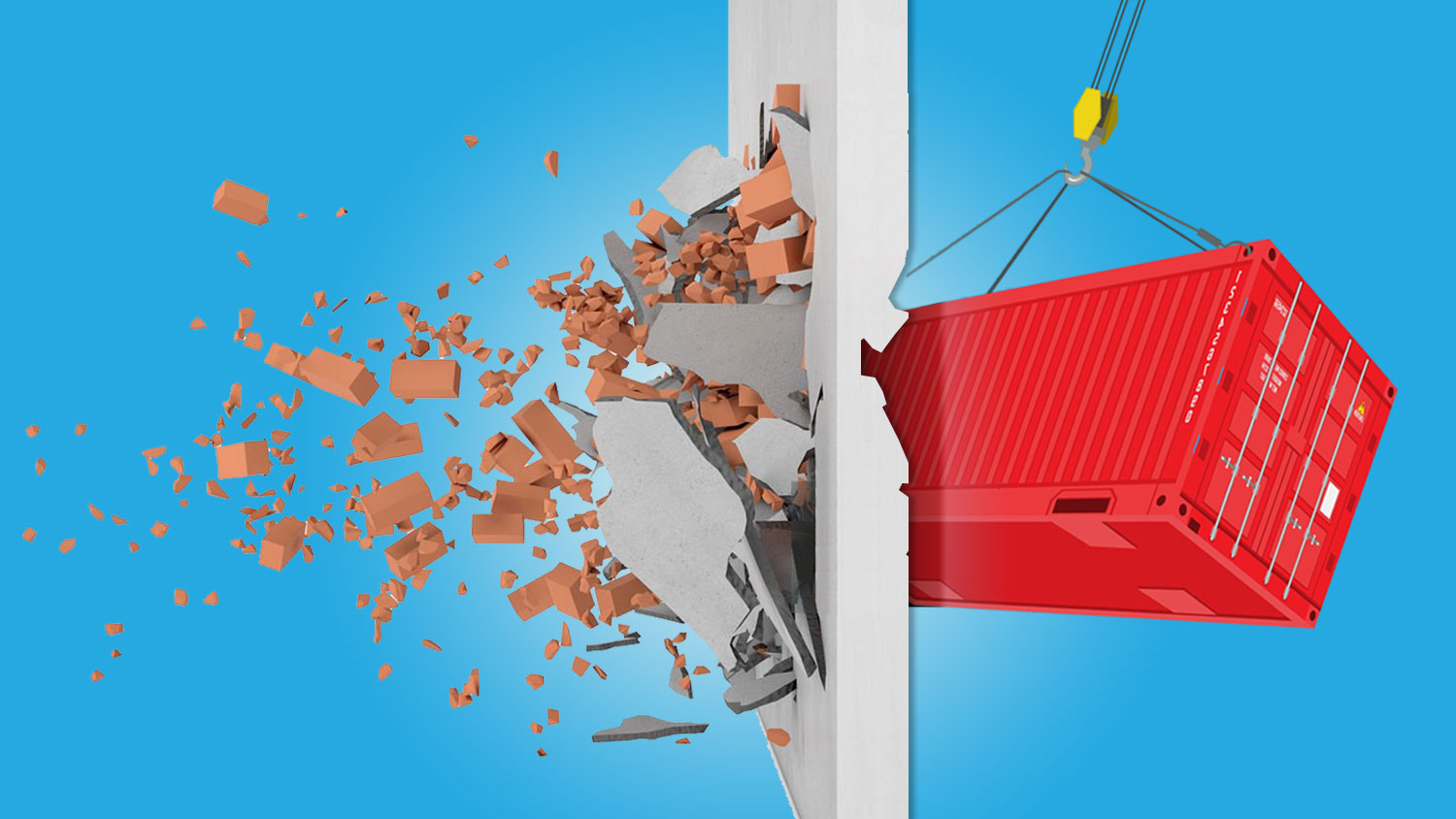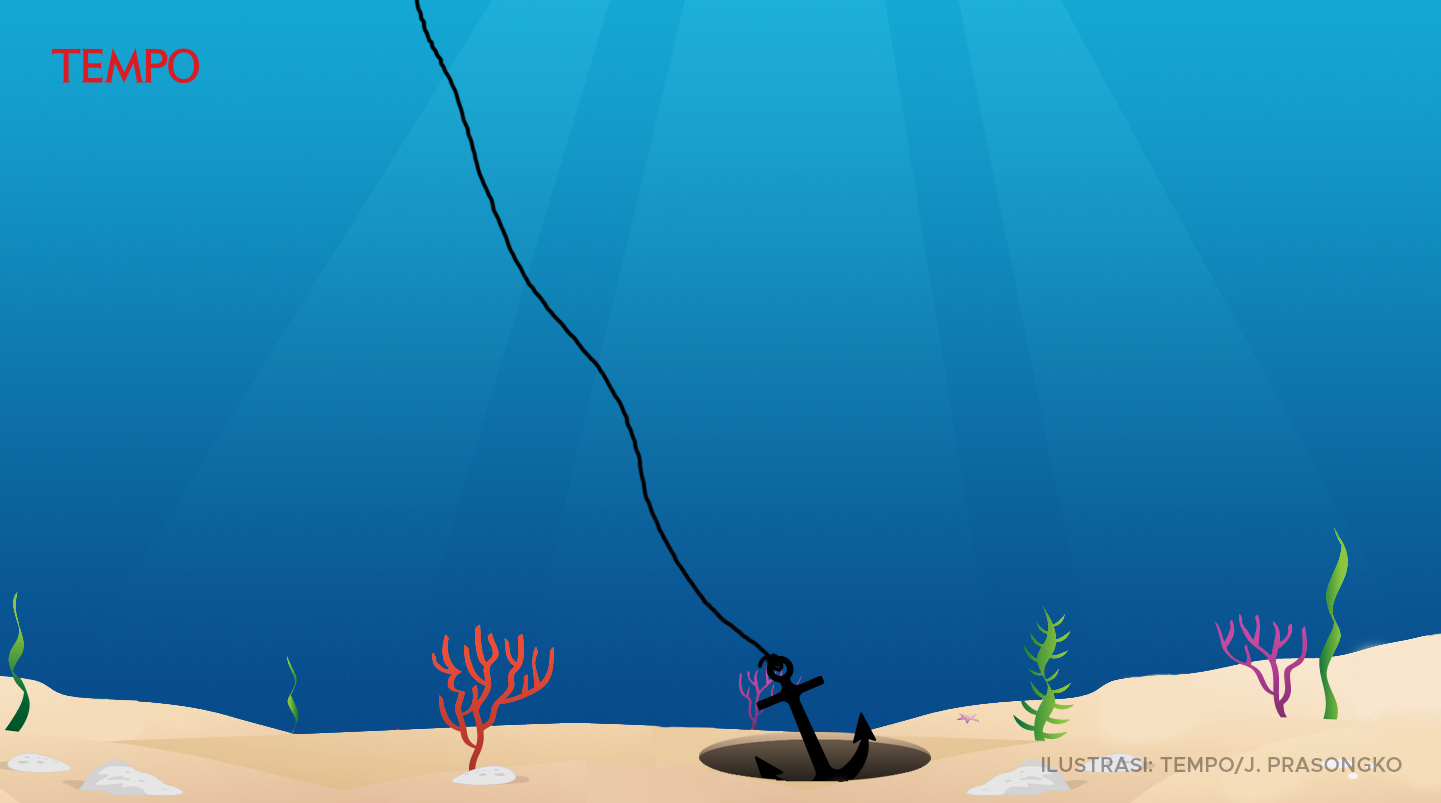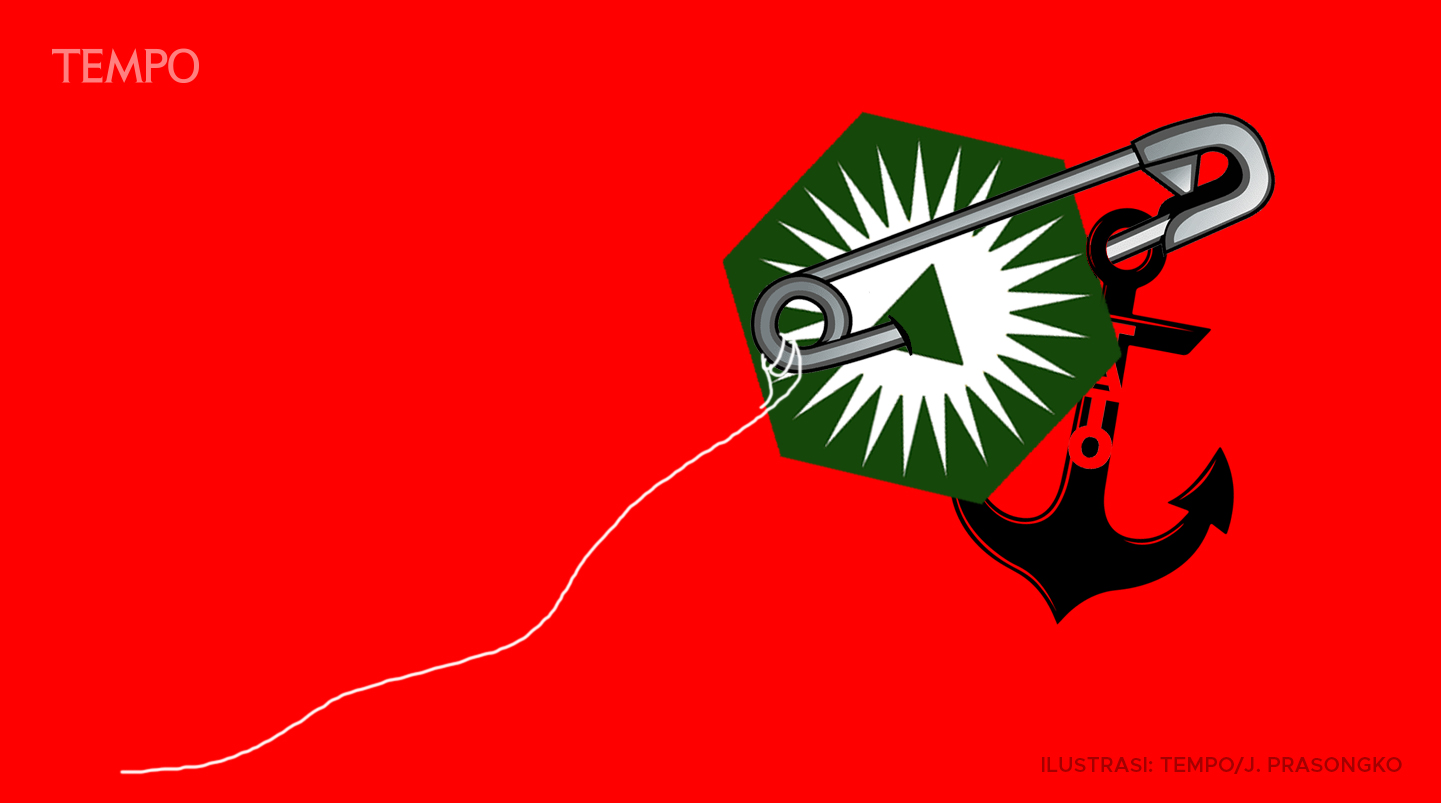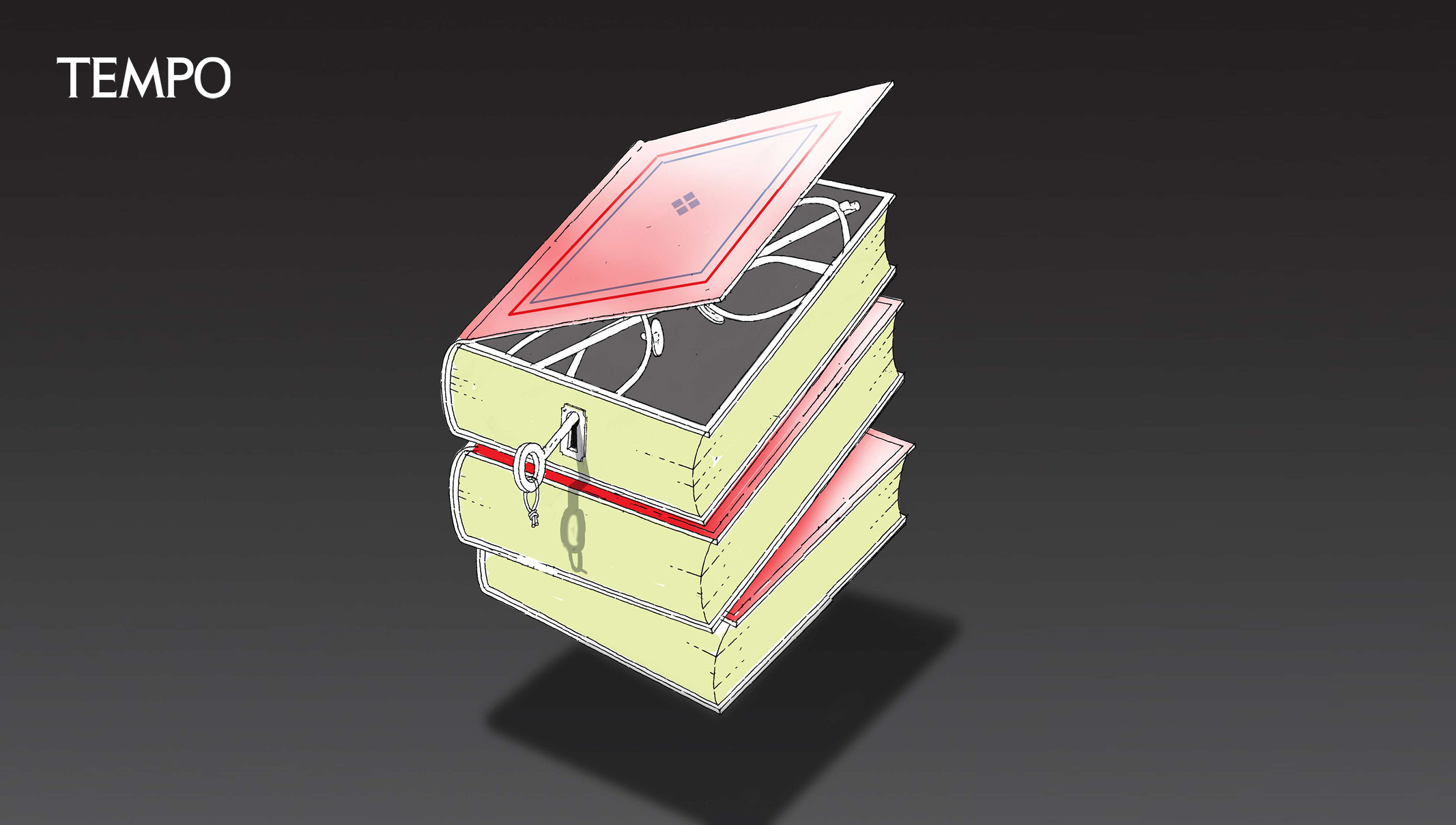Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PEMERINTAH mesti berhati-hati dalam menangani pengungsi Rohingya asal Myanmar. Tak boleh ikut larut dalam sentimen antipengungsi yang sedang berkembang, pemerintah perlu membedakan antara pengungsi yang datang karena perdagangan manusia dan yang benar-benar mengungsi karena terancam jiwa dan raganya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengaku mendapatkan informasi bahwa ada jaringan tindak pidana perdagangan orang di balik kedatangan para pengungsi Rohingya ke Aceh belakangan ini. Meskipun indikasinya kuat, dalih tersebut tidak boleh dipakai oleh pemerintah untuk memulangkan “manusia perahu” kembali ke Myanmar atau mengombang-ambingkan mereka di tengah laut.
Dalam sebulan terakhir, lebih dari 800 pengungsi Rohingya terdampar di sejumlah pantai di Aceh. Pemerintahan Myanmar tak mengakui etnis muslim itu sebagai warga negara meskipun sudah berabad-abad tinggal dan beranak-pinak di Rakhine, negara bagian yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Myanmar menganggap Rohingya sebagai imigran dari Chittagong, Bangladesh. Sebaliknya, Bangladesh menganggap mereka warga Myanmar.
Lebih dari sejuta pengungsi Rohingya diusir dari Myanmar sejak 1990-an. Sebelum genosida pada 2017, diperkirakan ada 1,4 juta warga Rohingya tinggal di Rakhine. Kini, sebagian besar dari mereka, lebih dari 960 ribu, tinggal di salah satu kemah pengungsian terbesar di dunia, Kutupalong dan Nayapara di Cox’s Bazar, kota bagian tenggara Bangladesh, yang berbatasan langsung dengan Rakhine.
Sebagian lainnya menyebar ke banyak negara, tak kecuali ke Asia Tenggara. Per awal Desember ini, ada sekitar 92 ribu pengungsi Rohingya di Thailand dan 107 ribu lebih di Malaysia. Di Indonesia “cuma” 1.487 orang. Sebagian besar berada di Aceh.
Akhir-akhir ini beredar isu di media sosial bahwa sejumlah pengungsi menolak makanan pemberian warga Aceh. Tersiar juga kabar bahwa mereka tak menghormati nilai-nilai setempat. Ujung-ujungnya muncul seruan mengusir Rohingya sampai menganjurkan kekerasan terhadap mereka.
Inilah bahayanya jika pemerintah tak lekas membaca situasi dan mengambil sikap tegas. Pemerintah tidak boleh mengikuti desakan tersebut. Satu pengungsi yang berperilaku buruk tak boleh dijadikan alasan untuk mengusir mereka semua.
Pemerintah harus ingat bahwa Indonesia terikat prinsip non-refoulement, yang melarang suatu negara mengembalikan pengungsi ke negara asal atau melepas mereka dalam kondisi bahaya lagi, seperti menundung ke tengah laut. Prinsip itu ada pada Konvensi Anti-Penyiksaan serta Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik yang telah kita ratifikasi pada 1998 dan 2005.
Pemerintah juga telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Berdasarkan itu, penanganan pengungsi bisa dilakukan lewat kerja sama pemerintah pusat, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dan organisasi internasional lainnya, seperti yang telah dilakukan selama ini. Bersama UNHCR dan badan-badan lain, pemerintah mesti segera mencari cara menyelesaikan masalah Rohingya. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan ASEAN agar lebih galak terhadap Myanmar yang tak mengakui Rohingya.
Rohingya bukan lagi masalah dalam negeri Myanmar. Rohingya sudah jadi problem kawasan. Tanpa membereskan sumber masalah di hulu, gelombang pengungsi akan terus berdatangan.
Sambil memaksa Myanmar menyelesiakan masalah Rohingya, sudah seharusnya Indonesia dan negara-negara ASEAN mencari solusi permanen buat etnis yang tertindas ini. Indonesia, misalnya, bisa mendorong ASEAN menghimpun dana bersama untuk mengongkosi bantuan kemanusiaan. Tanpa kerja sama lintas negara, masalah Rohingya—juga pengungsi dari negara lain yang tak kalah banyak jumlahnya di ASEAN—akan terus berulang.