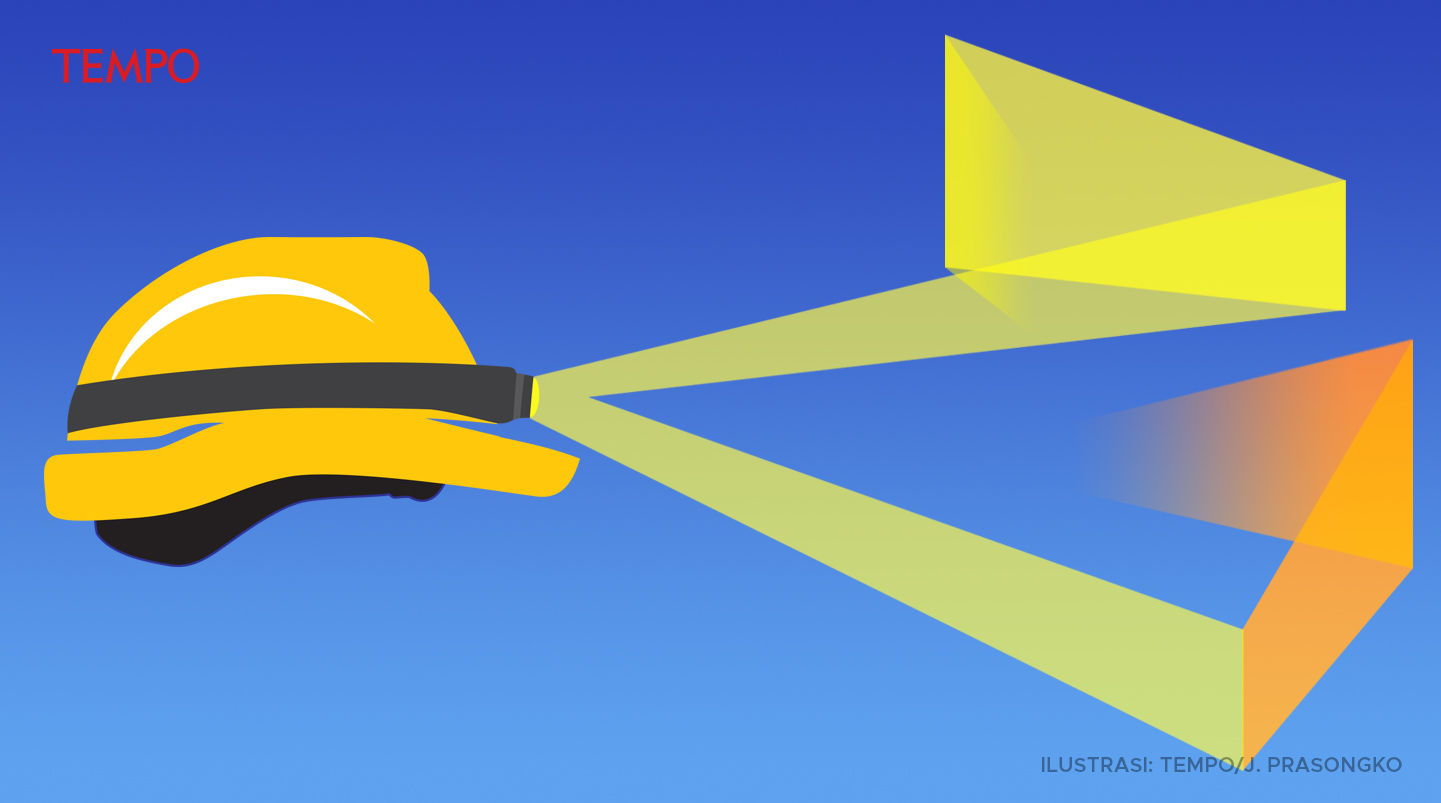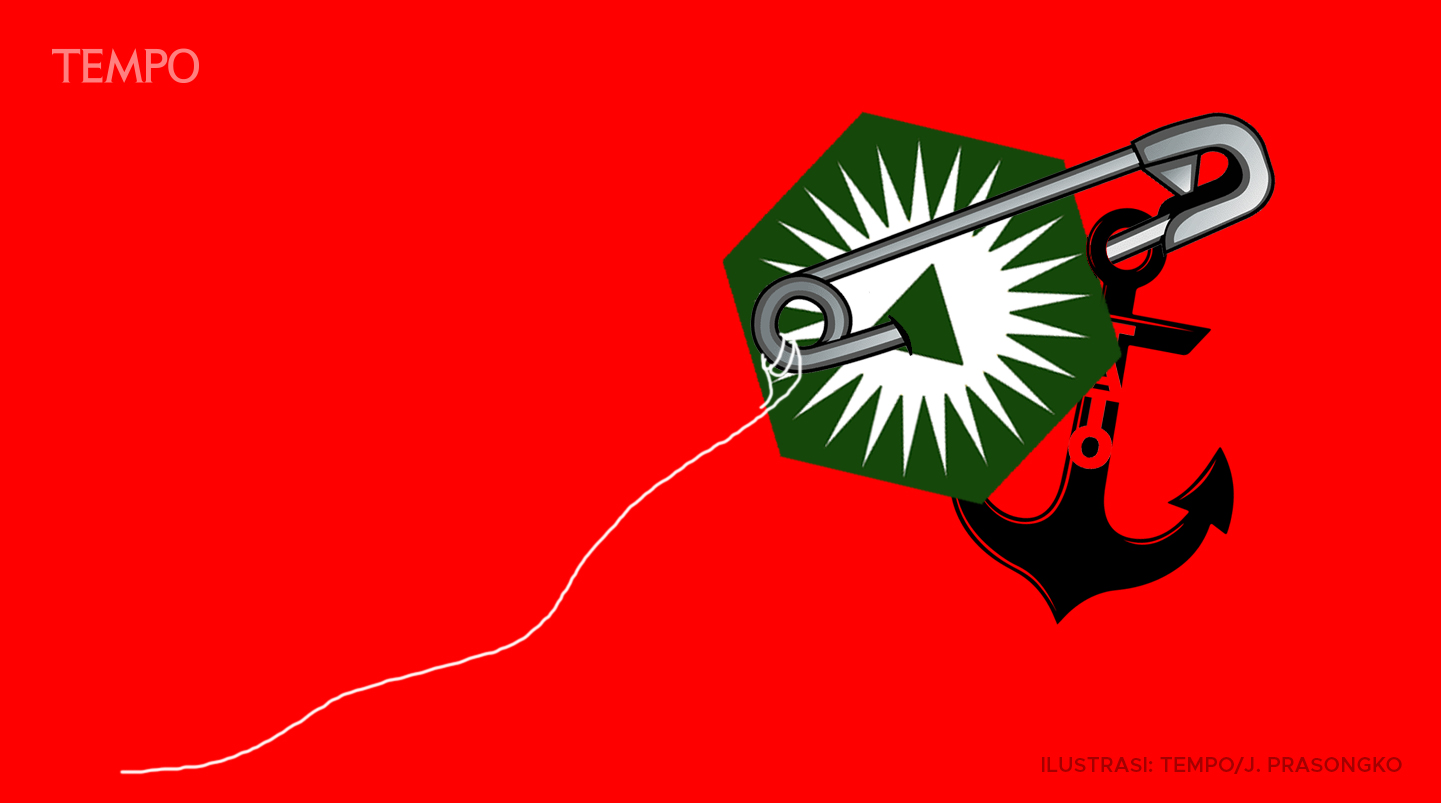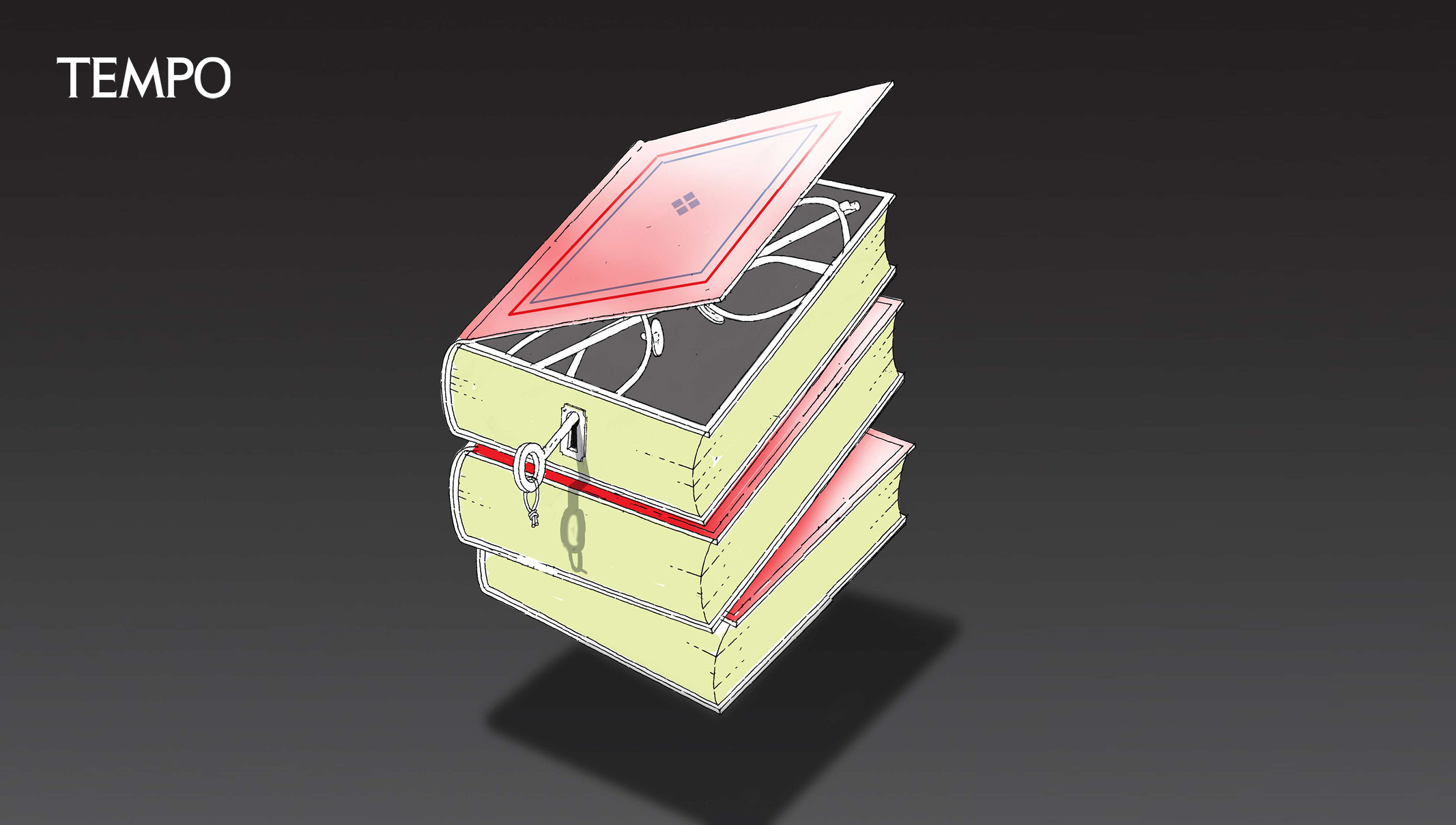Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Pasal penghinaan presiden dan perluasan zina dalam Rancangan KUHP (RKUHP) dapat menimbulkan mudarat di kemudian hari. Perluasan zina membuat korban perkosaan dan pelaku nikah siri rentan di hadapan hukum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Membahas RKUHP di DPR, sebaiknya kita mulai dari sebuah kata. Ironis sekali, jika kata "revisi" dalam pembahasan RKUHP di Dewan Perwakilan Rakyat dipergunakan untuk mengembalikan negeri ini ke aturan lampau yang sudah ketinggalan zaman alias bertentangan dengan demokrasi yang didorong oleh semangat reformasi 1998. Karena revisi mengandung makna progresif: memperbaiki hukum peninggalan era kolonial yang sudah usang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kalau pasal penghinaan presiden sebagaimana yang pernah berkali-kali disalahgunakan dalam haatzaai artikelen itu akan dihidupkan kembali, kita pun seperti kehilangan roh reformasi. Terlalu cepat jika sekarang kita melupakan reformasi, seraya menghidupkan kembali nilai-nilai kepemimpinan otoriter. Tentu sangat menyedihkan jika pasal yang telah dikuburkan Mahkamah Konstitusi pada 2006 melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dibangkitkan kembali melalui KUHP yang baru.
Pasal 284 RKUHP berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Sementara Pasal 285 menyebutkan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV bagi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan, gambar atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah.
Lantaran semangat yang terkandung dalam RKUHP pasal 284 dan 285 adalah larangan untuk menghina pemerintah, pasal-pasal itu pun disebut juga haatzaai artikelen. Haatzaai dalam bahasa Belanda berarti kebencian, artikelen berarti pasal.
Berbagai pembelaan terhadap pasal penghinaan presiden cepat terdengar sebagai jawaban atas kritik yang ditujukan kepada “hasil karya” penggodokan pikiran para anggota dewan dan pemerintah itu. Kepemimpinan Presiden Djoko Widodo boleh jadi terlalu "baik" untuk kelak menggunakan pasal ini dalam menghadapi kritik --kendati ini masih perlu dibuktikan lebih jauh. Namun kita harus ingat "umur" KUHP hasil revisi sudah pasti akan lebih panjang dari pemerintahan Djokowi, dan siapa bisa menjamin bahwa kepala-kepala negara Indonesia mendatang tak memiliki kecenderungan otoriter atau kelewat sensitif terhadap kritik.
Bukan cuma itu, soal perluasan istilah zina seperti yang termaktub dalam pasal 484 ayat 1 dan 2 RKUHP akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kedua pasal tersebut mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan secara sah berhubungan seks bisa dikenakan pidana. Kalau sudah begini, "pembuktian" adanya perkawinan yang sah bakal mendudukkan para pelaku nikah sirri yang tidak memiliki pengakuan di hadapan negara dalam posisi yang sangat rentan. Patut dicatat kelemahan administrasi ini juga terdapat di antara mereka yang menikah semata-mata secara adat.
Hal yang sama juga dapat menimpa perempuan korban perkosaan. Di bawah pasal ini, hukum yang seharusnya melindungi korban yang lemah, justru membuka kemungkinan bahwa mereka dapat dapat menjadi tersangka jika sang korban tak mampu membuktikan adanya perkosaan atau pelaku bersikukuh bahwa perbuatannya dilakukan tanpa paksaan.
Sebelum peraturan baru ditegakkan dan KUHP hasil revisi diwariskan kepada generasi setelah kita, ada baiknya dipikirkan kembali konsekuensi-konsekuensi yang mungkin ditimbulkan. *
Idus F. Shahab
Wartawan senior Tempo