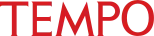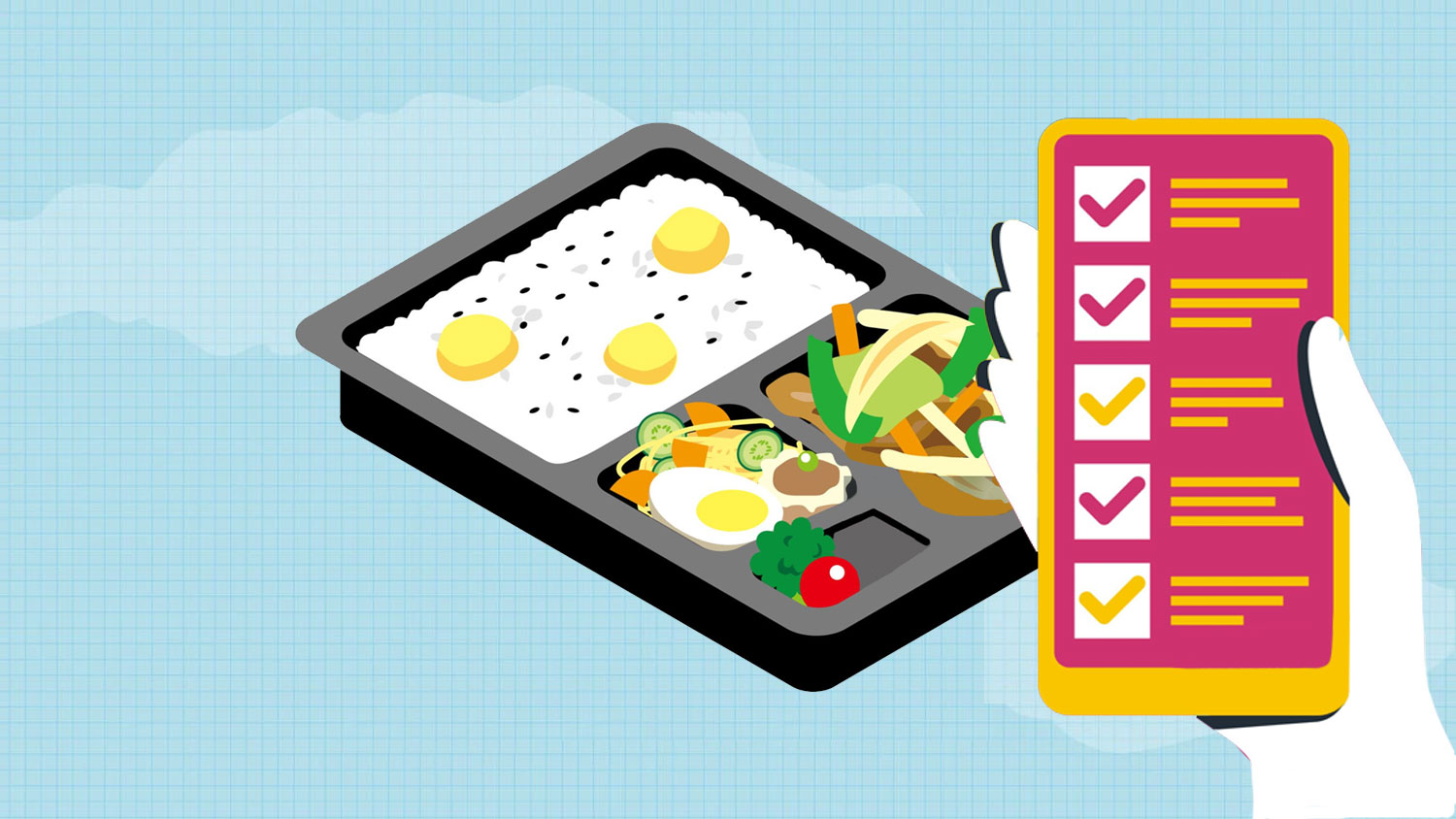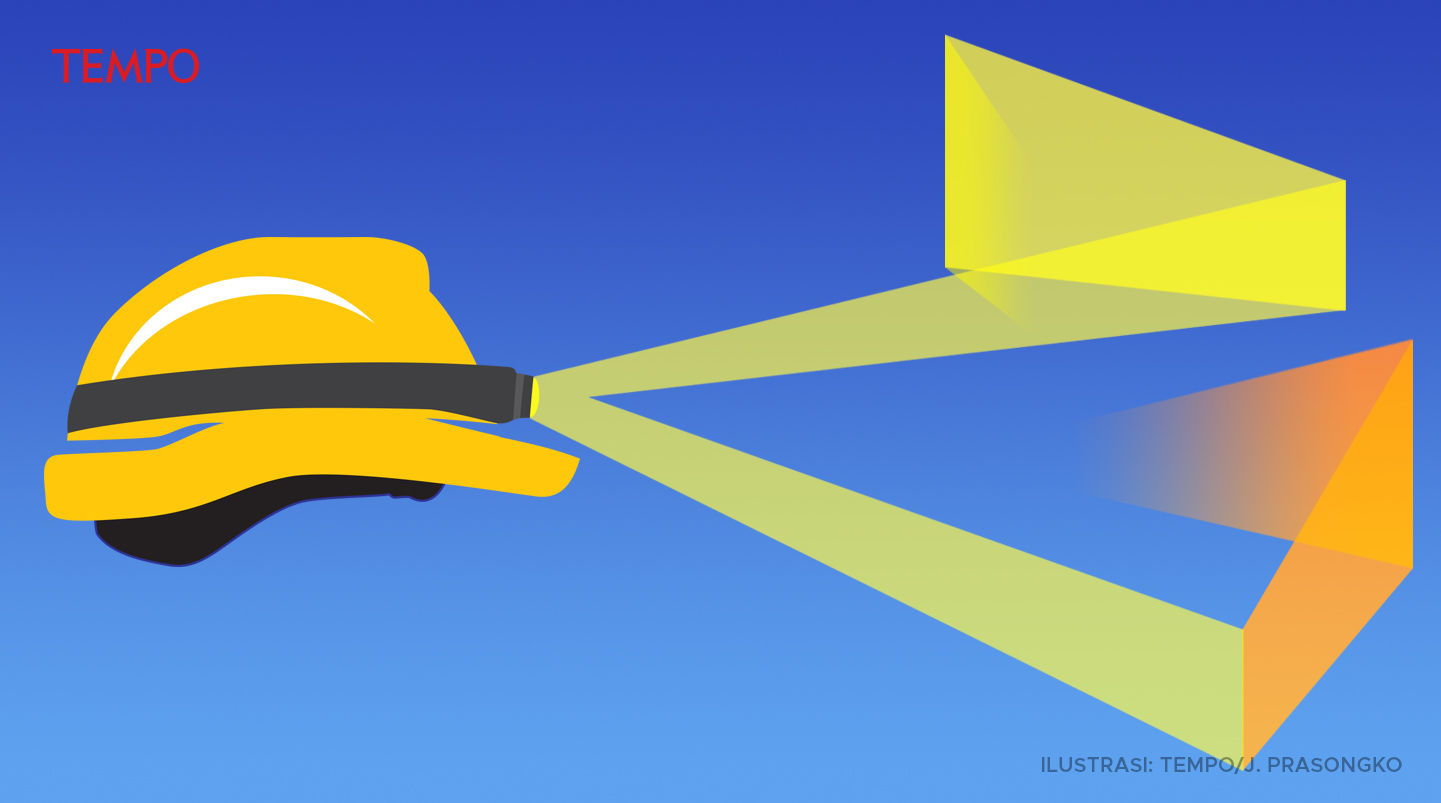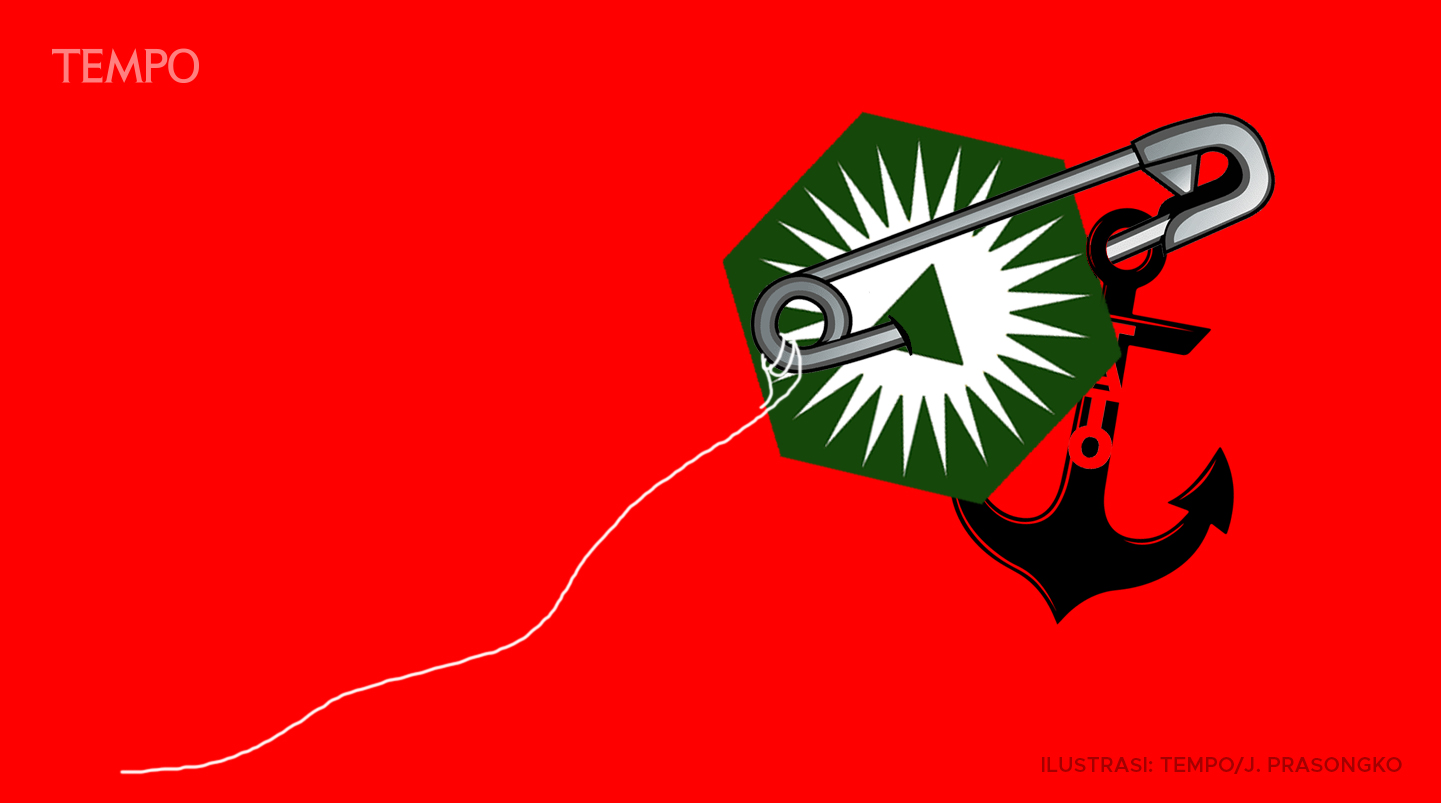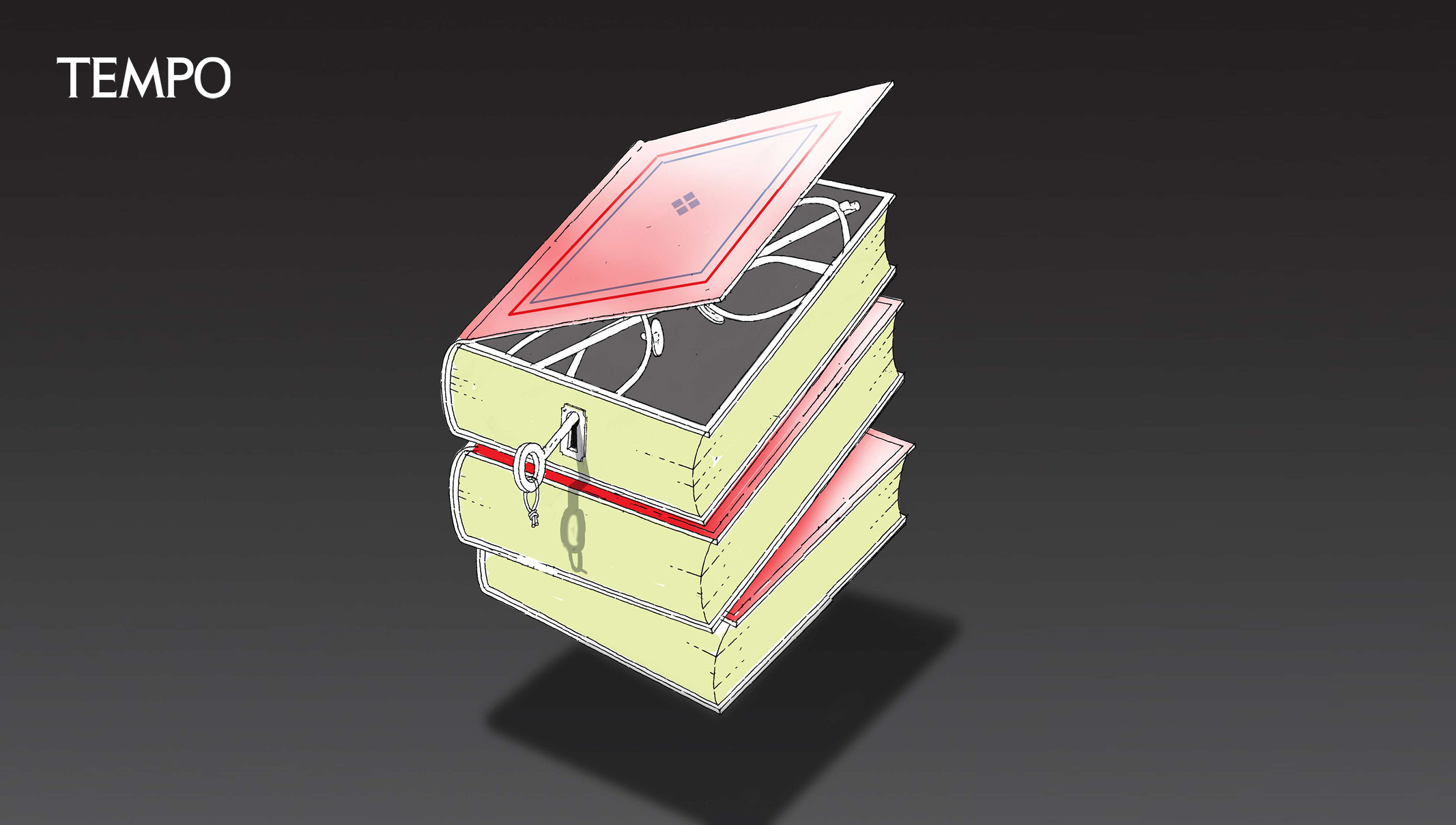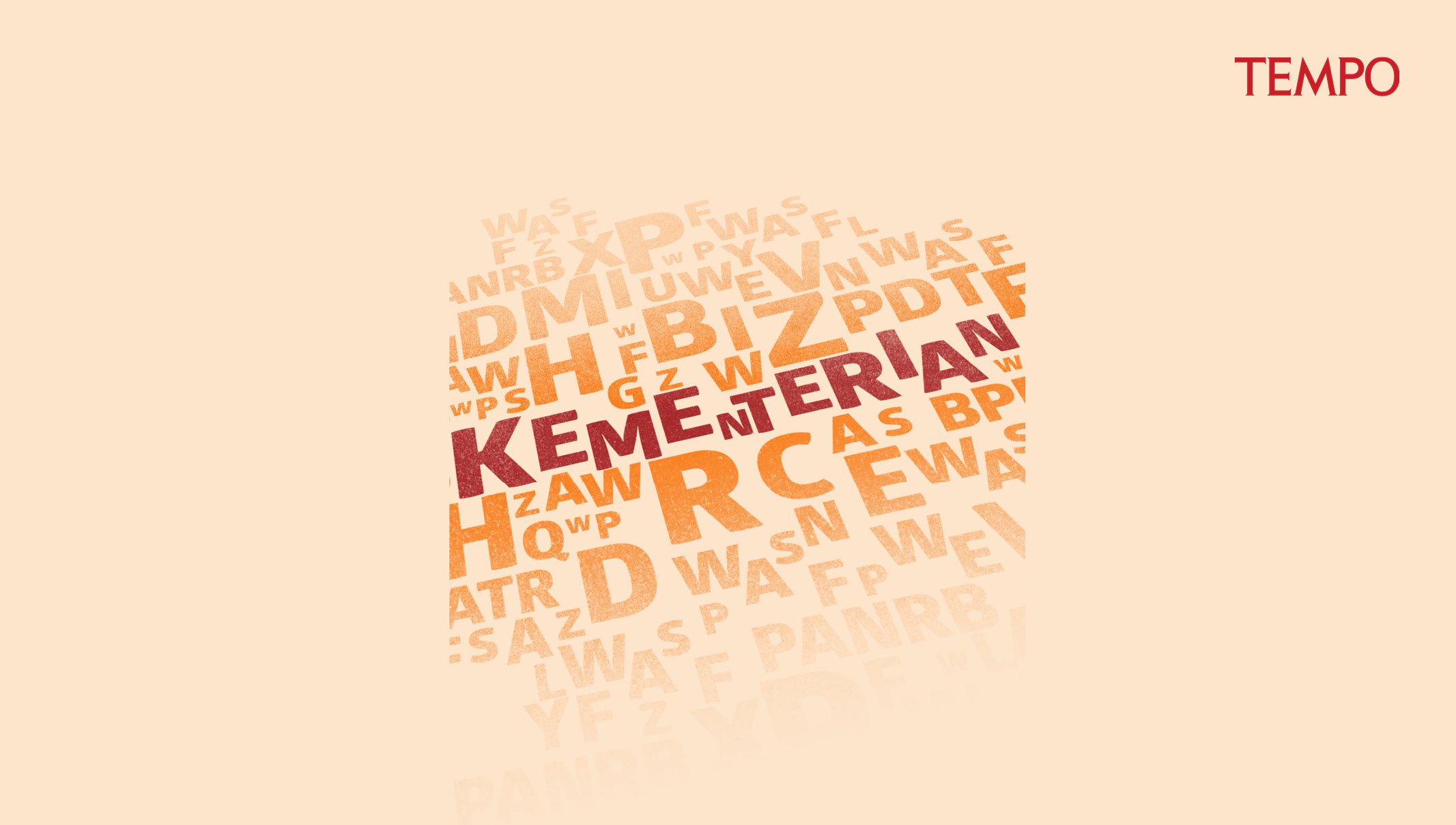Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

A. Ahsin Thohari
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Komisi Pemilihan Umum telah menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebesar 77,5 persen. Angka itu diyakini realistis untuk negara demokratis seperti Indonesia lantaran partisipasi pemilih dalam pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah hak asasi manusia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Partisipasi pemilih yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah partisipasi politik pemilih yang berkaitan dengan tingkat kehadiran pemilih di bilik suara dan secara sadar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya (voter turnout), atau sederhananya pemilih yang tidak golongan putih (golput).
Merespons suara-suara yang mengarah ke golput menjelang Pemilu 2019, kontra-narasi untuk melawannya dan ajakan untuk menggunakan hak pilih gencar dilakukan pelbagai pihak. Berkaca pada tren penurunan partisipasi pemilih pada pemilu era reformasi, kita patut membangun kewaskitaan.
Dalam pemilu pertama era reformasi pada 1999, partisipasi pemilih mencapai 92,6 persen dengan golput 7,3 persen. Namun angka fantastis ini mengalami koreksi dalam pemilu-pemilu berikutnya: 2004 (pemilihan legislatif 84,1 persen dengan golput 15,9 persen; pemilihan presiden putaran I 78,2 persen dengan golput 21,18 persen; dan pemilihan presiden putaran II 76,6 persen dengan golput 23,4 persen); 2009 (pemilihan legislatif 70,7 persen dengan golput 29,3 persen dan pemilihan presiden 71,7 persen dengan golput 28,3 persen); dan 2014 (pemilihan legislatif 75,2 persen dengan golput 24,8 persen dan pemilihan presiden 70,9 persen dengan golput 29,1 persen).
Tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu di negara demokratis tentu saja amat diinginkan, terutama oleh penyelenggara pemilu, sebagai afirmasi dan legitimasi atas sehatnya mekanisme aktualisasi kedaulatan rakyat yang berlandaskan partisipasi sadar dan aktif warga negara. Jadi, dia bukan hasil mobilisasi politik penguasa, yang tak jarang diiringi intimidasi dan persekusi, seperti sering terjadi dalam pemilu-pemilu yang digelar oleh rezim tiran di negara-negara otoriter.
Sebaliknya, rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu acap berasosiasi dengan kekecewaan atas kondisi masa lalu yang terhubung dan berlanjut dengan kondisi masa kini atau malah ketidakpedulian terhadap kelangsungan masa depan negara. Memang ada saat ketika institusi demokrasi mengalami keletihan manakala pemilu banyak digelar tapi tidak memandu perubahan-perubahan lanjutan yang diinginkan pemilih dan memicu apatisme politik. Inilah kondisi yang menyebabkan terjadinya kepenatan pemilih (voter fatigue) karena yang terbayang di benak pemilih adalah demokrasi sekadar siklus elektoral, metode ajek sirkulasi elite, serta statistik perolehan suara dan distribusi kursi yang kering makna bagi problem-problem nyata yang dihadapi dalam hidupnya.
Maka, bagi pemilih seperti ini, pemilu telah kehilangan jangkar epistemologinya sebagai penjamin tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa. Pemilih seperti inilah yang, di beberapa negara demokratis, menjadi penyumbang besar atas rendahnya partisipasi pemilih. Jika gagal mengantisipasinya dengan baik, kita juga akan terjerembap menjadi negara demokrasi dengan tingkat partisipasi kurang dari setengah pemilih yang memenuhi syarat (eligible voter).
Beberapa negara mengantisipasi fenomena rendahnya angka partisipasi pemilih dengan mewajibkan warga negaranya yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan konsekuensi sanksi tertentu jika abai (compulsory voting). Pada 1893, Belgia tercatat menjadi negara pertama di era modern yang menerapkan kewajiban berpartisipasi dalam pemilu bagi laki-laki dan baru pada 1948 berlaku juga bagi perempuan. Langkah Belgia ini diikuti beberapa negara, seperti Argentina pada 1912, Australia (1915), dan Ekuador (1936).
Selain mendongkrak angka partisipasi pemilih, compulsory voting dinilai menjadi instrumen cergas untuk mengadang apatisme politik, meminimalkan biaya kampanye, serta menghasilkan pemerintahan dengan stabilitas, legitimasi, dan mandat yang lebih baik. Meskipun demikian, pihak yang menentang gagasan ini berpendapat bahwa kewajiban memilih adalah ancaman kebebasan individu dan tidak memilih adalah sikap politik juga.
Saat ini partisipasi pemilu kita masih relatif aman bagi kelangsungan demokrasi yang masih terus tumbuh. Kita mungkin tidak perlu sampai pada kesimpulan menerapkan compulsory voting di masa mendatang sekiranya target tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen terpenuhi. Dengan sosialisasi yang maksimal serta administrasi penggunaan hak pilih yang relatif mudah dan difasilitasi dengan baik, kita percaya prospek partisipasi pemilih akan meningkat.