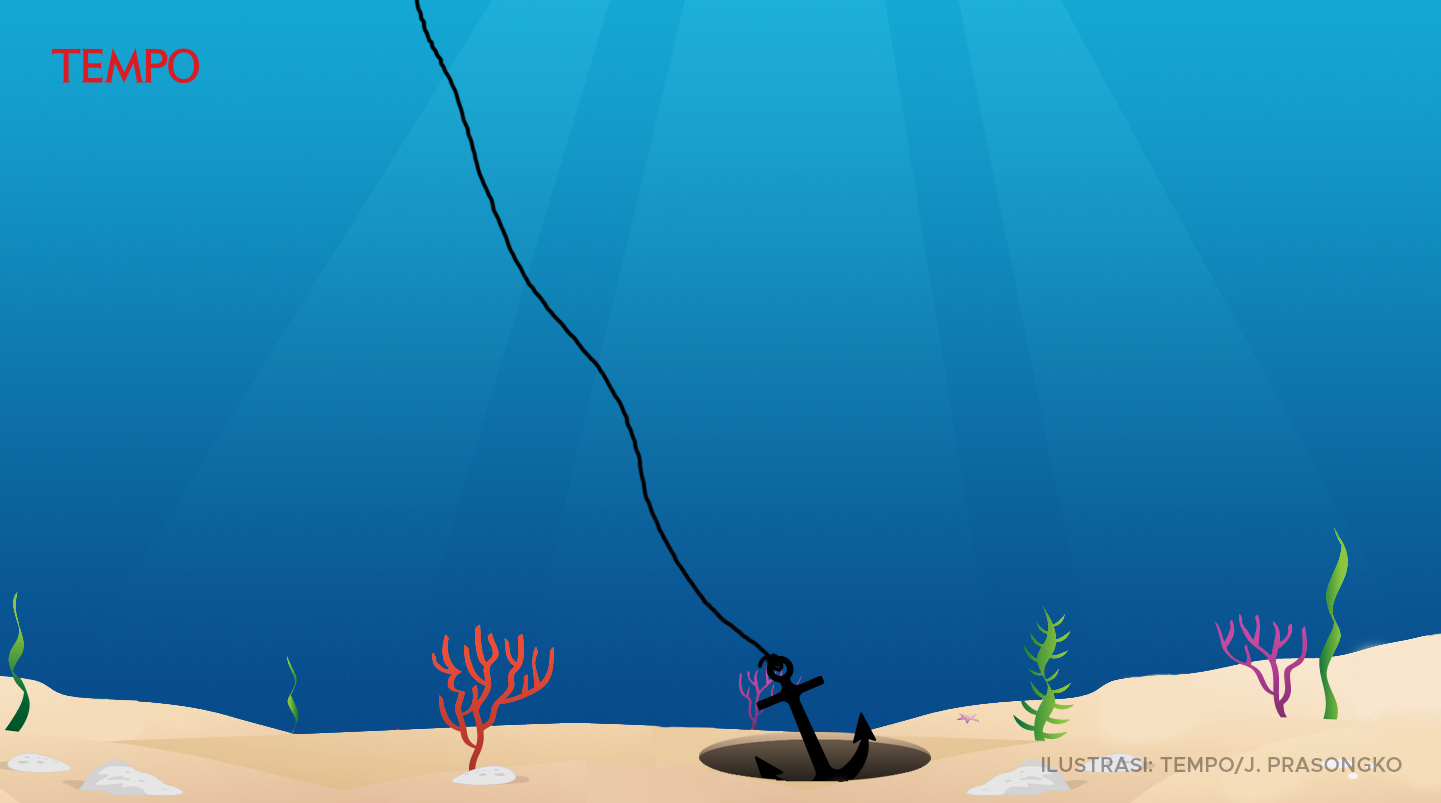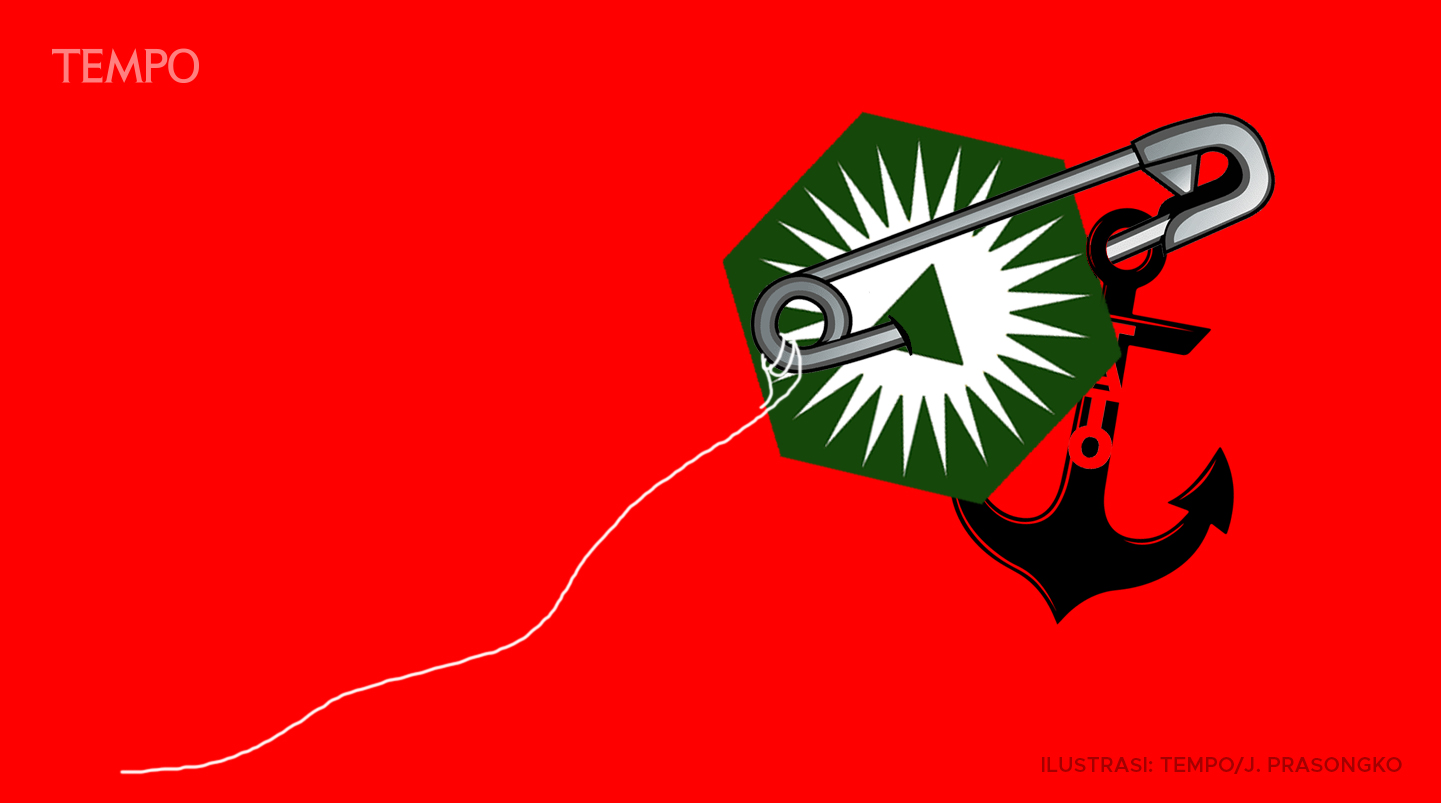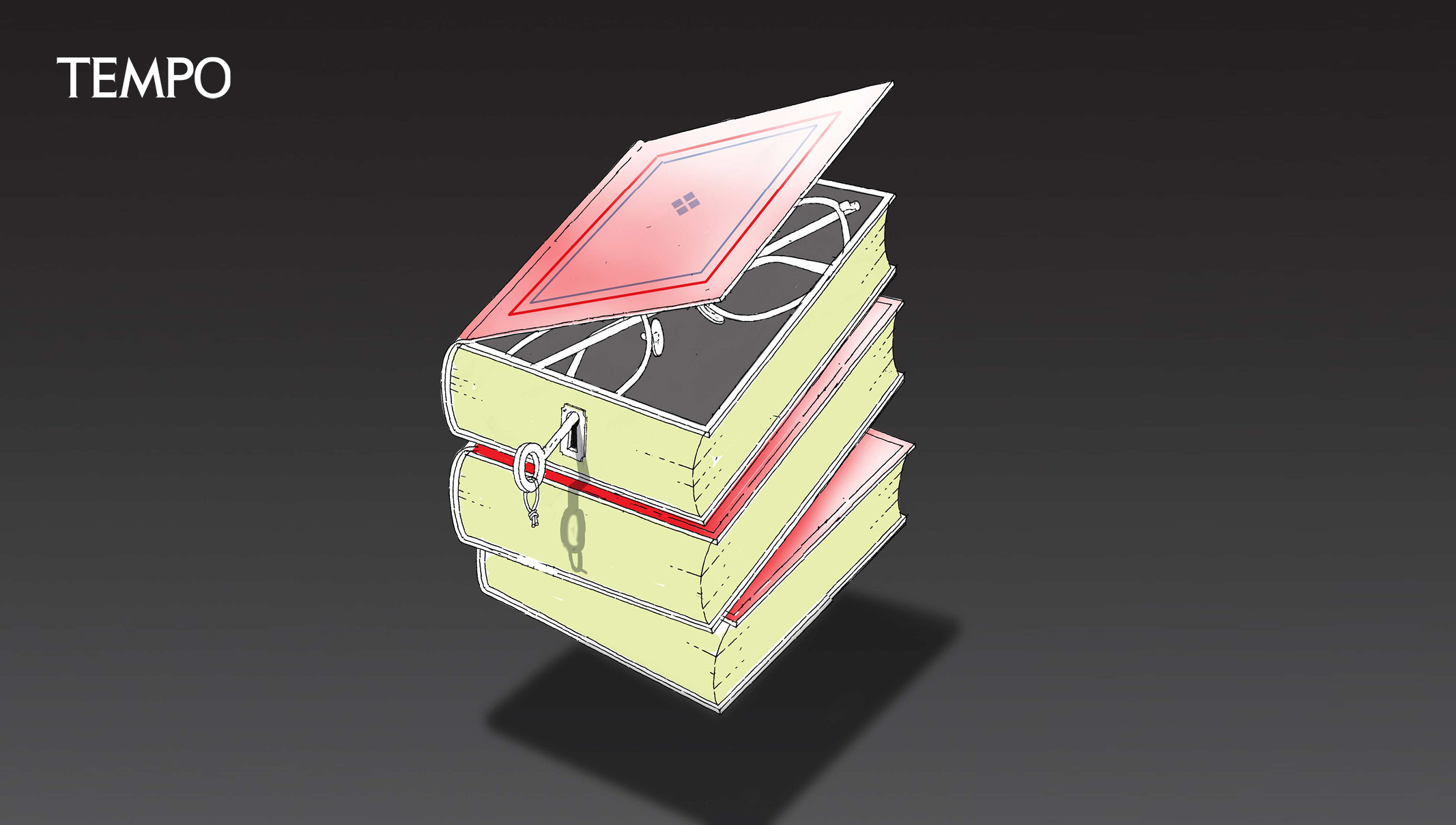Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BULAN suci Ramadan yang baru saja berlalu diwarnai sebuah fenomena sosial unik yang muncul dari "gurauan" di dunia maya: war takjil. Melalui ribuan konten yang berseliweran di berbagai platform media sosial, kita menyaksikan aneka menu khas berbuka puasa, seperti gorengan, kolak, dan jajanan lain, ikut diburu oleh mereka yang bukan umat Islam.
Kolom Hijau merupakan kolaborasi Tempo dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan. Kolom Hijau terbit setiap pekan.