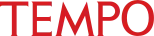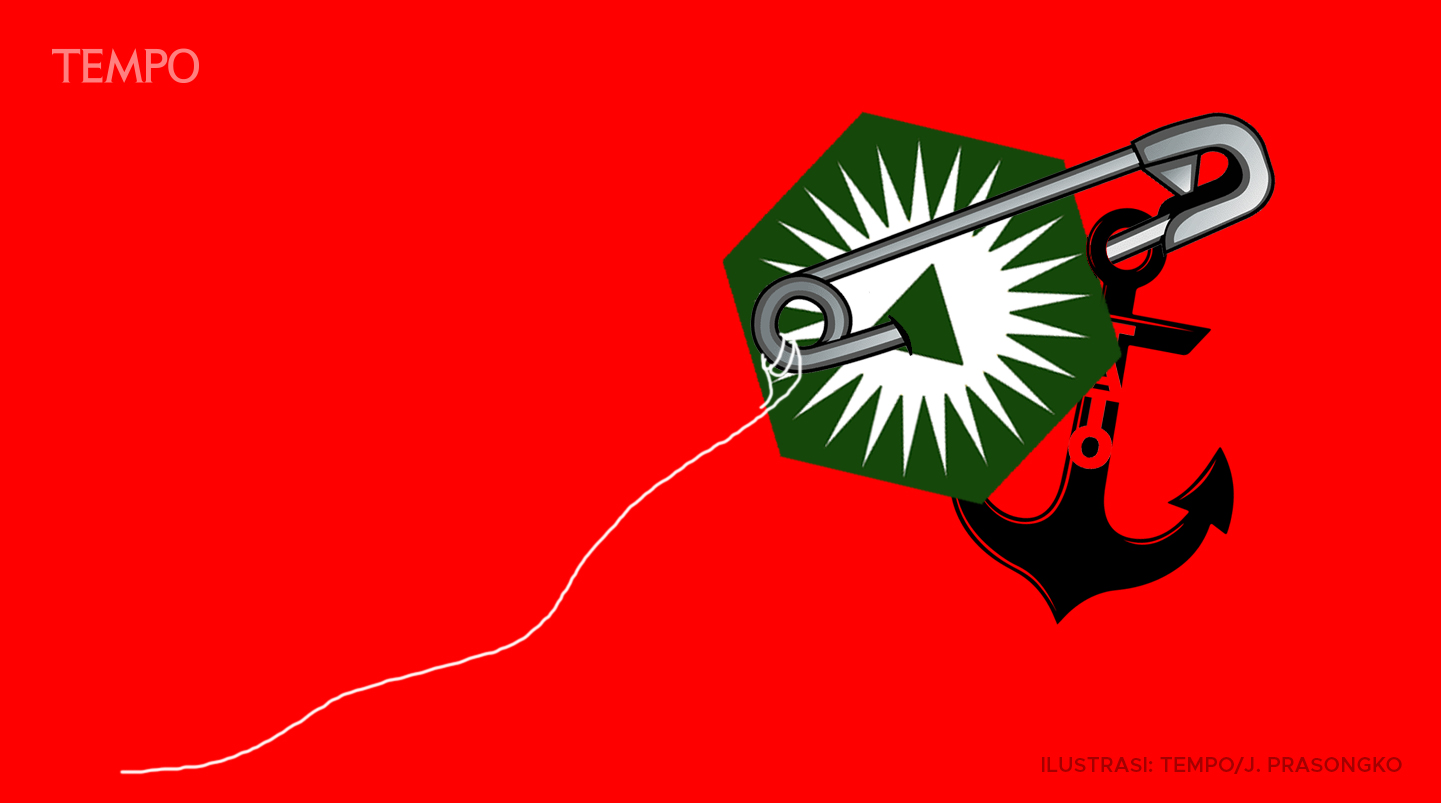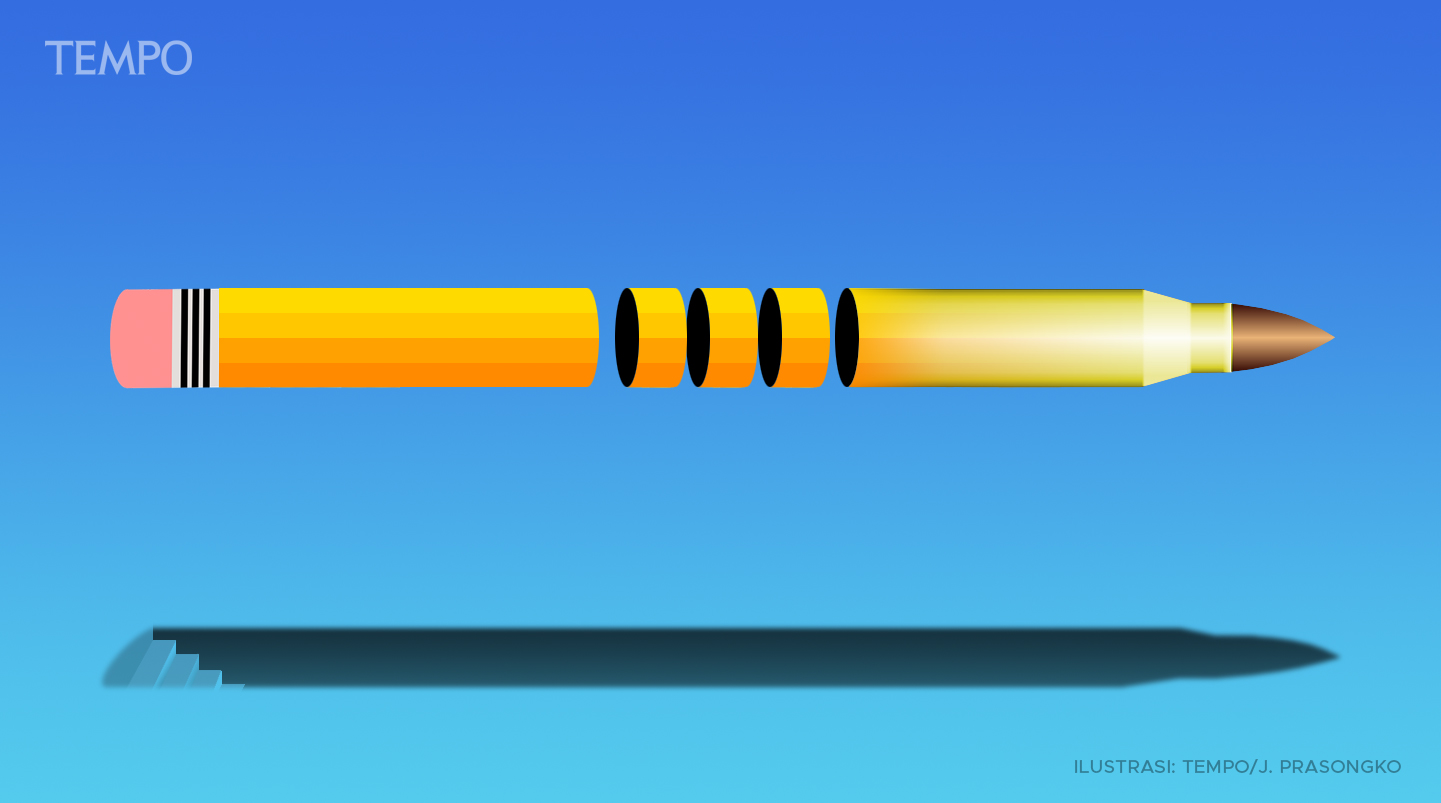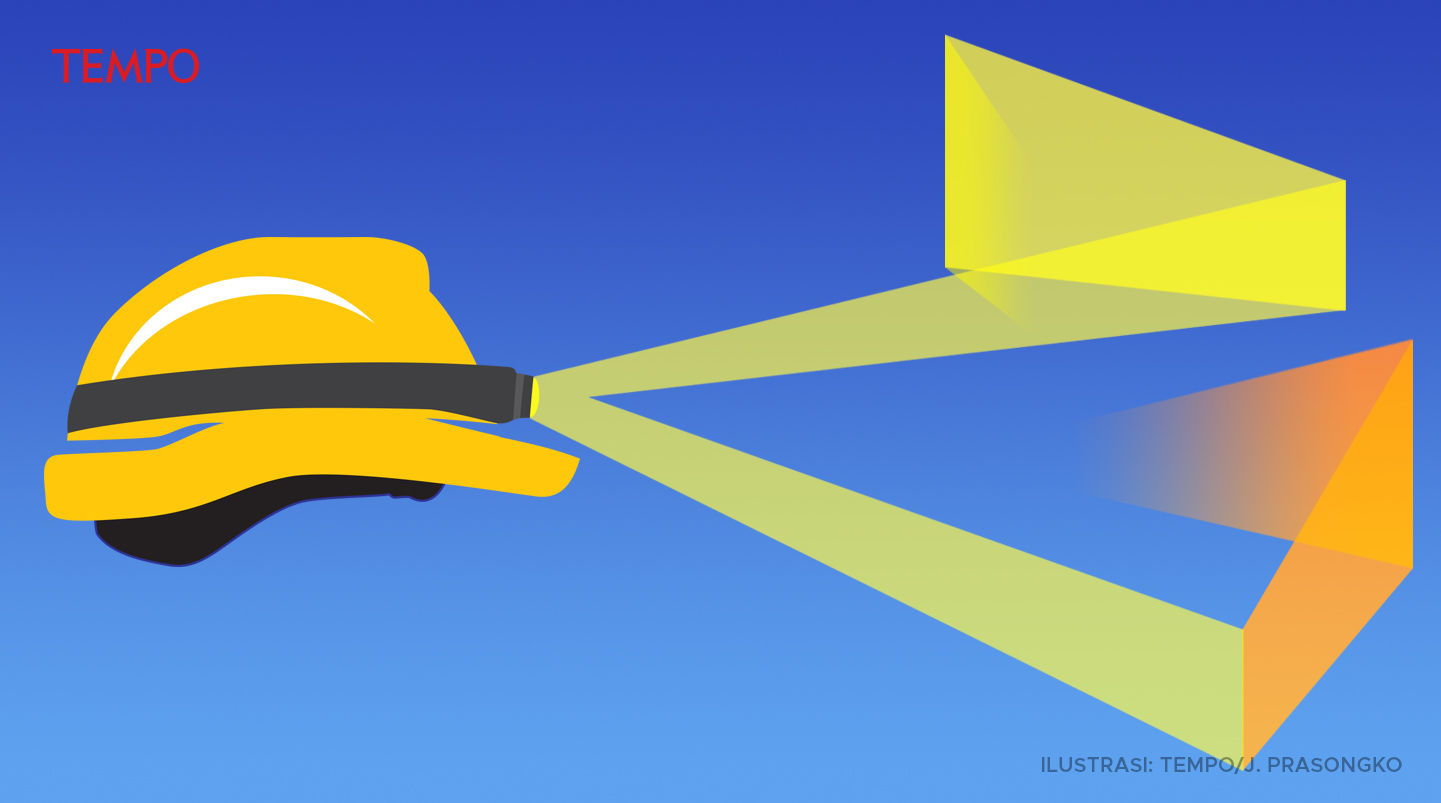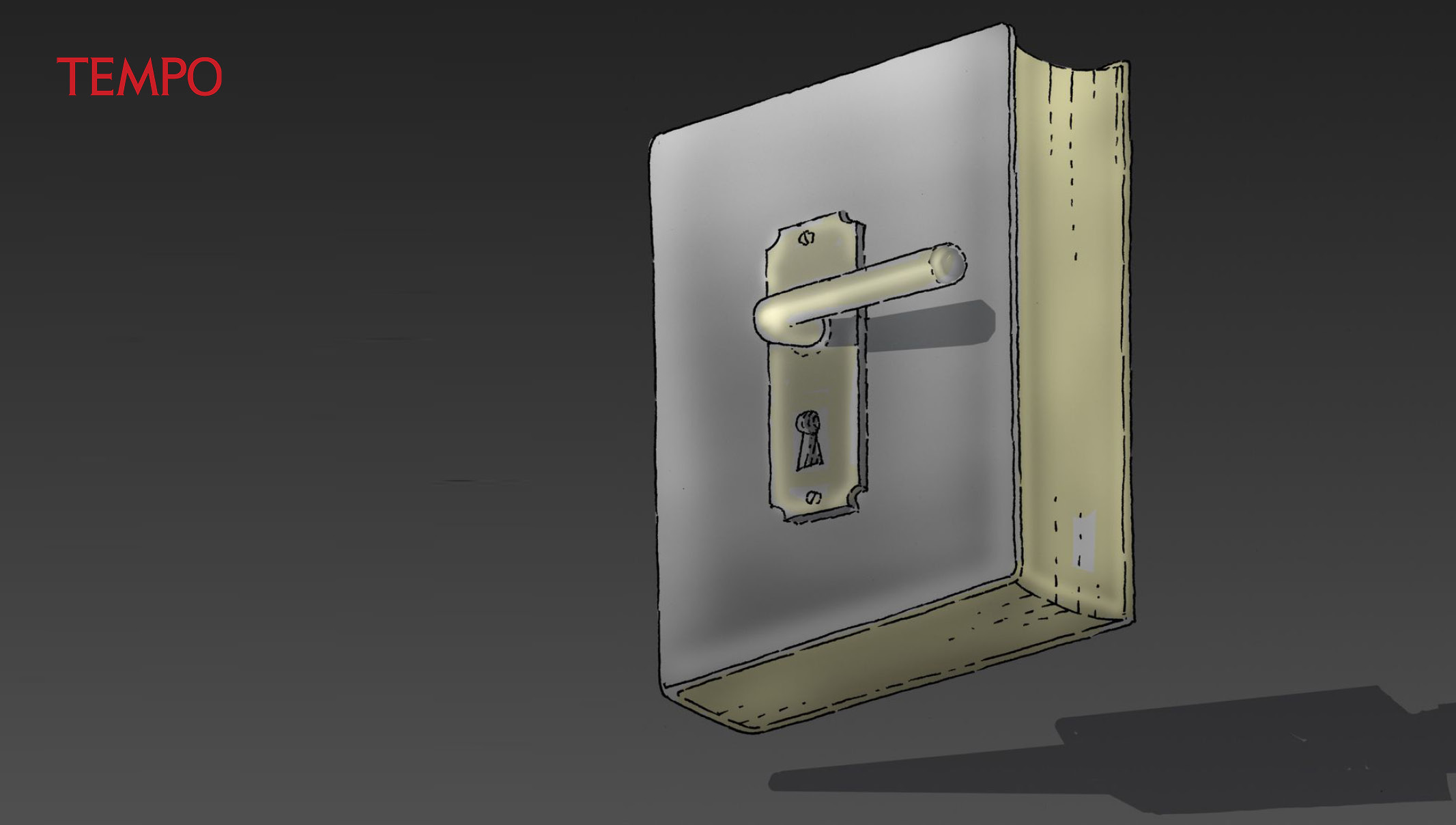Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Anggi Afriansyah
Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air agar lebih merata. Presiden juga meminta peninjauan dan penyesuaian kurikulum besar-besaran karena cepatnya perubahan zaman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Keinginan Presiden untuk menggunakan teknologi dan menyesuaikan kurikulum tentu patut didukung karena zaman memang berubah. Apa yang disampaikan Presiden juga sesuai dengan amanat Pasal 36 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang salah satu poinnya adalah kurikulum harus disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja dan dinamika perkembangan global.
Namun kedua hal tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek. Pertama, pemanfaatan teknologi perlu ditopang oleh infrastruktur yang memadai, seperti kelengkapan listrik dan Internet. Kedua, kurikulum secanggih apa pun tidak akan berjalan jika tidak ditopang oleh para guru yang mampu menyebarluaskannya di ruang kelas secara optimal.
Dua aspek tersebut akan berjalan jika beban pendidikan tidak hanya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan, tapi juga melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan elemen masyarakat sipil. Teknologi, misalnya, akan berjalan jika akses listrik dan Internetnya memadai. Kementerian Pendidikan harus bergotong-royong dengan lembaga lain agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilakukan.
Untuk aspek pertama, belum semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur listrik dan Internet yang memadai. Jadi, kedua infrastruktur tersebut harus dipenuhi lebih dulu.
Misalnya, ketika saya melakukan penelitian di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, mudah sekali menemukan sekolah-sekolah yang mendapat bantuan komputer dari pemerintah. Namun komputer tersebut tidak dapat digunakan anak-anak secara optimal karena akses listrik tidak memadai. Mereka mengandalkan panel tenaga surya yang sangat bergantung pada cuaca dan genset yang menggunakan solar. Untuk membeli solar, mereka harus pergi ke kota dengan jarak tempuh yang jauh, tidak mudah, dan biaya transportasi yang mahal. Akhirnya, komputer tersebut mangkrak.
Di sisi lain, habituasi pemanfaatan teknologi menjadi penting. Jangan sampai anak-anak menjadi gegar budaya karena mereka belum terbiasa menghadapi arus informasi yang begitu masif. Dalam beberapa kasus, ketika daerah mendapat aliran listrik, ternyata tidak dimanfaatkan untuk belajar, tapi menonton televisi.
Aspek kedua juga menjadi fundamen penting, yakni penguatan kapasitas guru melalui berbagai cara, seperti pelatihan dan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik. Seusai reformasi, partisipasi guru untuk mengikuti pelatihan memang lebih terbuka. Berbagai beasiswa untuk peningkatan kapasitas dan kualifikasi guru pun diberikan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun demikian, menurut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, rata-rata uji kompetensi guru (UKG) masih di bawah 70 (TK: 68,23; SD: 62,22; SMP: 67,76; dan SMA: 69,55), kecuali untuk guru SLB (71,70).
Guru adalah garda terdepan yang akan mengimplementasikan kurikulum tersebut di ruang-ruang pendidikan di seluruh Indonesia. Lagi-lagi, kita mengetahui betapa beragamnya negeri ini, juga kondisi gurunya. Kurikulum secanggih apa pun akan tumpul jika guru-guru tidak dapat memahami apa yang diinginkan dari kurikulum tersebut.
Pengembangan kurikulum perlu juga memperhatikan potensi daerah, kondisi satuan pendidikan, dan peserta didiknya yang berprinsip pada diversifikasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah amanat undang-undang itu bahwa pendidikan harus dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, serta menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa.
Meskipun setelah reformasi kurikulum yang "bias" Pulau Jawa sudah jauh berkurang, guru-guru di daerah masih mengeluhkan kurikulum yang diproduksi oleh pemerintah. Jadi, meskipun kurikulum berubah, ternyata materi, pola, dan metode pembelajaran di sekolah tidak berubah.
Di sisi lain, kurikulum yang dibuat, karena tidak memperhatikan lokalitas atau kondisi sosioekonomi setempat, ternyata hanya menjadikan pendidikan sebagai reproduksi sosialseperti yang dinyatakan oleh Bourdieu dan Passeron (1977)yang menguntungkan kelas sosial ekonomi tertentu karena mereka memiliki privilege dalam berbagai hal.
Kondisi tersebut membuat anak-anak yang tidak beruntungkarena tidak memiliki guru yang kompeten dan perangkat pembelajaran yang memadaisemakin tertinggal. Mereka akan merasa sekolah tidak relevan bagi mereka dan akhirnya menurunkan semangat atau motivasi untuk sukses.
Pada akhirnya, mempersiapkan anak-anak dan meningkatkan kapasitasnya tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan semata. Gotong-royong menjadi kunci dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Salah satu penyebab tidak berjalannya berbagai kebijakan pendidikan hingga saat ini adalah kurangnya gotong-royong lintas sektor untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Padahal pada pendidikanlah berbagai mimpi disematkan. Berbagai ikhtiar untuk memperbaiki pendidikan perlu dilakukan sepenuh hati.