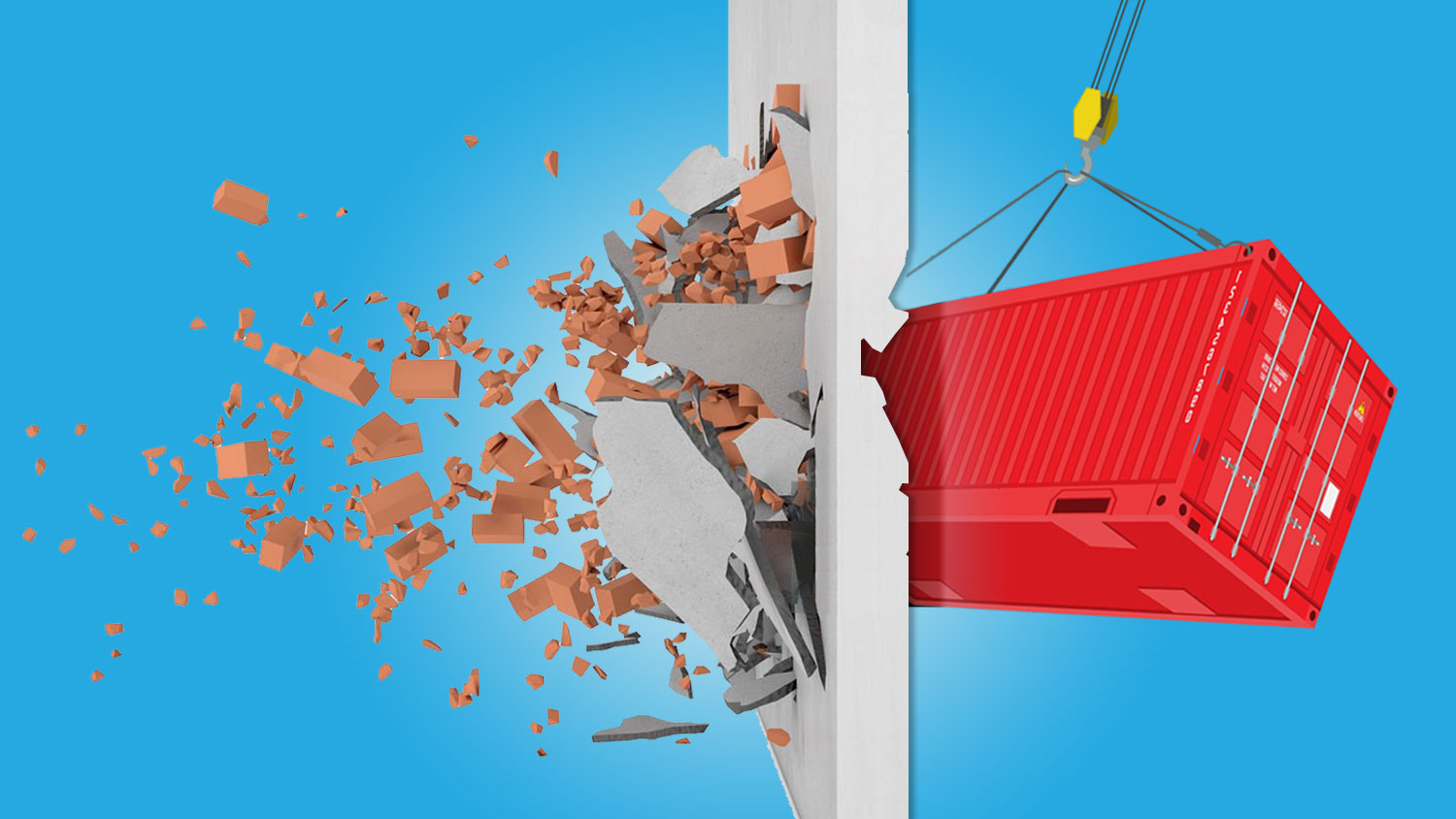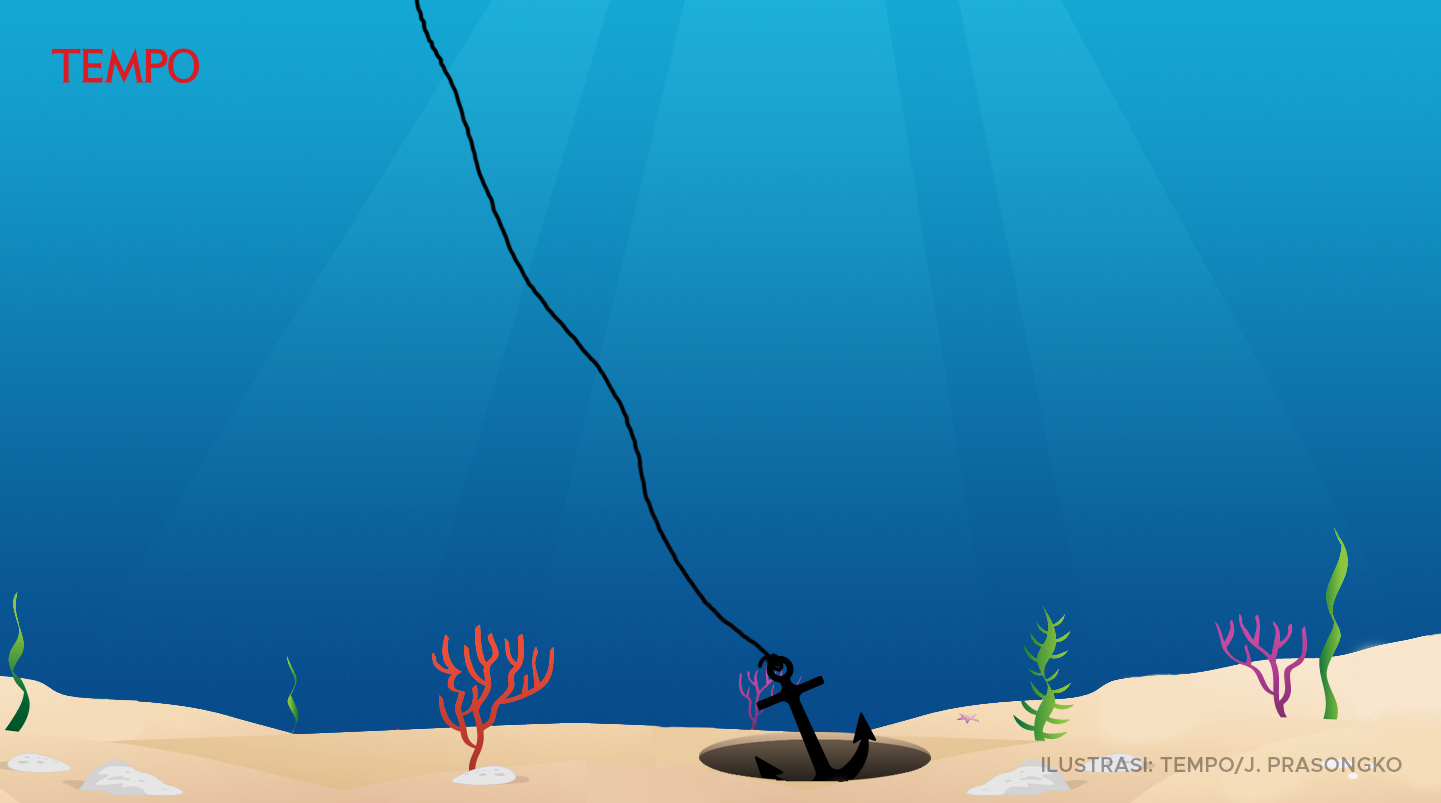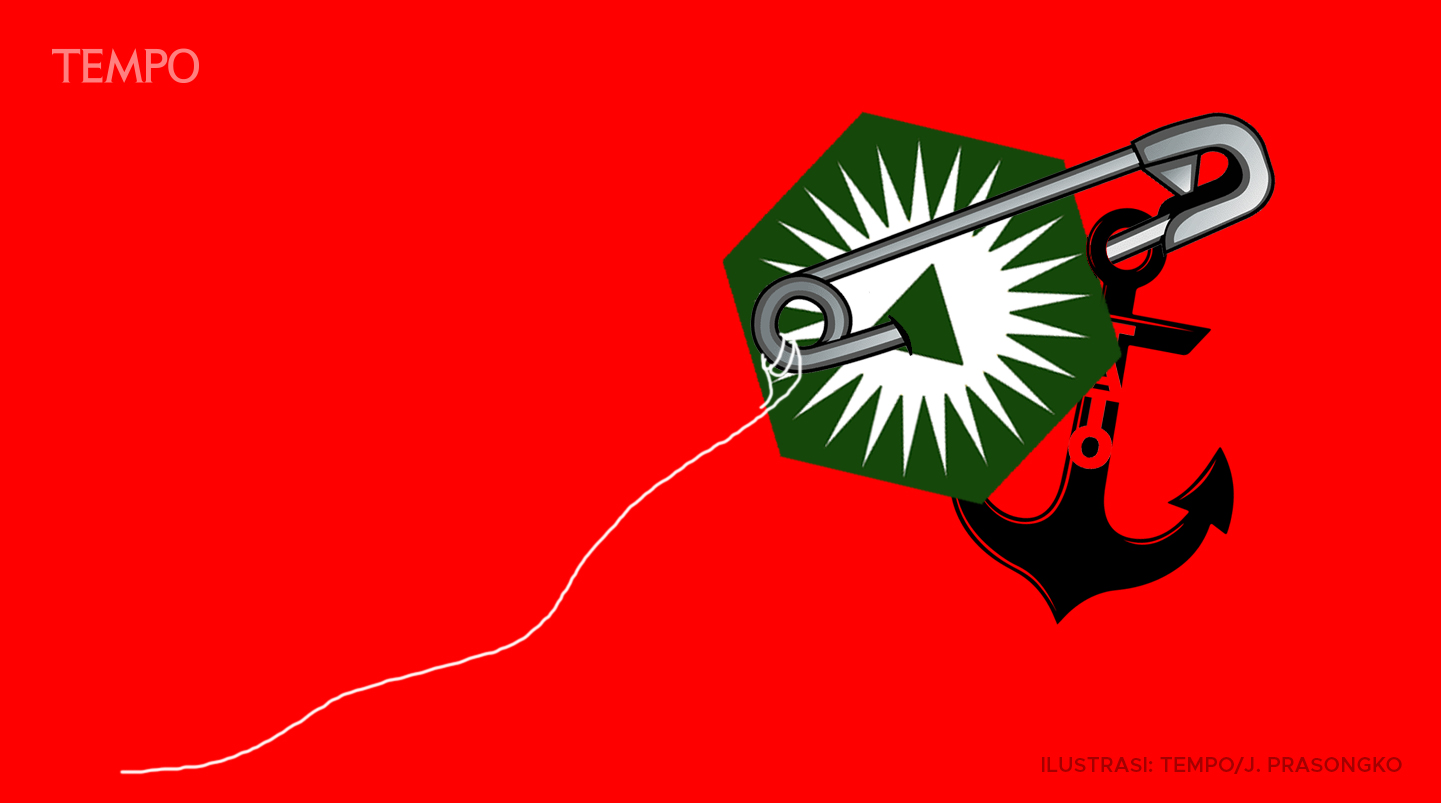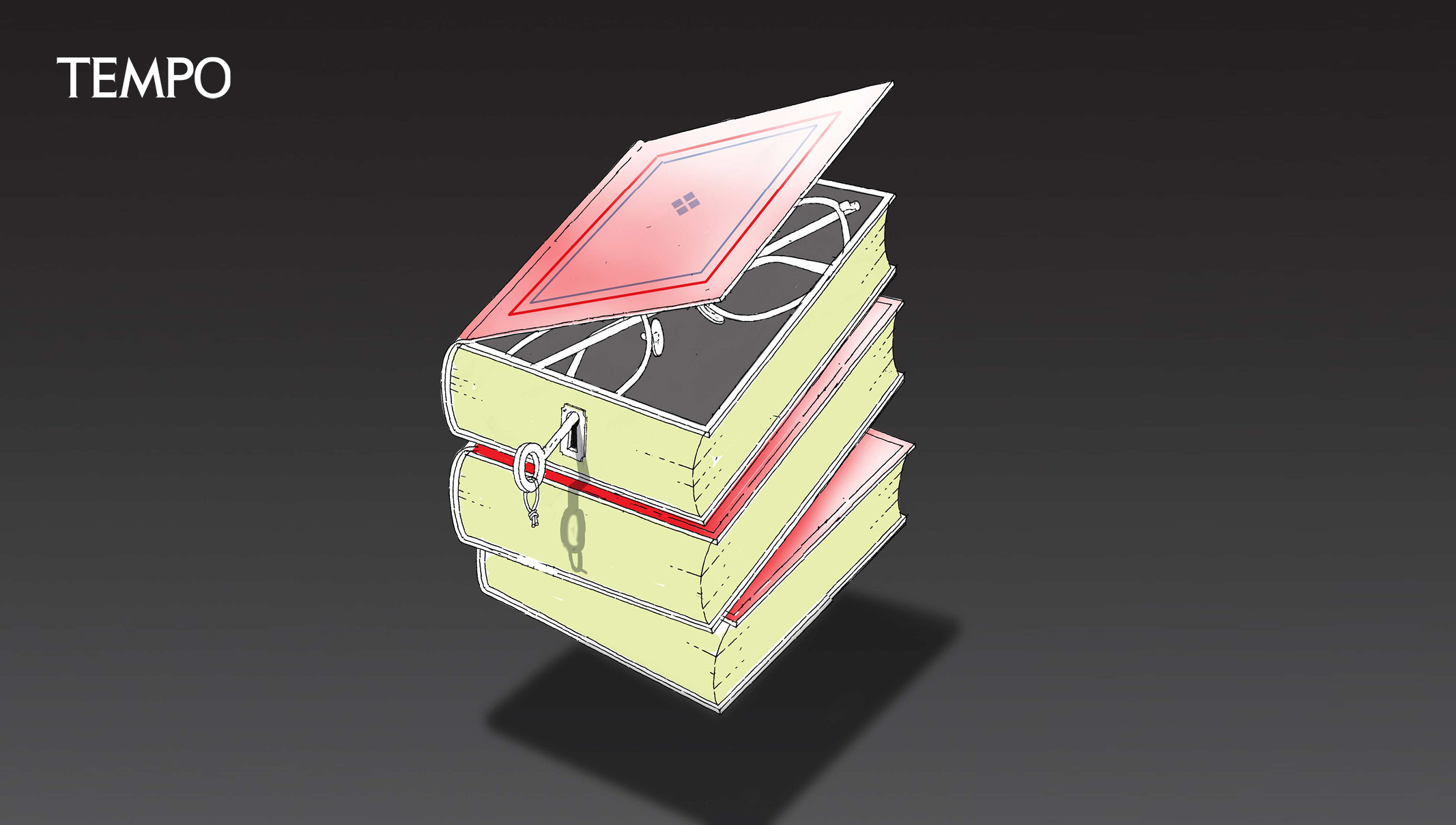Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Siapa yang memimpin para pemberontak yang menggedor Tripoli? Siapa yang mengomando ribuan orang yang menjatuhkan Mubarak dari Lapangan Tahrir di Mesir, mengerahkan ribuan orang yang memprotes di Puerta del Sol di Spanyol, dan mengarahkan demonstran yang menuntut demokrasi di jalanan kota Hamas di Suriah?
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo