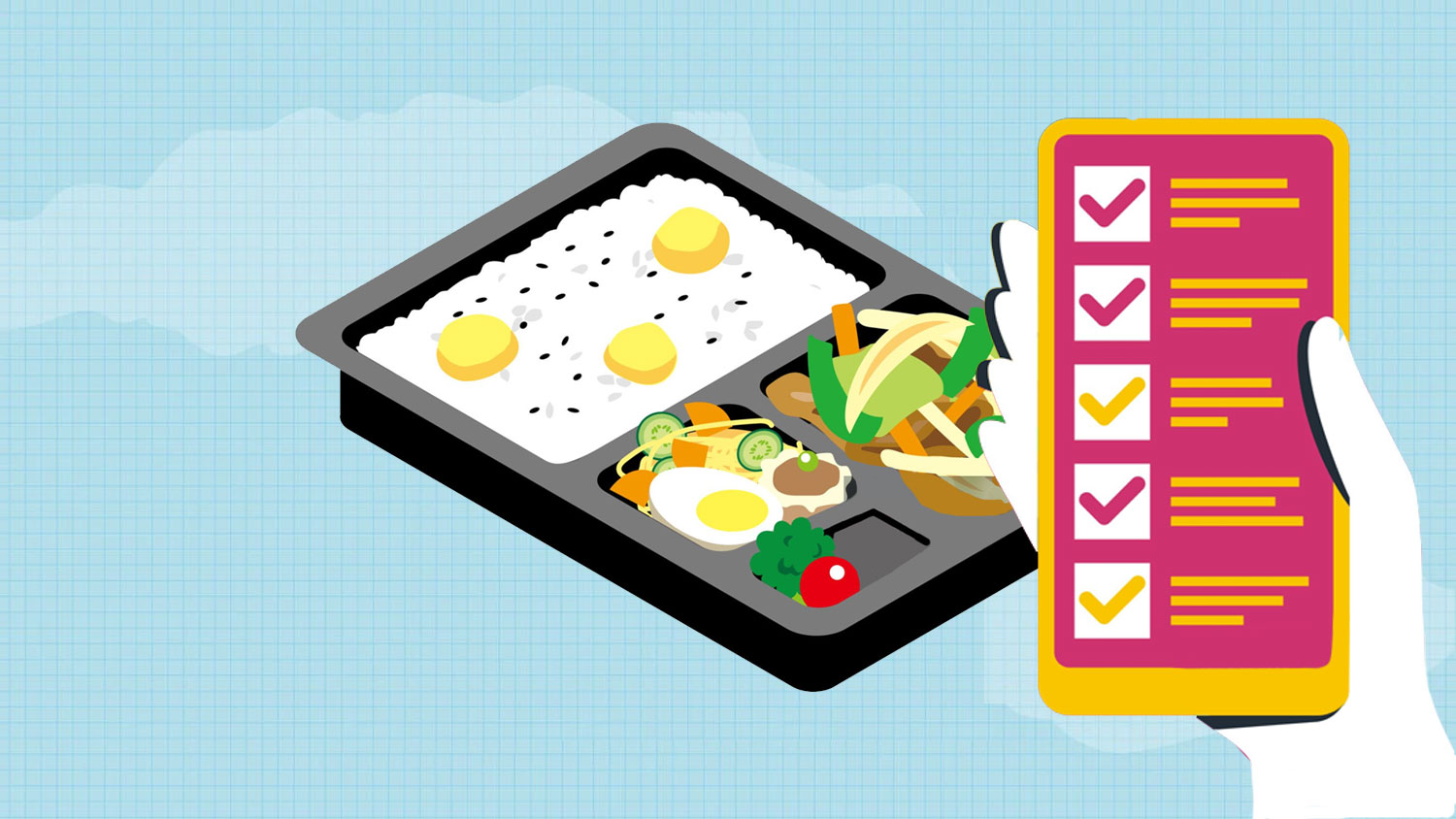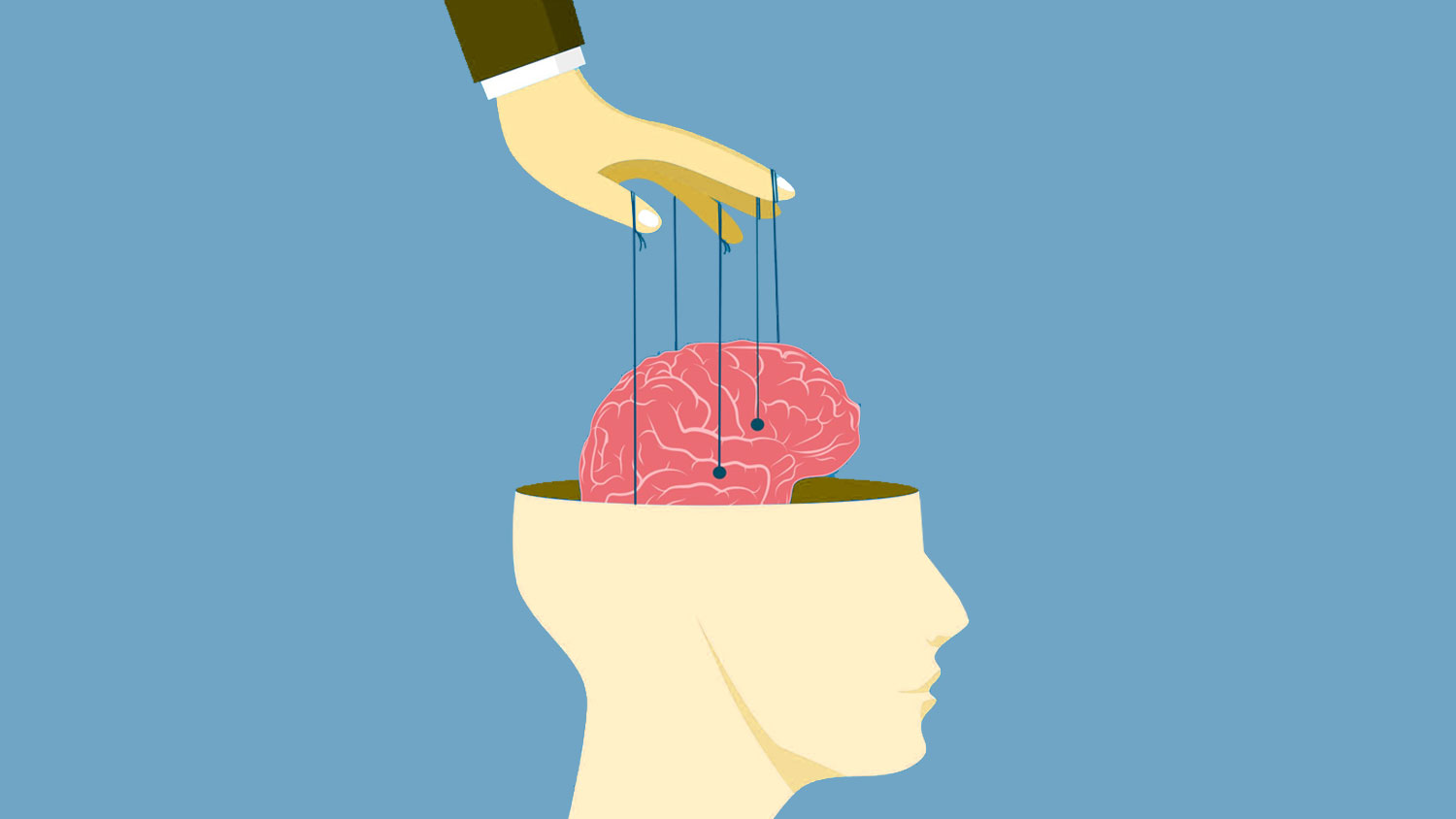Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

DALAM sebuah argumen, dilema dengan mudah kita kenali lewat konsekuensinya. Dilema menyudutkan seseorang untuk menegaskan setidaknya satu dari dua posisi, yang keduanya tidak diinginkan atau memberatkan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Politisasi Dilema"