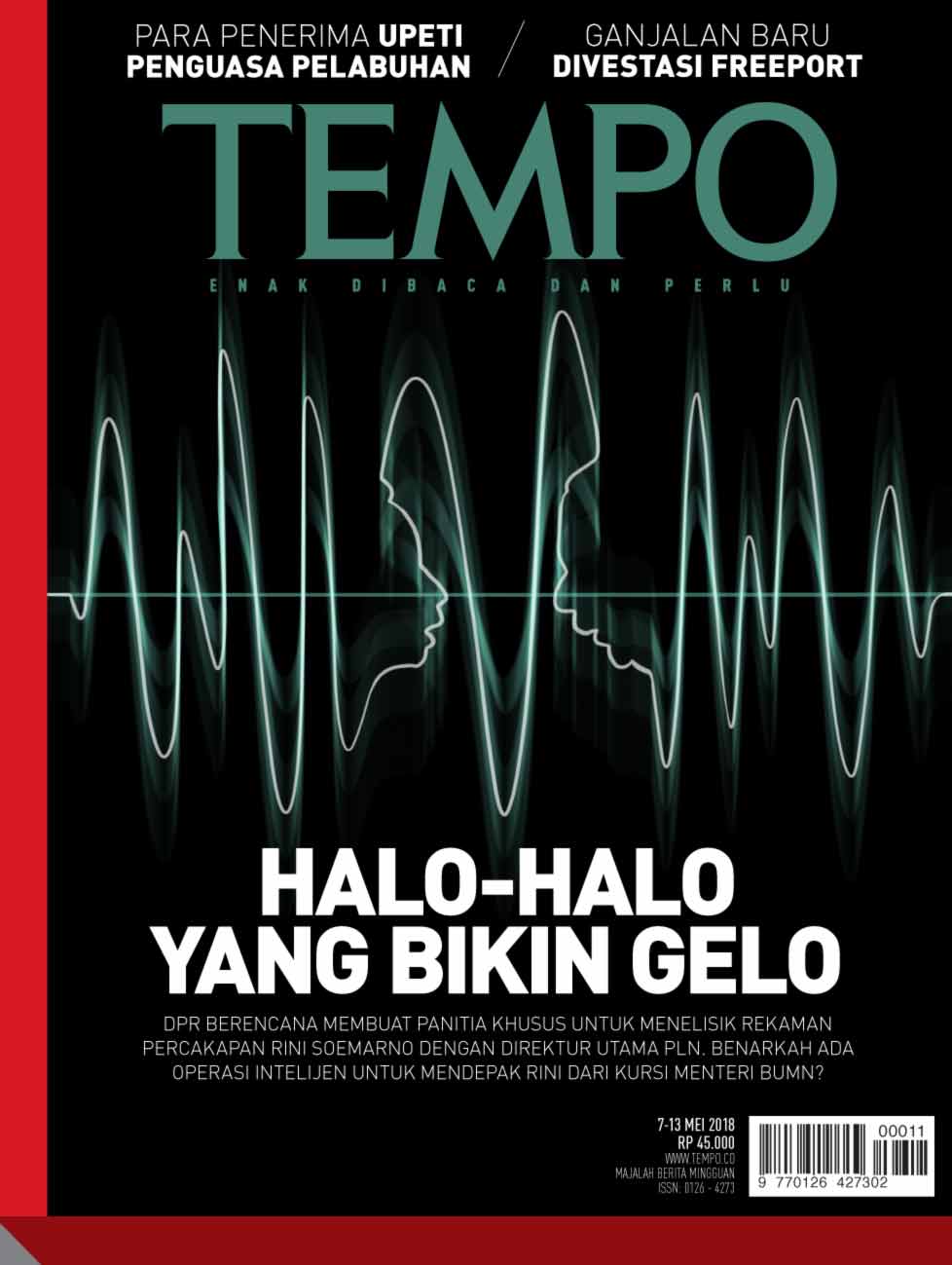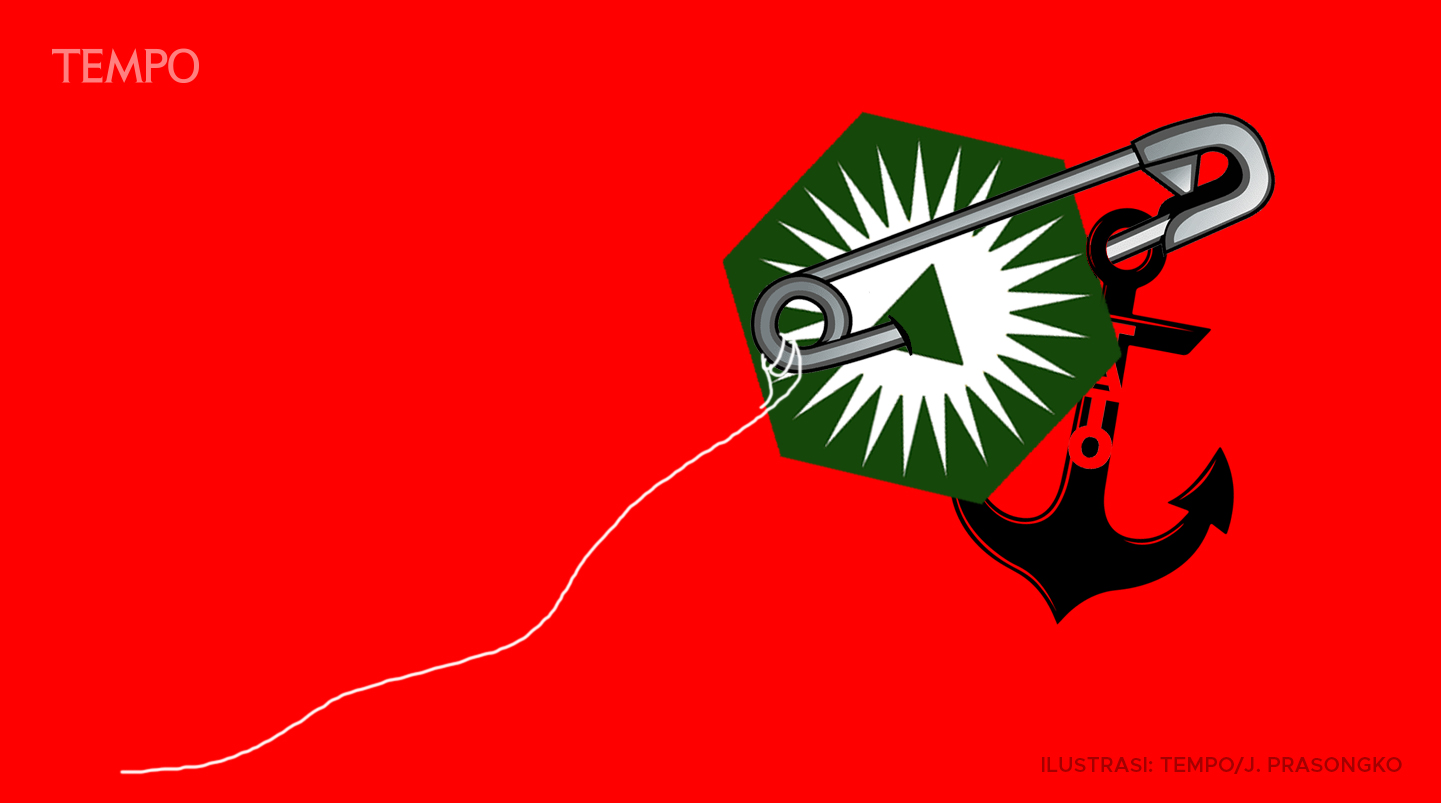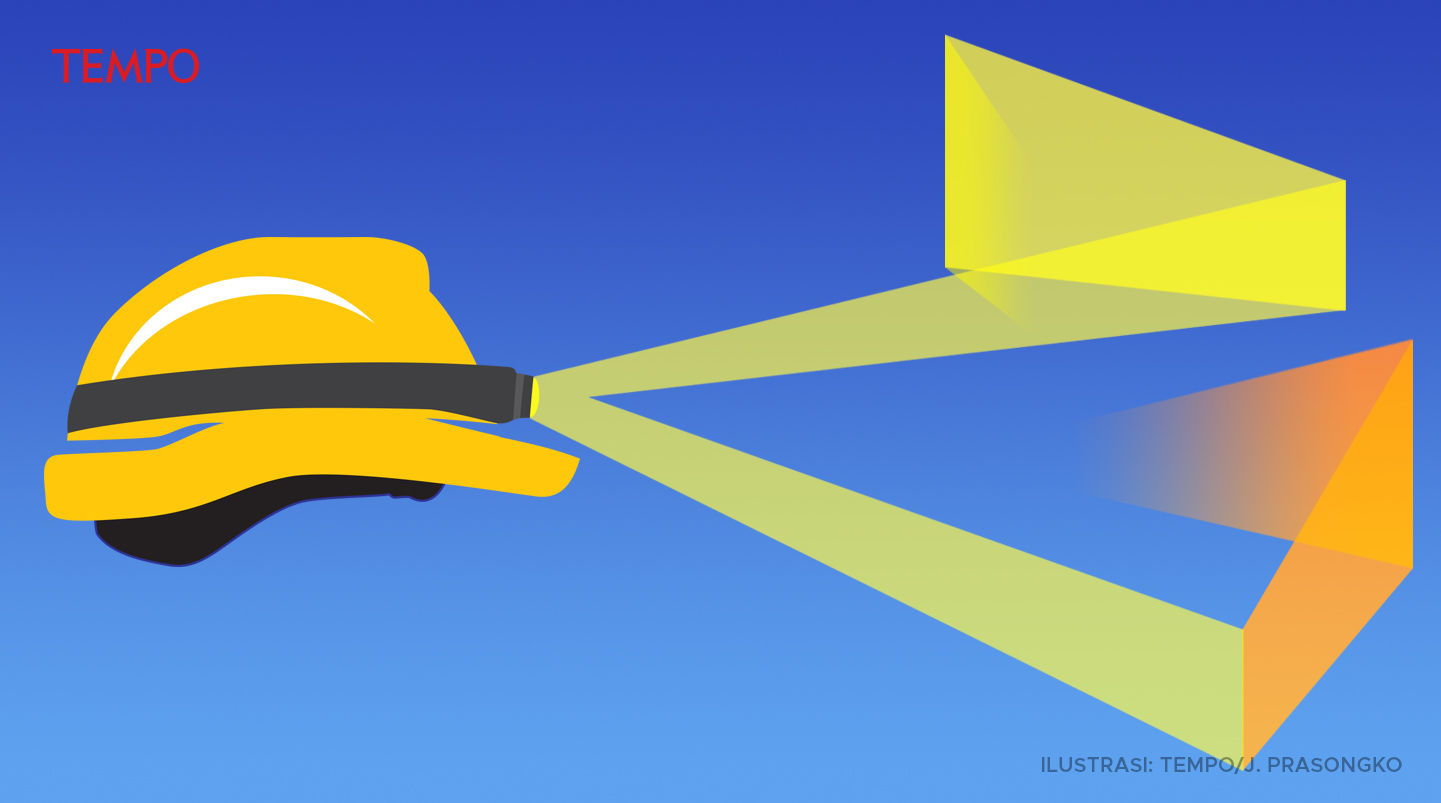Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

PERTEMUAN musim semi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dua minggu lalu di Washington, Amerika Serikat, datang dengan pesan: ketidakpastian ekonomi global masih tinggi akibat potensi perang dagang. Selain itu, ada pertanda bahwa inflasi mulai meningkat. The Fed mungkin harus menaikkan bunga lebih cepat. Ini disebabkan juga oleh meningkatnya defisit anggaran di Amerika Serikat akibat kebijakan pemotongan pajak oleh pemerintah Donald Trump.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo