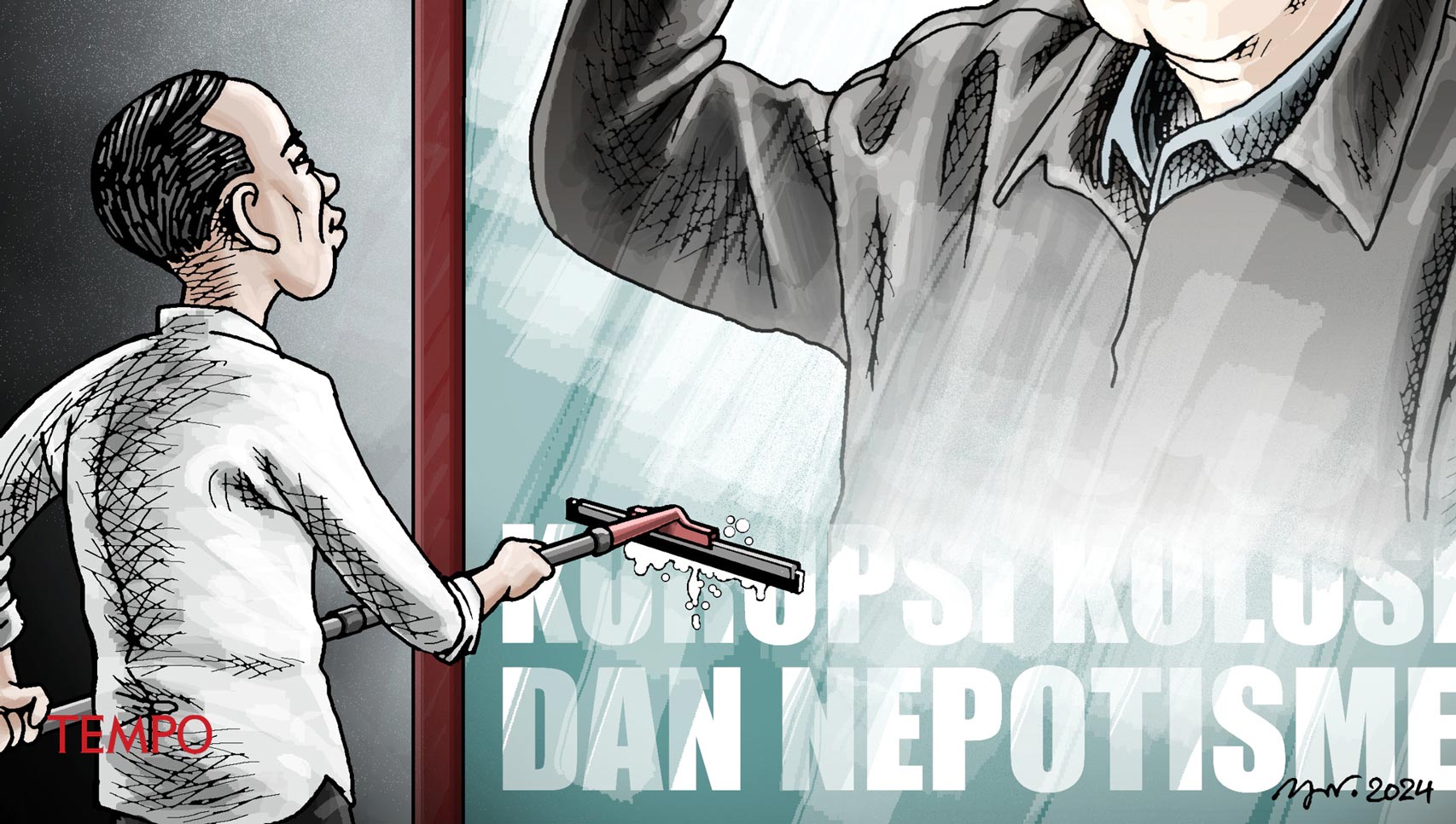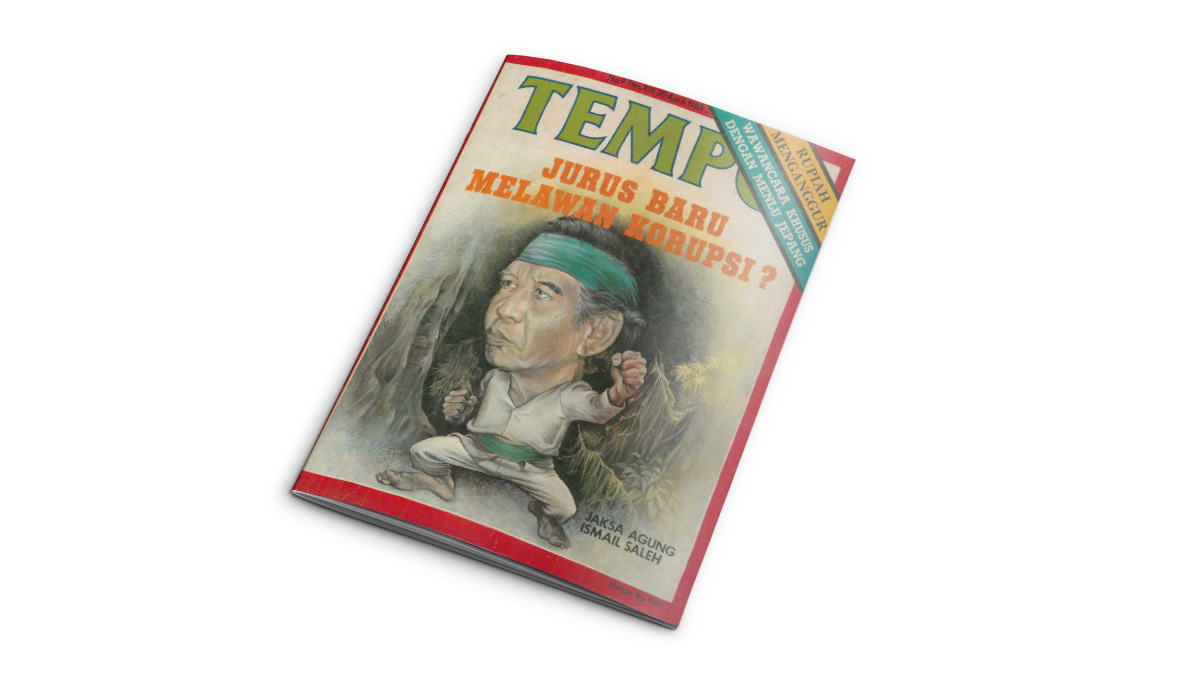Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Meski menyandang label lembaga pendidikan tinggi keagamaan, Institut Agama Islam Negeri tidak hanya mengajarkan soal agama. Bahasa yang diajarkan pun bukan cuma Arab, melainkan juga Inggris. Selain menghafal kitab, mahasiswanya dituntut menguasai berbagai disiplin ilmu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo