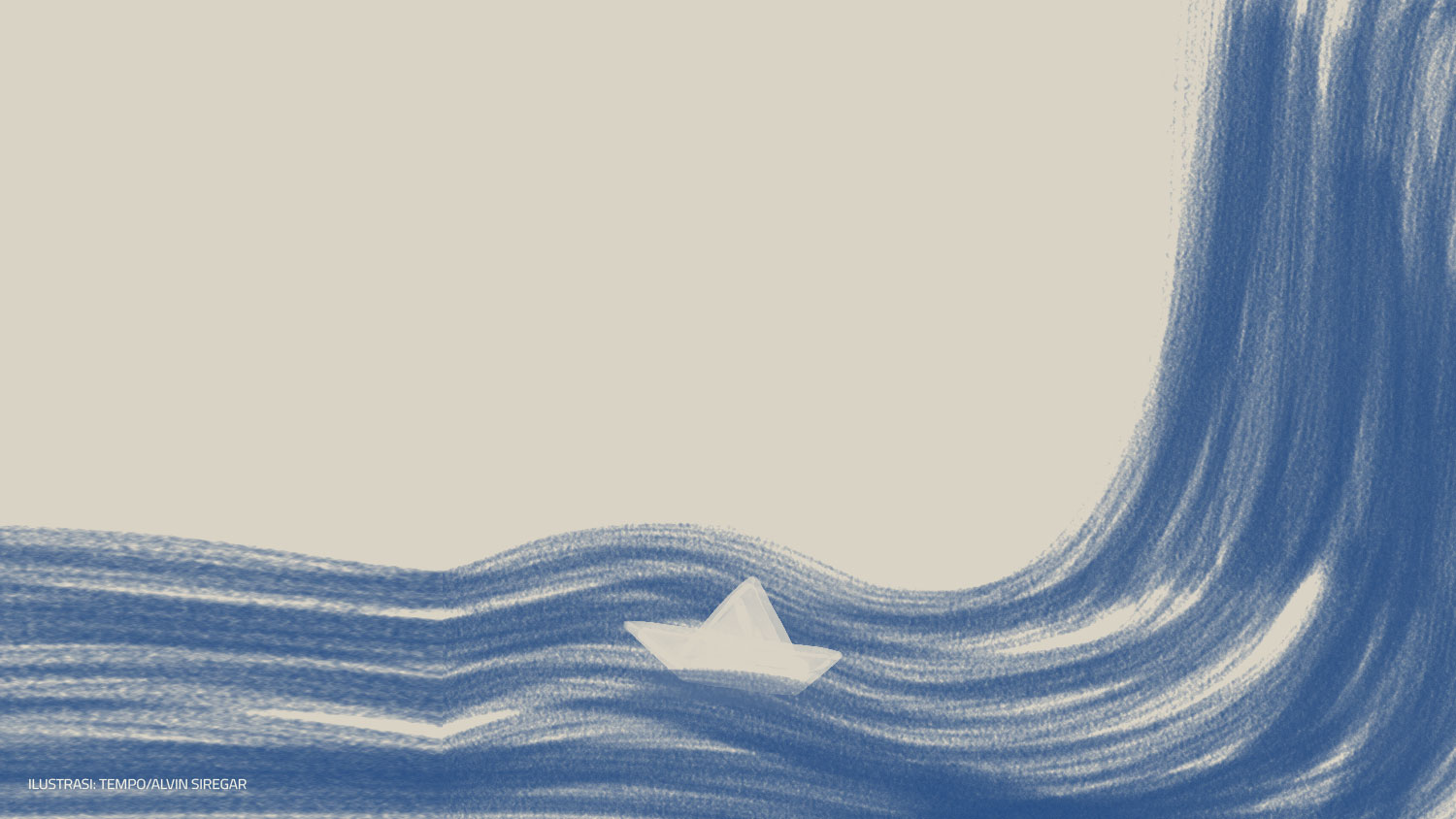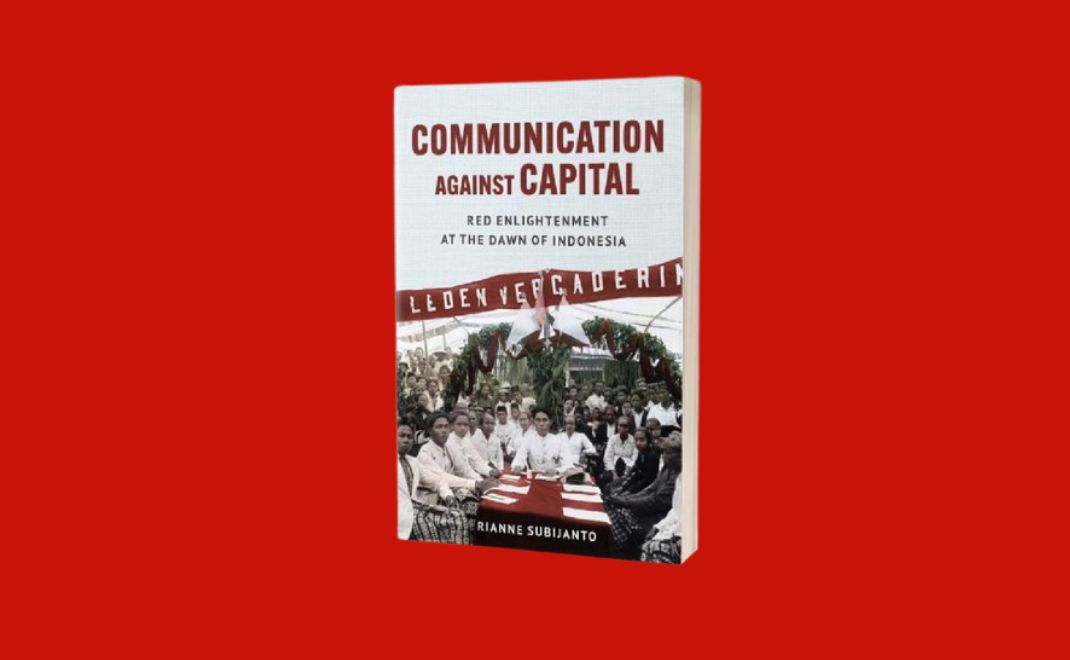Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hampir setiap hari, Addie Muljadi Sumaatmadja menghadiahkan sepotong senja untuk dirinya sendiri. Tepat pukul 16.30, dia akan berhenti bekerja dan membuat secangkir kecil espresso. Addie lalu pergi ke pinggir kolam renang di kompleks perumahannya di Pondok Labu, Jakarta Selatan, dan duduk di sana. Sendiri. Dia lalu menyulut sebatang cerutu, sesekali menyesap kopi, mendengarkan musik klasik, dan memandang langit yang memerah. Dengan telepon seluler, dia memotret lukisan senja. "Tak pernah ada langit senja yang sama," katanya bulan lalu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo