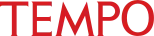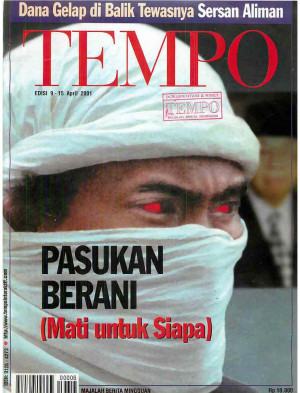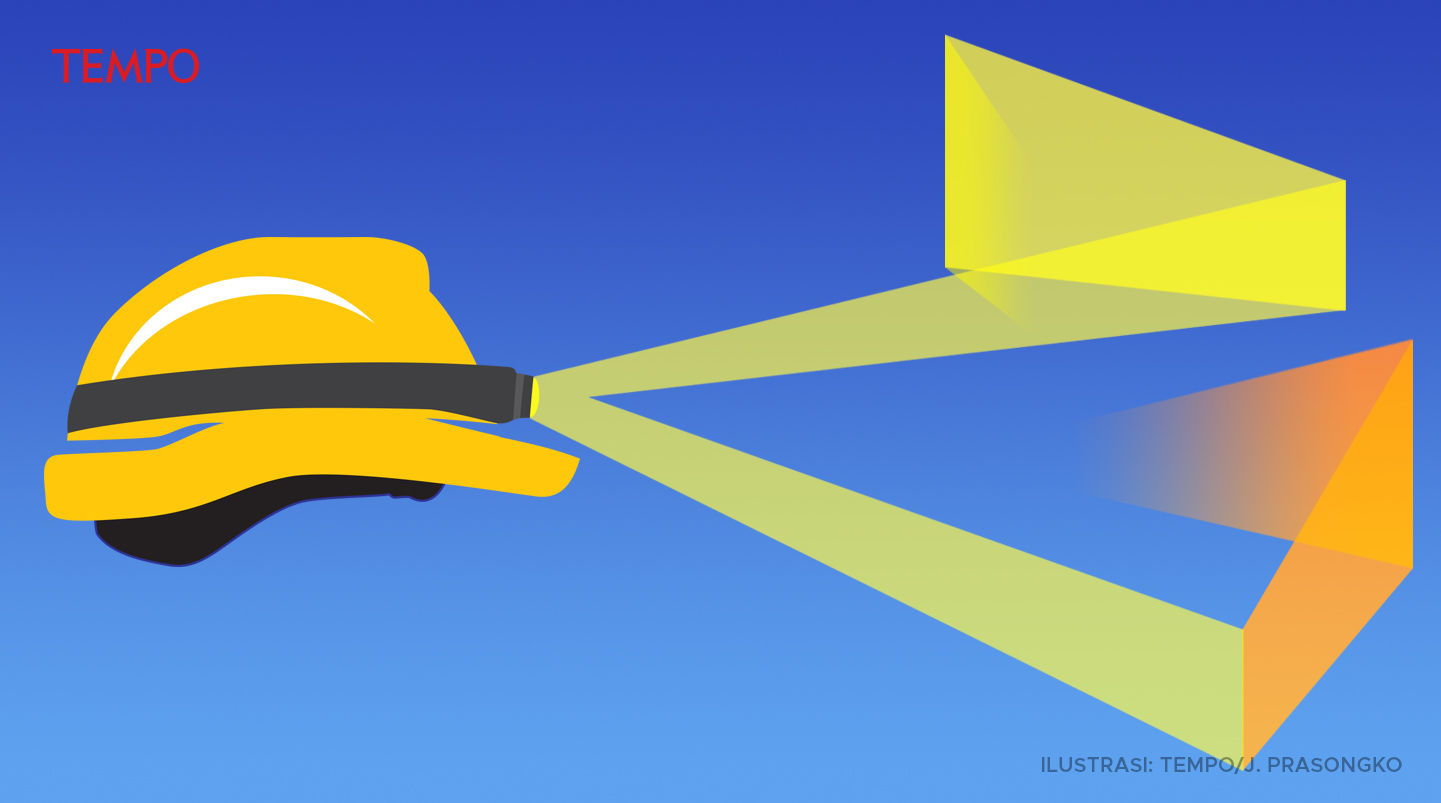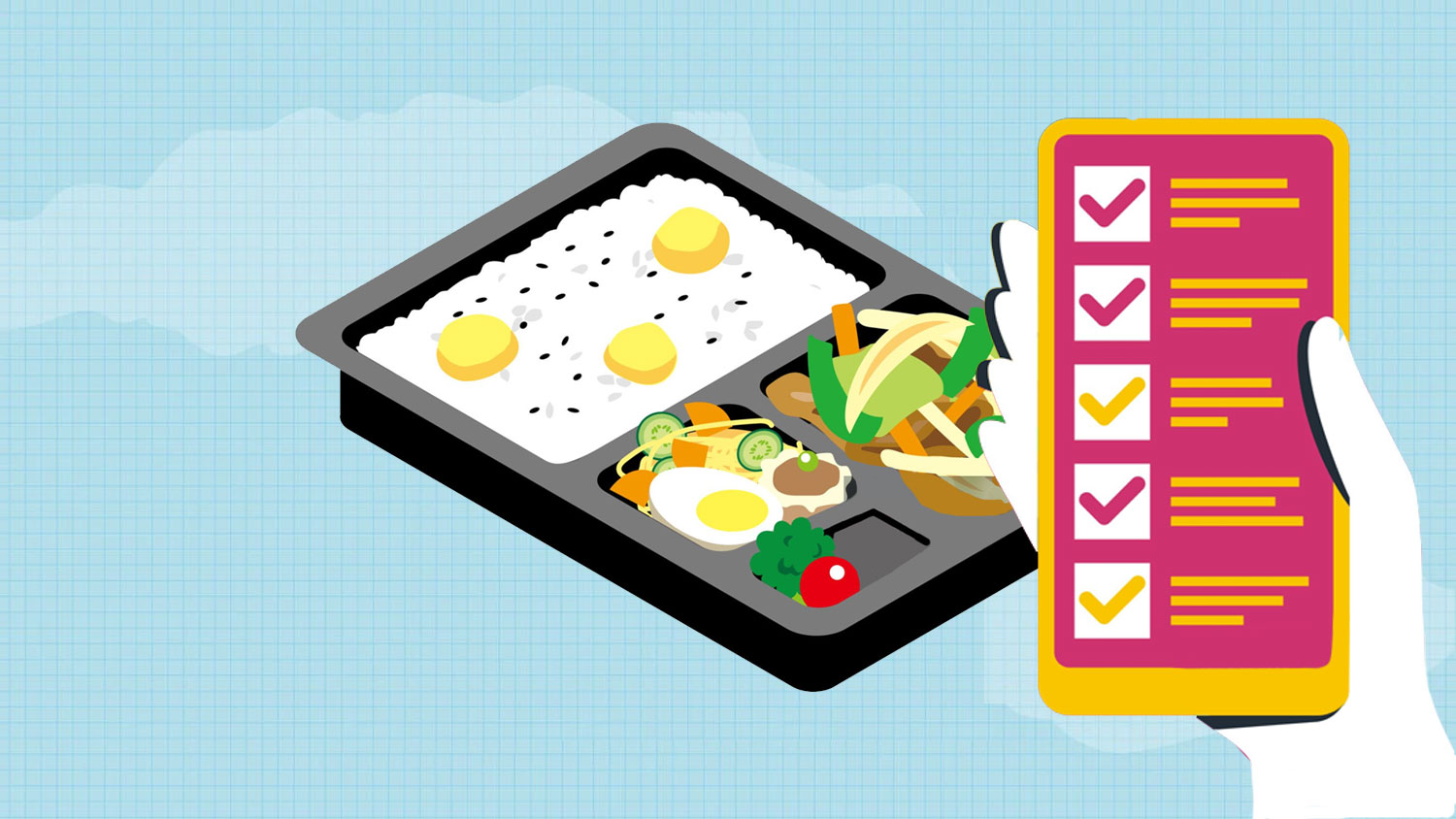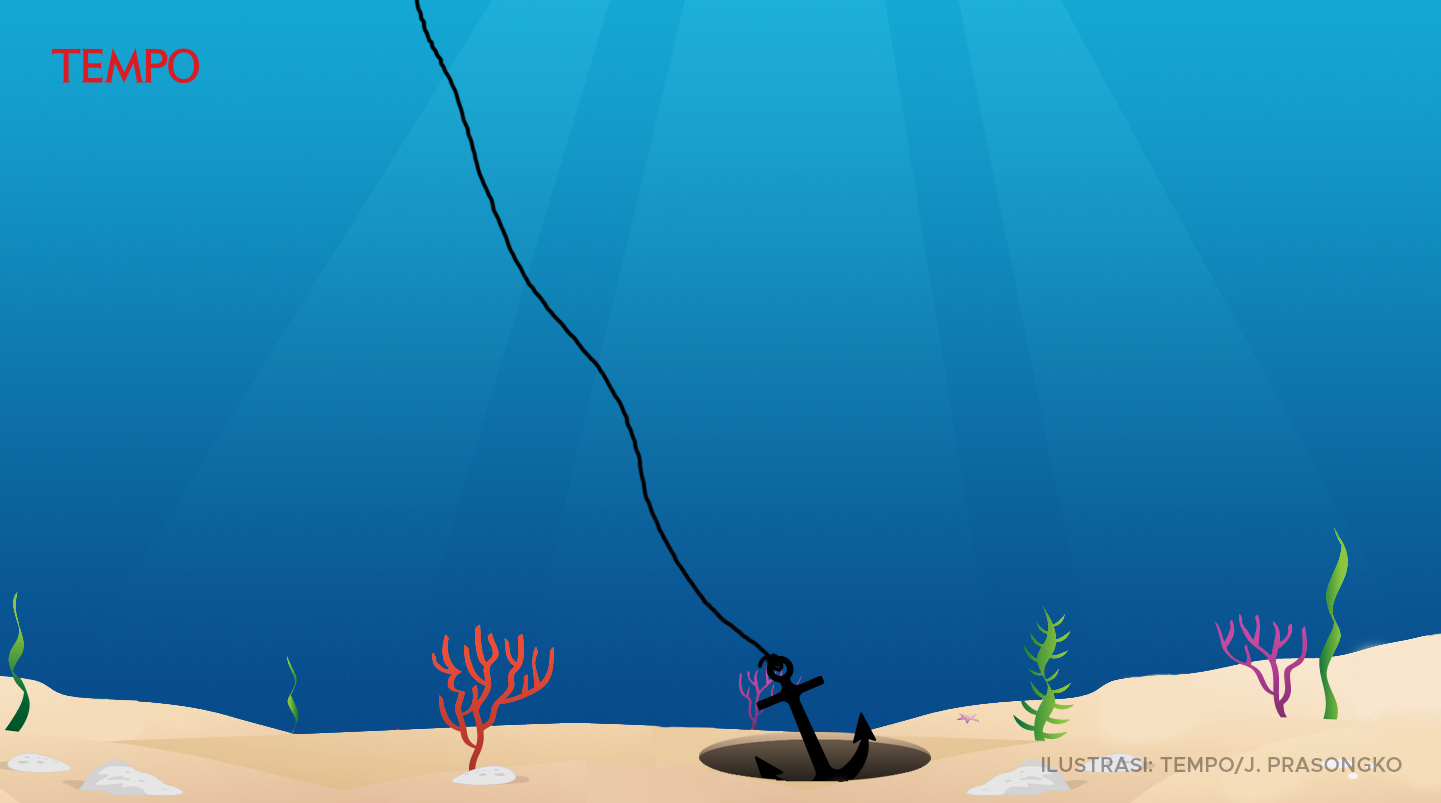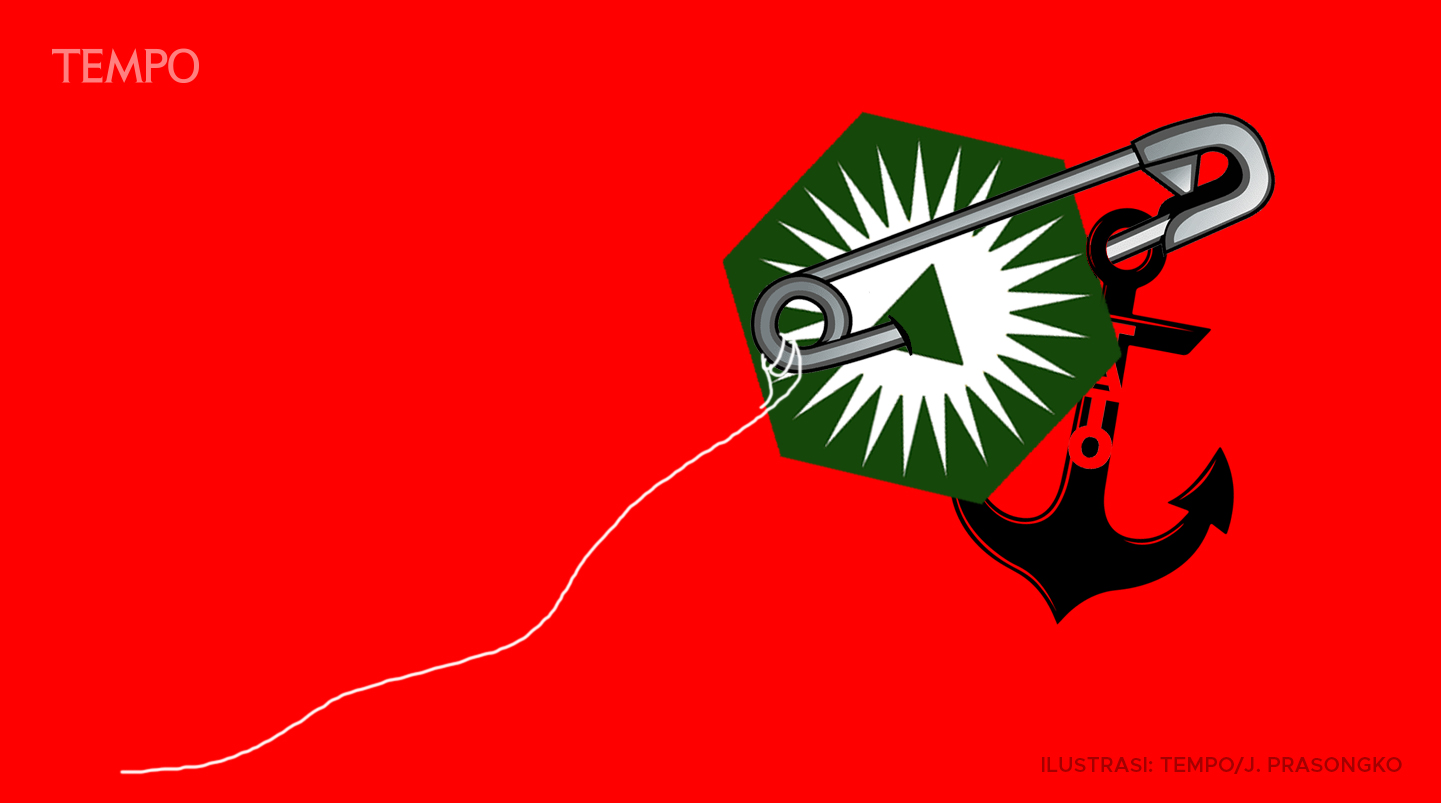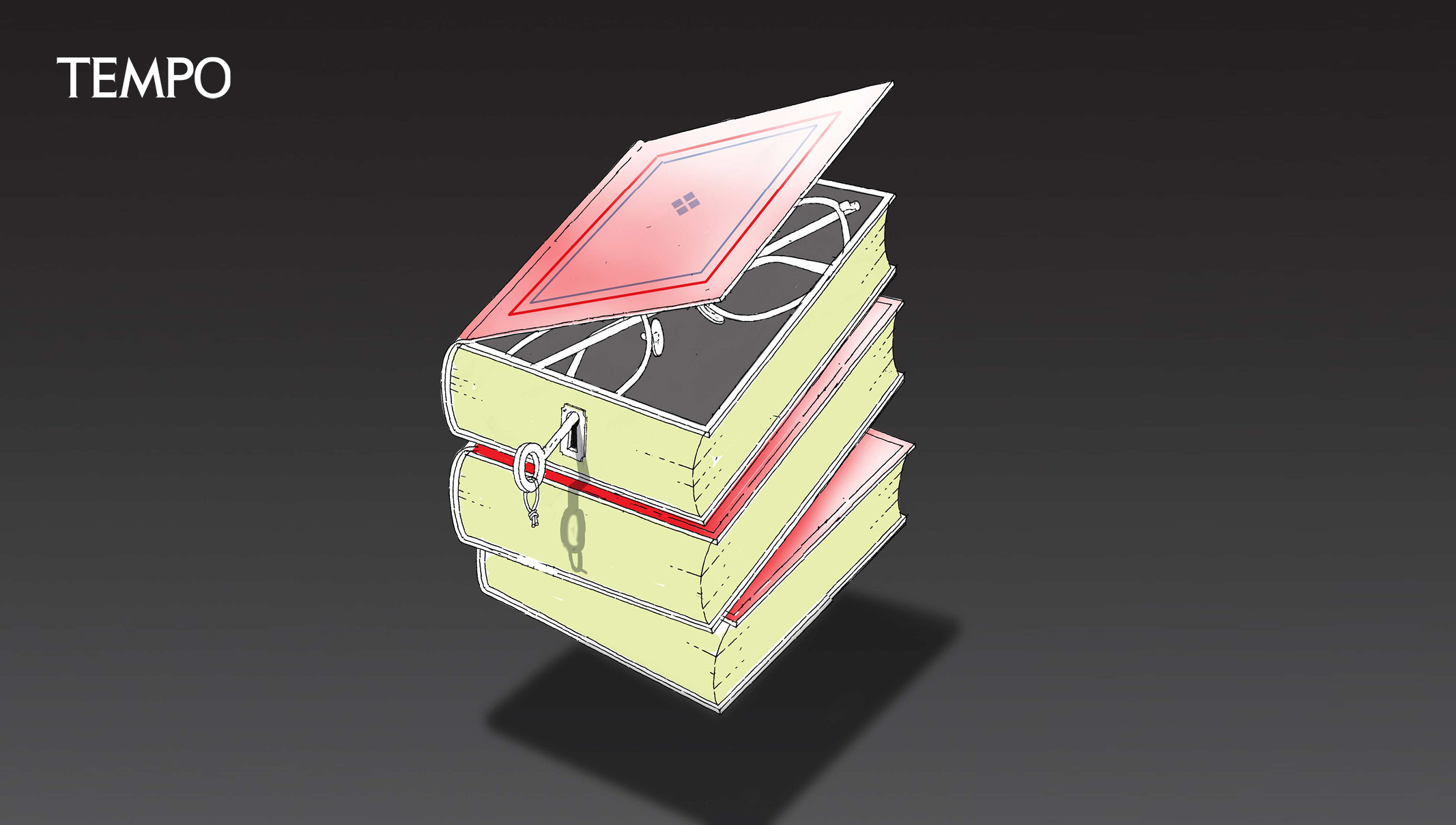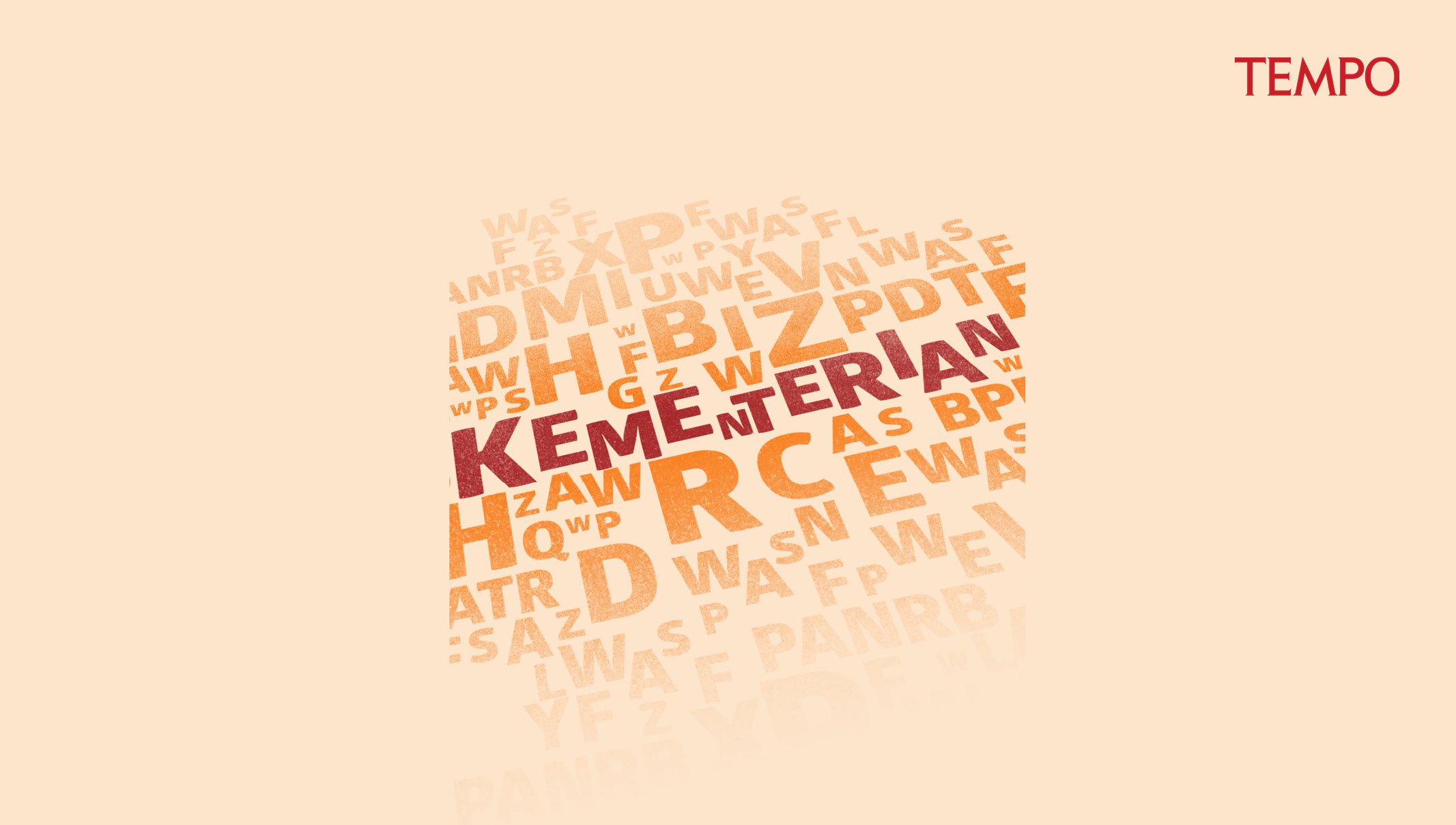Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TNI akan menjadi satu-satunya komponen utama pertahanan negara. Rencana undang-undang (ruu) pertahanan baru yang diajukan Menteri Pertahanan Mahfud Md. menyebutkan komponen utama pertahanan itu sebagai bala nyata yang siap menghadapi ancaman bersenjata. "Komponen utama hanya Tentara Nasional Indonesia". Rancangan ini memang menyebut perihal komponen cadangan. Tapi komponen cadangan tersebut hanya dikerahkan untuk "memperbesar dan memperkuat kekuatan aktif TNI melalui mobilisasi". Kalau RUU ini diloloskan parlemen tanpa perubahan, Indonesia hanya akan memelihara angkatan perang yang melulu terdiri dari tentara profesional. RUU memang menyebut keikutsertaan warga negara dalam bela negara, sebagaimana tertulis dalam kalimat "pelatihan dasar kemiliteran secara wajib" dan "pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib". Namun, pada pasal tentang TNI-nya sendiri tidak tertuang adanya tentara wajib yang tergabung ke dalamnya. RUU Pertahanan 2001 ini untuk mengganti konsep yang dianggap tak cocok dari Undang-Undang Ketentuan Pokok Hankamneg No. 20 Tahun 1982. Sebenarnya, undang-undang produk Orde Baru ini tegas menempatkan "rakyat terlatih sebagai komponen dasar pertahanan". Dan tentang ABRI sebagai komponen utama ditegaskan bahwa anggotanya terdiri dari prajurit karir, prajurit sukarela dinas pendek, prajurit cadangan penggal waktu, prajurit wajib dua tahun. Sialnya, undang-undang ini juga menempatkan ABRI sebagai kekuatan sosial-politik, hingga menjadi tak cocok lagi untuk masa sekarang, karena polisi (berdasarkan Tap VI MPR 2000) telah pisah dari ABRI. Pemahaman tentang tentara rakyat juga bisa dibaca dalam undang-undang sebelumnya, yaitu UU Pertahanan RI No. 29 Tahun 1954. Namun, legislasi pertahanan 1954 dan 1982 itu hanya konsisten dalam "membahasakan" muatan tentang tentara rakyat. Rakyat terlatih yang telah terpanggil sebagai tentara wajib ternyata meneruskan pengabdiannya sebagai tentara tetap. Fungsi penting ABRI sebagai "pelatih keprajuritan bagi rakyat" juga tak dijalankan. Jadi, yang ada dan dibangun selama ini melulu kekuatan pembela negara yang isinya pengabdi profesi, tentara gajian. Padahal, para pendiri negara dan sesepuh TNI seperti Sudirman,Urip, Nasution, sejak semula ingin membangun milisi dalam arti yang terorganisasi dalam barisan rakyat terlatih, pemusatan cadangan nasional, pemanggilan untuk waktu tertentu untuk dinas militer. Berdasarkan pengalaman itu, dan kini membaca muatan beserta penjelasan RUU 2001, tampaknya kita makin menutup kesempatan bagi rakyat secara merata menjadi patriot pembela negara. Tentara reguler-profesional yang kelewat besar, apalagi satu-satunya, bisa menjadi alat penguasa seperti terjadi di masa Orde Baru. Atau sebaliknya, bisa berpotensi mengudeta seperti di Pakistan. Pagar Makan Tanaman Konsep angkatan perang yang terdiri dari tentara profesional dan tentara wajib dianut hampir di seluruh dunia. Memang, banyak negara demokratis yang kaya, setelah berakhirnya Perang Dingin, beralih ke tentara yang sepenuhnya terdiri dari prajurit karir. AS menghapus wajib militer dan mengandalkan pertahanannya pada keunggulan teknologi yang canggih. Negara maju seperti Jerman menggunakan rasio 50:50. Artinya, bala nyatanya terdiri atas 50 persen tentara gajian, 50 persen tentara wajib. Yang mengisi elemen wajib adalah rakyat terlatih, yang datang dan pergi, silih berganti selang dua tahun. Yang kembali ke sipil pun tetap terdaftar dalam bala cadangan, bersama-sama rakyat terlatih lainnya. RI belum demokratis, masih jauh pula dari kaya. Untuk negeri yang sedang membangun demokrasi, termasuk demokrasi bidang pertahanan, rasio yang sehat adalah lebih banyak lapisan tentara wajib. Sedangkan tentara profesionalnya lebih sebagai inti dan pembina. Membangun lapisan tentara rakyat yang silih berganti mengisi bala nyata akan meminimalkan kemungkinan terbentuknya segolongan kasta kesatria, karena semua warga negara yang sehat berkesempatan menjadi kesatria. Mengenai pembagian komponen pertahanan dan fungsinya, RUU Pertahanan 2001 (dalam penjelasannya) memberikan alasan: "Agar pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip pembedaan antara kombatan dan nonkombatan". Para perancang undang-undang ini rupanya mengkhawatirkan, kalau semua rakyat terlatih dianggap sebagai balatentara, mereka adalah kombatan yang bisa ditembak oleh musuh yang menyerang. Kalau yang dimaksud "aturan hukum internasional" itu adalah Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War (diadopsi 12 Agustus 1949), kekhawatiran semacam itu tidak beralasan. Bukankah ketentuan Pasal 3 (1) dan Pasal 15 Konvensi tentang Kombatan dan Nonkombatan sangat jelas? Pada pasal-pasal itu ditegaskan bahwa anggota tentara, bisa tentara wajib, rakyat terlatih, milisi terorganisasi, selama mereka sedang tidak dalam dinas aktif militer (taking no active parts in the hostilities/laid down their arms) atau sedang tak mampu bertempur (placed hors de combat), tidak boleh dimusuhi. Konvensi ini lahir di jantungnya Swiss, negeri "biang"-nya tentara rakyat, yang 99,5 persen kekuatan pertahanannya adalah milisi. Kapan seorang warga negara menjadi kombatan dan kapan nonkombatan memang perlu diatur oleh undang-undang, seperti dalam undang-undang tentang pertahanan, tentang keadaan darurat, tentang prajurit, serta undang-undang tentang mobilisasi dan demobilisasi. Dan hal itu harus mengacu pada prinsip hak asasi manusia. Yang jadi pertimbangan para perancang undang-undang pertahanan 2001 tentang milisi adalah untuk menghadapi peperangan dengan musuh dari luar. Padahal, tinjauan "ke dalam" tak kalah pentingnya. Intinya, dengan adanya milisi, kekuatan pertahanan tidak menjadi "pagar makan tanaman". |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo