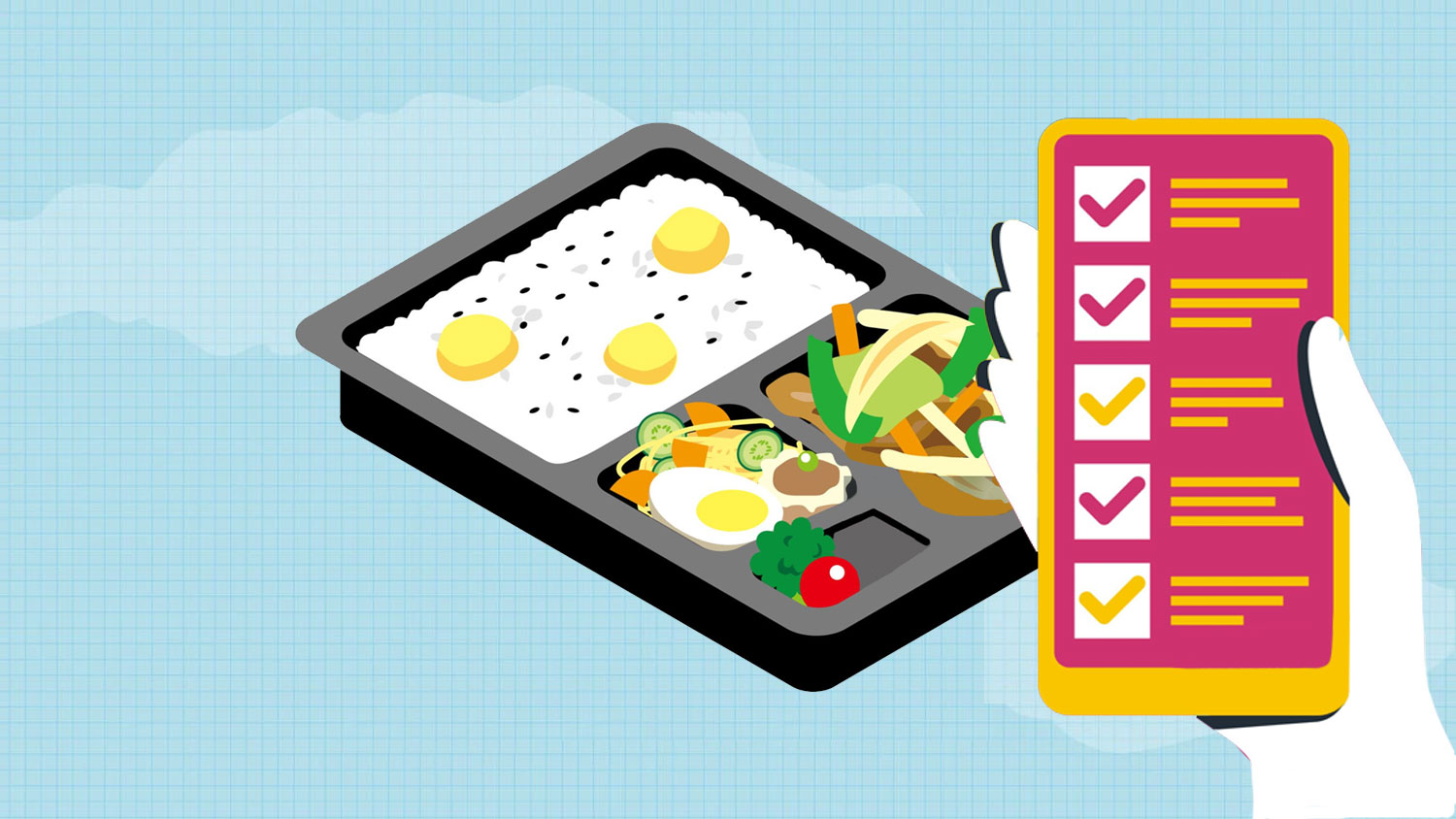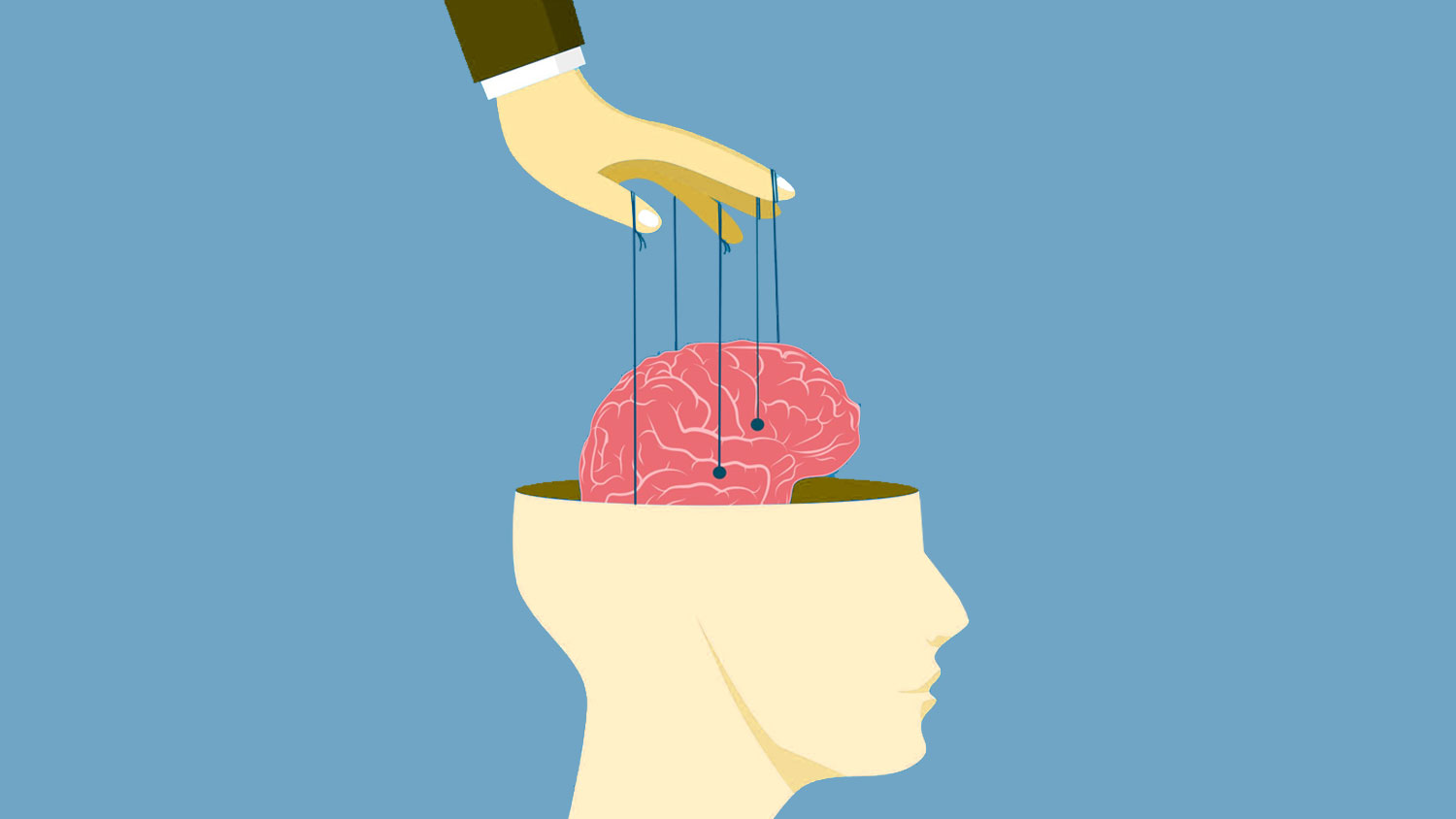Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

AKHIR Mei lalu, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002. Revisi ini merupakan inisiatif DPR yang mengundang polemik. Salah satu klausul kontroversial dalam aturan tersebut adalah perluasan wewenang kepolisian hingga ke ruang siber, sesuai dengan Pasal 16 poin (q), yang mencakup penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya memperlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.
Dialektika Digital merupakan kolaborasi Tempo bersama KONDISI (Kelompok Kerja Disinformasi di Indonesia). KONDISI beranggotakan para akademikus, praktisi, dan jurnalis yang mendalami dan mengkaji fenomena disinformasi di Indonesia. Dialektiga Digital terbit setiap pekan.
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.