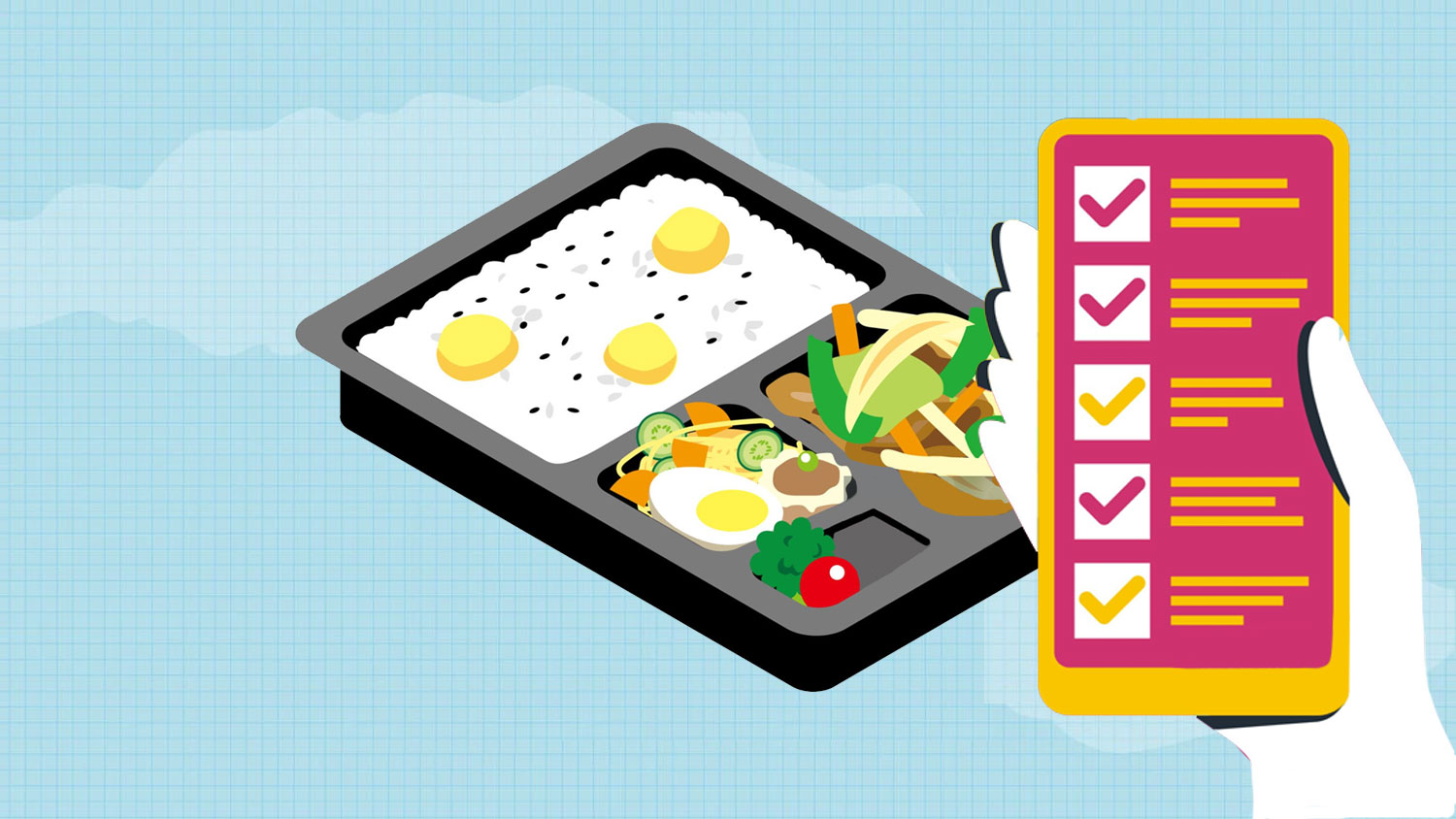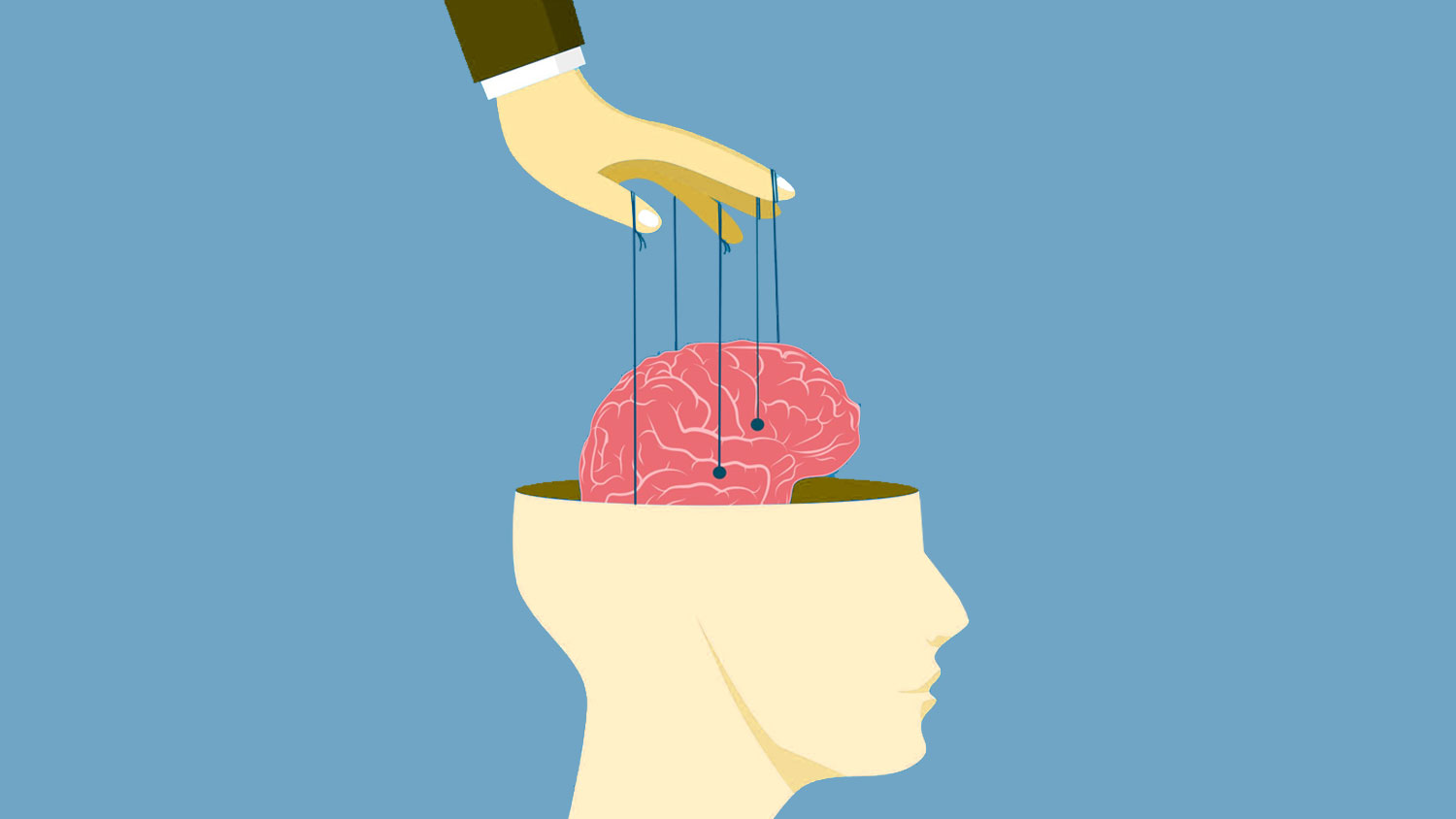Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

DALAM hal perlakuan terhadap buku, Kejaksaan Agung belum beranjak dari tabiat Orde Baru dan Orde Lama. Di zaman yang gelap itu, buku bisa dilarang beredar karena alasan yang samar. Jika bukan mengganggu ketertiban umum, alasan yang lazim diberikan adalah menyebarkan paham komunis/Marxisme-Leninisme. Banyak yang sudah jadi korban. Buku-buku Pramoedya Ananta Toer cuma salah satunya. Boleh tak percaya, Kejaksaan Agung bahkan pernah ”memeriksa dan mengawasi” Atlas Lengkap Indonesia dan Dunia—entah untuk alasan apa.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo