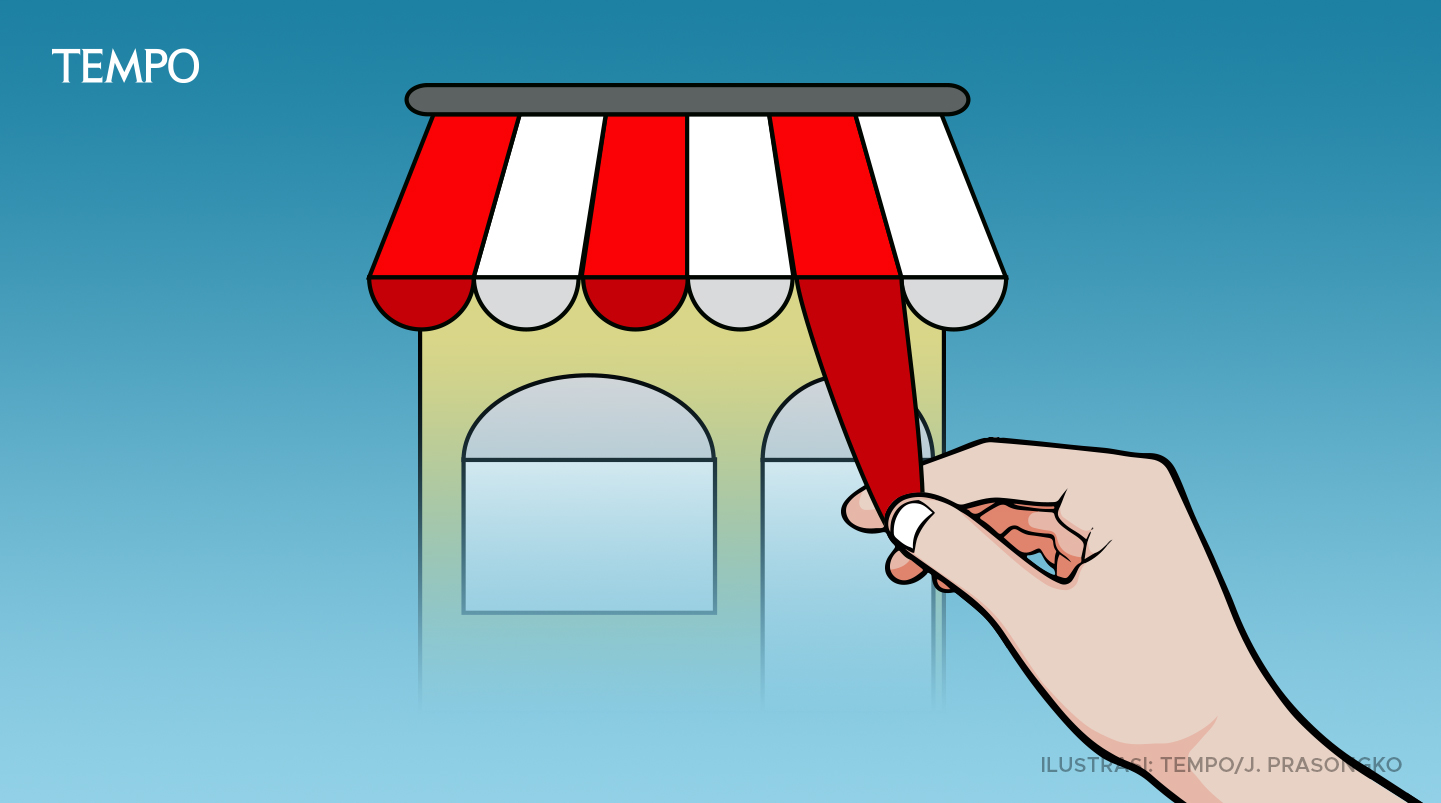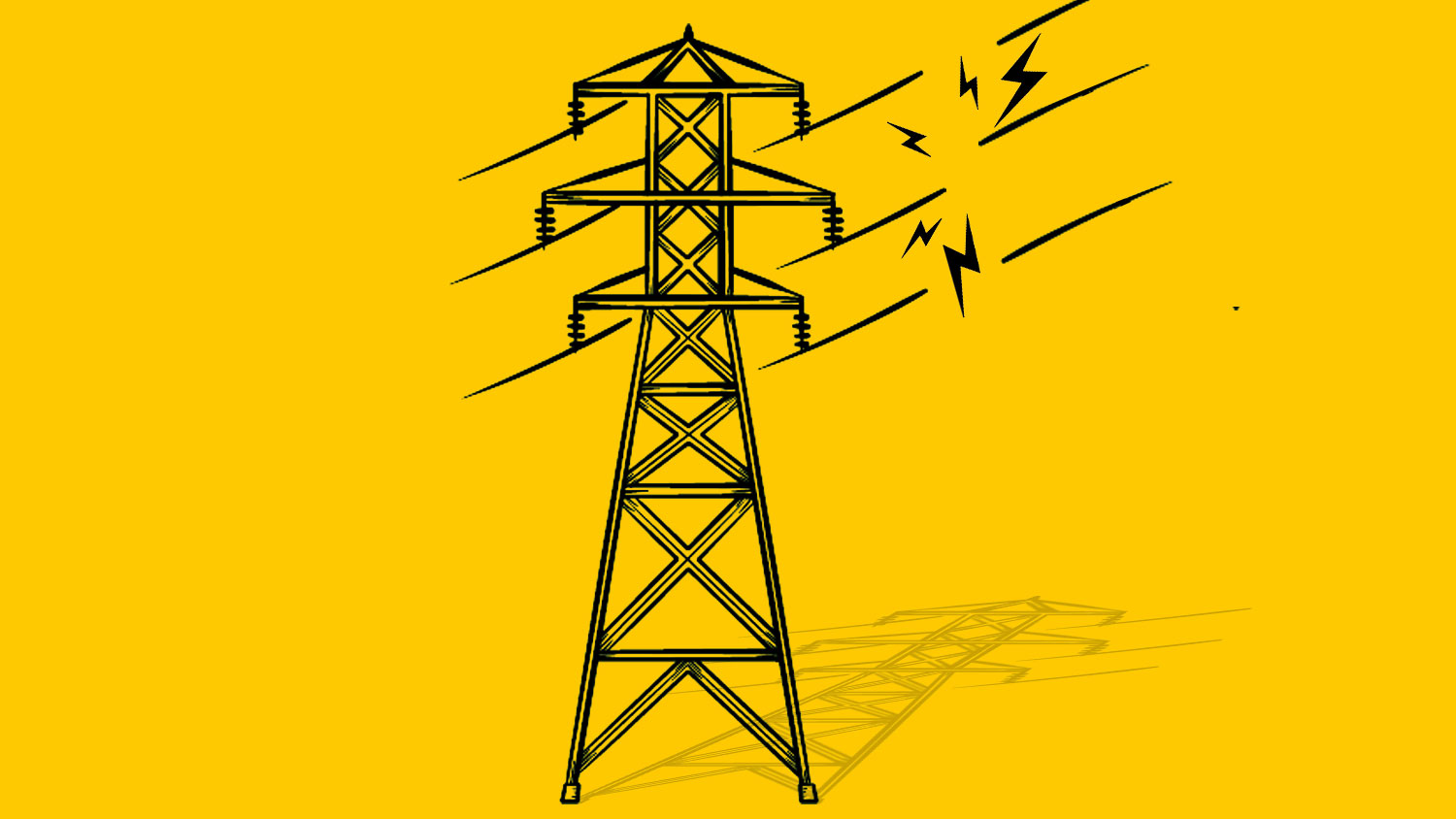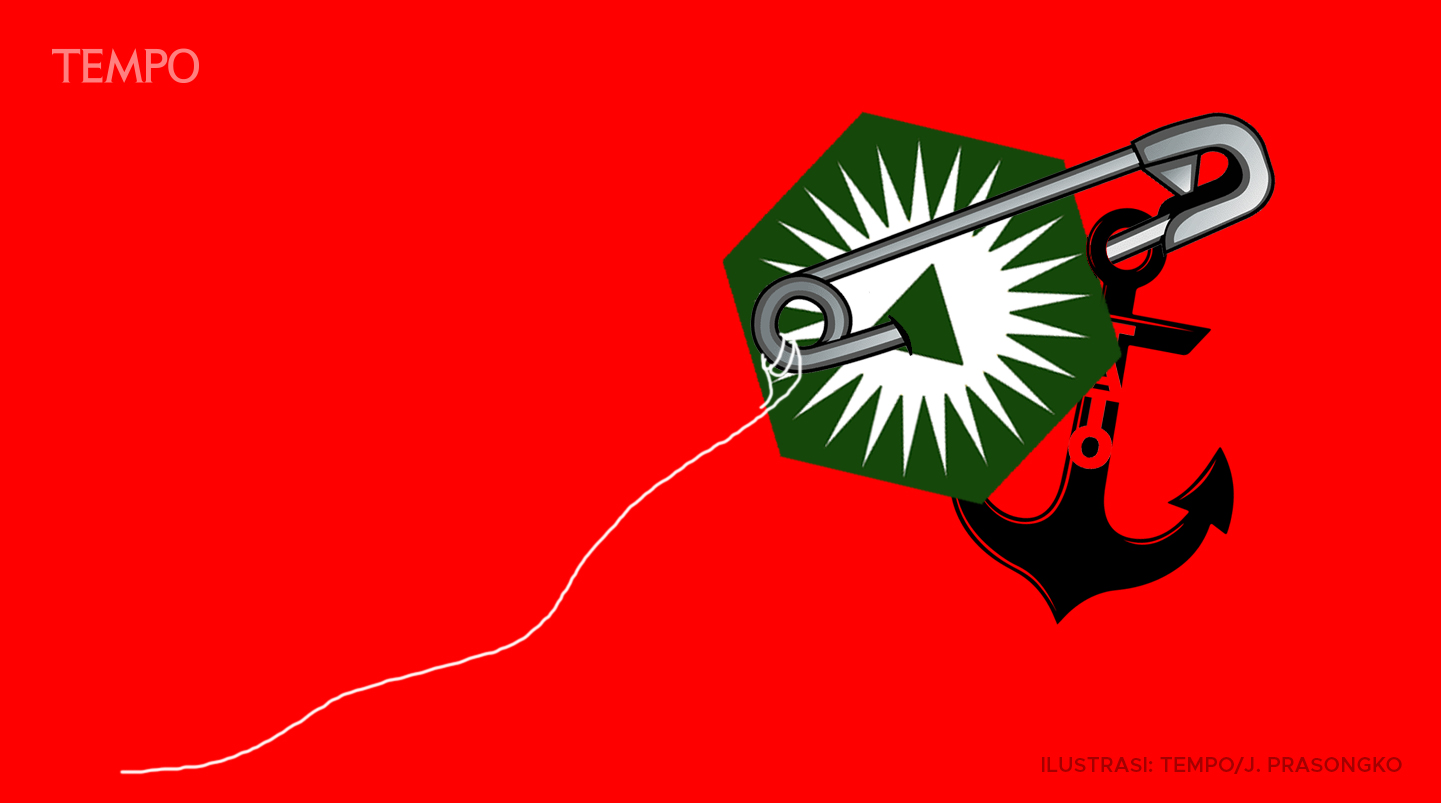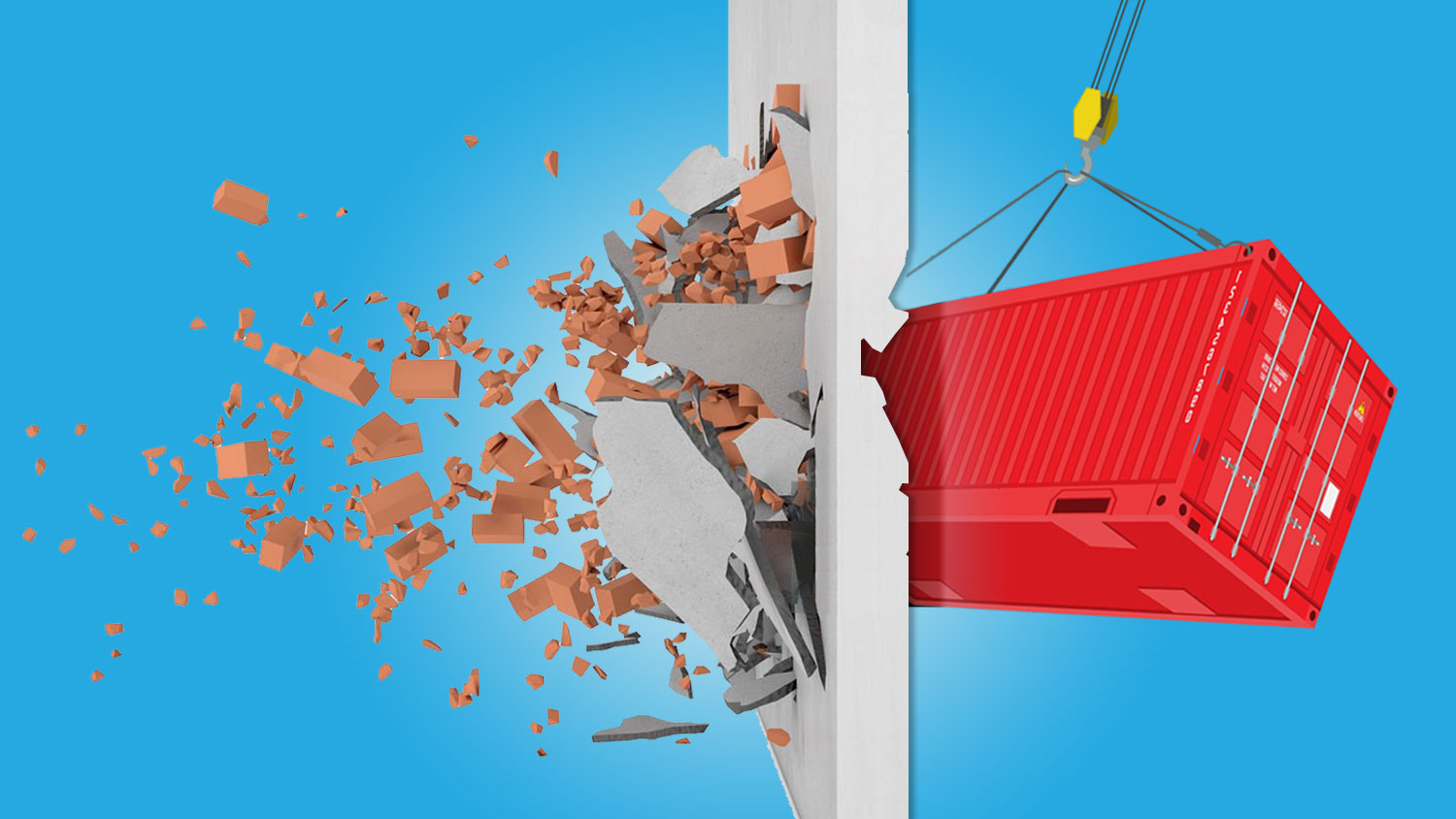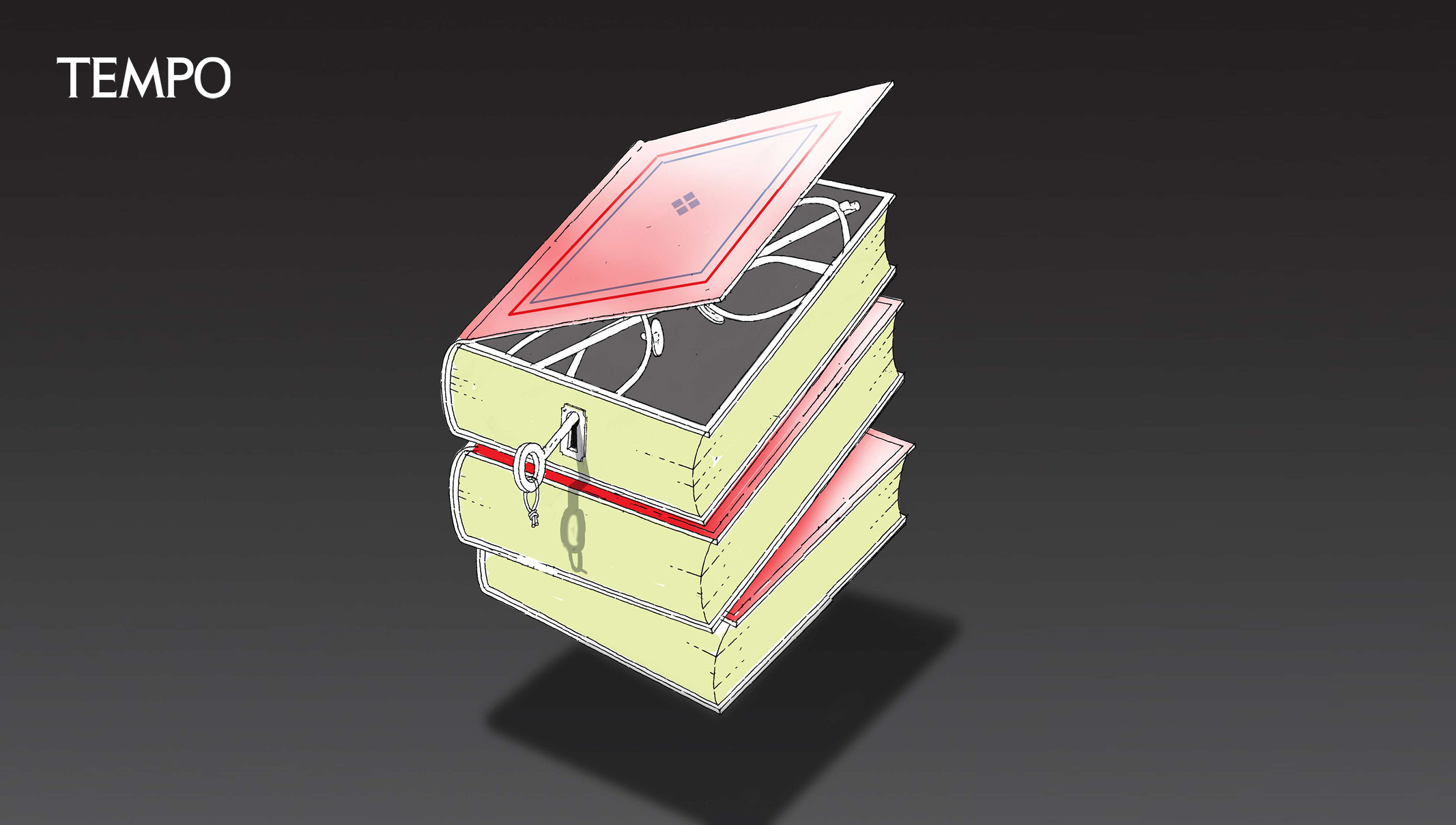Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KETIKA Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur pada 17 September 1963, negeri semenanjung itu terkesan gamam. Apalagi setelah pada tahun berikutnya Bung Karno mencanangkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), yang sasarannya cuma dua, yakni ”memperhebat ketahanan revolusi Indonesia” dan ”membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei.”
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo