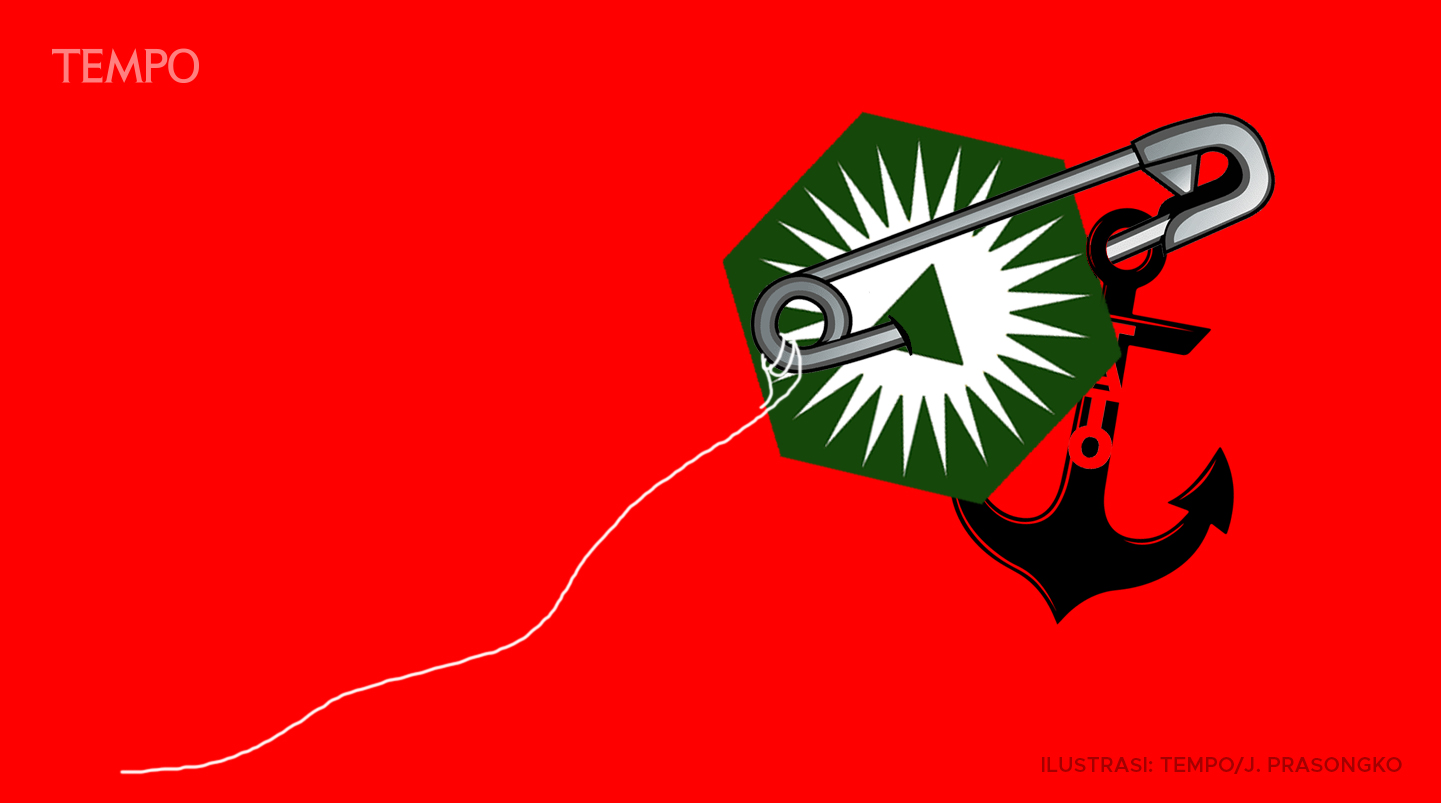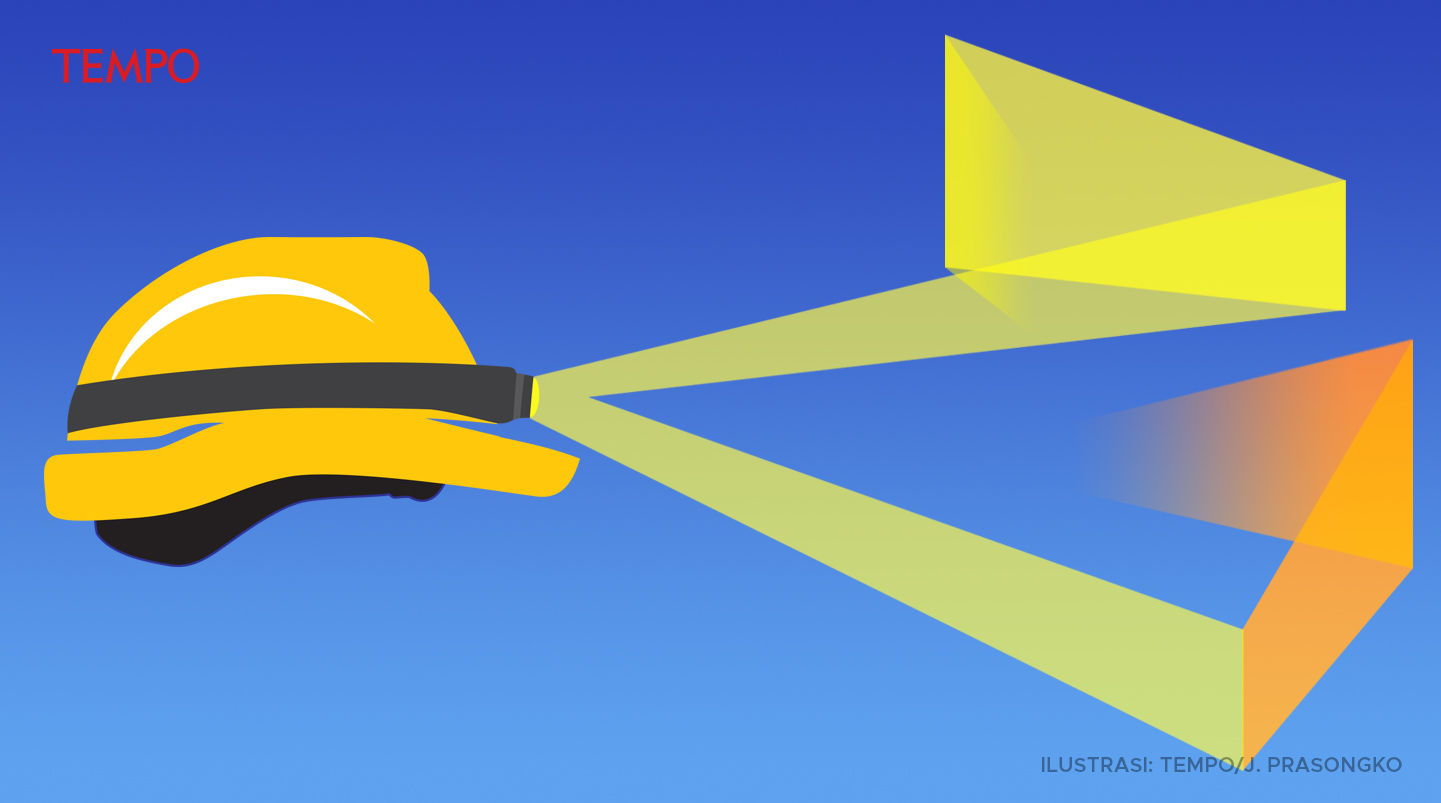Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Editorial Tempo.co
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

---------------------
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Rencana mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada Juli mendatang merupakan sikap bebal pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bertabur pasal-pasal bermasalah, RUU tersebut mestinya dibahas ulang dengan melibatkan masyarakat. Tanpa itu, sama artinya pemerintah dan DPR menutupi fakta bahwa batalnya pengesahan RUU ini pada 2019 karena derasnya penolakan publik.
Gelagat operasi kilat untuk mengesahkan RUU itu tampak dari keengganan DPR membahas ulang pasal-pasal bermasalah yang sebagian di antaranya diakui oleh Presiden Joko Widodo kala menyetop pengesahan RUU KUHP. Dalam rapat Komisi III pada 25 Mei lalu, mayoritas anggota Dewan menyatakan pembahasan kembali RUU KUHP tak diperlukan lantaran telah diketok dalam pembahasan tingkat I DPR periode 2014-2019.
Pandangan ini jelas keliru. Meski berstatus sebagai ‘RUU operan’, pembahasan lanjutan pasal-pasal kontroversial mutlak dilakukan. Banyak langkah mundur di dalam naskah RUU KUHP yang mengekang kebebasan sipil. Misalkan, masih bercokolnya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang membuat Indonesia kembali ke era hukum otoriter.
Perubahan delik pada pasal tersebut, dari delik biasa menjadi delik aduan, bukan hal penting. Soalnya bukan pada delik. Sebab, keseluruhan pasal penghinaan penguasa ini jelas kuno. Hanya penjajah yang memakainya. Hanya penguasa yang merasa tak memerlukan rakyat yang hendak menghukum rakyatnya sendiri karena kritik. Apalagi pasal penghinaan presiden ini sudah dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2006. KUHP yang bagus di negara demokrasi justru makin nihil pidana politik, bukan sebaliknya.
Tema-tema berbau kolonial dalam RUU KUHP yang seharusnya diperbaiki untuk mengikuti perkembangan zaman, justru dilestarikan. Pemerintah dan DPR berkeras mengesahkan RUU yang mengabaikan hak-hak asasi manusia dengan mempidanakan penodaan agama, hidup bersama tanpa pernikahan, hingga pidana berbasis orientasi seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Para pembuat hukum kita tak hanya kian konservatif, tapi bahkan hendak membunuh kemajemukan Indonesia. Mereka hendak menegakkan hukum yang berangkat dari pemikiran tunggal atau menginginkan keseragaman dengan memberangus perbedaan, ketika kini pemikiran dan konsep-konsep keberagaman berbasis hak asasi manusia kian maju.
Para legislator barangkali mesti diajarkan prinsip-prinsip dasar menyusun sebuah undang-undang. Pertama, pengaturannya tidak boleh sewenang-wenang, adil, dan tidak membuka celah untuk disalahgunakan oleh kekuasaan. Kedua, aturan di dalam undang-undang harus sangat terbatas pada hal-hal yang diperlukan untuk mencapai kebaikan publik, bukannya untuk menambah kekuasaan negara atau rezim.
Sedangkan prinsip ketiga ialah, dampak negatif dari pembatasan yang ditetapkan sebuah produk legislasi tidak boleh lebih besar daripada manfaatnya bagi masyarakat. Ambil contoh, menghukum orang hanya karena menulis pesan di media sosial dampaknya negatifnya lebih besar daripada pelanggaran prinsipil atas hak-hak orang lain yang terjadi.
Perlu diingat, pasal-pasal kontroversial yang menjadi ganjalan di 2019 sarat dengan muatan upaya penertiban dan penyeragaman yang luar biasa dari pemerintah. Penggiat hukum menyebutnya dengan istilah pedas: “lebih kolonial daripada KUHP warisan kolonial.” Istilah itu benar belaka. Bayangkan, KUHP yang dulu diboyong pemerintah kolonial Belanda ke Hindia Belanda pada 1915 untuk menindas pribumi, justru direproduksi saat ini. Mestinya, pemerintah dan legislator membawa paradigma baru, seperti penghapusan hukuman mati, penghilangan pasal penodaan agama, dan penghinaan kepada pemerintah.
Berkaca pada masih bercokolnya semua pasal-pasal bermasalah tersebut, pengesahan terburu-buru RUU KUHP harus dicegah. Libatkan publik dalam pembahasan ulang. Buka draf akhir rancangan yang sampai sekarang masih disimpan rapat-rapat oleh pemerintah. Jangan sampai pola politik hukum yang lazim di era pemerintahan Presiden Jokowi, seperti pembahasan dan pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Ibu Kota Negara, dan UU Cipta Kerja yang senyap dan tiba-tiba, terulang. Kita tidak ingin cara ‘mengendap-endap dalam gelap’ itu dilanggengkan.