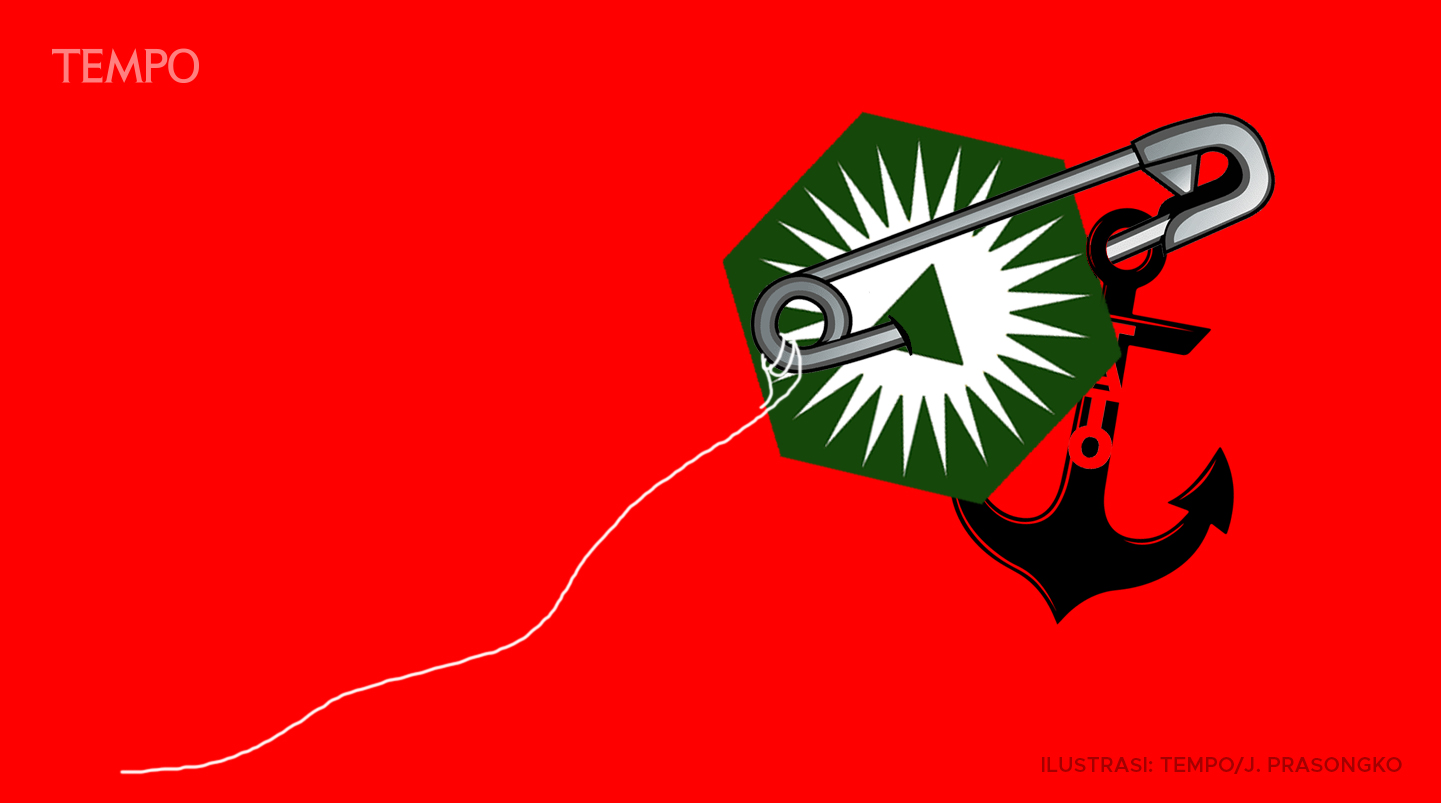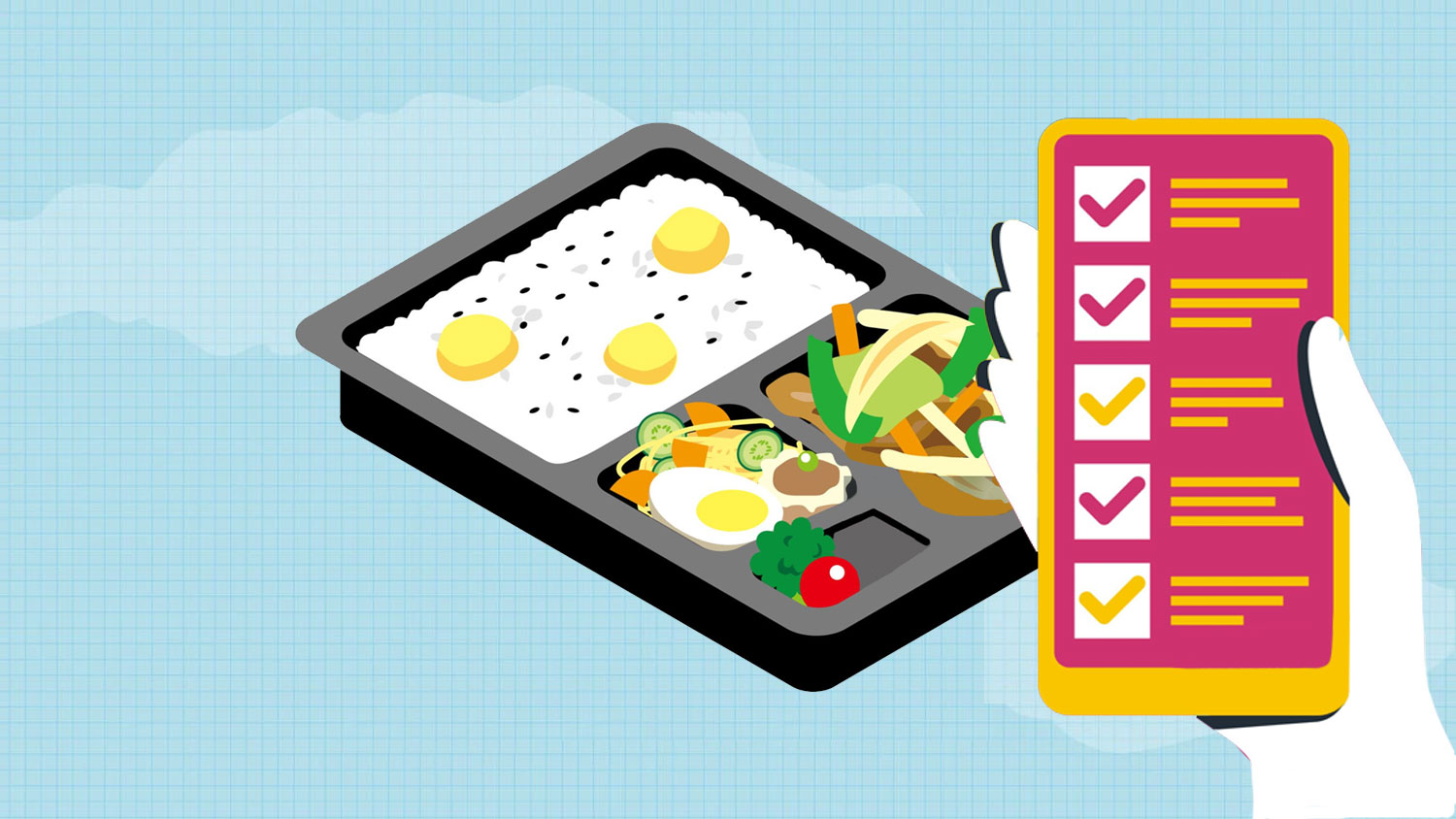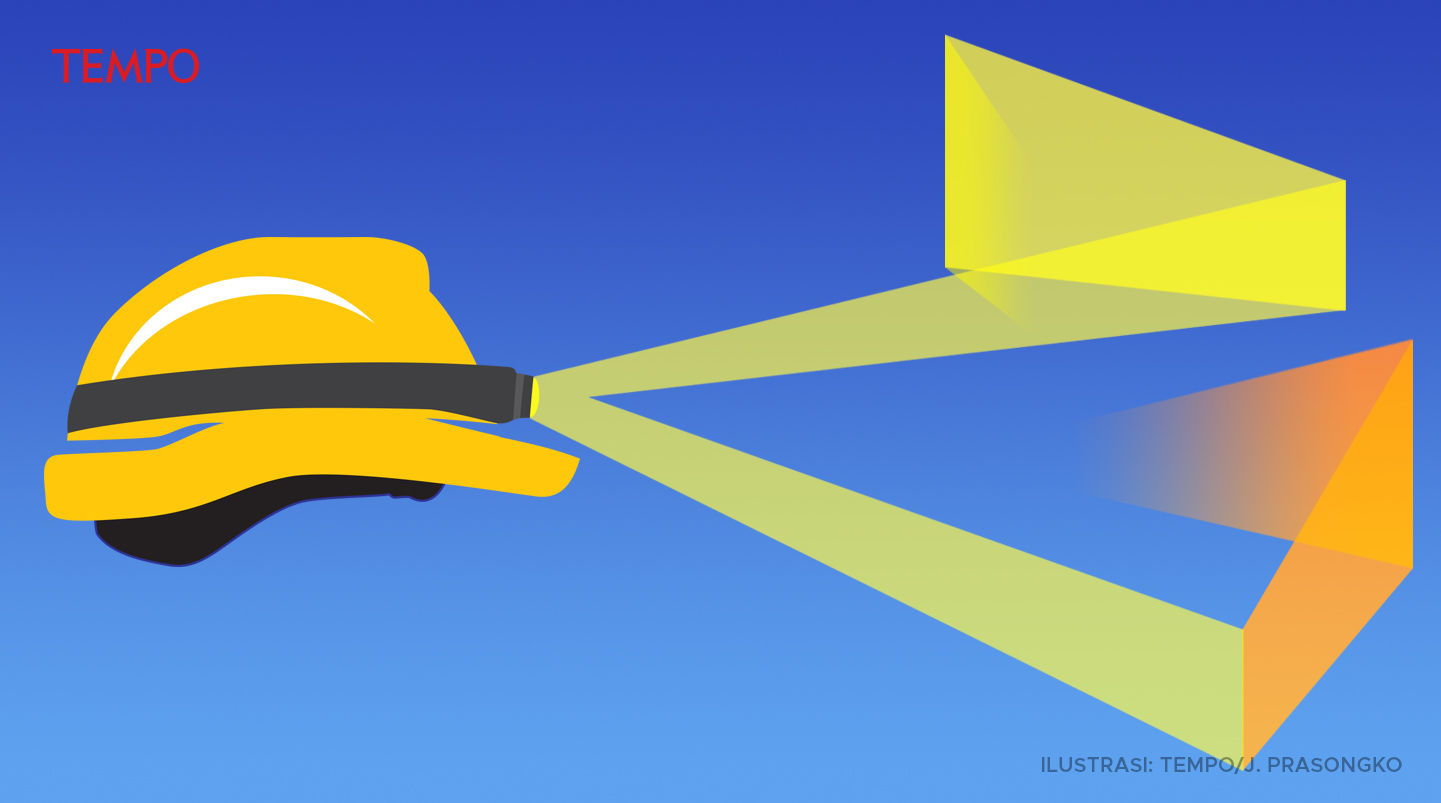Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Kampanye sejumlah partai politik untuk memberlakukan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) seolah-olah dilandasi semangat nasionalisme. Namun kampanye yang bertujuan mengamendemen kembali Undang-Undang Dasar itu menyimpan kekeliruan serius.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Dilandasi semangat reformasi 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengubah aturan dasar demokrasi. Presiden pun dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat sejak 2004-tidak seperti sebelumnya yang ditentukan oleh MPR. Presiden terpilih diberi kewenangan untuk menyusun program pembangunan sesuai dengan janji kampanyenya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Karena dipilih langsung oleh rakyat, presiden bukan lagi mandataris MPR. GBHN, yang ditetapkan oleh MPR sebagai pedoman pembangunan yang wajib dijalankan presiden, jelas menjadi tidak relevan lagi. Sebagai gantinya, disusunlah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Rencana pembangunan dibuat jangka panjang untuk periode 20 tahun, jangka menengah (lima tahun), dan tahunan.
Adanya sistem tersebut sekaligus menyanggah dalih para politikus yang menyatakan bahwa tidak ada kesinambungan pembangunan bila rezim berganti, atau tidak ada kesesuaian perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Sistem itu justru mensyaratkan ada pembahasan bersama masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan sampai pusat. Kesempatan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dalam pembangunan pun menjadi terwadahi.
Sebaliknya dengan GBHN, perencanaan pembangunan dipasrahkan kepada segelintir elite penghuni MPR. Artinya, menghidupkan kembali GBHN sama dengan mengembalikan kekuasaan oligarkis. Suara rakyat yang selama 15 tahun ini menjadi dasar cetak biru pembangunan akan ditelan kepentingan kartel politik yang bersembunyi di lembaga perwakilan. Singkatnya, rencana mengembalikan GBHN merupakan niat yang janggal.
Hal yang krusial bagi demokrasi itu kini menjadi bahan negosiasi dalam pembagian posisi pemimpin MPR periode mendatang. Partai yang menyetujui kembalinya GBHN bakal didorong untuk mengisi kursi tersebut. Ini lobi politik yang tak patut. Sebaliknya, membarter amendemen UUD untuk mendapatkan jabatan juga merupakan manuver yang rendah.
Sampai di sini, rencana menghidupkan lagi GBHN terlihat dibuat-buat. Bisa jadi, ngototnya partai politik karena ada maksud lainnya. Menyetujui kembalinya GBHN bisa membuka pintu amendemen lain, yaitu mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jika presiden kembali menjadi mandataris MPR, pemilihan presiden pun cukup dilakukan sekelompok politikus, seperti pada era Orde Baru. Presiden pun tidak dibatasi masa jabatannya-membuat Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun sebelum dipaksa mundur oleh mahasiswa pada 1998.
Skenario ini bukan mustahil terjadi. Sudah ada politikus yang mendengungkan amendemen UUD ke versi asli. Jika benar terjadi, ini jelas kemunduran luar biasa sekaligus akhir era demokrasi kita. Tak salah jika kita mengucapkan "selamat datang kembali era kegelapan". Maka, tak ada pilihan selain menolak rencana menghidupkan kembali GBHN.