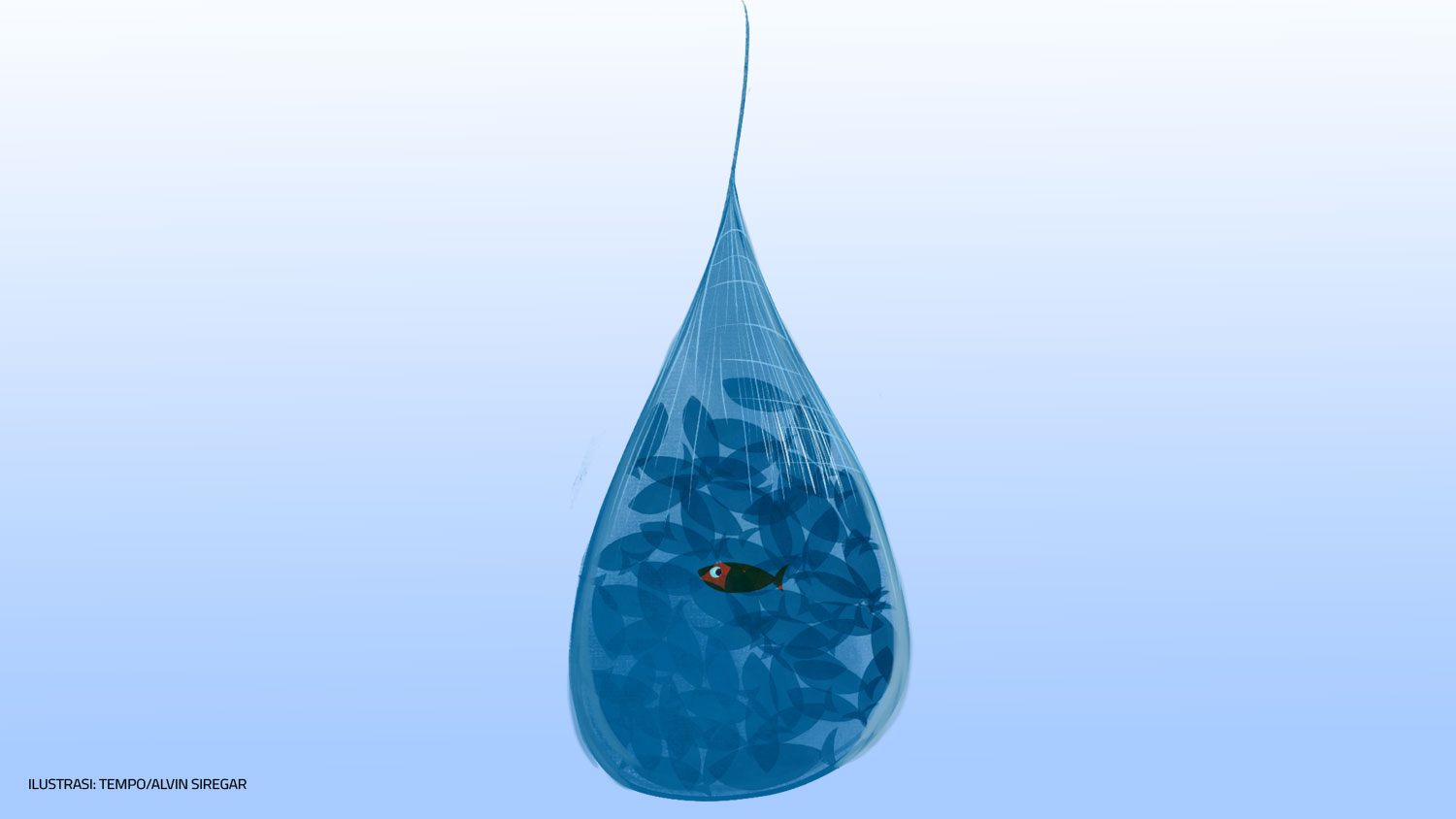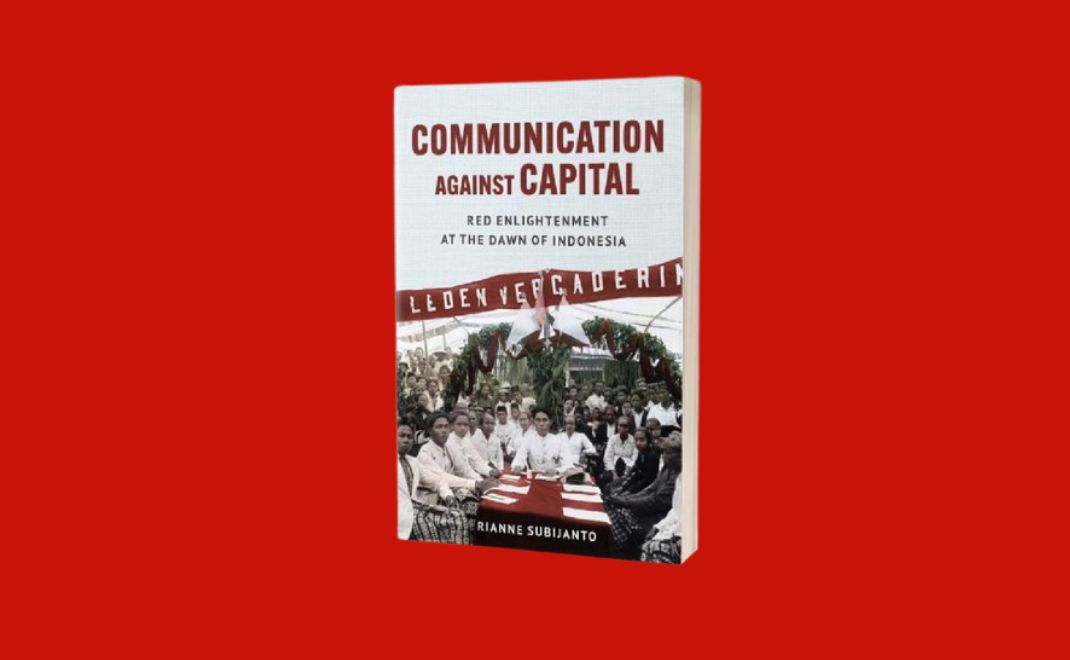Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mendung memayungi Desa Gerduren, Purwojati, sore itu. Di tengah desa yang terletak 30 kilometer dari Kota Banyumas, Jawa Tengah, itu berdiri sebuah balai desa berbentuk joglo yang sudah tua renta. Ada empat bocah yang asyik bermain sembari menanti gurunya, Warsiah, mengajarkan tari ronggeng.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo