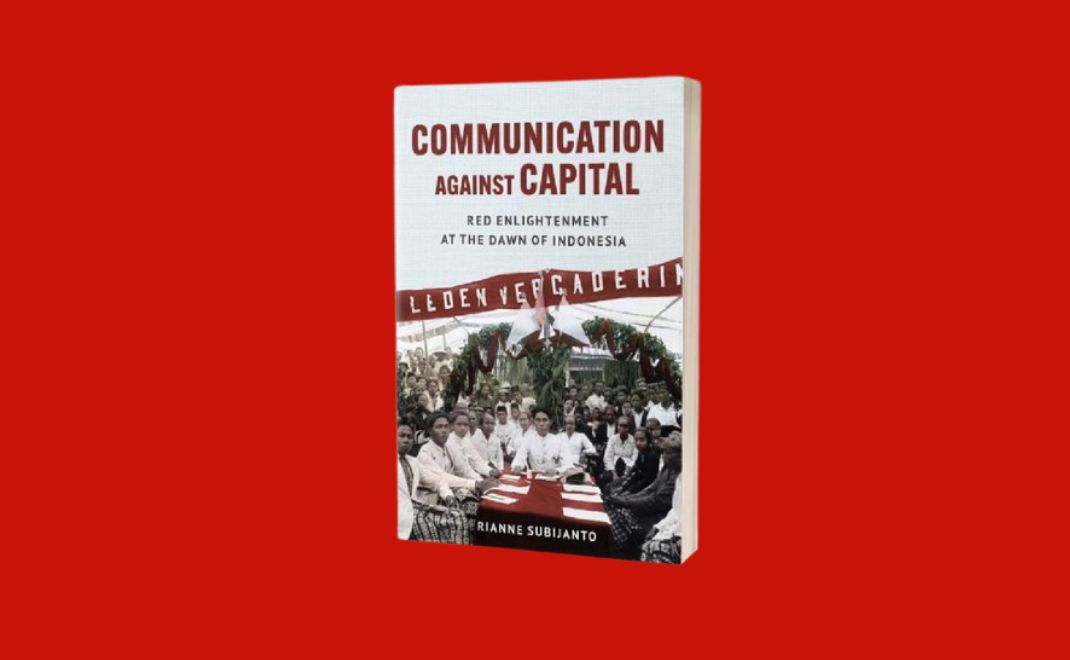Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA KERAS
(Pameran Foto Kota Kita)
Tempat : Galeri Foto Jurnalistik Antara
Waktu : 11 Agustus-5 September 1999
Karya : Alexander Louiciano, Alwis Rustam, Arizona Sudiro, Fajar S., M. Iqbal, Roy Rubianto, Widya S. Amrin.
USIANYA masih sangat muda. Ia mungkin baru lepas akil balig. Rambutnya dipotong pendek. Postur tubuhnya kerempeng. Tapi pada foto itu raut wajahnya tidak menunjukkan kemudaan. Garis mukanya keras. Matanya membelalak. Wajah itu juga menandakan semacam kedegilan: ujung alis mata yang tertarik ke atas serta beberapa anting yang terbuat dari peniti tertancap di cuping telinga. Ia menggenggam sebilah pisau.
Bocah dari Manggarai. Itulah salah satu foto yang dipamerkan di Pameran Foto Kota Kita yang bertajuk ''Jakarta Keras", di Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA); sebuah pameran foto reguler bertema Jakarta yang diadakan tiap tahun. Inilah foto yang menggambarkan betapa Jakarta sesungguhnya bukanlah kota yang nyaman. Perang antarkampung di Manggarai menjadi rutinitas sementara anak yang dibesarkan dalam budaya kekerasan.
Pameran foto kali ini memang memotret kekerasan dari pelbagai sudut dan dengan pelbagai interpretasi. Kekerasan tidak dipahami hanya sebagai relasi vertikal, misalnya kekerasan oleh aparat militer terhadap demonstrasi mahasiswa. Kekerasan, oleh tujuh fotografer peserta workshop tahunan GFJA ini, dibaca dengan lebih luas. Maka, yang lahir adalah serangkaian kisah berdarah tentang kehidupan di lingkungan Manggarai, tentang tawuran antarpelajar, atau parut besar di punggung seorang ibu muda akibat sabetan parang suami—orang yang semestinya jadi pagar kehidupannya.
Bahkan kekerasan bisa juga muncul dalam gambar laci-laci penyimpan mayat di rumah sakit yang lirih, atau mayat korban mutilasi: kepala yang tengadah dan leher yang penuh jahitan—seperti tubuh yang menahan rasa sakit.
Pilihan memberi interpretasi yang luas ini menjadi menarik. Para fotografer itu tampaknya berhasil keluar dari apa yang dalam dunia jurnalistik dikenal dengan istilah ''news peg", yakni sebuah tonggak yang menandai kehangatan berita (aktualitas) sehingga apa yang disajikan terasa hangat, tapi pada suatu ketika menyembunyikan kedalaman.
Pada periode paruh pertama 1999, ketika fotografer muda itu mengumpulkan bahan untuk pameran ini, sesungguhnya negeri ini tengah dipenuhi oleh peristiwa kekerasan yang memenuhi persyaratan news peg tadi. Sepanjang periode itu, bergelimpangan berbagai peristiwa kekerasan seperti demonstrasi mahasiswa, kampanye pemilu, pembantaian di Aceh, Timor Timur, dan Irianjaya. Kejadian semacam ini sesungguhnya sangat menggoda untuk direkam, tapi mereka toh tidak memilih topik itu—kecuali pada rekaman foto karya Mohamad Iqbal. Selebihnya, enam fotografer lain memilih sudut lain, kekerasan dalam skup yang berbeda.
Dengan sudut pandang itu, pameran foto ini menyajikan pemahaman yang berbeda tentang kekerasan. Kekerasan tidak cuma terjadi secara vertikal, tapi juga horizontal, misalnya kekerasan suami terhadap istri, kekerasan pelajar terhadap pelajar yang lain, atau kekerasan yang disebabkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan preman Blok-M yang riuh.
Selain itu, obyek dan subyek kekerasan menjadi tidak mudah untuk dituding. ''Kekerasan adalah kita. Sebagai pelaku sekaligus korban," demikian tulis Alexander Louiciano, salah seorang peserta, dalam kata pengantarnya. Mereka membuang pretensi untuk mencari tahu siapa penyebab dan siapa korban kekerasan. Dengan kata lain, kekerasan dipandang sebagai sebuah siklus. Hari ini seorang pelajar bisa remuk oleh lemparan batu dalam sebuah tawuran. Suatu ketika, ketika mereka besar dan menjadi suami, mereka adalah subyek kekerasan dalam keluarga.
Selebihnya adalah tragedi. Foto-foto hitam-putih disajikan dalam adegan-adegan yang mencekam. Tidak ada permainan teknis yang berlebihan, tapi yang diperoleh dari ketujuh fotografer itu adalah sebuah kedalaman.
Mereka masuk ke tengah-tengah masyarakat yang menjadi sasaran bidik, dan bergaul menjadi satu. Pendekatan etnografis inilah yang menjadikan foto-foto itu ''berbunyi" (lihat boks).
Jika dibandingkan dengan serial pameran foto serupa sebelumnya, pameran kali ini tampaknya menunjukkan serangkaian karya yang paling getir. Tiga tahun lalu, pameran dengan judul ''Jakarta Bermain" memang mengirimkan kepahitan—bahwa orang kehilangan ruang publik—karena tiba-tiba semua ruang berubah menjadi ''pasar". Tapi, karena di dalamnya ada elemen permainan, kepahitan itu tidak terlalu tampak dibandingkan dengan ''Jakarta Keras". Hal yang sama juga terjadi dalam pameran ''Jakarta Kota Tua", pada 1994.
Acungan jempol memang harus diberikan kepada GFJA, yang mau secara rutin menggarap pameran dan workshop semacam ini. Ini bukan cuma untuk melahirkan fotografer baru yang andal, tetapi juga bisa menghasilkan orang-orang yang mampu melihat kekerasan dari perspektif yang berbeda.
Arif Zulkifli
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo