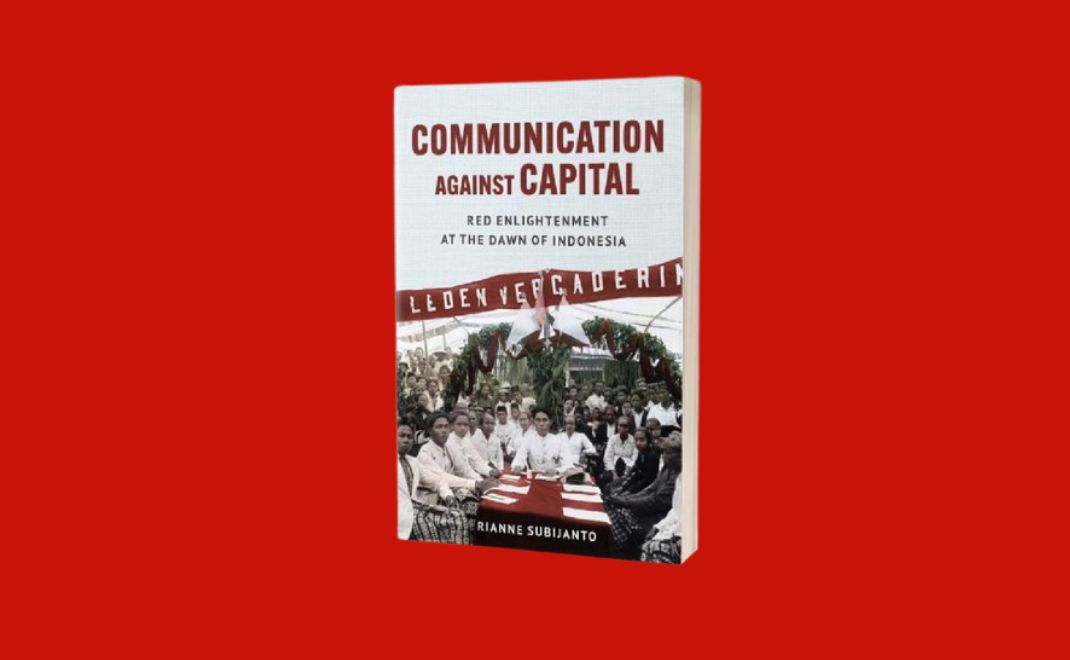Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Panggung gedung teater utama Esplanade sepenuhnya sunyi. Dari tangga bambu yang panjang, seseorang dengan hem putih, dengan posisi terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas, menyusur turun. Perlahan, tapi cukup mengejutkan. Lelaki dari "langit" itu adalah simbol kelahiran manusia modern.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo