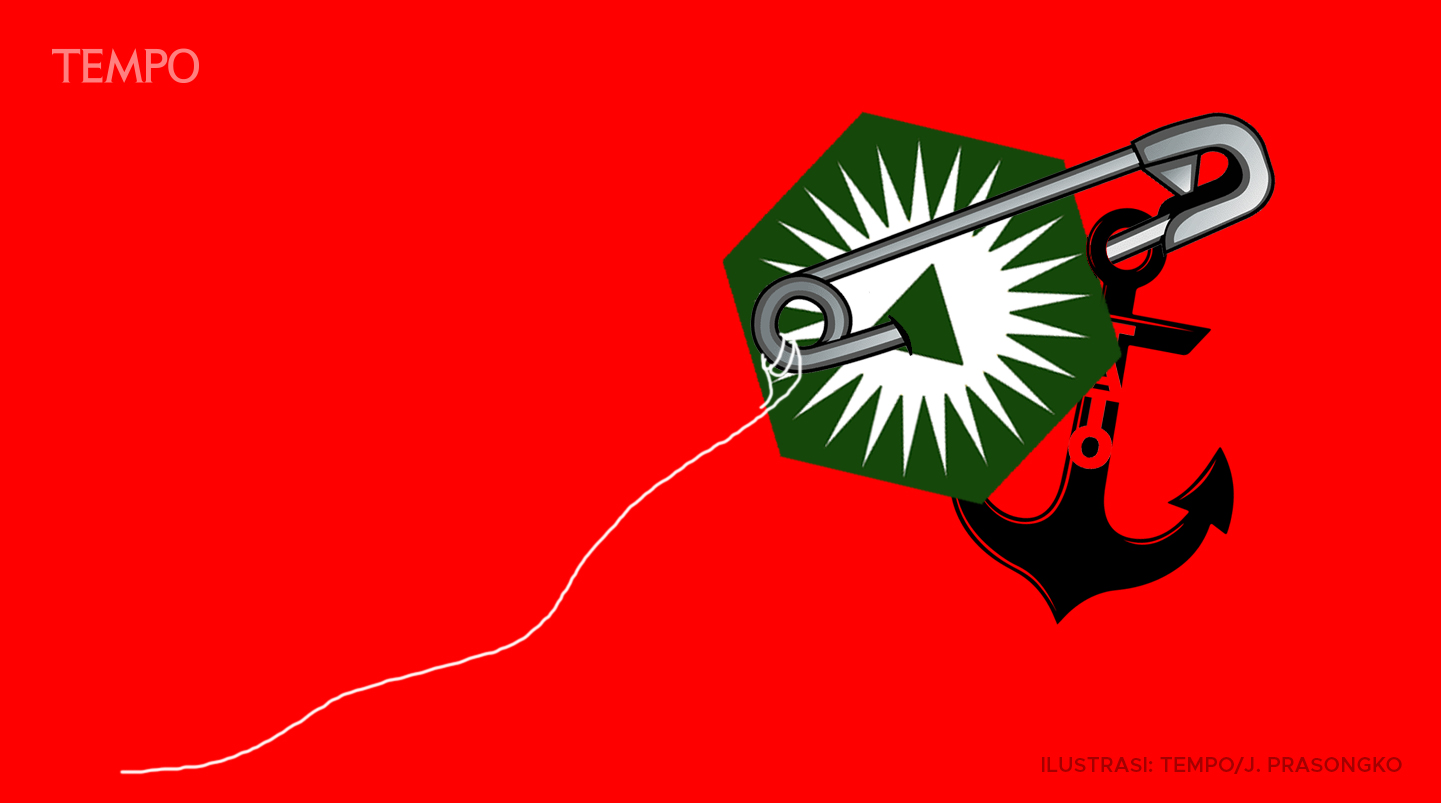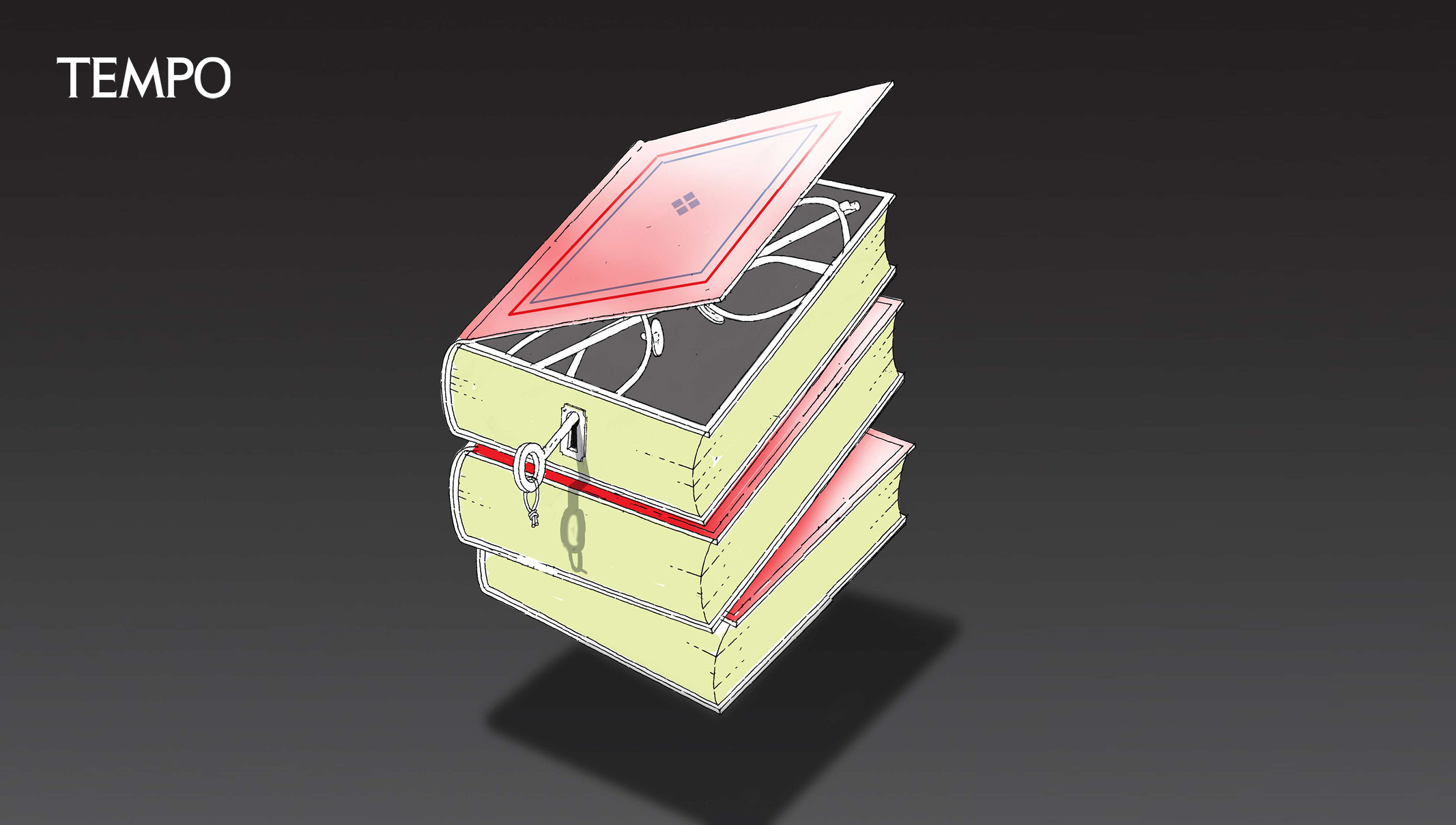Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

INDONESIA kini menjadi negara dengan keunikan yang mengkhawatirkan: secara formal ia punya semua ornamen menjadi negara demokratis, tapi pada saat yang sama, secara praktis, Indonesia makin memenuhi syarat menjadi negara nondemokratis yang diatur oleh kekuasaan otoriter. Keadaan ini melahirkan apa yang saya sebut sebagai “ambiguitas otoritarian”, yakni praktik memanipulasi demokrasi secara substansial melalui aspirasi sisi prosedural.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Ambiguitas Otoritatrian"