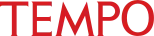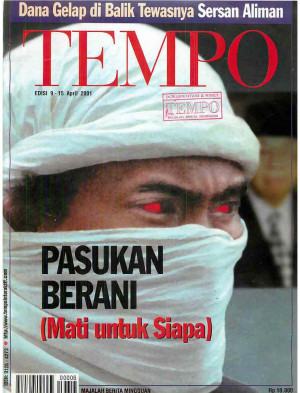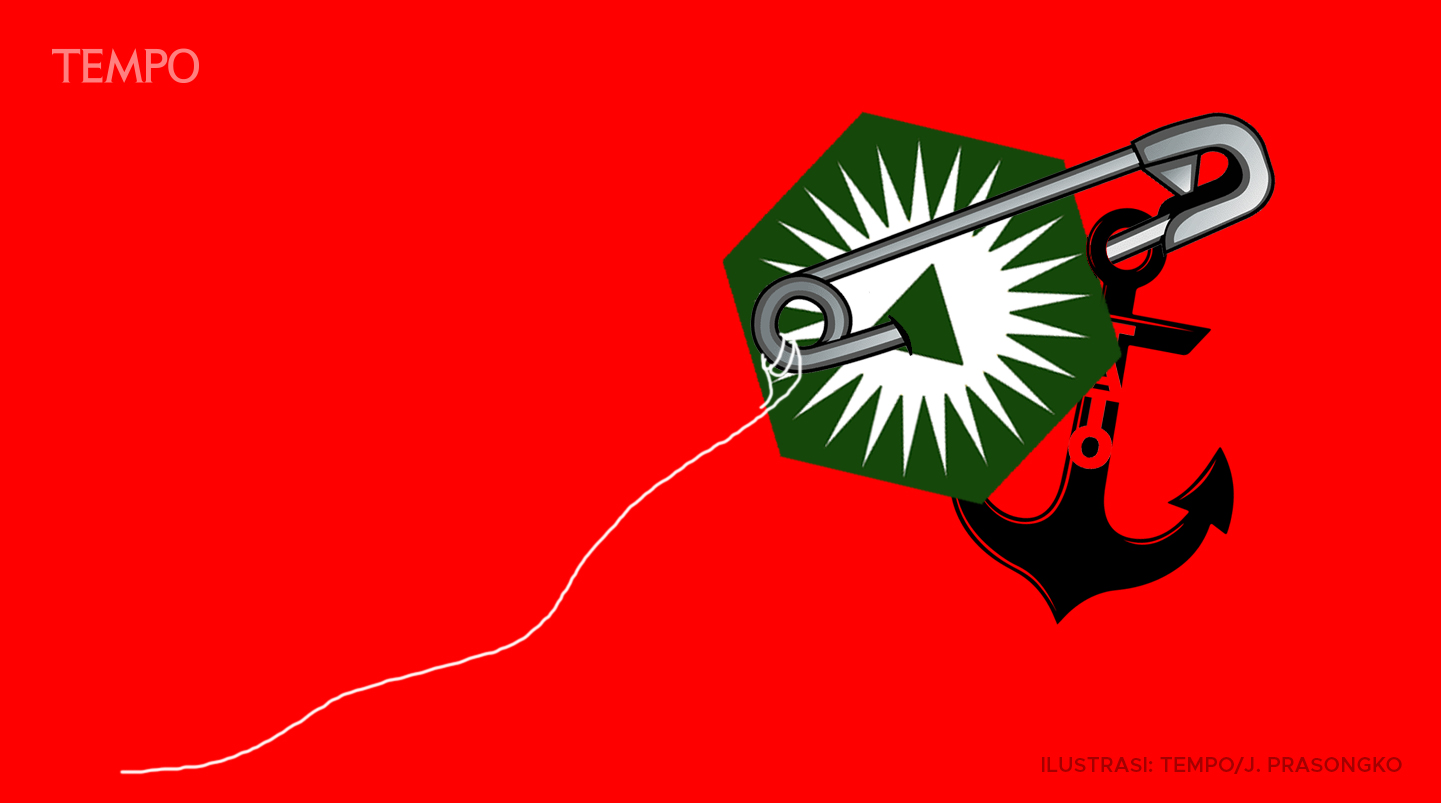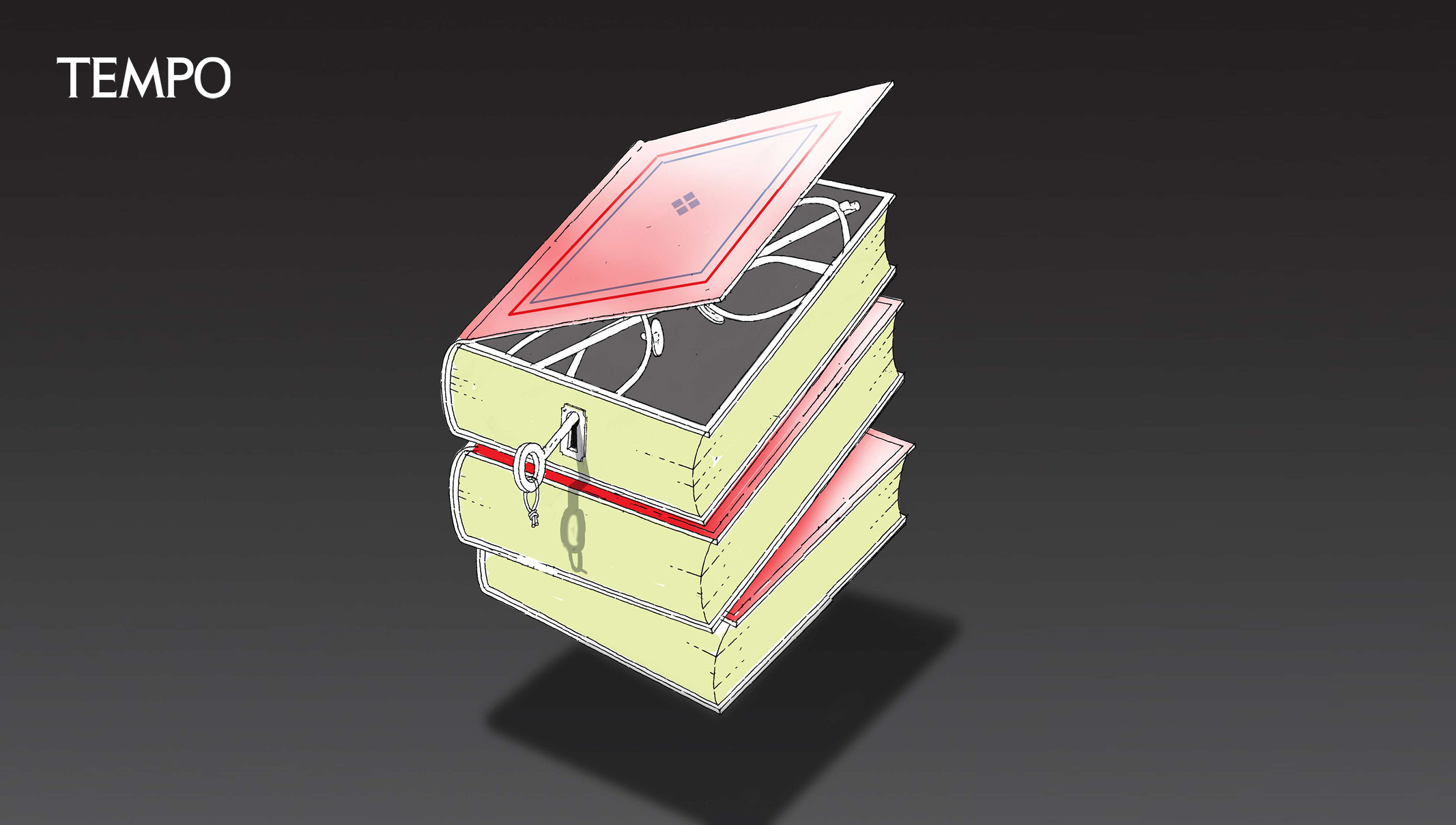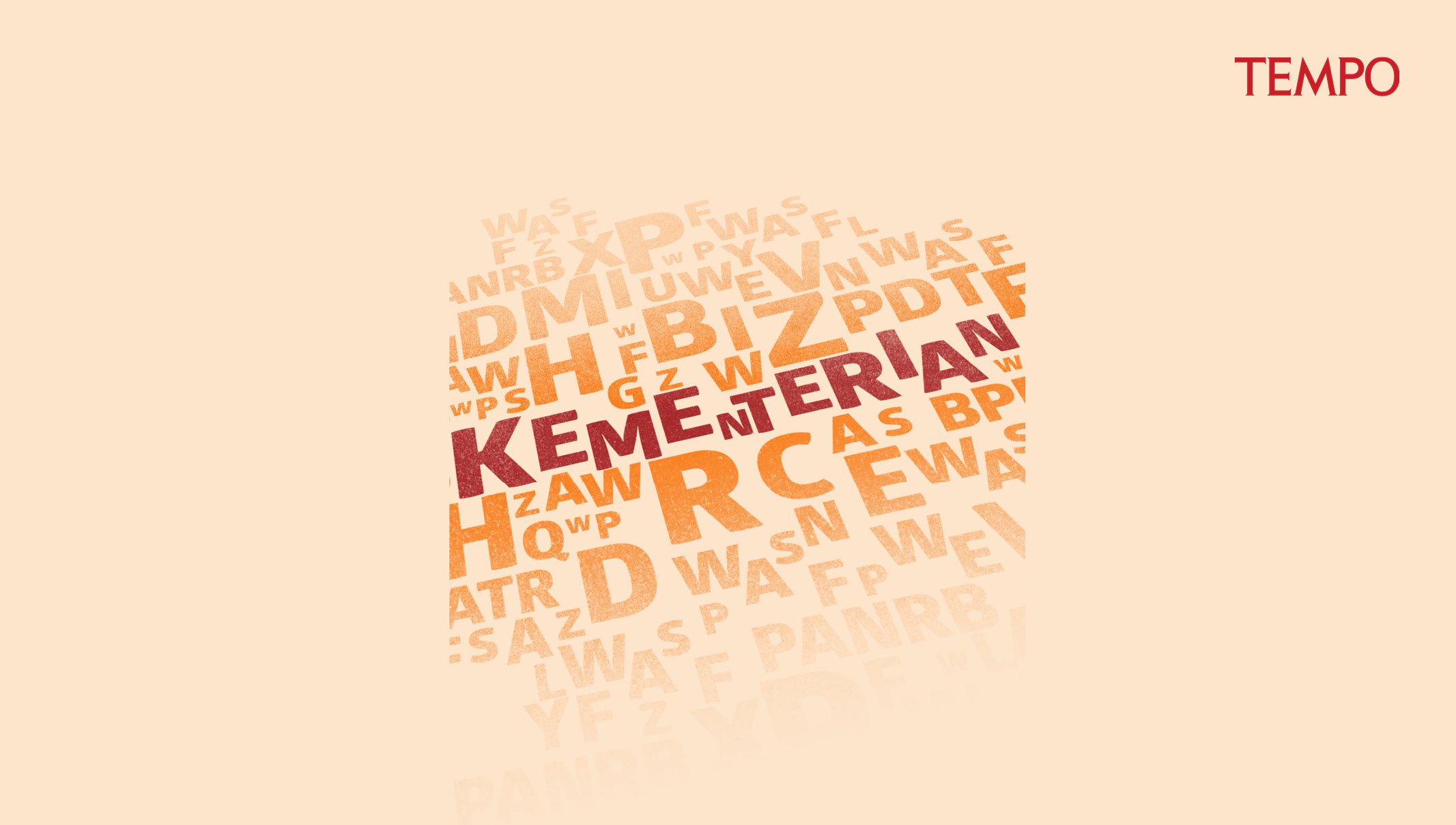Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Samuel Huntington keliru ketika mengatakan bahwa militer yang profesional cenderung enggan mengintervensi politik dalam negeri. Pengalaman Jerman dan Jepang sebelum Perang Dunia II membantah teorinya. Faktor profesionalisme memang mengekang nafsu militer untuk berpolitik. Tapi yang jauh lebih penting adalah keikhlasan militer menerima supremasi kekuasaan sipil. Dan itu tidak termasuk dalam definisi "profesionalisme". Intervensi: Kapan? "Intervensi militer" adalah penggantian kebijakan dan orang-orang pemerintahan sipil dengan kebijakan dan orang-orang militer. Intervensi bisa dilakukan secara aktif ataupun pasif. Kadang-kadang mereka melakukan tindakan yang berlawanan dengan kehendak pemerintah. Kadang-kadang mereka juga tidak mau disuruh melakukan sesuatu oleh pemerintah. Untuk intervensi harus ada motif, suasana, dan kesempatan. Tidak ada satu pun golongan yang menyatakan bahwa mereka melakukan suatu tindakan demi kepentingan mereka sendiri. Landasannya selalu "kepentingan nasional". Militer punya kedudukan istimewa dalam menggunakan landasan ini. Mereka berada di luar politik gabungan. Tugas mereka adalah tugas negara. Dan keberadaannya memang dimaksudkan khusus untuk membela negara tersebut. Lembaga kemiliteran merupakan simbol kemerdekaan dan kedaulatan yang paling menonjol. Lebih dari lembaga masyarakat lainnya, lembaga kemiliteran diliputi oleh ide nasional. Setiap latihan militer menekankan identitas nasional dan patriotisme. Jadi, kalau mereka mengintervensi dengan alasan kepentingan nasional, orang lebih mudah percaya. Motif lainnya lebih bersifat egoistis. Militer selalu menjaga kepentingan mereka sebagai lembaga yang otonom. Bila otonomi itu dirasakan terancam, mereka sering melakukan intervensi. Dalam bentuk defensif, motif ini menjurus ke semacam sindikalisme militer: sikap bersikukuh bahwa militer, dan hanya militer, yang berhak menentukan besar-kecilnya angkatan perang, perlengkapan militer, dan pendaftaran calon serdadu. Dalam bentuk yang lebih agresif, kekhawatiran tersebut menjurus pada tuntutan agar militer menentukan semua hal yang berdampak pada angkatan bersenjata. Ada dua suasana yang mendorong militer melakukan intervensi. Yang pertama adalah ge-er yang berlebihan. Kebanggaan atas korps serta etos mengenai diri sendiri sebagai elite yang paling bersih, paling patriotik, paling berdisiplin, dan paling berjasa untuk mempersatukan wilayah kedaulatan, memang, mengandung unsur kebenaran bila dibandingkan dengan kebobrokan sektor sipil. Tapi sikap ini dibarengi oleh kebiasaan memandang rendah terhadap kaum sipil: sipil tak becus, saling bertikai terus, mutunya rendah, penuh kebohongan, dan suka akal-akalan. Suasana yang satu lagi adalah kebalikan dari ge-er. Ia timbul dari perasaan dipermalukan, rasa terhina, dan nasib terpuruk. Militer Prancis merasakan hal ini setelah mereka dipaksa melepaskan Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Pukulan terhebat mereka alami setelah kalah perang di Dien Bien Phu. Reaksi mereka antara lain menjelma dalam pembentukan Organisasi Militer Rahasia. Kesempatan untuk melakukan intervensi datang kalau pemerintah sipil terlalu bergantung pada militer, kalau negeri dilanda krisis, kalau timbul vakum kekuasaan. Berkurangnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah, dan bertambahnya harapan pada militer, menciptakan kesempatan bagi militer untuk berkonsolidasi dan mendongkrak pengaruh. Kelak, bila konsolidasi telah rampung, bila kuku pengaruh militer sudah tertancap, pada saatnya semua beban kesalahan akan diletakkan di pundak sipil. Bab 4, 5, dan 6 buku Finer merupakan bagian yang paling mencekam. Unsur-unsur penyebab intervensi militer dalam bab-bab tersebut banyak yang sudah tampak di Indonesia masa kini. Motif intervensi ada, suasana keterpurukan militer ada, dan sudah pula mulai meluas pandangan jangka pendek: "Ude, deh, serahin ama militer aje!" Kultur Politik Variabel terpenting dalam menentukan kemungkinan, intensitas, dan metode intervensi militer adalah tingkat kultur politik suatu masyarakat. Kultur politik bisa tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Ukurannya terletak pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Adakah konsensus tentang cara pergantian kekuasaan dan apakah cara yang menyimpang dari konsensus ini dianggap hampa legitimasi? (2) Adakah konsensus tentang siapa atau apa yang memegang kedaulatan dan apakah konsensus tersebut tidak mengakui legitimasi pihak yang bukan orang atau badan termaksud? (3) Apakah anggota masyarakat yang peduli "politik" cukup banyak dan cukup aktif dalam perhimpunan nonpemerintah seperti gereja, pengajian, industri, buruh, perusahaan, dan partai politik? Makin tinggi kultur politik, makin positif jawaban atas tiga pertanyaan itu dan kian tipis pula kemungkinan intervensi militer ke bidang nonmiliter. Kelompok "kultur politik tinggi" mencakup negara Barat seperti AS, Inggris, Selandia Baru, Kanada, Australia, dan tentunya sekarang Masyarakat Eropa. Pada masyarakat yang berkultur politik "berkembang", lembaga sipil sangat maju. Mobilisasi dan organisasi masyarakat pun cukup meluas. Namun, bagaimana cara pengalihan kekuasaan politik atau siapa yang pantas memegang kedaulatan masih dipertengkarkan. Jerman dan Jepang, pada masa di antara dua Perang Dunia, masuk dalam kategori ini. Kategori ketiga adalah masyarakat yang kultur politiknya "rendah". Jumlah orang yang peduli politik relatif kecil. Mereka juga tak terorganisasi dalam perhimpunan yang aktif mengejar kepentingannya. Opini di kalangan masyarakat kurang anti kepada intervensi militer. Dalam kekacauan dan suasana cakar-cakaran politik, banyak lapisan masyarakat bahkan berharap militer turun tangan dan memberikan pelajaran cinta-bangsa kepada politisi yang mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Kultur politik yang sangat rendah menganggap sepi pendapat umum. Organisasi politik dan kepentingan amat lemah. Dan lingkungan peduli politik juga sangat kecil. Agaknya, sebagian masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat kultur politik yang sangat rendah ini. Formula Finer Tingkat kultur politik terkait dengan nilai tinggi atau rendah yang dilekatkan masyarakat pada legitimasi kekuasaan. Nilai legitimasi ini menentukan kedalaman intervensi militer di bidang politik, metode pencapaian tujuan, dan bentuk rezim yang dihasilkan. Kultur politik yang tinggi memberikan nilai amat penting pada legitimasi. Dalam kultur semacam itu, tak mungkin legitimasi diraih oleh kaum militer. Di sini tiada kedalaman intervensi. Yang dikejar pihak militer sekadar pengaruh. Bentuk pemerintahannya adalah "sipil", sedangkan pengaruh militer bersifat terbatas dan tak langsung. Dalam kultur politik "berkembang", legitimasi suatu rezim dianggap sangat perlu. Nilai legitimasi semacam ini sulit melekat ke tubuh militer. Untuk mencapai tujuannya, militer melakukan "pemerasan" (blackmail). Pejabat sipil diintimidasi, atau diajak berkolusi, dan elite politik sipil diancam. Ancaman (dari pihak militer) berbentuk penolakan bekerja sama, atau secara diam-di- am tidak melaksanakan tugas yang dibebankan. Ada unsur sabotase dalam upaya semacam ini. Bentuk rezim tetap sipil, sedangkan intervensi militer dilakukan secara terbatas dan tak langsung. Dalam kultur politik rendah, legitimasi suatu rezim masih dianggap perlu, tapi dalam kondisi sudah jauh mencair. Intervensi militer berlangsung secara terang-terangan. Itulah yang sekarang terjadi di Pakistan atau di Burma. Militer secara sengaja tidak melindungi pemerintah sipil dari kekerasan. Mereka mengancam tidak mau bekerja sama. Sesekali mereka juga menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Kultur politik yang sangat rendah tidak mempedulikan legitimasi. Intervensi militer berlangsung secara terbuka, intensif, dengan metode dan tipe rezim yang sama seperti pada masyarakat kultur politik rendah. Akhirnya, militer hanya bisa berkuasa dalam perekonomian yang masih sederhana. Begitu ekonomi maju dan menjadi kompleks, begitu sektor industri dan jasa berkembang serta membutuhkan birokrasi yang profesional, tentara mulai kewalahan. Buku ini terbit pada 1962. Banyak deskripsi yang sudah usang. Tapi banyak pula bagian buku ini yang mengejutkan karena daya ramalnya yang tajam. Mengenai Indonesia, 40 tahun lalu Finer meramal: "...entah demokrasi terbuka atau demokrasi terpimpin, kemungkinan disintegrasi sosial sangat besar. Legitimasi pemerintah dijadikan sumber cekcok, prosedur-prosedurnya sulit dimengerti, dan masyarakat tercabik-cabik oleh golongan-golongan yang sulit bersepakat. Ini adalah masyarakat yang hidup di tepi jurang krisis terbuka, yang akan meledak pada saat simbol-simbol kemerdekaannya meredup. Dalam keadaan demikian, pemerintah bisa berdiam dan menonton golongan yang satu membantai golongan yang lain, atau memanggil bantuan militer untuk menumpas kegilaan golongan-golongan tersebut." |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo