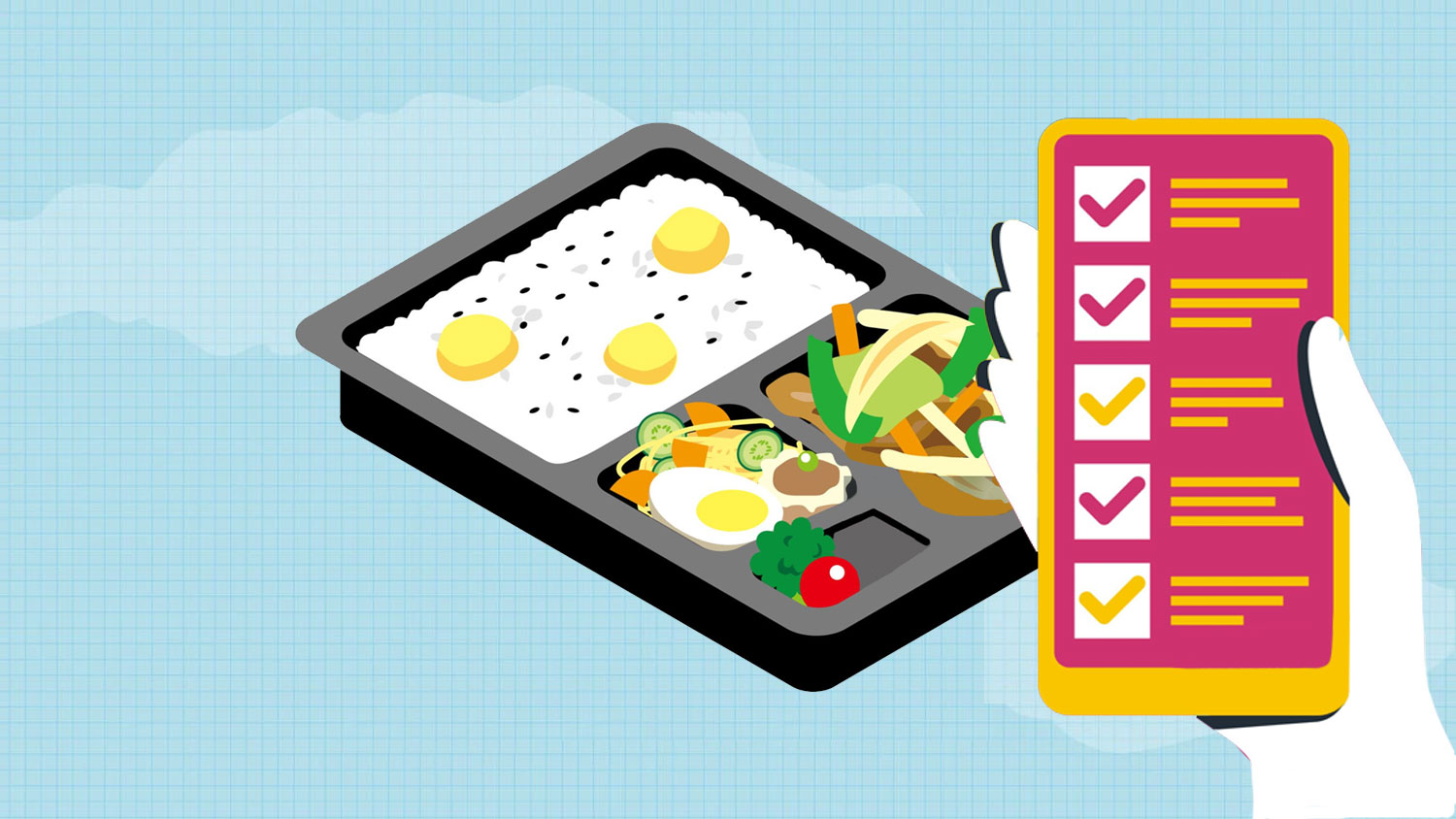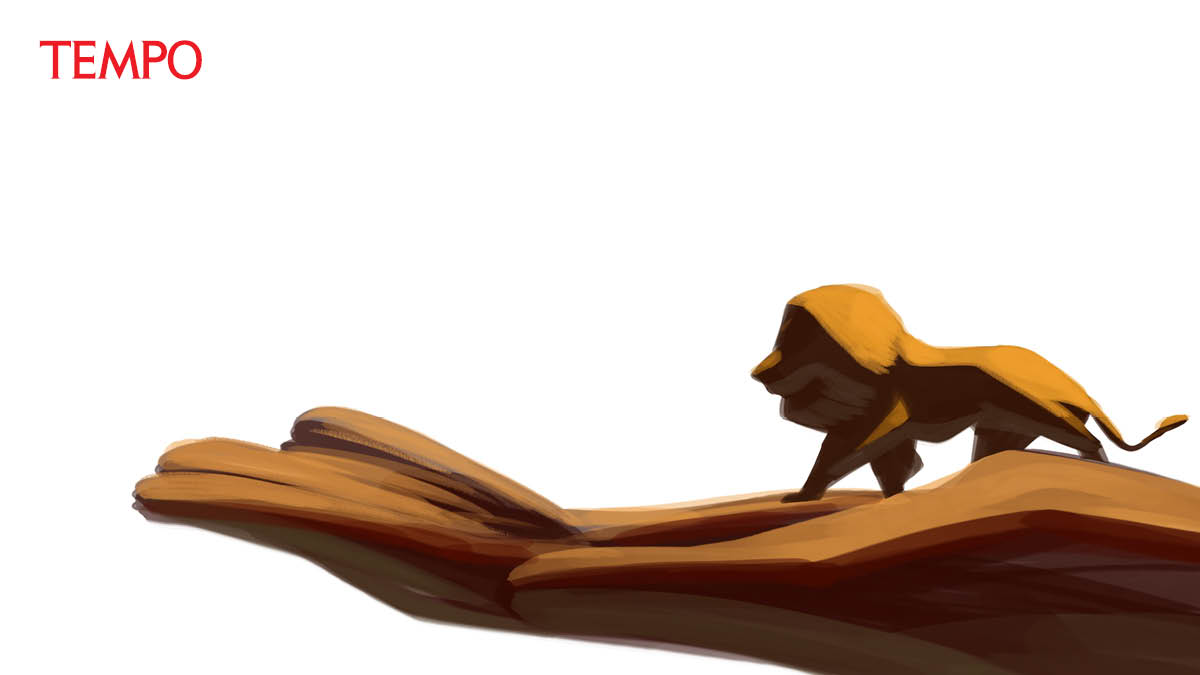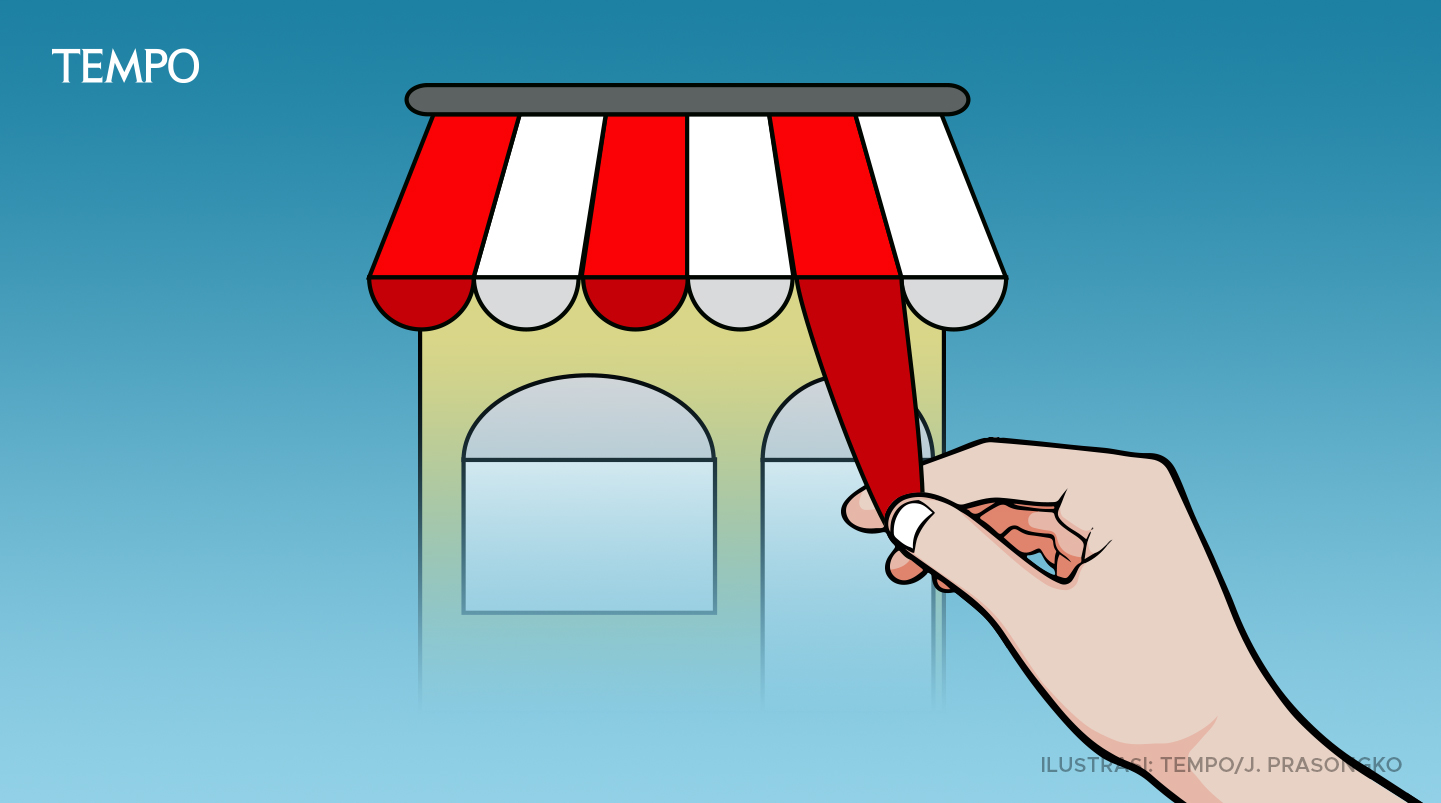Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta- Film produksi Prancis ini, amat disayangkan, gagal menerjemahkan dongeng yang justru lahir dari negaranya sendiri. Pemain dengan nama besar tapi penggarapan dan skenarionya lemah.
***
“A life for a rose.”
Demikian La Bête Si Buruk Rupa (Vincent Cassel) meraung. Ayah Belle, La Marchand, kembali ke rumah dan dengan murung menceritakan kepada enam anaknya tentang ancaman makhluk besar buruk muka gara-gara sang ayah mencuri setangkai bunga mawar untuk Belle di istana milik La Bête. Tentu saja Belle, anak perempuan kesayangan sang pedagang, menawarkan diri untuk menjadi “tawanan” Si Buruk Rupa karena merasa bersalah telah meminta setangkai mawar dari ayahnya.
Akibatnya: a life for a rose. Satu jiwa ditukar dengar seharga setangkai mawar.
Belle merasa harus bertukar diri dengan ayahnya sebagai tawanan Si Buruk Rupa, yang sejarahnya terkuak perlahan selama menetap di istana megah yang gelap dan kelam itu. Melalui sebuah kaca, Belle seperti dipersilakan menjenguk ke masa silam Si Buruk Rupa, yang ternyata seorang pangeran beristri seorang cantik jelita. Seperti dongeng di Indonesia juga, sang istri cantik melarang Pangeran yang gemar berburu itu untuk memburu seekor kijang emas cantik yang sudah lama diincar Pangeran dan kawan-kawannya. Tentu saja peringatan itu tak diindahkan. Kijang dihajar dengan panah, dan si kijang emas berubah menjadi... si cantik yang telanjang, berdarah, yang kemudian membuat Pangeran meraung ke langit....
Kisah Belle et la Bete atau Beauty and the Beast yang sedang ditayangkan di bioskop Indonesia ini sebetulnya produksi tahun 2014 yang mengambil cerita versi Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1740). Itulah sebabnya ada beberapa kisah latar belakang Si Buruk Rupa dan bahkan keluarga Belle yang sangat berbeda dengan cerita yang kita kenal umumnya. Film animasi Beauty and the Beast versi Disney (Gary Trousdale dan Kirk Wise, 1991) dengan penyanyi Broadway Paige O’Hara sebagai pengisi suara Belle, dan Robby Benson sebagai Si Buruk Rupa, mengambil versi Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont (1756). Film yang kemudian meledak dan menjadi film animasi pertama yang dinominasikan sebagai Film Terbaik Academy Award, selain juga lima nominasi lain. Keberhasilan film ini kemudian membawanya ke Broadway dan menjadi salah satu pertunjukan musikal yang berhasil yang kini akan menyambangi Indonesia.
Cerita Beauty and the Beast versi Beaumont jelas lebih “ringan”—dan karena itu lebih mudah diangkat sebagai format musikal—tetapi juga mendekati dongeng yang cocok untuk semua umur. Sedangkan versi de Villeneuve lebih redup, kelam, dan mengandung beberapa subplot dongeng yang ternyata tak jauh dengan berbagai dongeng Asia. Namun versi yang lebih gelap ini ternyata tak berhasil dibuat sebagai karya yang mengandung dinamit.
Dimulai dengan adaptasi cerita Villeneuve menjadi skenario dalam film ini saja sudah menjadi problem. Sutradara Gans mencoba membukanya dengan tokoh yang diperankan Léa Seydoux di sebuah “masa kini” mendongeng kepada anak-anaknya tentang seorang pangeran yang terkutuk menjadi “binatang” Si Buruk Rupa. Tak jelas tujuan sutradara membuat prolog seperti ini, karena kita toh sudah tahu yang berperan sebagai Belle kelak adalah Léa Seydoux juga. Problem kedua, dan sangat penting, sang sutradara dan penata kostum menggunakan kostum film untuk panggung. Sang pangeran seperti mengenakan topeng berbulu belaka seperti kostum Halloween, sementara Léa Seydoux, yang namanya sedang harum berkat perannya dalam film pemenang Palm D’or 2013 Blue is the Warmest Colour, bukan hanya tak bisa bergerak di dalam korset yang tampak mengekang, tapi juga tak bisa mennggeliat dari skenario yang mengurungnya dalam dialog yang banal dan klise.
Pada dasarnya cerita Beauty and the Beast, pada semua versi, sering dikritik sebagai sebuah dongeng yang mengandung “Stockholm Syndrome”: Belle yang ditawan akhirnya mencintai Si Buruk Rupa yang memenjarakannya. Di masa lalu tentu saja “Stockholm Syndrome” belum dianggap masalah psikologi yang problematik seperti sekarang. Karena itu sangat penting bagi sutradara modern untuk menekankan problem psikologi Sang Pangeran Buruk Rupa. Tak ada justifikasi untuk sebuah penculikan atau penawanan, tetapi film-film yang mengangkat tema seperti ini semacam Tie Me Up, Tie Me Down (Pedro Almodovar, 1990), yang menceritakan seorang aktris yang ditawan fans fanatiknya, berhasil membuat penonton mencoba menggali kejiwaan sang penculik, ada apa gerangan yang bergolak di otaknya hingga menculik dan menawan gadis cantik itu.
Film Beauty and the Beast versi 2014 dengan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantar–sementara yang di bioskop entah mengapa harus disulih suara dengan bahasa Inggris—berupaya menggebrak dengan visual. Yang terjadi adalah kekonyolan.
Vincent Cassel sebagai Si Buruk Rupa seolah tengah mengenakan topeng mainan anak-anak itu lebih mirip aktor yang sedang bermain dalam film Fifty Shades of Grey untuk pesta Halloween. Serangkaian subplot yang diotak-atik sutradara juga tak ada gunanya selain sutradara Gans ingin memperlihatkan dialah kreator film ini—penyakit yang perlu dibasmi—misalnya: jumlah anak si pedagang seharusnya hanya tiga, maka oleh Gans diubah menjadi enam. Buat apa? Hanya untuk menunjukkan bahwa pada awal abad ke-19 orang gemar beranak pinak?
Babak ketiga film ini yang berupaya “memaksimalkan” teknologi CGI (computer-generated imagery) justru memberi contoh bagaimana teknologi malah memperburuk sebuah film jika digunakan berlebihan.
Film ini juga merasa harus menampilkan “the real villain”, penjahat sesungguhnya, (yang tentu saja bukan Si Buruk Rupa) si lelaki bercodet di wajah itu juga tak ada gunanya, sama mubazirnya dengan adik kakak Belle yang digambarkan manja dan tukang buang duit. Mereka semua itu pada akhirnya cuma tambahan karena toh Si Buruk Rupa akan bisa kembali jadi pangeran jika ada yang mencintainya.
Bahkan film Beauty and the Beast versi Jean Cockteau (1946) yang masih hitam putih dan menggunakan konsep panggung itu masih lebih enak ditonton, karena semua visualisasi dan kostum sesuai dengan konsep.
Kekecewaan ini mungkin bisa kita buang saja karena tahun depan Bill Condon akan memulai syuting adaptasi film musikal versi baru Beauty and the Beast dengan Emma Watson sebagai Belle, Dan Stevens sebagai Si Buruk Rupa, Kevin Kline sebagai ayah Belle, Maurice dan Emma Thompson sebagai Mrs Pott. Dengan nama-nama yang menjanjikan ini, dan juga reputasi Bill Condon menggarap Sister, Sister (1987), Kinsey (2004), dan Dream Girls (2006)--sembari kita pura-pura melupakan Condon juga pernah ikut membuat The Twilight Saga: Breaking Dawn I dan II--mudah-mudahan versi ini akan menghilangkan kenangan buruk kita terhadap versi Christophe Gans.
Leila S. Chudori
BEAUTY AND THE BEAST
(Belle et la Bete)
Sutradara: Christophe Gans
Skenario: Christophe Gans dan Sandra Vo-AnhBerdasarkan kisah yang ditulis Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1740)
Pemain: Vincent Cassel (La Bête atau The Beast), Léa Seydoux (Belle), André Dussollier (Le Marchand, ayah Belle)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini